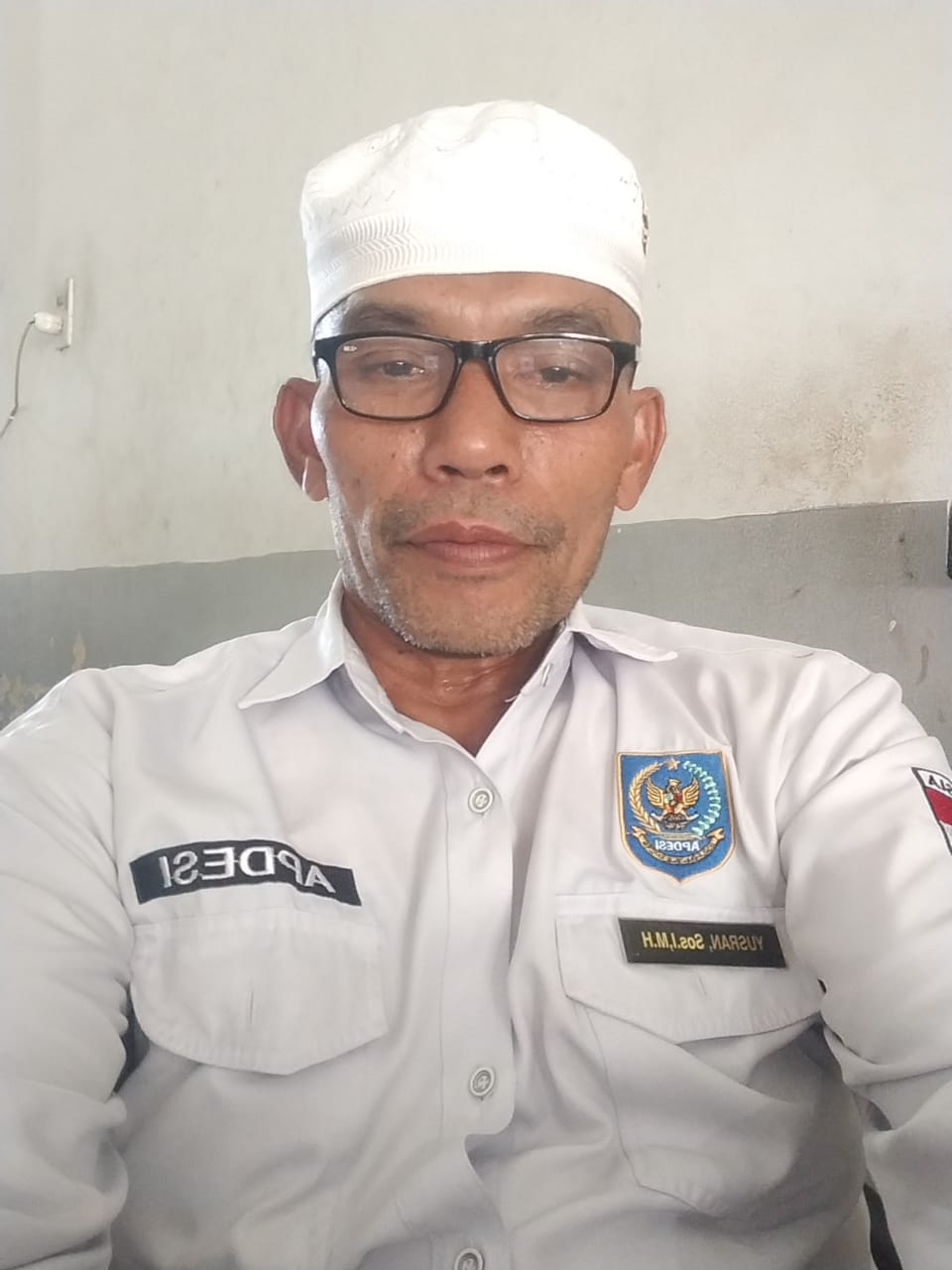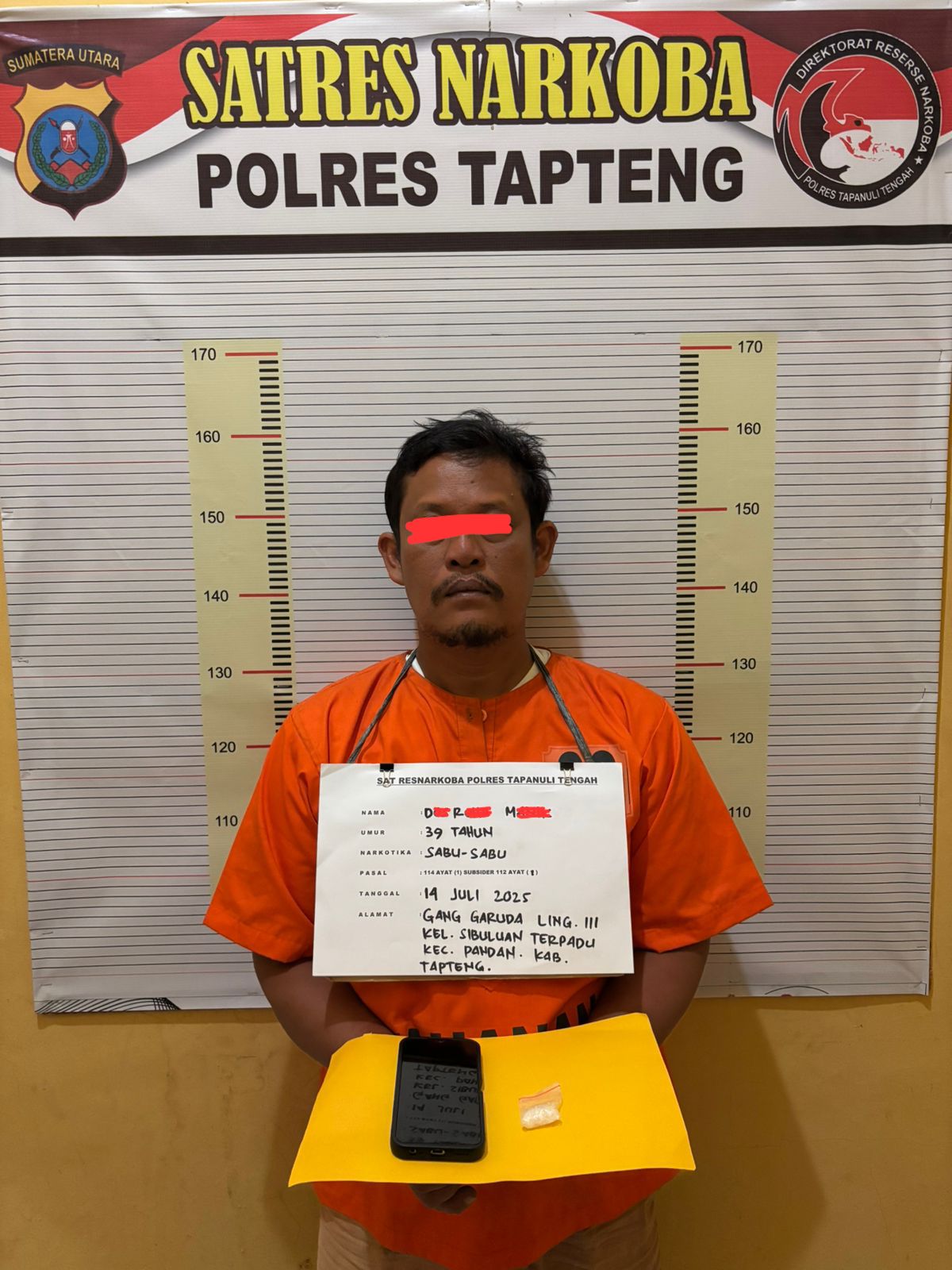Oleh Shohibul Anshor Siregar
Naskah tua ini mengajarkan pelajaran paradoksal. Ia mengingatkan bahwa pengetahuan paling rinci pun bisa menjadi alat penaklukan
Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN
Artikel ini tentang masyarakat Batak dalam sorotan kolonial. Tentang narasi etnografi dan kuasa yang ditulis dalam sebuah dokumen berjudul Batakspiegel (1926). Dokumen kuning berjilid kulit itu tergeletak di atas meja kayu Gedung Bataksch Instituut Leiden, memancarkan aura pengetahuan sekaligus penguasaan. Batakspiegel atau “Cermin Batak” terbitan 1926 ini bukan sekadar kumpulan data geografis dan adat istiadat, melainkan mesin politik yang menyamar sebagai karya ilmiah.
Setiap halamannya membisikkan kisah ganda: upaya dokumentasi etnografis yang rinci berpadu dengan agenda kolonial yang terselubung rapi. Naskah setebal 382 halaman ini menjadi saksi bisu bagaimana pengetahuan direkayasa untuk melayani kekuasaan, sambil tak sengaja mengawetkan fragmen-fragmen dunia Batak yang mulai retak diterpa modernitas.
Karya monumental ini lahir dari rahim Bataksch Instituut, lembaga kolonial Belanda yang berdiri tahun 1908 dengan misi ambisius: mengumpulkan data selengkap mungkin tentang “Bataklanden” beserta penduduknya. Pada edisi kedua tahun 1926, peta-peta baru hasil survei Topografische Dienst menggantikan sketsa usang, mencerminkan perluasan cengkeraman administratif pasca-aneksasi 1904-1908.
Peta itu sendiri menjadi metafora sempurna, garis batas yang digambar Belanda memotong-motong tanah leluhur marga, mengubah hubungan sakral dengan tanah menjadi sekadar blok-blok teritorial yang bisa diatur, dipajak, dan dieksploitasi.
Jejak Kaki Di Bumi Bergolak
Penjelajah Eropa awal seperti Anderson (1823) dan Van der Tuuk (1852) membuka jalan dengan catatan perjalanan penuh prasangka. Mereka terpesona sekaligus jijik menyaksikan praktik kanibalisme ritual, mengabaikan kompleksitas sistem hukum adat di baliknya. Junghuhn dalam ekspedisi 1840 melintasi Mandailing, matanya lebih tertarik pada potensi perkebunan kopi ketimbang falsafah Dalihan Na Tolu. Baru pada pergantian abad, dengan berdirinya Bataksch Instituut, pengumpulan data menjadi sistematis, sekaligus lebih berbahaya.
Misi penelitian Joustra dan Volz tahun 1904-1906 beriringan dengan derap sepatu lars tentara Kolonial. Ketika peneliti mencatat struktur marga di Karo, serdadu merampas senjata tradisional. Saat etnograf menggambar peta persawahan Toba, petugas pajak menyusun register penduduk. Kolaborasi antara sarjana dan penguasa ini mencapai puncaknya dalam “missie-Colijn” 1904, ekspedisi ilmiah yang sekaligus merancang peta aneksasi wilayah-wilayah Batak terakhir.
Anatomi Kekuasaan Dalam Tinta
Bagian-bagian Batakspiegel membelah kehidupan Batak menjadi kategori-kategori yang mudah dicerna administrasi kolonial. Deskripsi geografis yang memetakan enam wilayah utama, Karoland, Timoerland, Pakpakland, Toba, Angkola, Mandailing, disusun seperti laporan intelijen militer. Data kepadatan penduduk di Si Lindoeng (20 jiwa/km²) dan sawah Toba bukan sekadar fakta demografis, melainkan alat menghitung potensi pajak dan tenaga kerja rodi.
Sistem kekerabatan marga yang rumit dipadatkan menjadi skema administratif. Konsep boroe (pernikahan antar kelompok) yang dinamis direduksi menjadi tabel statis. Pengamat kolonial salah menafsirkan hubungan spiritual marga dengan tanah sebagai “kepemilikan”, membuka jalan bagi perampasan tanah adat atas nama “pengelolaan lahan tak bertuan”. Padahal bagi Batak, tanah persawahan adalah jelmaan nenek moyang, bukan komoditas.
Ritual tondi dan bëgoe yang sakral dihadirkan sebagai “takhyul primitif”. Upacara menghormati tondi (nyawa) dalam kelahiran, pernikahan, dan kematian dicap sebagai praktik takhayul. Penyembahan bëgoe (roh leluhur) yang menjadi landasan kosmologi Batak direndahkan menjadi “kekuatan gelap”. Deskripsi tentang kanibalisme ritual sengaja dibesar-besarkan untuk membenarkan misi “pembudayaan”, meski praktik ini sudah memudar sebelum kedatangan Belanda.
Mesin Ekonomi Di Balik Topeng Ilmu
Data etnografis dalam Batakspiegel bekerja untuk mesin uang kolonial. Catatan rinci tentang jaringan sungai dan jalur perdagangan tradisional berubah jadi peta logistik pengangkutan kopi. Register marga menjadi alat kontrol untuk kerja paksa herendiensten. Bahkan penghapusan perbudakan tahun 1876 yang diagungkan sebagai kemenangan moral, dalam praktiknya menciptakan sistem baru: mantan budak berubah menjadi buruh murah di perkebunan tembakau Deli.
Pembaca jeli akan menemukan jejak pahit eksploitasi terselip di antara deskripsi netral. Ketika teks menyebut produksi kemenyan di Barus, tak diungkap bahwa Belanda memonopoli perdagangannya sejak 1834. Saat memaparkan kesuburan tanah Karo, disembunyikan fakta bahwa 40% tanah adat sudah dirampas untuk korporasi asing. Laporan tentang “kemajuan” jalan raya Arnhemia-Karo ternyata dibangun dengan pungutan tenaga kerja paksa.
Suara Yang Dibungkam
Di balik kesan objektif, Batakspiegel membungkam lebih banyak hal daripada yang diungkapkannya. Suara perempuan Batak absen dalam naskah ini, padahal mereka memegang peran kunci dalam pewarisan ulos dan ritual pertanian. Perlawanan halus seperti gerakan Parhudamdam yang menolak pajak hanya disebut sekilas sebagai “kekacauan”. Yang paling menyedihkan, adaptasi kreatif masyarakat Batak menghadapi kolonialisme – seperti sinkretisme keyakinan animis dengan Kristen atau Islam – disederhanakan sebagai “kemajuan menuju peradaban”.
Tokoh seperti Singamangaraja XII, pemimpin spiritual yang memimpin perlawanan selama 30 tahun, hanya muncul sebagai catatan kaki tentang “kematian pemimpin pemberontak”. Padahal jejaknya masih hidup dalam tradisi lisan Batak sebagai pahlawan budaya. Sementara misionaris seperti Nommensen diagungkan sebagai pembawa terang, padahal sekolah zending sengaja didirikan di atas tanah keramat untuk memutus hubungan spiritual dengan leluhur.
Warisan Yang Retak
Satu abad kemudian, Batakspiegel masih memantulkan bayangan kompleks. Di satu sisi, teks ini menyelamatkan detail budaya yang sudah punah, struktur rumah adat Simalungun, ritual mangongkal holi pembongkaran tulang leluhur, atau sistem kalender tradisional berdasarkan siklus bulan. Tanpa catatan Joustra, mungkin dunia sudah kehilangan jejak dialek Batak Phakpak yang kini terancam punah.
Di sisi lain, warisan paling abadi justru kerangka birokrasi kolonial yang tertanam dalam pemerintahan modern. Pembagian administratif Sumatera Utara masih mengikuti garis batas buatan Belanda. Sertifikasi tanah masih bermasalah karena berbenturan dengan konsep kepemilikan adat. Bahkan kebanggaan modern orang Batak terhadap “tradisi” seringkali merupakan tradisi yang sudah disaring dan dibentuk ulang oleh lensa kolonial dalam teks-teks seperti ini.
Kini banyak suara yang yang keluar dari Nurani paling dalam mengeluhkan ketercabik-cabikan karena Pembangunan yang ditandai oleh fakta industry yang memaksa banyak hal tergerus, termasuk ha katas tanah karena korporasi membutuhkan kayu.
Membaca Batakspiegel hari ini seperti membedah arsip dengan dua pisau. Pisau pertama membuka lapisan-lapisan kekuasaan: bagaimana data disusun untuk kontrol, bagaimana budaya dibekukan menjadi “objek studi”, bagaimana manusia direduksi menjadi angka statistik. Pisau kedua menyibak celah-celah perlawanan: tradisi lisan yang bertahan, praktik adat yang beradaptasi, memori kolektif yang menolak lupa.
Naskah tua ini mengajarkan pelajaran paradoksal. Ia mengingatkan bahwa pengetahuan paling rinci pun bisa menjadi alat penaklukan. Tapi sekaligus membuktikan, upaya membekukan kebudayaan dalam teks tak pernah sepenuhnya berhasil. Roh tondi orang Batak terus hidup melampaui halaman-halaman kertas yang mengira telah memenjarakannya. Seperti sungai Asahan yang deras mengalir dari Danau Toba, kolonialisme bisa membendungnya sementara, tapi takkan pernah menghentikan arusnya yang abadi.
Merdeka itu susah, Lae. Susah.
Penulis adalah Dosen Fisip UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.