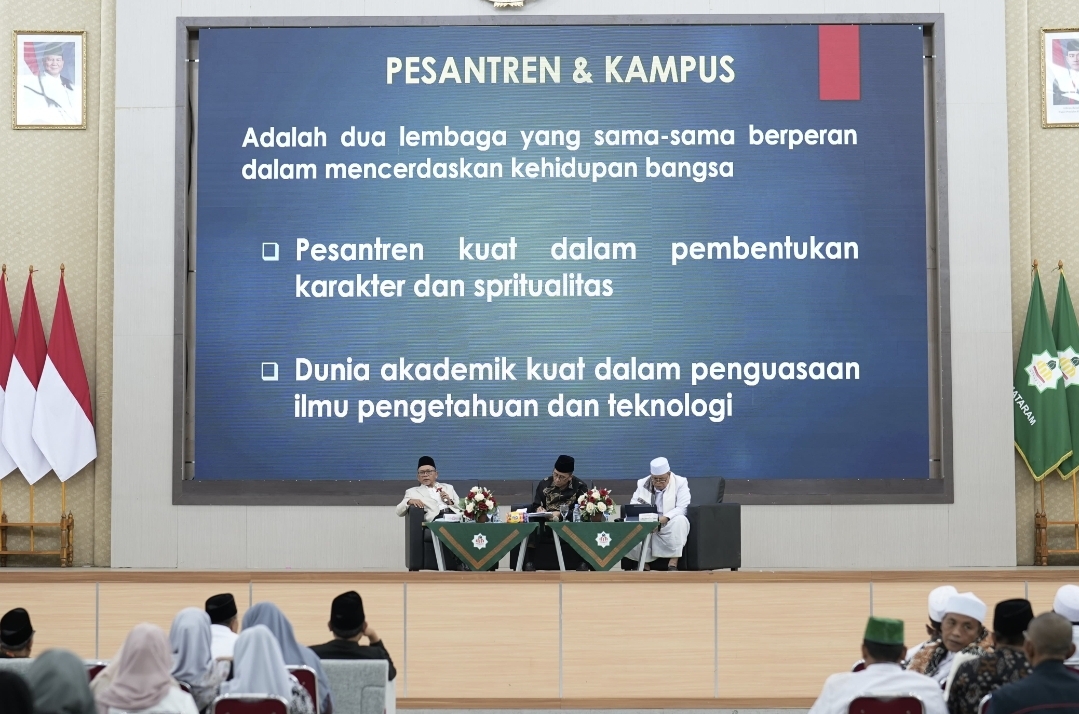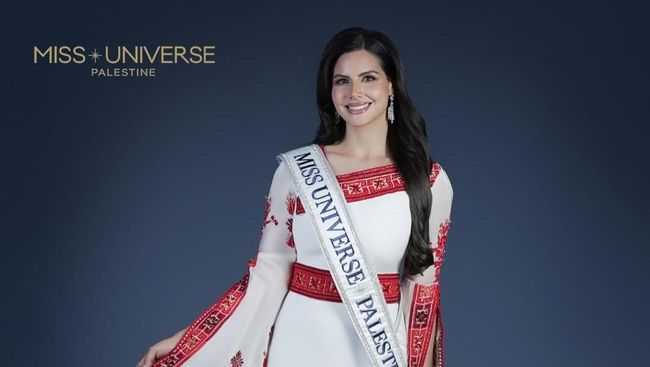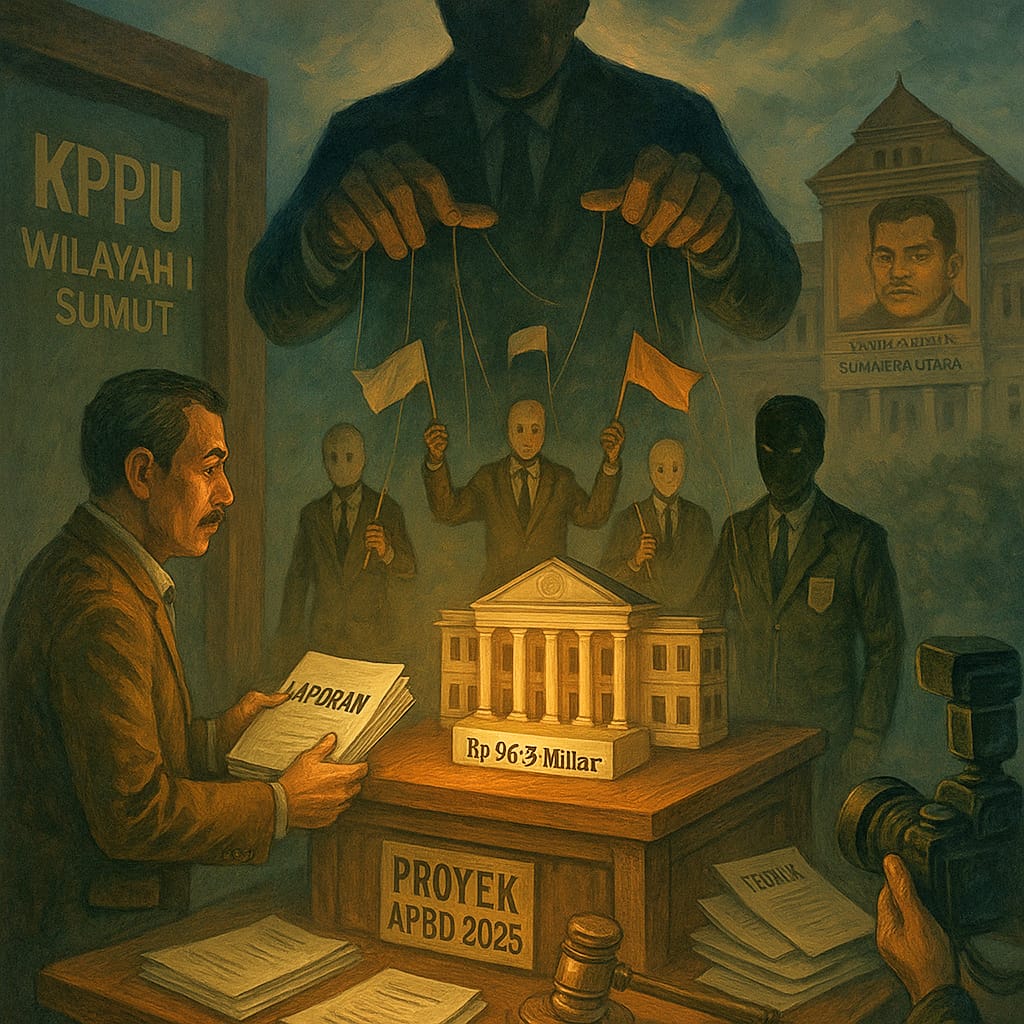Oleh Dr. H. Ikhsan Lubis, SH, SpN, M.Kn
Di tengah krisis legitimasi yang perlahan melanda institusi-institusi demokrasi di berbagai belahan dunia—termasuk Indonesia—perlu kiranya kita kembali menilik akar filosofis dan etimologis dari konsep kedaulatan rakyat sebagai fondasi negara hukum modern. Salah satu frasa Latin yang patut ditempatkan di garis depan dalam diskursus ini adalah potestas in populo est—kekuasaan ada pada rakyat. Ungkapan ini bukan sekadar retorika klasik yang berdebu di lemari filsafat, melainkan menyimpan kekuatan normatif yang aktual dan kontekstual, terutama di tengah praktik demokrasi prosedural yang kian menjauh dari substansi.
Dalam kajian etimologi, potestas merujuk pada kekuasaan atau otoritas yang sah dan sahih; in menunjukkan letak atau keberadaan; dan populo—turunan dari populus—berarti rakyat. Maka secara harfiah, potestas in populo est berarti “kekuasaan berada di tangan rakyat”. Frasa ini membawa implikasi yang radikal dalam pemikiran politik: bahwa kekuasaan yang sah tidak bersumber dari takhta, senjata, garis keturunan, melainkan berasal dari kehendak kolektif rakyat. Ia menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, rakyat bukan sekadar objek dari kuasa negara, melainkan subjek yang menjadi sumber legitimasi segala bentuk otoritas publik.
Secara historis, konsep ini berakar pada pemikiran filsuf Romawi seperti Cicero, lalu berkembang melalui teori kontrak sosial dari pemikir modern seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau. Dalam kerangka social contract, negara lahir bukan dari dominasi, melainkan dari kesepakatan bersama untuk melindungi hak-hak dasar manusia. Dalam konteks ini, rakyat memberikan mandat kepada negara untuk bertindak atas nama mereka, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, ketika negara menyimpang dari mandat tersebut, rakyat memiliki legitimasi moral dan hukum untuk melakukan koreksi.
Potestas in populo est bukanlah konsep asing dalam hukum tata negara. Ia menjadi inti dari berbagai konstitusi modern yang menjunjung tinggi prinsip popular sovereignty. Bahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat ini termanifestasi secara implisit dalam kalimat, “… dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas …”, yang menegaskan bahwa rakyat adalah subjek hukum yang menentukan arah dan struktur negara. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Ini adalah bentuk konvergensi antara nilai klasik dari tradisi Latin dan konstruksi hukum modern Indonesia.
Untuk memperdalam refleksi ini, sejumlah frasa Latin lain dapat memperkaya diskursus. Misalnya, populus est supremus—rakyat adalah yang tertinggi—menekankan bahwa tidak ada otoritas yang boleh melebihi kehendak rakyat secara moral maupun politik. Imperium a populo, artinya kekuasaan berasal dari rakyat, bukan diberikan oleh kekuatan adikodrati atau dinasti. Bahkan, dalam bentuknya yang paling lugas, populus imperat (“rakyat memerintah”) menjadi artikulasi eksplisit dari sistem pemerintahan berbasis partisipasi kolektif dan legitimasi horizontal. Di sisi lain, frasa vox populi, vox Dei—“suara rakyat adalah suara Tuhan”—meskipun bersifat teologis dan sempat diperdebatkan, tetap menjadi simbol kuat tentang supremasi aspirasi rakyat dalam proses politik.
Sebagai pembanding yang relevan, kita juga mengenal istilah primus inter pares—“yang pertama di antara yang setara”—yang lazim digunakan dalam konteks kepemimpinan kolektif. Dalam sistem parlementer, perdana menteri dianggap sebagai primus inter pares, yakni pemimpin di antara sesama menteri, tetapi bukan yang paling berkuasa secara absolut. Konsep ini menekankan kesetaraan dalam struktur kekuasaan, bukan dominasi. Dalam kerangka demokrasi, frasa ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan harus berbasis pada koordinasi, bukan superioritas sepihak. Konsep seperti ini memberi pelajaran penting tentang gaya kepemimpinan yang berakar pada legitimasi moral, bukan kekuasaan yang sentralistik.
Korelasi antara potestas in populo est dan primus inter pares melahirkan pemahaman yang lebih utuh mengenai relasi rakyat dan negara. Yang pertama menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, sedangkan yang kedua mengingatkan bahwa pemimpin, seberapapun tingginya, tetap berada dalam kerangka kesetaraan. Keduanya merepresentasikan model kekuasaan yang egaliter dan etis. Dalam praktik demokrasi yang sehat, kedua prinsip ini menjadi penyeimbang antara kebutuhan akan struktur dan jaminan bahwa struktur tersebut tetap dikendalikan oleh rakyat.
Namun realitas politik hari ini sering kali tidak mencerminkan ideal tersebut. Lembaga negara kerap menjadi instrumen dari elite politik atau kekuatan oligarki, bukan cermin kehendak rakyat. Prosedur demokrasi dijalankan, tetapi substansinya tereduksi menjadi transaksi kuasa yang jauh dari nilai publik. Dalam kondisi seperti ini, menegaskan kembali bahwa potestas in populo est bukan sekadar retorika, melainkan peringatan konstitusional dan etis agar kekuasaan selalu tunduk pada mandat rakyat.
Oleh karena itu, menghidupkan kembali frasa seperti potestas in populo est dalam ruang publik, lembaga pendidikan, dan pembentukan kebijakan bukanlah langkah simbolik belaka. Ia adalah upaya untuk merawat ingatan kolektif bahwa demokrasi bukan hanya urusan prosedur, tetapi juga moralitas politik. Prinsip ini bisa menjadi bagian dari semboyan institusional, nilai dasar pembelajaran kewarganegaraan, atau bahkan filter dalam evaluasi kebijakan publik. Sebuah negara yang mengklaim dirinya demokratis harus memastikan bahwa rakyat tidak hanya dihitung suaranya setiap lima tahun, tetapi juga didengar aspirasinya dalam setiap perencanaan dan implementasi kebijakan.
Dengan demikian, potestas in populo est bukan sekadar adagium hukum, melainkan semacam norma dasar (grundnorm) yang perlu terus diperjuangkan dalam praktik bernegara. Sebab, tanpa keterlibatan aktif rakyat, kekuasaan kehilangan legitimasi; dan tanpa legitimasi, hukum hanyalah produk prosedural yang hampa nilai. Di tengah maraknya populisme, sentralisasi kekuasaan, dan politik simbolik, frasa ini layak kembali didengungkan—bukan untuk romantisme masa lalu, tetapi sebagai penegasan bahwa kekuasaan sejati hanya bisa hidup bila berpijak pada kehendak rakyat.
Primus inter Potestates: Menegaskan Kedaulatan Rakyat sebagai Pusat Legitimasi Kekuasaan
Dalam wacana ketatanegaraan modern, ketika konsep demokrasi sering dikerdilkan menjadi sekadar rutinitas elektoral, kita perlu kembali menyuarakan prinsip dasar yang bersifat etimologis sekaligus filosofis: primus inter potestates—yang pertama di antara segala kekuasaan. Frasa Latin ini, meskipun terdengar klasik, memuat muatan yang sangat kontemporer: bahwa dalam sistem demokrasi konstitusional, rakyat bukan hanya bagian dari struktur kekuasaan, melainkan entitas normatif tertinggi yang mendahului dan mengatasi seluruh cabang kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Dalam teori politik modern, konsep ini menyatu dengan doktrin popular sovereignty—bahwa kekuasaan sah (legitimate power) tidak berasal dari kekuatan koersif negara, melainkan dari konsensus rakyat yang memberi mandat melalui mekanisme yang disepakati bersama. Karena itu, dalam sistem constitutional democracy, kekuasaan negara harus dibatasi dan dibagi melalui prinsip separation of powers. Namun, pembagian kekuasaan itu bersifat derivatif—turunan dari sumber kekuasaan yang sejati: rakyat. Bila demikian, maka rakyatlah yang layak disebut primus inter potestates: pemegang mandat asal, titik pusat legitimasi, dan fondasi utama seluruh struktur kenegaraan.
Perspektif ini menegaskan bahwa konstitusi bukan sekadar dokumen hukum buatan elite birokrasi atau teknokrat hukum, tetapi kontrak sosial yang lahir dari volonté générale—kehendak umum rakyat. Kita bisa melihat ini dalam narasi pembukaan konstitusi banyak negara. Amerika Serikat memulai Konstitusinya dengan “We the People…”, sementara Indonesia menegaskannya secara implisit dalam Pembukaan UUD 1945 melalui kalimat: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur…”—sebuah frasa yang menempatkan rakyat sebagai pencipta dan pemilik kehendak dasar bernegara.
Dalam kerangka ini, rakyat bukan hanya subjek pasif yang memberi suara dalam pemilu setiap lima tahun, melainkan aktor aktif yang memiliki kedudukan hukum tertinggi dalam siklus kekuasaan. Kedaulatan bukan sekadar istilah normatif, melainkan posisi konstitusional yang hidup dan dinamis. Di sinilah pentingnya membedakan antara kekuasaan yang delegatif—yang dipegang oleh lembaga negara berdasarkan mandat—dan kekuasaan originair yang dimiliki oleh rakyat. Konsep primus inter potestates hadir sebagai koreksi terhadap pemahaman kekuasaan yang menempatkan negara seolah-olah di atas rakyat, padahal seluruh otoritas publik hanya sah sejauh mencerminkan kepentingan publik yang diberi mandat.
Menariknya, konsep ini berkaitan erat dengan frasa Latin lain yang telah lebih dulu dikenal, yakni potestas in populo est—kekuasaan berada di tangan rakyat. Jika potestas in populo est menekankan sumber kekuasaan, maka primus inter potestates menggarisbawahi kedudukan tertinggi rakyat dalam hirarki kekuasaan negara. Keduanya membentuk fondasi etimologis dan konseptual yang kokoh untuk membangun argumen hukum dan politik yang berpihak pada kedaulatan rakyat. Terlebih dalam konteks Indonesia saat ini, ketika praktik demokrasi kian terjebak dalam jebakan elektoralisme dan kooptasi oligarki, penguatan konsep-konsep seperti ini menjadi relevan sekaligus mendesak.
Kita dapat melihat kegentingan ini dalam dinamika politik belakangan, di mana kepercayaan publik terhadap institusi-institusi negara terus menurun. Menurut berbagai survei nasional, lembaga legislatif, partai politik, dan bahkan lembaga penegak hukum mengalami penurunan legitimasi yang signifikan. Penyebabnya beragam: mulai dari ketertutupan proses legislasi, konflik kepentingan dalam penganggaran, hingga represivitas negara terhadap gerakan sipil. Dalam situasi seperti itu, rakyat semakin menjauh dari struktur negara, bukan karena apatis, tetapi karena tidak melihat dirinya diwakili secara otentik. Apabila hal ini dibiarkan, maka demokrasi akan kehilangan jiwanya. Demokrasi tanpa rakyat bukan hanya kontradiksi konseptual, tetapi juga krisis normatif. Seperti dicatat Hans Kelsen dalam Pure Theory of Law, legitimasi norma dasar (grundnorm) tidak hanya bersandar pada keabsahan formal, tetapi juga pada penerimaan sosial. Jika rakyat menolak legitimasi kekuasaan karena merasa tidak diikutsertakan, maka seluruh struktur hukum akan goyah secara etis dan politis.
Oleh karena itu, membangkitkan kembali kesadaran akan frasa seperti primus inter potestates bukanlah agenda akademis yang elitis, melainkan bagian dari upaya merawat akal sehat publik dalam menghadapi disorientasi kekuasaan. Konsep ini dapat menjadi jangkar moral bagi pemimpin politik, hakim konstitusi, pembuat undang-undang, hingga birokrasi. Bahwa kekuasaan bukanlah alat dominasi, tetapi instrumen pelayanan terhadap rakyat yang memegang mandat tertinggi.
Sebagai pembanding, primus inter pares—yang berarti “yang pertama di antara yang setara”—sering digunakan dalam konteks kepemimpinan kolektif, seperti perdana menteri dalam sistem parlementer. Tetapi primus inter potestates membawa makna yang lebih fundamental: rakyat tidak hanya setara dengan kekuasaan lain, tetapi mendahului dan melegitimasi semuanya. Dalam demokrasi yang sehat, tidak boleh ada kekuasaan yang berdiri lebih tinggi dari rakyat. Setiap kebijakan publik, anggaran negara, hingga penegakan hukum harus berakar pada dan kembali kepada kepentingan rakyat.
Maka, dalam situasi politik yang semakin kompleks dan relasi negara-masyarakat yang kian renggang, penting bagi kita semua—baik pembuat kebijakan, aktivis sipil, maupun akademisi—untuk menegaskan kembali prinsip ini: bahwa primus inter potestates bukan sekadar frasa Latin kuno, melainkan prinsip konstitusional yang harus terus dihidupkan dalam praktik bernegara. Tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi cangkang kosong: prosedural tapi tak bermakna, formal tapi tak berkeadilan. Sebab pada akhirnya, tanpa rakyat, tidak ada kekuasaan yang sah. Dan tanpa kedaulatan rakyat, tidak ada demokrasi yang utuh.
Adagium Hukum-Politik untuk Demokrasi Modern
Dalam pusaran zaman yang memperlihatkan kerapuhan institusi demokrasi, ketimpangan representasi, dan krisis kepercayaan terhadap kekuasaan negara, penting bagi bangsa-bangsa modern untuk kembali menegaskan fondasi filosofis dari sistem hukum dan politiknya. Dalam konteks ini, adagium Latin Primus inter potestates: populus est suprema lex—yang berarti “Yang pertama di antara segala kekuasaan: rakyat adalah hukum tertinggi”—layak diajukan sebagai semboyan hukum-politik modern yang mengandung bobot etis, filosofis, dan konstitusional sekaligus. Frasa ini tidak sekadar menggabungkan dua prinsip agung dalam filsafat politik klasik—potestas (otoritas yang sah) dan lex suprema (hukum tertinggi)—tetapi juga memformulasikan ulang prinsip popular sovereignty ke dalam rumusan yang lebih padat, tegas, dan menyeluruh: bahwa rakyat bukan hanya sumber kekuasaan, tetapi juga tujuan dan batas tertinggi dari kekuasaan itu sendiri.
Adagium ini berangkat dari semangat lama yang hidup sejak masa Romawi: salus populi suprema lex esto (“keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi”), yang dikemukakan oleh Cicero sebagai norma etika dalam pemerintahan Republik. Namun dalam transformasi semantik yang lebih progresif, populus est suprema lex tidak hanya menempatkan keselamatan rakyat sebagai tolok ukur legitimasi, tetapi menegaskan eksistensi rakyat sebagai norma grundnorm—norma dasar dari seluruh sistem hukum dan politik. Artinya, rakyat tidak semata-mata menjadi objek perlindungan atau pemelihara stabilitas negara, melainkan menjadi aktor konstitutif yang memiliki otoritas tertinggi. Dalam konstruksi ini, hukum bukan alat kekuasaan, melainkan artikulasi dari kehendak rakyat; dan kekuasaan negara hanya sah sejauh ia tunduk dan mengabdi kepada hukum yang berpijak pada kedaulatan rakyat.
Selain itu, dalam praktik ketatanegaraan modern, adagium ini dapat berfungsi sebagai normative compass—kompas etis yang mengarahkan tafsir terhadap fungsi konstitusi, hukum, dan lembaga negara. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan publik, dalam bentuk dan cabang apa pun—eksekutif, legislatif, maupun yudikatif—hanyalah bentuk turunan dari mandat rakyat. Maka, jabatan publik tidak boleh dianggap sebagai privilese atau warisan kekuasaan, tetapi sebagai derivatif dari kehendak rakyat yang harus terus-menerus diuji dalam terang prinsip lex suprema. Presiden, hakim konstitusi, anggota parlemen, hingga pejabat birokrasi harus menyadari bahwa semua keputusan—baik yang tertuang dalam undang-undang, putusan pengadilan, maupun kebijakan administratif—pada hakikatnya harus diukur dari satu parameter utama: apakah keputusan itu menguatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, atau justru menjauhkannya dari ruang partisipasi dan kontrol?
Relevansi adagium ini menjadi semakin mendesak ketika kita menyaksikan gejala degradasi demokrasi ke dalam bentuk electoral authoritarianism, di mana legitimasi diperoleh lewat prosedur demokratis, tetapi substansinya dikendalikan oleh logika kekuasaan yang eksklusif. Di sinilah Primus inter potestates: populus est suprema lex menjadi koreksi mendalam terhadap kecenderungan formalisme hukum yang memisahkan legalitas dari legitimasi rakyat. Negara hukum yang sejati tidak hanya menjunjung tinggi prinsip rule of law, tetapi juga menjamin bahwa hukum itu sendiri dibentuk dan ditegakkan dalam semangat rule by the people. Jika tidak, hukum hanya menjadi jubah untuk membenarkan dominasi elit atas ruang publik.
Lebih jauh, adagium ini dapat berfungsi sebagai constitutional narrative yang mendorong reinterpretasi terhadap relasi antara rakyat dan negara. Dalam tradisi hukum publik kontemporer, kekuasaan dinyatakan sah bukan karena bersumber dari konstitusi semata, tetapi karena konstitusi itu sendiri bersumber dari kehendak rakyat. Dalam hal ini, adagium populus est suprema lex menjadi penanda bahwa tidak ada norma hukum, sekuat apapun, yang dapat bertahan jika bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat bukan hanya pembayar pajak atau pemilih lima tahunan, tetapi penentu arah kekuasaan dan sumber legitimasi setiap norma.
Oleh karena itu, adagium ini seharusnya tidak berhenti sebagai rumusan filosofis atau artefak akademik. Ia perlu dihidupkan kembali sebagai semboyan institusional, panduan konstitusional, dan materi pendidikan kewarganegaraan. Di tengah iklim politik yang didominasi oleh oligarki ekonomi, kooptasi partai, dan kelesuan partisipasi publik, Primus inter potestates: populus est suprema lex adalah pengingat bahwa demokrasi sejati hanya dapat bertahan jika rakyat tetap menjadi pusat dari seluruh orientasi kekuasaan. Frasa ini bukan sekadar kalimat Latin yang indah, melainkan artikulasi moral bahwa hukum tanpa rakyat adalah kehampaan, dan kekuasaan tanpa rakyat adalah penyimpangan.
Primus inter Potestates: Kedaulatan Rakyat Tak Tergoyahkan
Dalam diskursus hukum dan politik modern, adagium Latin bukan sekadar ornamen retoris, tetapi juga wadah filosofis yang menyimpan nilai-nilai normatif yang tajam. Salah satu frasa yang relevan untuk menegaskan kembali prinsip dasar demokrasi konstitusional adalah Primus inter potestates: populus est suprema lex—“Yang pertama di antara segala kekuasaan: rakyat adalah hukum tertinggi.” Ungkapan ini bukan hanya kombinasi terminologis dari dua konsep klasik, potestas (otoritas sah) dan suprema lex (hukum tertinggi), tetapi merupakan pernyataan prinsipil bahwa dalam tatanan negara hukum yang demokratis, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari rakyat itu sendiri.
Adagium ini lahir dari upaya untuk memperluas makna yang terkandung dalam frasa sebelumnya, primus inter pares—“yang pertama di antara yang setara”—yang lazim digunakan dalam sistem kepemimpinan kolegial seperti parlemen atau sinode gereja. Namun, ketika pares (setara) diganti dengan potestates (kekuasaan), orientasi etimologisnya pun berubah: bukan lagi soal keutamaan dalam kesetaraan struktural, melainkan soal supremasi normatif dari rakyat atas seluruh struktur kekuasaan negara. Dengan demikian, primus inter potestates menegaskan rakyat sebagai pemilik mandat paling awal, sumber otoritas tertinggi, dan titik pusat dari seluruh legitimasi konstitusional.
Dalam ranah hukum tata negara, prinsip ini memiliki tiga dimensi penting. Pertama, hak rakyat untuk berdaulat (the people’s sovereign right), yang menempatkan rakyat sebagai entitas penguasa paling fundamental dalam struktur politik. Kedua, hak asal-usul (original right), yang mengacu pada fakta bahwa rakyat sudah memiliki kedaulatan bahkan sebelum negara, konstitusi, atau lembaga kekuasaan dibentuk. Ketiga, hak konstitutif (constitutive right), yang menandai bahwa eksistensi negara dan hukum hanya sah jika dibentuk melalui kehendak rakyat. Dengan tiga dimensi ini, adagium primus inter potestates bukanlah simbolisme kosong, melainkan fondasi ideologis yang menyangga demokrasi konstitusional secara substantif.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan jurang lebar antara prinsip dan praktik. Dalam konteks Indonesia pasca-Reformasi, meskipun rakyat secara formal diakui sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, praktik politik sering kali tidak mencerminkan penghormatan terhadap prinsip tersebut. Demokrasi cenderung direduksi menjadi ritual elektoral lima tahunan, sementara proses legislasi dan pengambilan keputusan strategis berlangsung di ruang-ruang tertutup, jauh dari partisipasi publik. Kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak—seperti alih kelola sumber daya alam, revisi undang-undang penting, hingga reformasi kelembagaan—kerap diambil secara sepihak, dengan minim transparansi dan akuntabilitas.
Ambil contoh revisi UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan UU KPK, yang disahkan dalam tempo cepat, tanpa proses deliberasi publik yang memadai. Mahkamah Konstitusi bahkan sempat menyatakan UU Cipta Kerja “inkonstitusional bersyarat”, sebuah sinyal jelas bahwa tata kelola legislasi kita tengah mengalami krisis keterwakilan. Ketika kebijakan tidak lahir dari kehendak rakyat, apalagi mengabaikan suara mereka, maka negara telah menjauh dari prinsip primus inter potestates dan mereduksi kedaulatan rakyat menjadi ilusi simbolik belaka.
Dalam sektor ekonomi, dominasi oligarki dalam pengelolaan sumber daya alam juga menjadi pengkhianatan terhadap semangat Pasal 33 UUD 1945. Liberalisasi sektor energi, pertambangan, dan pangan telah membuka ruang luas bagi penetrasi kepentingan korporasi besar—sering kali asing—yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam konteks ini, rakyat sebagai primus inter potestates justru menjadi pihak yang paling dirugikan, karena kehilangan kendali atas kekayaan kolektifnya dan tereksklusi dari proses pengambilan keputusan.
Jean-Jacques Rousseau dalam The Social Contract mengingatkan, “Sovereignty, being only the exercise of the general will, can never be alienated.” Kedaulatan, sebagai ekspresi kehendak umum, tidak dapat dipindahtangankan. Pesan ini menegaskan bahwa tidak ada otoritas legal, betapapun kuatnya, yang dapat melampaui kehendak rakyat. Bung Hatta pun menegaskan, “Indonesia tidak akan kuat jika rakyatnya tidak berdaulat dalam politik dan ekonomi.” Pernyataan ini bukan sekadar kutipan historis, melainkan pengingat yang terus relevan bahwa kekuatan negara hanya akan bermakna apabila rakyat sungguh-sungguh menguasai arah politik dan perekonomian nasional.
Menjaga primus inter potestates berarti menjaga jiwa demokrasi. Ia bukan hanya prinsip hukum, tetapi kompas etika yang memastikan negara tetap berpihak kepada rakyat, bukan kepada elite atau kekuatan pasar semata. Tanpa kesetiaan pada prinsip ini, republik hanya akan menjadi rangka institusional tanpa jiwa—hampa, kaku, dan mudah dibajak oleh kekuasaan otoriter yang dibungkus prosedur legalitas.
Dalam kerangka ini, pendidikan politik, literasi hukum, dan ruang partisipasi publik menjadi syarat mutlak bagi rakyat untuk mampu menjalankan haknya sebagai primus inter potestates. Rakyat yang sadar dan terorganisasi akan menjadi tembok penghalang terhadap ekspansi kekuasaan yang melampaui batas. Rakyat yang kritis tidak akan membiarkan demokrasi dikendalikan oleh kekuatan uang, politik dinasti, atau kooptasi hukum oleh kekuasaan.
Namun perjuangan ini tidak bisa berjalan satu arah. Negara pun harus menunjukkan keberpihakan nyata dalam menegakkan keadilan sosial sebagai bagian dari pemenuhan mandat rakyat. Sebab primus inter potestates tidak hanya soal partisipasi dalam pemilu, tetapi juga menyangkut siapa yang mengakses manfaat ekonomi, siapa yang mengontrol sumber daya, dan siapa yang menentukan arah kebijakan. Demokrasi sejati hanya mungkin terwujud jika semua elemen kekuasaan tunduk pada prinsip ini—bukan sekadar dalam retorika, tetapi dalam kebijakan dan tindakan nyata.
Pada akhirnya, Primus inter potestates bukan hanya adagium klasik, tetapi refleksi dari kontrak sosial modern yang menempatkan rakyat di atas segala struktur kekuasaan. Ia adalah penanda bahwa demokrasi tidak dapat berjalan tanpa rakyat yang sadar akan haknya, negara yang tunduk pada mandat rakyat, dan hukum yang berpihak pada keadilan. Sebagaimana Bung Karno pernah menegaskan, “Kedaulatan rakyat tidak boleh hanya menjadi kata-kata, tetapi harus menjadi kenyataan.” Maka menjaga dan memperjuangkan primus inter potestates adalah tugas bersama: rakyat, negara, dan seluruh institusi demokrasi—agar Republik Indonesia tidak hanya berdiri secara legal, tetapi juga hidup secara moral.
Primus inter Potestates: Cermin Demokrasi dari DPRD Sumatera Barat
Dalam lanskap demokrasi konstitusional, adagium Primus inter potestates—“yang pertama di antara segala kekuasaan”—menyimpan makna fundamental: rakyat adalah entitas tertinggi dalam struktur kekuasaan negara. Populus est suprema lex, kata para filsuf klasik, yang berarti bahwa hukum tertinggi dalam suatu negara demokratis bukanlah lembaga, aturan, atau jabatan, melainkan rakyat itu sendiri. Dalam bingkai inilah tindakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat yang menerima aspirasi massa demonstran dengan tenang dan terbuka patut dicermati, bukan sebagai peristiwa administratif, melainkan sebagai refleksi hidup dari semangat primus inter potestates itu sendiri.
Tidak seperti di banyak daerah lain yang diwarnai ketegangan bahkan kekerasan saat rakyat menyampaikan aspirasi, DPRD Sumatera Barat menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai konstitusional. Mereka membuka pintu, mendengar dengan seksama, dan bahkan menyetujui tuntutan yang diajukan massa aksi—dalam dokumen sederhana berwarna merah muda. Tindakan ini, meskipun tampak kecil, merepresentasikan bentuk konkret dari pengakuan terhadap kedaulatan rakyat sebagai lex fundamentalis dari sistem ketatanegaraan kita.
Sikap yang ditunjukkan para wakil rakyat di Ranah Minang itu bukan semata-mata bentuk keramahan politis, melainkan cerminan dari pemahaman mendalam bahwa kekuasaan yang mereka emban bukan berasal dari kekuatan koersif, melainkan dari mandat yang diberikan rakyat secara sah. DPR bukan pemilik kedaulatan; ia hanya trustee, wakil yang dititipi amanat. Maka, ketika rakyat datang membawa suara dan harapan, menerima mereka bukan pilihan moral, melainkan kewajiban konstitusional. Menolak mereka adalah bentuk pengingkaran terhadap sumber legitimasi kekuasaan itu sendiri.
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Kalimat ini bukan sekadar teks hukum, melainkan prinsip normatif tertinggi yang mendasari seluruh arsitektur kelembagaan republik ini. Dalam konteks inilah DPRD Sumatera Barat telah menunjukkan, meski dalam tindakan yang sederhana, bahwa mereka memahami posisi mereka dalam hierarki kekuasaan: bukan sebagai supremus auctoritas, tetapi sebagai servus populi—pelayan rakyat.
Namun demikian, demokrasi tidak berhenti pada penerimaan simbolik. Tantangan sesungguhnya justru terletak pada tindak lanjutnya: apakah aspirasi yang telah diterima itu akan diwujudkan dalam kebijakan konkret? Apakah tanda tangan pada dokumen berwarna merah muda itu akan diterjemahkan menjadi keberpihakan nyata dalam ruang sidang? Di sinilah letak ujian integritas wakil rakyat: konsistensi antara sikap di hadapan publik dan posisi dalam perumusan kebijakan.
Komparasi dengan sejumlah DPRD di daerah lain memperlihatkan kontras yang mencolok. Tidak sedikit wakil rakyat yang menolak menerima aspirasi demonstran, bahkan merespons dengan kekerasan simbolik maupun fisik. Di beberapa kota, aksi massa berujung pada bentrokan dan perusakan fasilitas negara—konsekuensi dari ketidakmampuan perwakilan rakyat memahami esensi popular sovereignty. Peristiwa-peristiwa itu menunjukkan bahwa krisis demokrasi sering kali bukan bersumber dari rakyat yang marah, melainkan dari elite politik yang lupa diri.
Dalam situasi sosial-politik yang semakin kompleks, aspirasi rakyat kini tidak lagi terbatas pada tuntutan lokal. Isu-isu seperti keadilan agraria, pemerataan pendidikan, dan pemberantasan korupsi adalah bagian dari panggilan kolektif untuk menegakkan keadilan sosial. Rakyat di pedesaan menuntut pengakuan atas tanah yang mereka garap turun-temurun; mahasiswa menuntut sistem pendidikan yang inklusif dan bebas komersialisasi; masyarakat luas menginginkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. Semua ini adalah ekspresi dari primus inter potestates, bahwa rakyat tidak lagi mau sekadar menjadi objek kebijakan, tetapi subjek yang aktif menentukan arah bangsa.
Jean-Jacques Rousseau, dalam The Social Contract, mengingatkan bahwa “sovereignty, being only the exercise of the general will, can never be alienated.” Kedaulatan tidak bisa dialihkan kepada siapa pun karena ia adalah ekspresi dari kehendak umum. Dalam terang pemikiran ini, menerima, mendengar, dan mewujudkan aspirasi rakyat bukanlah bentuk kebaikan hati lembaga politik, melainkan kewajiban struktural yang melekat pada keberadaan mereka.
DPRD Sumatera Barat telah memulai langkah yang patut diapresiasi. Tetapi langkah pertama ini harus diikuti dengan kerja konkret yang bisa diverifikasi publik. Tanda tangan pada selembar kertas tidak akan berarti tanpa tindakan nyata di ruang kebijakan. Aspirasi rakyat harus masuk ke meja perumusan peraturan daerah, menjadi prioritas dalam penganggaran, dan diwujudkan dalam kontrol terhadap eksekutif. Jika tidak, keramahan yang ditunjukkan di depan kamera hanya akan dikenang sebagai gestur politis tanpa makna substantif.
Tulisan ini ingin menegaskan bahwa primus inter potestates bukan semboyan kosong yang tergantung di dinding ruang sidang. Ia adalah prinsip yang hidup, yang harus membentuk cara wakil rakyat berpikir, bertindak, dan memutuskan. Rakyat adalah sumber suara, bukan sekadar pengisi kotak suara. Ketika wakil rakyat melupakan hal ini, maka demokrasi berubah menjadi sekadar mekanisme prosedural tanpa jiwa. Sebaliknya, ketika prinsip ini dihidupkan dalam laku dan kebijakan, maka republik ini akan menemukan kembali makna terdalamnya: sebagai negara yang sungguh-sungguh berakar pada rakyat.
Sebagaimana Bung Karno pernah berpesan, “Kedaulatan rakyat tidak boleh hanya menjadi kata-kata, tetapi harus menjadi kenyataan.” Maka sejarah tidak akan mencatat siapa yang pernah menjabat, melainkan siapa yang dengan tulus menjaga marwah kedaulatan rakyat. DPR hanyalah jalan; rakyatlah tujuan. DPR hanyalah suara yang dipinjamkan; rakyatlah sumber suara itu sendiri. Bila prinsip ini benar-benar ditegakkan, maka primus inter potestates akan menjadi napas hidup demokrasi Indonesia—bukan hanya dalam konstitusi, tetapi dalam praktik sehari-hari kenegaraan.
Primus inter Potestates: Refleksi Sikap DPRD Sumbar terhadap Aspirasi Rakyat
Dalam lanskap demokrasi modern, adagium Latin primus inter potestates—yang berarti “yang utama di antara kekuasaan”—mengandung makna konstitusional yang dalam. Ia menyiratkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara demokratis bukan berada pada lembaga legislatif, eksekutif, atau yudikatif, melainkan pada rakyat. Sebagai suprema lex, rakyat bukan hanya menjadi sumber legitimasi, tetapi juga tujuan akhir dari seluruh struktur kekuasaan negara. Dalam konteks ini, tindakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat yang bersikap terbuka terhadap aspirasi massa aksi merupakan refleksi konkret dari penghormatan terhadap prinsip primus inter potestates tersebut.
Ketika demonstran datang dengan membawa tuntutan keadilan sosial, DPRD Sumbar tidak menyambut mereka dengan pagar besi, barikade aparat, atau retorika dingin. Sebaliknya, mereka menunjukkan sikap humanis—mendengar secara langsung, menyimak dengan kepala dingin, merangkul tanpa prasangka, dan bahkan menandatangani komitmen yang diajukan oleh rakyat. Tindakan ini, yang secara kasat mata tampak sederhana, sesungguhnya mencerminkan tingkat kedewasaan politik dan pemahaman konstitusional yang tidak lazim ditemukan di banyak daerah lain. Di tengah kegaduhan nasional yang sering memperlihatkan antipati institusional terhadap demonstrasi, Sumatera Barat justru menjadi pengecualian yang patut dicatat dan diapresiasi.
Dalam sistem demokrasi representatif, jabatan anggota DPR bukanlah hak istimewa, tetapi mandat yang berasal dari kehendak rakyat. Ketika rakyat datang menyampaikan aspirasi, mereka tidak sedang mengemis kebijakan, melainkan menagih janji perwakilan. Dalam kerangka ini, penolakan atau sikap arogan terhadap aspirasi rakyat bukan hanya pelanggaran etika politik, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap prinsip dasar konstitusi. Primus inter potestates mengingatkan kita bahwa DPR bukanlah pemilik kekuasaan, melainkan perantara mandat rakyat. Maka, mendengar suara rakyat bukanlah kemurahan hati; itu adalah kewajiban konstitusional.
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Kedaulatan dalam hal ini bersifat inalienable—tidak dapat dialihkan secara permanen kepada lembaga atau individu mana pun. Rakyat tetap dan akan selalu menjadi pemilik sah republik ini. DPR, baik di tingkat pusat maupun daerah, hanyalah instrumen pelaksana yang menerima kekuasaan secara delegatif. Maka, ketika DPRD Sumatera Barat menanggapi demonstrasi dengan kepala dingin dan hati terbuka, mereka sesungguhnya sedang menghidupkan kembali semangat konstitusi yang kerap menjadi teks mati dalam praktik politik kita.
Namun demikian, demokrasi tidak cukup hanya dengan gestur simbolik. Penandatanganan dokumen aspirasi rakyat, betapapun ikhlasnya, tidak akan berarti jika tidak diikuti oleh tindakan nyata dalam legislasi, pengawasan, dan alokasi anggaran yang berpihak pada rakyat. Di sinilah letak tantangan terbesar bagi DPRD Sumbar: membuktikan bahwa sikap terbuka mereka bukan sekadar performatif atau respons sesaat terhadap tekanan publik, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang terhadap penguatan kedaulatan rakyat.
Apa yang terjadi di Sumatera Barat sepatutnya menjadi refleksi bagi banyak daerah lain yang gagal memahami fungsi representatifnya. Di sejumlah wilayah, demonstrasi berujung kericuhan, pengusiran paksa, hingga perusakan gedung DPRD. Situasi tersebut bukan semata karena massa yang anarkis, tetapi lebih sering dipicu oleh sikap defensif dan elitis dari wakil rakyat yang menutup diri terhadap kritik. Hal ini mencerminkan kegagalan struktural dalam membangun saluran partisipasi yang sehat dan dialogis. Padahal, dalam teori popular sovereignty, setiap ekspresi aspirasi rakyat merupakan bentuk koreksi terhadap kekuasaan yang sedang dijalankan.
Tentu, aspirasi rakyat tidak lahir dari ruang hampa. Tuntutan keadilan agraria, akses pendidikan yang inklusif, serta pemberantasan korupsi yang konsisten merupakan bagian dari agenda demokrasi substantif. Ketiga isu ini mewakili denyut nadi rakyat yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan yang lebih menguntungkan oligarki atau pasar. Ironisnya, banyak parlemen justru memproduksi kebijakan yang abai terhadap realitas ini—dari revisi Undang-Undang Minerba hingga pasal-pasal kontroversial dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Ketiadaan keberpihakan inilah yang membuat prinsip primus inter potestates kehilangan makna di banyak ruang kekuasaan.
Dalam titik inilah kita dapat melihat DPRD Sumatera Barat sebagai pengecualian yang layak dirayakan, sekaligus diuji. Tidak cukup hanya menerima aspirasi; mereka juga harus memastikan bahwa suara rakyat benar-benar memengaruhi arah kebijakan. Transparansi dalam proses legislasi, pembukaan ruang partisipasi yang lebih representatif, serta penguatan akuntabilitas politik menjadi prasyarat mutlak agar demokrasi kita tidak berhenti pada formalitas lima tahunan. Demokrasi prosedural, tanpa jiwa substantif, hanya akan melanggengkan kekuasaan elite yang terputus dari basis sosialnya.
Tulisan ini mengingatkan bahwa sejarah tidak menulis siapa yang duduk di kursi kekuasaan, melainkan siapa yang setia menjaga dan menghidupi kedaulatan rakyat. Dalam konteks itulah DPR hanyalah jalan, rakyatlah tujuan. DPR hanyalah suara yang dipinjamkan, rakyatlah sumber suara itu sendiri. Bila prinsip ini benar-benar dijalankan, demokrasi Indonesia akan semakin kuat, dan kedaulatan rakyat tidak lagi hanya menjadi teks dalam pembukaan konstitusi, tetapi menjadi napas hidup dalam setiap kebijakan dan keputusan politik.
Konsistensi terhadap prinsip primus inter potestates harus diwujudkan bukan hanya oleh DPRD Sumbar, tetapi oleh seluruh perwakilan rakyat di Indonesia. Ini bukan sekadar tuntutan moral, melainkan kewajiban hukum dan politik yang melekat dalam sistem demokrasi yang sehat. Kedaulatan rakyat harus diterjemahkan dalam pendidikan politik yang memampukan rakyat memahami hak-haknya, serta dalam lembaga-lembaga publik yang transparan, responsif, dan akuntabel.
Akhirnya, ketika kita berbicara tentang masa depan demokrasi Indonesia, kita berbicara tentang keberanian untuk mengakui bahwa kekuasaan tidak lahir dari kekuatan, tetapi dari kepercayaan. Dan kepercayaan itu hanya akan bertahan jika rakyat dihormati sebagai primus inter potestates—yang utama di antara kekuasaan. Karena tanpa rakyat yang berdaulat, negara kehilangan jiwanya; dan tanpa pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, demokrasi hanya akan menjadi topeng bagi tirani yang dilegalkan.
Penguatan dan Tantangan dalam Implementasi Kedaulatan Rakyat
Dalam doktrin konstitusional modern, frasa primus inter potestates—yang berarti “yang utama di antara segala kekuasaan”—merupakan penegasan filosofis bahwa rakyat adalah pemilik otoritas tertinggi dalam sistem demokrasi. Kedaulatan bukanlah hak turunan dari negara atau pemerintah, melainkan berasal langsung dari rakyat sebagai entitas politik yang mendahului berdirinya negara itu sendiri. Dalam konteks ini, lembaga perwakilan seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau DPRD pada hakikatnya hanyalah instrumen delegatif yang mendapat mandat untuk mewujudkan kehendak rakyat. Namun, pengakuan normatif terhadap kedaulatan rakyat ini belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik demokrasi Indonesia secara substansial.
Realitas politik dan birokrasi di Indonesia masih dibayangi oleh persoalan struktural yang kompleks. Kendala utama muncul dari dominasi kepentingan elit, praktik korupsi yang meluas, serta ketimpangan akses terhadap informasi dan partisipasi. Dalam banyak kasus, rakyat dihadapkan pada dinding kekuasaan yang tebal, yang membuat suara mereka tertahan atau bahkan tereduksi menjadi sekadar formalitas belaka. Dalam sistem seperti ini, relasi antara wakil dan yang diwakili menjadi timpang: DPR cenderung bergerak dalam logika kekuasaan yang tertutup, bukan dalam semangat representation of will sebagaimana yang dikehendaki dalam teori popular sovereignty.
Oleh karena itu, implementasi kedaulatan rakyat menuntut lebih dari sekadar gestur normatif. Ia memerlukan bangunan institusional yang mampu menjamin keberlanjutan respons terhadap aspirasi rakyat. Sikap terbuka dan humanis dari DPR, sebagaimana ditunjukkan oleh DPRD Sumatera Barat saat menerima dan menindaklanjuti aspirasi para demonstran, adalah langkah penting. Namun, sikap tersebut harus diikuti dengan penyusunan mekanisme internal yang sistematis: mulai dari dokumentasi aspirasi, penetapan tindak lanjut dalam agenda kelembagaan, hingga pembukaan ruang pertanggungjawaban secara periodik kepada publik.
Dalam kerangka tersebut, peran media dan masyarakat sipil menjadi sangat vital. Mereka bukan sekadar penonton dalam panggung demokrasi, melainkan aktor kunci yang menjaga ritme transparansi dan akuntabilitas kekuasaan. Media, dengan daya jangkau dan kapasitas kontrol sosialnya, dapat mencegah penyimpangan mandat dengan mengungkap celah-celah ketertutupan dan konflik kepentingan. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil memiliki peran strategis sebagai penghubung antara rakyat dengan lembaga formal negara—menyuarakan yang tak terdengar, membela yang tak terbela.
Namun, kontrol eksternal saja tidak cukup jika rakyat sebagai pemilik kedaulatan belum sepenuhnya sadar akan hak-haknya. Di sinilah urgensi pendidikan politik menjadi mutlak. Kesadaran politik yang rendah, ditambah dengan budaya patronase yang masih kuat, sering membuat rakyat terseret dalam logika transaksional dan loyalitas semu terhadap figur kekuasaan, bukan terhadap prinsip dan kebijakan. Pendidikan politik harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas rakyat sebagai subjek aktif dalam demokrasi: mampu menilai, memilih, dan mengoreksi. Bukan hanya di masa pemilu, tetapi dalam keseharian proses pengambilan keputusan publik.
Penting untuk dipahami bahwa demokrasi bukan sistem yang bekerja otomatis. Demokrasi adalah proses yang hidup, yang hanya dapat berlangsung jika seluruh elemen bangsa bersedia mengambil bagian secara kritis dan konstruktif. Dalam proses ini, DPR memiliki peran sentral—bukan hanya sebagai legislator, tetapi sebagai jembatan antara suara rakyat dan arah kebijakan negara. DPR harus bersikap rendah hati, mendengarkan dengan tulus, dan bertindak dengan keberanian moral. Mereka harus membuktikan bahwa kursi yang mereka duduki bukan sekadar jabatan politis, melainkan amanah konstitusional yang lahir dari kehendak rakyat.
Sikap DPRD Sumatera Barat yang menerima aspirasi rakyat dengan kepala dingin adalah cerminan dari harapan bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki ruang untuk tumbuh secara sehat. Namun, pembuktian sesungguhnya terletak pada keberlanjutan dari sikap itu: apakah diterjemahkan dalam kebijakan yang berpihak, atau berhenti sebagai pencitraan dalam suasana politis tertentu. Legitimasi kekuasaan tidak dibangun dari gestur simbolik, melainkan dari keberanian untuk berpihak kepada rakyat dalam setiap keputusan yang berdampak nyata.
Dalam jangka panjang, demokrasi tidak akan bertahan dari kekuatan simbol semata. Ia memerlukan fondasi moral yang kokoh dan sistem yang berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, tidak cukup jika hanya DPR atau pemerintah yang diseru untuk menjaga kedaulatan. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga dan menghidupkan semangat primus inter potestates dalam praktik sehari-hari. Menjaga demokrasi adalah menjaga agar kekuasaan tidak menjauh dari rakyat. Menjaga demokrasi adalah memastikan bahwa setiap kebijakan negara mengakar pada kebutuhan riil masyarakat, bukan pada kalkulasi elektoral atau kepentingan sempit elit politik.
Pada akhirnya, primus inter potestates bukanlah frasa yang berhenti di tataran konstitusional, melainkan prinsip hidup yang harus terus diperjuangkan. Ia adalah napas dari sistem demokrasi yang sejati: bahwa rakyat adalah pemilik negeri ini, dan setiap bentuk kekuasaan yang menjauhi rakyat hanyalah selubung kosong yang kehilangan legitimasi. Maka, refleksi ini bukan sekadar perenungan akademik, melainkan ajakan bagi kita semua—wakil rakyat, pemerintah, media, masyarakat sipil, dan individu warga negara—untuk menegakkan kembali prinsip kedaulatan rakyat sebagai fondasi bagi keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian dalam kehidupan berbangsa.
Penulis adalah Ketua Pengwil Sumut Ikatan Notaris Indonesia
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.