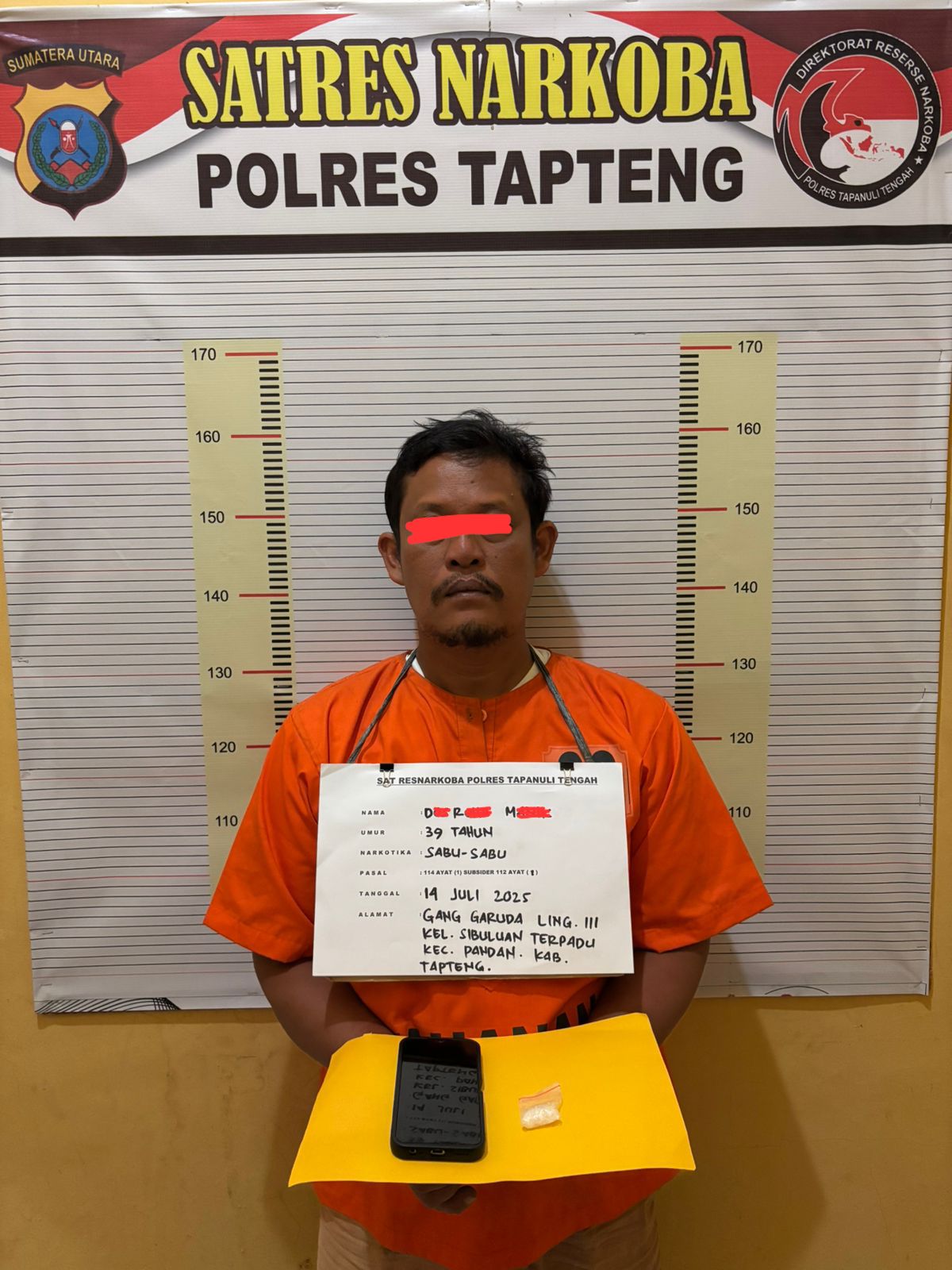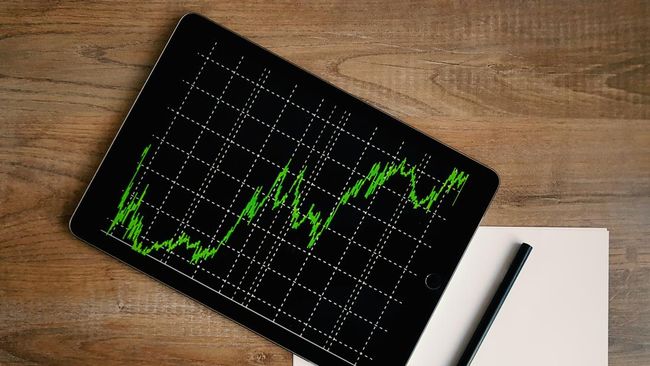Oleh Darwis Simbolon, S.Pd., M.Pd
Pada akhirnya, budaya dongkrak nilai yang masih banyak dipraktikkan oleh lembaga pendikan harus didobrak, dikikis dan dihanguskan. Masing-masing kita harus introspeksi diri dan berusaha memperbaiki diri tanpa perlu mencari-cari kambing hitam
Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN
Dalam konteks pendidikan kita di Indonesia hari ini, dimana praktik kecurangan sistematis seperti penggelembungan nilai atau yang lebih familiar disebut sebagai “budaya dongkrak nilai” telah menjadi fenomena yang tidak terbantahkan. Salah satu bentuk praktiknya yang sangat mencolok adalah ketika nilai asli seorang peserta didik yang sangat rendah bisa dinaikkan atau diganti sesuai kebutuhan dan pesanan.
Hal ini bertujuan untuk memenuhi “tuntutan zaman” berupa syarat administratif masuk sekolah favorit. Atau tuntutan lain untuk memenuhi ambang batas kelulusan dan gengsi demi mempertahankan citra suatu lembaga pendidikan. Fenomena yang sangat miris ini sebenarnya tidak semata berkaitan dengan perubahan angka di atas kertas, melainkan mengindikasikan adanya suatu borok persoalan serius dalam sistem pendidikan nasional, Secara khusus menyangkut krisis integritas dan moral yang sedang menjangkiti atau menggerogoti sendi-sendi pendidikan kita.
Praktik manipulasi untuk mendongkrak nilai siswa sejatinya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai dasar pendidikan, terutama nilai kejujuran dan objektivitas. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan bahwa tujuan utama pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
Dengan demikian, sistem pendidikan yang dilakoni sejatinya tidak hanya bertujuan untuk mencetak lulusan dengan nilai tertinggi. Apalah arti dari nilai-nilai tersebut jika ternyata siswa tidak memiliki kompetensi sesuai harapan. Maka hal ini sama saja dengan kebohongan yang dilakukan oleh insan pendidik. Hal ini sudah sangat jauh menyimpang dari filosofis dasar pendidikan kita yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter luhur para siswa. Maka, dapat dipastikan bahwa praktik dongkrak nilai secara tidak proporsional merupakan bentuk degradasi moral yang menjadi keprihatinan bersama.
Mungkin kita sering mendengar bahwa guru disebut atau dikenal dengan gelar mulianya sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa,” kedudukan guru atau pendidik berada pada posisi yang sangat strategis dalam sistem pendidikan. Namun, ketika seorang guru atau pendidik justru turut terlibat dalam praktik kotor berupa manipulasi nilai, maka kredibilitas atau kejujuran dari profesi tersebut sebenarnya sedang dipertaruhkan.
Alih-alih menjadi pembentuk integritas dan karakter generasi bangsa, guru atau pendidik justru sedang terjebak dan tejerat dalam perannya sebagai “pendukung sistem palsu” yang menjauhkan pendidikan dari esensinya yang sangat vital. Pada kasus semacam ini, yang gagal bukan hanya siswa dalam proses belajar, tetapi pemerintah sebagai mengambil kebijakan sekaligus para guru karena menjalankan fungsinya yang bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur pendidikan.
Namun demikian, praktik “kecurangan terstruktur” atau katakanlah kesalahan yang sistematis dan masif ini tidak sepenuhnya pada guru. Karena jika persoalan ini hanya di todongkan kepada para guru secara sepihak, tentu merupakan tuduhan yang sanga tidak adil. Justru dalam banyak kasus, masih banyak guru yang jujur dan idealis untuk melaksanakan amanat pendidikan. Namun, karena tuntutan dan kebijakan yang buruk, membuat guru harus tersudut dan menyerah dalam tekanan struktural yang bertentangan dengan hati nuraninya.
Stimulus buruk tersebut bisa datang dari kepala sekolah, desakan dari orang tua, hingga instruksi tidak langsung dari dinas pendidikan sehingga guru atau pendidik berada dalam posisi dilematis. Sebenarnya, banyak guru yang menjadi korban dalam sistem ini sehingga kerap terpaksa “memainkan angka” demi mempertahankan citra positif atau reputasi sekolah atau tujuan lain untuk menghindari sanksi administratif. Maka, membuat standar kelulusan yang seragam dengan nilai-nilai yang sangat memuaskan tanpa sesuai dengan kemampuan atau potensi peserta didik, sejatinya merupakan bentuk kecurangan dan pembodohan yang terus melanggengkan budaya dongkrak nilai.
Fenomena dongkrak nilai ini sebenarnya menjadi indikasi berupa terjadinya pergeseran fungsi sekolah yang seharusnya menjadi pembinaan karakter dan peningkatan kompetensi berubah menjadi “pabrik ijazah.” Karena ketika angka-angka di raport menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas siswa dalam pendidikan, maka substansi dari proses pembelajaran dan pembentukan nilai-nilai moral menjadi terabaikan. Walhasil, meritokrasi dalam pendidikan menjadi terganggu.
Siswa yang kurang disiplin, minim kemampuan akademik dan bakat, bahkan malas hingga melanggar pun sekalipun masih bisa “lulus” karena memang nilainya bisa direkayasa. Jangan pernah menganggap bahwa dampak dari praktik ini sederhana. Justru ini laksana bom waktu yang akan menciptakan generasi ilusi. Berupa lahirnya siswa atau generasi yang secara administratif terlihat kompeten, namun pada kenyataannya tidak memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai.
Sehingga mereka akan menjadi beban karena menghadapi kesulitan besar saat berhadapan dengan realitas di dunia kerja maupun jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Padahal dunia nyata tidak hanya menuntut ijazah, tetapi juga keterampilan, etika, dan kecakapan yang teruji. Bila ternyata pondasi akademik dan etika telah rapuh sejak di bangku sekolah, maka masa keruntuhan sistem sosial dan ekonomi bangsa ini hanya menunggu waktu.
Selanjutnya, budaya dongkrak nilai yang masif juga menjadi indikasi lemahnya atau tidak berfungsinya sistem pengawasan pendidikan. Mulai dari level kepala sekolah, pengawas dinas pendidikan, hingga kementerian pendidikan. Dan sering kali “oknum” tersebut malah terkesan tutup mata bahkan memihak secara tidak langsung. Salah satu contoh yang banyak terjadi adalah dukungan pada praktik manipulasi data dalam proses akreditasi suatu institusi pendidikan.
Semua ini karena adanya tuntutan berupa pengakuan dan pencitraan institusi. Maka yang terjadi kemudian adalah, prosedur evaluasi mutu suatu lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi mekanisme perbaikan, justru terjebak dalam rutinitas administratif dan formalitas belaka. Sehingga mau tidak mau, banyak elemen yang terseret dalam pusaran negatif tersebut. Salah satunya adalah integritas profesi guru atau pendidik yang harus dipertaruhkan dan tercoreng di mata publik.
Ketika masyarakat sudah mulai mencium “aroma busuk” ini, secara simultan mereka mulai meragukan kejujuran guru, otoritas moral dan pedagogisnya dalam mendidi. Karena itu, perlu adanya gebrakan nyata berupa gerakan pemulihan integritas guru secara sistemik dan berkelanjutan. Tentunya, pemulihan ini tidak bisa dilakukan sebatas diksusi, seremonial dan himbauan moral semata. Melainkan berproses melalui program kerja nyata untuk reformasi menyeluruh.
Maka tidak mungkin persoalan besar ini bisa diselesaikan dengan hanya menerbitkan surat edaran. Aplagi sebatas seminar-seminar yang justru menghabiskan banyak anggaran. Satu hal mendasar yang sangat dibutuhkan adalah kerjasama, perubahan paradigma dan kebijakan pendidikan.
Proses evaluasi pendidikan harus bersifat holistik, tidak hanya berorientasi pada nilai, melainkan memperhatikan pentingnya proses belajar yang menanamkan nilai kejujuran, penanaman karakter, dan perkembangan kompetensi siswa secara utuh. Guru juga harus diberi kebebasan “idealisme mendidik” atau semacam ruang untuk bersikap jujur, profesionalisme tanpa dibayang-bayangi rasa takut akan dimutasi, teguran, atau pengucilan individu karena bersikap jujur dan tegas kepada siswa.
Karena itulah, sekolah atau madrasah sebagai institusi pendidikan harus menata kembali budaya objektivitas dalam penilaian. Serta mengembalikan fokus atau misi utama pendidikan untuk mewujudkan siswa yang berkarakter dan kompeten menghadapi tantangan zaman. Selain itu, sistem reward and punishment bagi guru juga harus berlandaskan atau berdasarkan pada indikator integritas, bukan hanya capaian nilai akademik peserta didiknya. Maka di sinilah pentingnya kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk mendorong lahirnya ekosistem pendidikan yang sehat, jujur, dan berorientasi pada kualitas dan kapabilitas.
Pada akhirnya, budaya dongkrak nilai yang masih banyak dipraktikkan oleh lembaga pendikan harus didobrak, dikikis dan dihanguskan. Masing-masing kita harus introspeksi diri dan berusaha memperbaiki diri tanpa perlu mencari-cari kambing hitam dan menyudutkan pihak lain. Pada dasarnya, kita semua bertanggung jawab untuk mengoreksi, mengkritisi, dan mengambil peran langsung untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang masih bertumpu pada nilai akademik. Tentu, hal ini bukan perkara mudah seperti membalikkan tangan.
Mulailah dengan berani dan jujur mengakui kesalahan dan kelemahan sistem pendidikan hari ini. Dimana salah satu tantangan beratnya adalah krisis kejujuran dan integritas. Sekali lagi, pembahasan atau kritik ini tidak ada manfaatnya tanpa kita berusaha keras untuk berbenah dan menerapakan nilai kejujuran kolektif untuk revolusi pendidikan secara menyeluruh.
Penulis adalah Wakadiv Office Of International Affairs (OIA) Pesantren Darul Mursyid, Tapanuli Selatan.
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.