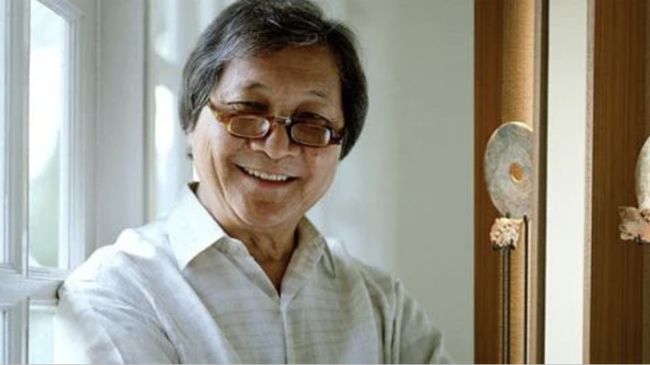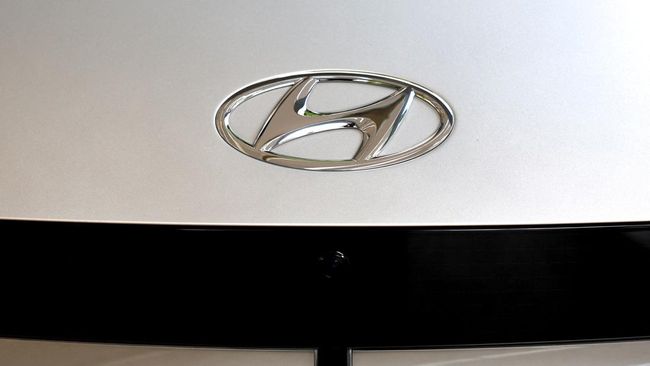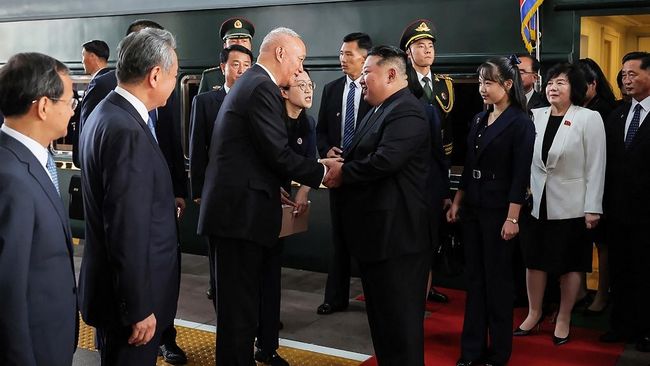Jakarta, CNBC Indonesia - Pertanian merupakan salah satu roda penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian memainkan peran penting dalam meningkatkan output nasional, mengurangi kemiskinan, dan menyerap tenaga kerja khususnya di wilayah perdesaan.
Hal ini tercermin dari publikasi Badan Pusat Statistik tentang perekonomian nasional pada triwulan III-2025. Dengan kontribusi mencapai 14,35%, sektor pertanian menjadi salah satu penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan.
Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 juga menunjukkan kontribusi sektor pertanian sebagai penyerap tenaga kerja terbesar.
Sektor pertanian mampu menyerap hingga 28,15% dari total tenaga kerja nasional. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja di sektor ini juga menjadi yang paling pesat, yakni mencapai 0,49 juta orang selama periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025.
Meski menjadi kunci penggerak perekonomian, tingkat kesejahteraan pekerja sektor pertanian justru mengkhawatirkan.
Rata-rata upah pekerja tani hanya sekitar Rp2,54 juta per bulan, lebih rendah dari rata-rata upah buruh keseluruhan yang berada di kisaran Rp3,33 juta. Tingkat upah ini bahkan menjadi yang paling rendah kedua dari seluruh sektor usaha. Dengan kata lain, pekerja tani menjadi salah satu yang kesejahteraannya paling rendah diantara seluruh kelas pekerja.
Belum lagi fakta bahwa lapangan kerja di sektor pertanian didominasi oleh pekerjaan informal. Data BPS menunjukkan tenaga kerja informal sektor pertanian mencapai 87,31% pada 2024.
Pekerja di sektor informal ini lebih rentan karena tidak memiliki jaminan sosial maupun perlindungan hukum. Sektor informal juga tidak wajib memenuhi upah minimum yang ditetapkan pemerintah, sehingga upah yang diterima seringkali lebih rendah.
Di Amerika Serikat, beberapa usaha tani tidak wajib membayar upah minimum, misalnya usaha tani kecil dengan intensitas kerja kurang dari 500 hari per tahun.
Beberapa pekerja tani juga tidak terlindungi oleh ketentuan upah minimum, seperti pekerja yang berasal dari anggota keluarga, pekerja yang terlibat dalam produksi ternak, buruh panen tangan lokal yang dibayar berdasarkan produktivitas (upah borongan), dan anak di bawah umur 16 tahun non-lokal yang bekerja dengan upah borongan bersama orang tuanya.
Penerapan kebijakan upah minimum di sektor pertanian juga terbatas, terutama pada kasus pekerja imigran ilegal. Pekerja yang tidak terlindungi kebijakan upah minimum ini juga relatif lebih sulit mendapat kenaikan upah.
Sektor pertanian seringkali dimodelkan dalam kerangka teori "dual labor market", dimana pasar tenaga kerja dikategorikan menjadi pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer ditandai dengan pekerjaan yang stabil, upah tinggi, serta memiliki kondisi kerja dan keamanan kerja yang baik.
Sementara pasar sekunder terdiri dari pekerjaan yang tidak stabil, upah rendah, serta memiliki kondisi kerja yang buruk dan keamanan yang tidak terjamin.
Jika merujuk pada teori tersebut, upah yang rendah pada sektor pertanian seharusnya mendorong perpindahan tenaga kerja ke sektor yang menawarkan upah lebih tinggi.
Data BPS menunjukkan share tenaga kerja sektor pertanian terhadap total tenaga kerja cenderung menurun dalam lima tahun terakhir, kecuali pada 2021 yang meningkat 0,28% dari 2020.
Kondisi ini membuktikan bahwa teori dual labor market terjadi pada sektor pertanian nasional. Rendahnya upah pada sektor pertanian memicu terjadinya "migrasi" pekerja ke sektor dengan upah lebih tinggi.
Umumnya pekerja dari sektor pertanian berpindah ke sektor industri maupun jasa. Ditambah dengan pandangan bahwa pekerjaan tani dianggap "keras", berisiko tinggi, dan tidak bergengsi. Ini yang semakin membuat masyarakat, terutama anak muda, meninggalkan pertanian dan mencari pekerjaan lain yang dianggap lebih menjanjikan.
Migrasi pekerja sektor pertanian ke sektor lain berpotensi menimbulkan transformasi pada berbagai hal. Kekurangan tenaga kerja dapat berimplikasi pada penurunan produktivitas, terutama pada subsektor yang padat karya seperti tanaman pangan dan hortikultura.
Apalagi subsektor yang padat karya tersebut biasanya lebih sensitif terhadap perbedaan tingkat upah. Belum lagi jika pekerja yang bermigrasi adalah pekerja muda, sehingga yang tersisa tinggal pekerja yang berusia lebih tua dan kurang produktif. Penurunan produksi ini kemudian juga berdampak pada kenaikan harga komoditas pangan. Dalam jangka panjang, penurunan produktivitas pertanian dapat mengancam ketahanan pangan dan meningkatkan ketergantungan terhadap impor pangan.
Masalah yang lebih besar bisa muncul jika migrasi sektoral ini tidak diimbangi dengan industrialisasi yang kuat. Jika sektor industri atau jasa belum mampu menyerap tenaga kerja baru secara optimal, perpindahan pekerja malah menciptakan pengangguran dan kemiskinan.
Untuk menekan laju migrasi pekerja pertanian besar-besaran, pemberian upah yang layak menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan. Perlu adanya upaya pengembangan kebijakan remunerasi yang efektif dan adil. Selain meningkatkan kesejahteraan pekerja tani, kenaikan upah juga dapat mendorong investasi yang lebih tinggi, sehingga dapat memperkuat kinerja pertanian nasional.
CNBC INDONESIA RESEARCH
[email protected]

 1 month ago
21
1 month ago
21