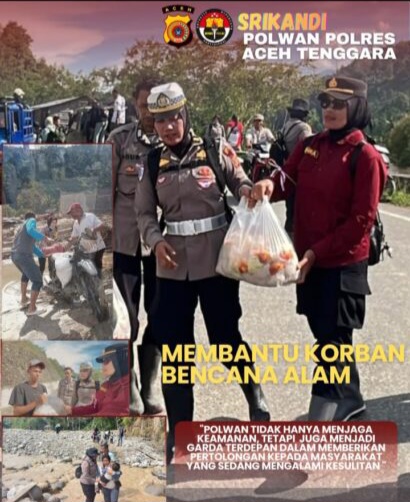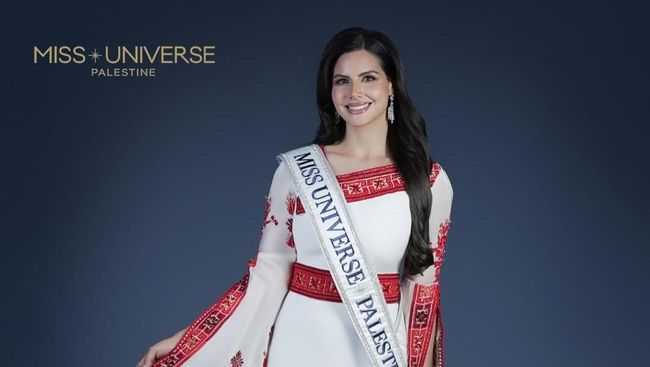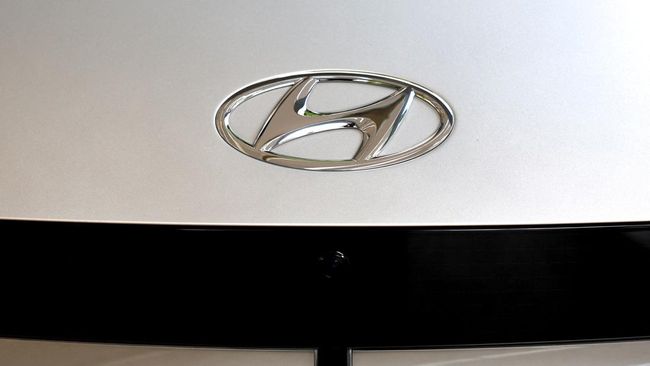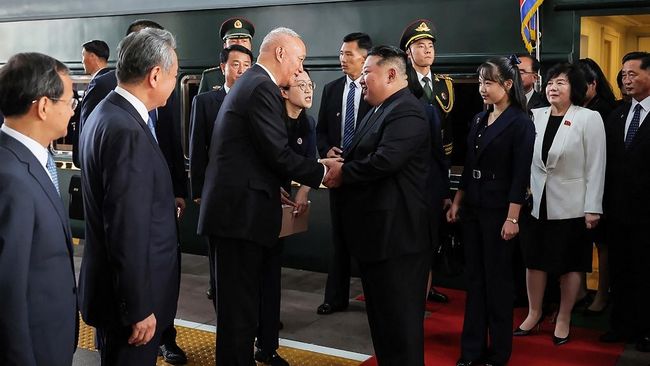Oleh Suwardi Lubis
Dalam era post-truth, batas antara fakta dan fiksi menjadi kabur. Banyak pelaku komunikasi, baik individu, lembaga media, maupun politisi terjebak pada strategi komunikasi manipulatif…
Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN
DI era digital saat ini, informasi menyebar dengan kecepatan cahaya, tetapi tidak selalu dengan kebenaran yang menyertainya. Kita memasuki era yang disebut sebagai post-truth, di mana emosi dan opini pribadi lebih dominan memengaruhi pandangan publik dibandingkan fakta objektif.
Fenomena ini membawa tantangan besar terhadap etika komunikasi, terutama dalam ruang-ruang publik seperti media massa, media sosial, politik, dan pendidikan. Pertanyaannya, bagaimana menjaga nilai-nilai etis dalam komunikasi ketika kebenaran tak lagi menjadi pusat wacana?
Apa Itu Era Post-Truth?
Istilah post-truth pertama kali menjadi perhatian global ketika Oxford Dictionaries menetapkannya sebagai “Word of the Year” pada 2016. Secara harfiah, post-truth merujuk pada situasi di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Dalam konteks ini, narasi yang menyentuh perasaan lebih mudah diterima publik meskipun belum tentu benar.
Merujuk pada Oxford Dictionaries, post-truth didefinisikan sebagai, “relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief (Dictionaries, 2016). Definisi ini menggarisbawahi lebih pentingnya emosi dan keyakinan personal daripada fakta objektif dalam membangun opini publik. Sementara The Cambridge Dictionary mendefinisikan era post-truth sebagai situasi di mana orang menjadi lebih menerima argumentasi berbasis emosi dan keyakinan daripada argumen yang berbasis fakta. (Bradford Vivian, 2018).
Era post-truth ditandai dengan meluasnya penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kemudahan dalam menyebarkan informasi, rendahnya literasi digital masyarakat, dan meningkatnya polarisasi sosial (Tandoc et, 2018).
Media sosial dan algoritma digital memperparah situasi ini. Informasi yang viral bukanlah yang paling benar, tetapi yang paling menarik perhatian. Di sinilah letak masalah etika komunikasi, ketika kejujuran dan akurasi informasi dikorbankan demi popularitas dan keterlibatan (engagement).
Peran Etika Komunikasi
Etika komunikasi adalah prinsip moral yang mengarahkan individu atau institusi dalam menyampaikan informasi secara bertanggungjawab, jujur, dan adil. Dalam teori komunikasi, etika bertugas menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai seperti kebenaran, kejujuran, keadilan, dan rasa hormat menjadi pilar utama.
Namun, dalam era post-truth, batas antara fakta dan fiksi menjadi kabur. Banyak pelaku komunikasi, baik individu, lembaga media, maupun politisi terjebak pada strategi komunikasi manipulatif demi kepentingan tertentu. Ketika informasi disusun bukan untuk mencerdaskan, tetapi untuk memengaruhi dan memanipulasi, maka etika menjadi korban.
Etika berkomunikasi erat kaitannya dengan penggunaan bahasa yang santun, tidak menjurus dan membangkitkan emosi negatif, menghindari SARA, berhati-hati menyebarkan foto yang tidak umum (Rachman, 2020); tidak membully, mengatakan sesuatu dengan baik, membaca kembali apa yang ditulis, menyapa seseorang, dan mengecek pesan sebelum dikirim (Mutiah, 2019). Pranowo menambahkan bahwa untuk berbicara santun, perlu memperhatikan, antara lain kesadaran penutur dalam menjaga perasaan petutur, menjaga tuturan agar dapat diterima petutur, menjaga tuturan agar memperlihatkan posisi petutur berada lebih tinggi daripada penutur, apa yang dikatakanpetutur turut dirasakan penutur (Pranowo, 2012).
Tantangan Utama
Disinformasi dan Hoaks. Salah satu tantangan terbesar adalah banjirnya disinformasi dan hoaks di ruang digital. Banyak individu menyebarkan informasi tanpa memverifikasi kebenarannya terlebih dahulu. Lebih parah, ada pula aktor-aktor yang secara sengaja memproduksi informasi palsu demi kepentingan politik, ekonomi, atau ideologis.
Disinformasi bukan hanya ancaman terhadap kebenaran, tetapi juga terhadap etika komunikasi. Komunikator yang etis seharusnya tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan. Namun, di era post-truth, informasi palsu justru sering menjadi senjata efektif untuk memengaruhi persepsi publik.
Polarisasi. Media sosial menciptakan ruang yang memperkuat pandangan searah. Melalui algoritma, pengguna cenderung hanya terpapar informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka. Akibatnya, dialog terbuka tergantikan oleh monolog kelompok yang tertutup.
Polarisasi ini membuat diskusi publik tidak lagi dilandasi oleh pertukaran argumen yang rasional, melainkan oleh sentimen dan prasangka. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi yang etis menjadi sulit diwujudkan karena ruang dialog yang sehat tergantikan oleh saling serang dan labelisasi.
Komodifikasi Informasi. Informasi di era digital sering kali diperlakukan sebagai komoditas. Tujuan utamanya bukan lagi edukasi atau pencerdasan publik, tetapi klik, tayangan, dan keuntungan iklan. Media, termasuk yang arus utama, tidak luput dari godaan ini. Judul-judul bombastis (clickbait), penyederhanaan narasi, bahkan distorsi fakta kerap dilakukan demi menjaring audiens.
Ini menjadi tantangan besar bagi jurnalis dan institusi media dalam menjaga integritas profesi. Ketika etika dikalahkan oleh keuntungan ekonomi, maka publik akan terus disuguhi informasi yang sensasional, bukan substansial.
Keteladanan Figur Publik. Figur publik seperti politisi, selebritas, dan influencer memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Namun, tidak semua dari mereka memegang teguh prinsip komunikasi yang etis. Banyak yang dengan sengaja menyebarkan narasi yang membingungkan, ambigu, atau bahkan bohong demi citra diri atau kepentingan pribadi.
Ketika figur publik tidak memberi contoh komunikasi yang bertanggung jawab, masyarakat akan menormalisasi praktik komunikasi yang menyesatkan. Akibatnya, nilai-nilai etika semakin terpinggirkan.
Memulihkan Etika Komunikasi
Di tengah tantangan yang kompleks ini, apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan etika dalam praktik komunikasi?
Literasi Media dan Informasi. Pendidikan literasi media menjadi krusial. Masyarakat perlu dilatih untuk berpikir kritis, mengevaluasi sumber informasi, dan membedakan antara opini dan fakta. Sekolah, kampus, dan lembaga masyarakat memiliki peran penting dalam menanamkan kemampuan ini sejak dini.
Literasi informasi tidak hanya membantu masyarakat menghindari jebakan hoaks, tetapi juga membentuk budaya komunikasi yang sehat, terbuka, dan bertanggungjawab.
Penguatan Etika Profesi. Profesi komunikasi seperti jurnalis, public relations, atau content creator perlu terus memperkuat kode etiknya. Institusi media harus mengedepankan nilai-nilai objektivitas, akurasi, dan keberimbangan. Dewan Pers dan organisasi profesi lainnya mesti lebih aktif menegakkan standar etika dan memberikan sanksi pada pelanggar. Tanpa komitmen kolektif dari para pelaku komunikasi, etika akan terus menjadi jargon tanpa implementasi nyata.
Regulasi Digital yang Bijak. Pemerintah juga memiliki peran penting melalui regulasi yang adil dan transparan. Platform digital seperti Facebook, X (Twitter), dan YouTube harus didorong untuk bertanggung jawab atas penyebaran konten palsu. Namun regulasi tidak boleh digunakan sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi.
Regulasi yang etis adalah yang mampu menyeimbangkan antara kebebasan informasi dan perlindungan publik dari dampak destruktif disinformasi.
Keteladanan dan Komunikasi Empatik. Etika komunikasi tidak hanya soal kebenaran, tapi juga soal empati. Masyarakat, terutama figur publik, perlu membangun kebiasaan komunikasi yang tidak hanya benar secara data, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain. Komunikasi yang empatik menghindari ujaran kebencian, tidak merendahkan, dan mendorong dialog, bukan konflik.
Penutup
Era post-truth memang menjadi tantangan besar bagi dunia komunikasi. Di tengah banjir informasi yang tidak selalu benar, nilai-nilai etika sering kali terpinggirkan. Namun, justru dalam situasi seperti inilah prinsip etika komunikasi harus ditegakkan lebih kuat dari sebelumnya.
Kebenaran mungkin tidak selalu populer, tetapi tetap harus diperjuangkan. Etika dalam komunikasi bukan sekadar norma akademis, melainkan fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil, cerdas, dan beradab.
Karena itu, setiap individu, institusi, dan negara harus bersama-sama memelihara ekosistem komunikasi yang sehat, yang mengutamakan kebenaran, menghormati perbedaan, dan bertanggung jawab terhadap dampak dari setiap kata yang disampaikan.
Penulis adalah Guru Besar Universitas Sumatera Utara (USU).
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.