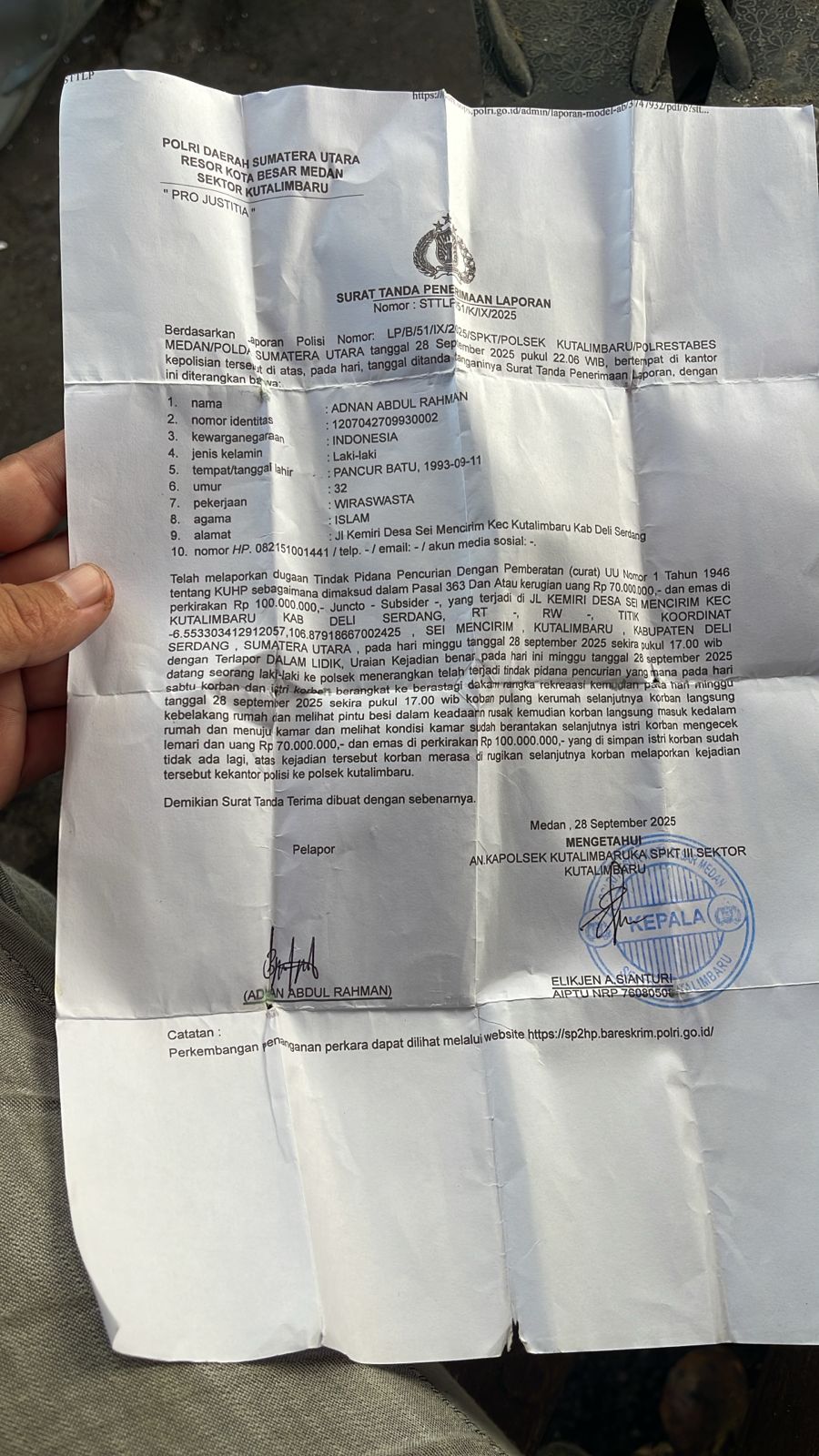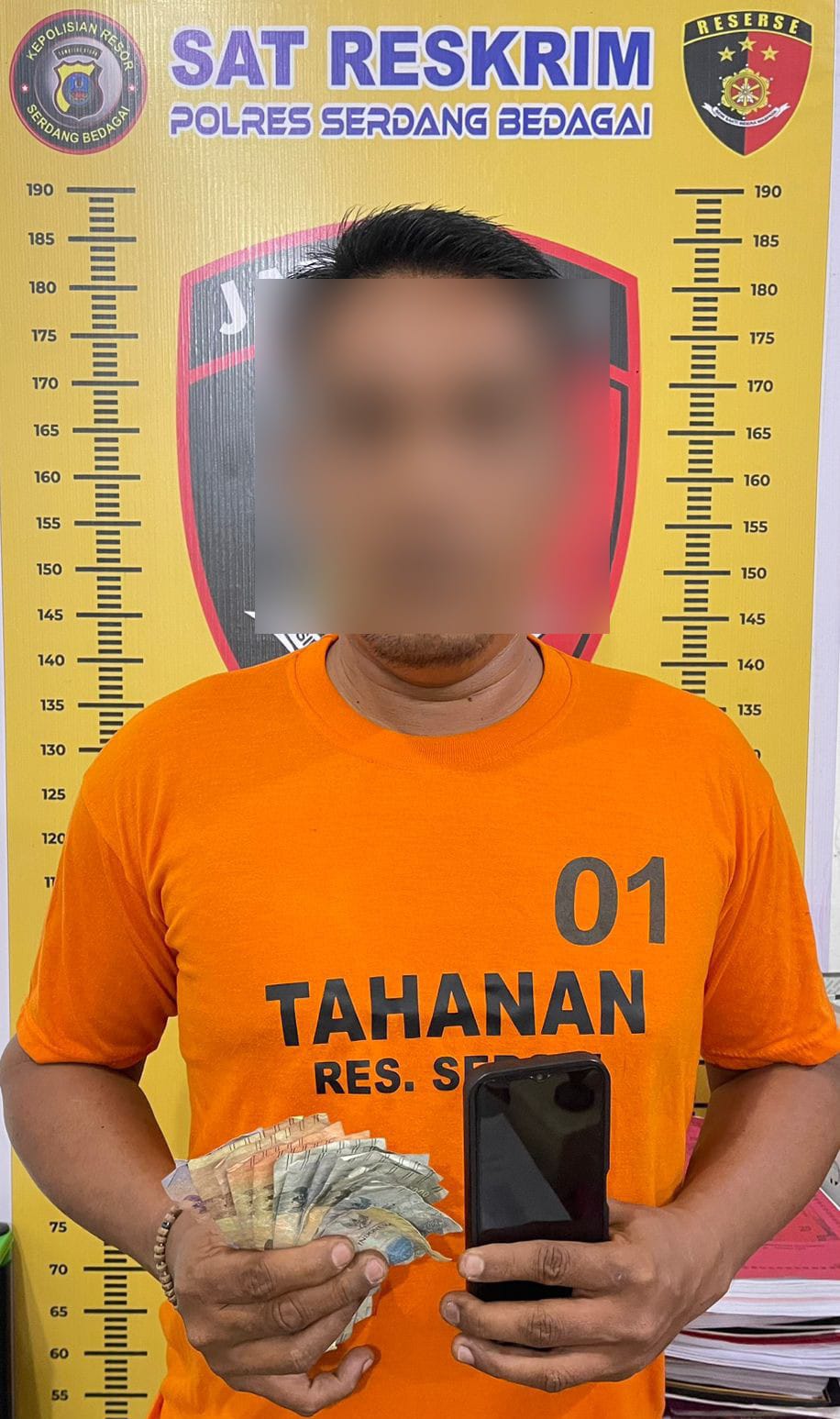Oleh: Farid Wajdi
Banjir besar di Sumatera kembali membuka tabir lama: warga bergerak lebih cepat dibanding negara. Relawan turun ke jalan-jalan penuh lumpur sebelum sirene birokrasi dibunyikan.
Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN
Donasi publik mengalir melalui kanal swadaya, dari komunitas kecil hingga organisasi besar, dari gerakan kerelawanan seperti Lazismu hingga komunitas Railfans Indonesia yang berhimpun menggalang dana tanpa menunggu komando.
Energi solidaritas ini tumbuh bukan sebagai pelengkap kebijakan negara; justru mengisi kekosongan yang seharusnya tidak pernah muncul.
Pakar kebencanaan UGM, Budi Santosa (2023), menegaskan kesenjangan antara kapasitas rakyat dan dinamika pemerintah daerah sering muncul pada fase awal bencana.
Menurutnya, kecepatan respons publik mencerminkan sensitivitas yang organik, sedangkan aparatur terjebak pada ekosistem administratif yang mengutamakan prosedur ketimbang urgensi kemanusiaan.
Penilaian tersebut terasa relevan melihat bagaimana rakyat justru lebih dahulu membangun dapur umum, pos logistik, dan evakuasi mandiri.
Fenomena ini sejalan dengan kajian CHUB Fisipol UGM (2020) yang menyebut altruisme publik bekerja melalui jejaring kepercayaan horizontal. Rakyat bergerak karena nurani kolektif, bukan mandat institusional.
Pemerintah memiliki perangkat, anggaran, kewenangan, dan aparat; publik hanya bersenjata kepedulian. Namun dalam kejadian ini, yang bersenjata nurani justru lebih tangkas menyelamatkan sesama.
Gelombang bantuan dari warga memperlihatkan paradoks besar: negara seolah punya sumber daya, publik memiliki kecepatan. Negara memiliki kewenangan, publik memiliki ketulusan. Kegagapan negara semakin terasa saat laporan lapangan menggambarkan korban yang menunggu berhari-hari tanpa bantuan dasar.
Air bersih minim, tenda terbatas, dan distribusi logistik sering macet pada rantai birokrasi. Kondisi ini diperburuk isu “panggung politik” yang mencoreng berbagai kunjungan pejabat, sebagaimana dikritik analis politik Tempo (2025) yang menilai kehadiran pejabat di lokasi bencana lebih sering tampil seremonial ketimbang operasional.
Narasi ini mendapatkan resonansi dalam analisis Magdalene (2025) yang menyorot performativitas elit ketika kamera hadir di lokasi. Banyak pejabat turun hanya untuk memberi citra tanggap, tetapi langkah institusional yang mestinya menyusul justru gagal menunjukkan konsistensi.
Publik menyaksikan betapa jarak antara simbol dan layanan nyata semakin lebar.
Antropolog bencana, Irwan Abdullah (2024), pernah mengingatkan risiko terbesar dalam tata kelola bencana: negara kehilangan “rasa hadir” karena terlalu terpaku pada mekanisme formal.
Peran negara dalam kondisi kritis seharusnya bekerja seperti responden awal, bukan administrator laporan. Ketika pemulihan masih memerlukan legalitas, para korban hanya bisa menunggu di ruang hampa kebijakan.
Di lapangan, rakyat tidak menunggu waktu. Mereka memikul karung beras, menembus banjir setinggi pinggang, menyalurkan bantuan dari rumah ke rumah, bahkan menarik perahu karet swadaya demi menjangkau lansia dan anak-anak. Kata “menunggu” tidak pernah cocok dimasukkan dalam kamus solidaritas warga.
Paradoks semakin mencolok ketika berbagai organisasi sosial, komunitas hobi, dan kelompok informal justru menyusun sistem distribusi yang lebih presisi. Railfans Indonesia misalnya, mengorganisir donasi dalam hitungan jam.
Mereka mengidentifikasi titik kritis di Sumatera Barat, mengeksekusi distribusi melalui relawan lokal, dan memastikan transparansi menggunakan sistem laporan digital. Efektivitas ini menunjukkan kemampuan publik membaca kebutuhan secara langsung tanpa piramida komando berlapis.
Pakar kebijakan publik, Agus Pambagio (2022), berkali-kali mengingatkan birokrasi Indonesia bekerja lambat akibat kultur administrasi yang lebih mengutamakan hierarki daripada aksi.
Situasi bencana membutuhkan keputusan cepat, bukan mata rantai persetujuan. Ketika keputusan lamban, nyawa terancam. Ketika laporan lebih penting daripada logistik, rakyat bergerak sendiri.
Isu pembiaran semakin terasa ketika beberapa daerah mengeluhkan lambatnya distribusi bantuan pemerintah pusat. Warga di banyak titik banjir melaporkan minimnya tenda, makanan siap saji, hingga selimut anak.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: mengapa negara dengan perangkat lengkap tetap tidak bergerak setangkas warga yang tidak punya fasilitas? Pengamat bencana dari Unair, Ali Rohman (2025), menyebut ketidaksiapan ini sebagai “defisit manajemen lapangan”, sebuah kondisi ketika perencanaan tidak berjumpa dengan eksekusi.
Ruang publik menjadi saksi bagaimana negara kehilangan kecepatan, namun publik mengisi celah itu tanpa keluh. Negara memiliki struktur, publik memiliki empati. Ketika negara sibuk menghitung inventaris, publik menghitung detik untuk menyelamatkan hidup.
Di sinilah frasa “rakyat bantu rakyat” menemukan makna paling kuat. Bukan karena publik menyingkirkan negara, melainkan karena publik tidak rela melihat penderitaan berlarut.
Kritik paling menohok terletak pada pertanyaan mendasar: mengapa publik harus bergerak sebagai garda terdepan dalam bencana berskala besar? Pemerintah telah memiliki BNPB, BPBD, alokasi anggaran kontinjensi, dan berbagai instrumen mitigasi. Namun fakta di lapangan menunjukkan seakan seluruh perangkat itu baru hidup setelah tekanan publik menguat.
Solidaritas warga layak diapresiasi setinggi-tingginya. Para dermawan anonim, relawan yang bekerja dalam senyap, donatur kecil yang menyisihkan pendapatan harian, serta komunitas-komunitas yang tidak mencari panggung adalah pilar moral bangsa.
Mereka tidak menunggu kamera, tidak menunggu sambutan pejabat, tidak menunggu undangan konferensi pers. Mereka hanya hadir, menolong, dan kembali ke rutinitas tanpa tepuk tangan.
Rakyat menyalakan cahaya ketika negara redup. Cahaya itu tidak boleh padam. Namun negara wajib menyalakan kembali fungsi utamanya: melindungi warga tanpa jeda, tanpa kalkulasi keliru, tanpa prosedur yang mematikan keputusan.
Solidaritas warga telah menjadi cahaya yang menembus gelap. Kini tiba saatnya negara menyalakan lampu besar yang selama ini padam. Rakyat telah melakukan bagiannya. Kini giliran negara bekerja, bukan bicara!
Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU.
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.