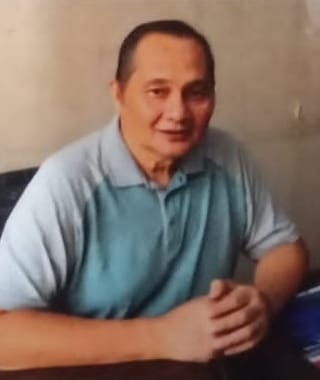Oleh Shohibul Anshor Siregar
Secara keseluruhan, sumber-sumber sejarah Batak bikinan Eropa ini, meskipun menyediakan data berharga bagi orang yang cukup kritis, memerlukan pembacaan yang lebih waspada untuk mengungkap bagaimana bias-bias Eropa, kolonial, dan agama…
Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN
Figur Singa Mangaraja, seorang pemimpin yang sangat dihormati di Tanah Batak, telah menjadi subjek berbagai tulisan, terutama dari perspektif Eropa selama periode kolonial. Analisis literatur bersifat umum yang penulis lakukan mengungkapkan bahaya bias ini, baik bias Eropa, bias kolonial, dan bias agama, sangat signifikan membentuk, dan tak jarang mendistorsi pemahaman tentang asal-usul, peran, dan makna gelar “Singa” dalam konteks budaya dan sejarah Batak.
Dampak ketidakjelasan sejarah pembentukan (konstruk) Singa Mangaraja dan asal-usul gelarnya sendiri telah membuka ruang bagi berbagai interpretasi dari luar, yang sering kali selaras dengan agenda dan pandangan dunia para penulisnya. Kesesatan dalam membaca dan mempersiapkan masa depan bangsa-bangsa bekas jajahan di seluruh dunia hingga abad 21 ini, umumnya berawal dari kesulitan mereka melakukan dekolonisasi.
Di Simalungun, misalnya, banyak orang tak sanggup memilih bangga atau tersinggung ketika seorang ksatria (Tuan Rondahaim Saragih Garingging gelar Raja Raya Namabajan, 1828-1891), dijuluki oleh Belanda sebagai Napoleon der Bataks. Siapa Garingging, siapa Napoleon dan apa konteks perjuangan keduanya menjadi pokok persoalan.
Bias Eropa
Pandangan Eropa terhadap Singa Mangaraja umumnya berakar pada upaya untuk memahami dan mengkategorikan budaya yang “eksotis” melalui lensa mereka sendiri. Sumber-sumber awal Eropa, seperti Nicola di Conti (1395–1469), João de Barros (1496–1570), Jacques de Beaulieu / Augustin de Beaulieu (1589–1637), Odoardo Barbosa (aktif awal abad ke-16), William Marsden (1754–1836), Franz Wilhelm Junghuhn (1809–1864) dan lain-lain, sering kali menyoroti praktik-praktik yang mereka anggap unik, seperti kanibalisme dan tato pada masyarakat Batak. Fokus pada aspek-aspek ini, dengan cara melebih-lebihkan dan dramatisasi, menunjukkan pandangan yang berorientasi pada perbedaan dan “keanehan”, bahkan dengan tujuan penegasan hegemoni, berbanding dengan norma-norma Eropa yang mereka paksakan sebagai ukuran universal.
Interpretasi mengenai makna gelar “Singa” sendiri mencerminkan bias ini. Salah satu penafsiran yang umum di kalangan Eropa adalah bahwa “Singa” secara harfiah berarti “singa” (hewan), yang digunakan untuk menunjukkan bahwa Singa Mangaraja adalah raja yang paling berkuasa di antara raja-raja Batak.
“Aangaande de beteekenis van den naam Si Singa Mangaradja, die kan men wellicht in verband brengen met het woord „Singa” of leeuw, om daarmee aan te duiden, dat Si Singa Mangaradja de machtigste koning der Bataksche koningen was geweest.” (“Mengenai arti nama Si Singa Mangaradja, itu mungkin dapat dikaitkan dengan kata ‘Singa’ atau singa, untuk menunjukkan bahwa Si Singa Mangaradja adalah raja terkuat di antara raja-raja Batak”).
Interpretasi lain menyebut “Singa” sebagai “perancang rencana” (ontwerper van plannen), yang mengindikasikan bahwa Singa Mangaraja adalah perancang tata pemerintahan. “Een andere beteekenis van „Singa” is echter het ontwerpen van plannen, zoodat daarmee Si Singa Mangaradja als de ontwerper der bestuursinrichting werd aangeduid.” (“Namun, arti lain dari ‘Singa’ adalah ‘perancang rencana’, sehingga Si Singa Mangaradja disebut sebagai perancang tata pemerintahan”).
Meskipun kedua interpretasi ini dicatat, framing-nya cenderung bersifat rasionalistik dan fungsional, hanya berusaha untuk tujuan memahami gelar tersebut dalam kerangka kekuasaan dan administrasi Barat yang sedang berusaha menjajah. Penekanan pada karya-karya filolog Eropa seperti Dr. H.N. van der Tuuk dalam membuat bahasa Toba-Batak “dapat diakses” (toegankelijk gemaakt) bagi dunia ilmiah juga mencerminkan pandangan bahwa pengetahuan Eropa adalah kunci untuk memahami dunia non-Eropa.
Kritik terhadap historiografi lokal juga muncul, dengan klaim bahwa “seseorang harus memiliki pemahaman yang sangat naif tentang ‘sejarah’ jika ia memberikan makna historis pada data yang, setelah pengumpulan yang cermat selama belasan tahun, disajikan kepada kita!”. Pandangan ini merendahkan validitas narasi lisan atau sumber lokal hanya karena tidak memenuhi standar metodologi sejarah Barat.
Bias Kolonial
Bias kolonial sangat kentara dalam narasi seputar Singa Mangaraja, yang seringkali digambarkan dalam konteks penaklukan dan pembentukan otoritas Belanda. Klaim kematian Singa Mangaraja pada 17 Juni 1907 di Pakpak secara eksplisit digambarkan sebagai momen keterbukaan pintu gerbang besar “pemerintahan kami [Belanda] didirikan untuk selamanya di atas dasar yang kuat” (ons bestuur voorgoed, op stevigen grondslag gevestigd). Ini menunjukkan bahwa klaim keberadaan dan kematiannya hanya dilihat sebagai batu loncatan bagi konsolidasi kekuasaan kolonial.
Laporan-laporan militer, seperti “Aanhangsel van het voorschrift voor de uitoefening van de politiek-politioneele taak van het leger” (Lampiran untuk Pedoman Pelaksanaan Tugas Politik-Kepolisian Tentara), digunakan sebagai sumber utama untuk mencatat rincian klaim kematiannya. Penggunaan sumber semacam ini secara inheren mencerminkan perspektif militeristik dan penaklukan, yang menekankan keberhasilan operasi militer Belanda dalam menghadapi perlawanan lokal.
Selain itu, upaya administrasi kolonial untuk mengkategorikan dan mengatur masyarakat Batak juga menunjukkan bias ini. Perhatian terhadap struktur desa Batak, seperti peran “kapalo kampoeng” (kepala desa) dan “ripê-hoofden” (kepala kasta), menunjukkan upaya Belanda untuk memahami sistem lokal guna memfasilitasi kontrol dan pemerintahan.
Meskipun sumber-sumber mengakui pengaruh budaya lain (seperti Aceh dan Minangkabau) pada masyarakat Batak, hal ini juga dapat menjadi bagian dari strategi kolonial untuk membagi dan menguasai, dengan menyoroti heterogenitas internal yang mungkin melemahkan persatuan lokal. Dokumen-dokumen yang membahas “adatrecht” (hukum adat) dan publikasinya oleh Adatrecht-stichting di Leiden juga menegaskan bagaimana Belanda berusaha mengkodifikasi dan mengontrol sistem hukum lokal.
Bias Agama
Persepsi Kristen terhadap Singa Mangaraja dan masyarakat Batak juga memiliki dampak yang signifikan dalam literatur. Setelah pengisahan atas klaim invasi Padri, disebutkan bahwa gereja dan “guru” (pendeta/pengajar Kristen) mulai didirikan di wilayah seperti Pulaugodang. Hal ini menggarisbawahi upaya Kristenisasi yang berkembang di Tanah Batak.
Literatur bias ini juga menyoroti perpecahan identitas yang muncul akibat perbedaan agama, khususnya antara Batak Utara yang kemudian mayoritas menjadi Kristen dan Mandailing di Selatan yang mayoritas Muslim. Perdebatan mengenai “particularistic chauvinism” Mandailing yang ingin memisahkan identitas mereka dari Batak Kristen juga tercatat. Publikasi misionaris, seperti “Merga Si Lima” dan “Bendera Kita”, muncul sebagai media yang memberikan “segala yang dibutuhkan orang Batak dalam bidang agama”, menunjukkan aspirasi dominasi narasi keagamaan yang dikendalikan para missionaris.
Ironisnya, beberapa kritik juga datang dari dalam lingkaran Eropa-Kristen. Van der Tuuk, misalnya, seorang penerjemah Alkitab, menyatakan “penghinaan” (minachting) terhadap orang yang belajar bahasa hanya untuk tujuan menerjemahkan Alkitab dan menyebut pekerjaan Alkitab sebagai “morswerk” (pekerjaan asal-asalan). Ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan Kristenisasi ada, tidak semua individu di dalamnya sepakat dengan metodenya atau memandang rendah studi bahasa murni untuk tujuan misionaris.
Namun demikian, ketersediaan jenis huruf Batak dipandang sebagai “penyelamat” dari “pemerintahan Turki” (merujuk pada Padri), yang mengindikasikan bahwa penyebaran agama Kristen juga dilihat sebagai alat pembebasan dari pengaruh non-Kristen yang lain.
Analisis Kritis & Implikasi
Secara kritis, literatur yang ada menunjukkan bahwa pemahaman tentang Singa Mangaraja sangat dibentuk oleh perspektif asing. Gelar dan sejarahnya yang “samar” dari sudut pandang Barat dapat diartikan sebagai kegagalan untuk sepenuhnya mengakui dan memahami kompleksitas narasi lokal yang mungkin tidak sesuai dengan kerangka historis atau ilmiah Barat yang ketat.
Pernyataan seperti “Seseorang harus memiliki pemahaman yang sangat naif tentang ‘sejarah’ jika ia memberikan makna historis pada data yang… disajikan kepada kita!” adalah contoh nyata dari superioritas intelektual yang tersirat, yang cenderung meremehkan validitas sumber lisan atau tradisi lokal Batak dalam membentuk sejarah mereka sendiri.
Interpretasi makna “Singa” yang berganda, baik sebagai simbol kekuatan atau perancang tata kelola, meskipun dicatat, mungkin tidak sepenuhnya menangkap dimensi spiritual dan keagamaan dari figur Singa Mangaraja yang dianggap sebagai “pangeran-dewa” (god-vorst) dan “Putra Dewa” (putra Batara Guru). Fokus pada aspek politik dan militernya oleh narasi kolonial seringkali menggeser makna sakral ini, mereduksinya menjadi ancaman yang perlu ditaklukkan.
Pengakuan akan adanya “endapan unsur-unsur mitos Hinduistik, terutama Siwaistik, dan mungkin juga Buddha” dalam figur Singa Mangaraja menunjukkan kesadaran akan lapisan budaya yang lebih tua, namun tetap dalam kerangka akademis Barat yang mengklasifikasikan “mitos” dan agama non-Kristen.
Secara keseluruhan, sumber-sumber sejarah Batak bikinan Eropa ini, meskipun menyediakan data berharga bagi orang yang cukup kritis, memerlukan pembacaan yang lebih waspada untuk mengungkap bagaimana bias-bias Eropa, kolonial, dan agama telah membentuk representasi Singa Mangaraja.
Mereka sering kali memprioritaskan narasi penaklukan, kontrol administrasi, dan penyebaran agama, sambil meremehkan atau menyaring kedalaman budaya, spiritualitas, dan otonomi historis masyarakat Batak. Dengan memahami bias ini, pembelajar dapat mulai merekonstruksi sejarah Singa Mangaraja dengan pandangan yang lebih holistik dan menghargai keragaman sumber dan interpretasi.
Representasi masyarakat lokal dalam tulisan-tulisan ini sering merendahkan, menyimpangkan fakta, dan menghapus suara asli komunitas adat. Upaya verifikasi terhadap sumber-sumber ini bukan sekadar koreksi akademik, melainkan juga tindakan kultural untuk memulihkan martabat dan memori kolektif bangsa.
Penulis adalah Dosen Fisip UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS).
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.