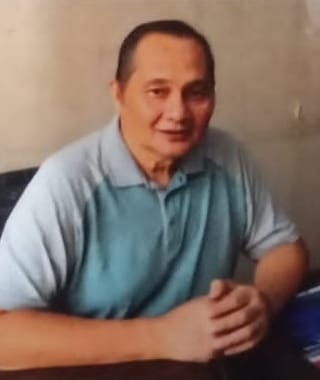Oleh Farid Wajdi
Apakah nasionalisme gagal? Tentu tidak. Justru sebaliknya, nasionalisme yang hidup. Nasionalisme yang menggugat, mempertanyakan, dan memaksa kita meninjau ulang makna kemerdekaan
Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN
Pekik “Merdeka!” akan segera menggema di seluruh penjuru negeri. Tanggal 17 Agustus tinggal hitungan hari. Merah Putih telah berkibar di tiang-tiang jalan, sekolah, hingga pekarangan rumah. Namun, tahun ini ada yang tak biasa—di tengah kemeriahan simbol-simbol kemerdekaan, berkibar pula bendera bajak laut bertopi jerami, lambang dari kru bajak laut Topi Jerami dalam anime One Piece. Reaksi pun beragam: mulai dari decak kagum, rasa geli, kebanggaan kreatif, hingga tudingan sebagai tindakan subversif.
Pertanyaannya kini bukan lagi sekadar “apa itu Jolly Roger”, tetapi “apa makna yang sedang dikibarkan anak muda dengan bendera itu?” Apakah ini bentuk penghinaan terhadap Merah Putih? Apakah publik sedang menyaksikan pergeseran nilai nasionalisme? Atau justru ini adalah ekspresi simbolik dari kegelisahan rakyat yang tidak lagi merasa memiliki negara sepenuhnya?
Dari Proklamasi Ke Pop Culture
Sejak kemerdekaan, nasionalisme kita ditopang oleh simbol-simbol kuat: lagu kebangsaan, lambang negara, dan tentu saja sang saka Merah Putih. Namun zaman berubah. Generasi digital tak lagi hanya hidup dari buku-buku sejarah, mereka tumbuh bersama meme, fandom, dan storytelling global. Dalam konteks ini, bendera Topi Jerami bukan sekadar “bendera bajak laut”, tetapi bagian dari lanskap budaya populer yang sarat makna. Bagi penggemarnya, One Piece bukan hanya anime. Ia adalah cerita tentang solidaritas, perjuangan, keberanian menantang kekuasaan korup, dan setia kawan dalam menghadapi ketidakadilan. Kapten Luffy bukan bajak laut biasa; dia penentang sistem dunia yang zalim, yang menolak tunduk pada otoritas korup demi menyelamatkan kawan dan menegakkan kebebasan (Suara.com, 2025).
Saat anak muda memilih mengibarkan Jolly Roger Luffy di tengah perayaan kemerdekaan, itu bukan karena mereka ingin melecehkan Merah Putih, melainkan karena mereka melihat kemerdekaan itu sendiri sedang “diperjuangkan ulang”—dalam bentuk baru, dalam bahasa yang mereka pahami. Luffy, dalam banyak hal, mungkin lebih terasa “heroik” daripada banyak tokoh publik yang bicara soal nasionalisme hanya saat bulan Agustus.
Namun sayang, sebagian elite politik menanggapinya dengan respons yang tergesa dan minim empati. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, bahkan menyebut aksi ini sebagai “upaya pecah belah bangsa” (Kompas, 2025). Pernyataan ini langsung menuai kritik dari publik. Benarkah sekelompok anak muda yang mengibarkan simbol imajinatif dari dunia fiksi bisa dituduh sebagai ancaman bagi keutuhan bangsa?
Reaksi berlebihan seperti ini menunjukkan sempitnya pemahaman terhadap bahasa simbolik generasi muda. Alih-alih berdialog dan mencoba memahami apa yang sedang dikatakan melalui simbol itu, negara justru memilih jalan represi simbolik—seolah nasionalisme adalah milik eksklusif negara dan tidak bisa dinegosiasikan bentuknya oleh rakyat. Padahal, ekspresi simbolik ini justru bisa dibaca sebagai “peringatan diam dalam sunyi” dari generasi muda yang kecewa pada keadaan. Mereka tidak membakar bendera negara, tidak meneriakkan slogan anti-NKRI, tapi mengibarkan simbol yang menyampaikan kegelisahan: “Kami belum merasa merdeka sepenuhnya”.
Merdeka Dari Apa, Untuk Siapa?
Pertanyaan ini terus bergema: “Merdeka dari apa, dan untuk siapa?” Pada 1945, jawabannya jelas: merdeka dari penjajahan asing, untuk rakyat Indonesia. Tapi di 2025, siapa penjajahnya? Siapa yang menikmati hasil kemerdekaan? Kesenjangan sosial masih menganga. Suara kritik sering dibungkam. Ruang sipil mengecil. Rakyat yang bersuara dikriminalisasi. Ketika bendera bertopi jerami dikibarkan, mungkin itu adalah refleksi dari keinginan untuk mengatakan: “Kami ingin keadilan. Kami ingin pemimpin seperti Luffy yang berani melawan tirani, bukan penguasa yang hanya beretorika nasionalis saat kampanye atau upacara kenegaraan”.
Seperti dikatakan sosiolog Ariel Heryanto, nasionalisme hari ini mengalami “kebingungan makna”, sebab simbol-simbol kenegaraan menjadi formalitas belaka dan tidak lagi menjangkau batin rakyat (Heryanto, 2015). Dalam situasi seperti ini, rakyat mencari simbol alternatif yang lebih resonan dengan kenyataan mereka—dan seringkali simbol itu lahir dari budaya populer. Bendera Topi Jerami adalah satire. Ia adalah kritik kultural dalam bentuk yang damai, kreatif, dan menghibur. Dalam studi budaya, satire adalah bentuk komunikasi simbolik yang digunakan untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap status quo tanpa harus turun ke jalan (Eco, 1986). Ia tidak merusak, tapi menyengat. Ia tidak frontal, tapi menusuk!
Anak muda tidak bodoh. Mereka sadar Merah Putih adalah simbol negara yang tidak boleh diganti. Tapi mereka juga sadar, simbol itu tidak bisa lagi berdiri sendiri tanpa makna yang hidup. Mereka ingin bendera itu kembali bermakna, bukan sekadar dikibarkan lalu dilupakan. Simbol seperti Jolly Roger menjadi penanda bahwa generasi ini butuh ruang untuk bicara dengan bahasa mereka sendiri. Mereka ingin merayakan kemerdekaan, tapi juga ingin didengar. Ketika negara menanggapi simbol budaya dengan paranoia politik, yang terjadi bukan penguatan nasionalisme, melainkan alienasi.
Apakah ini nasionalisme gagal? Tentu tidak. Justru sebaliknya, ini adalah nasionalisme yang hidup. Nasionalisme yang menggugat, mempertanyakan, dan memaksa kita untuk meninjau ulang makna kemerdekaan. Nasionalisme bukan hanya soal menghafal sila Pancasila atau hormat bendera tiap Senin pagi, tapi juga tentang mencintai negeri ini dengan cara yang tulus, termasuk dengan cara yang berbeda. Bendera Luffy bukan anti-nasionalisme, ia adalah bentuk lain dari nasionalisme kritis—yang berani bertanya: “Apakah negara ini masih memihak rakyatnya?”
Dengarkan, Bukan Hukum
Alih-alih mengancam atau menuduh subversif, negara seharusnya belajar mendengar. Dalam demokrasi yang sehat, suara rakyat bukan musuh yang harus dibungkam, melainkan cermin yang perlu dibaca. Ketika generasi muda mengangkat simbol seperti bendera bajak laut bertopi jerami, respons terbaik bukan pelaporan atau penghakiman moral, tetapi dialog. Tugas pemimpin bukan memadamkan suara-suara baru, melainkan membaca tanda-tanda zaman dan memahami bahasa generasi yang tumbuh dalam era digital, budaya populer, dan kegelisahan global.
Di sinilah negara seharusnya menunjukkan kedewasaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, bisa mengambil peran proaktif: bukan hadir sebagai polisi moral, tetapi sebagai fasilitator perbincangan nasional. Mungkin ini saatnya menyelenggarakan forum publik bertajuk “Nasionalisme Generasi Z: Antara Meme, Makna, dan Merdeka” atau “Simbol, Satire, dan Semangat Kebangsaan Baru.” Biarkan generasi muda menjelaskan sendiri apa makna bendera Luffy bagi mereka—tanpa prasangka, tanpa kriminalisasi.
Nasionalisme tidak bisa terus dimaknai sebagai keseragaman. Ia bukan seragam, bukan formasi baris-berbaris, bukan pula sekadar hafalan Pancasila di depan kelas. Nasionalisme adalah kesadaran kolektif tentang nasib bersama, tentang cita-cita yang diwariskan dan diperjuangkan. Dan seperti setiap zaman melahirkan bahasanya sendiri, nasionalisme juga mesti terus diperbarui agar tidak menjadi fosil. Pendidikan kewarganegaraan pun sudah saatnya direformulasi. Bukan sekadar modul kaku tentang struktur negara, tapi ruang refleksi tentang makna menjadi warga di tengah ketidakpastian zaman. Generasi baru tidak bisa dijejali doktrin yang beku. Mereka butuh narasi kebangsaan yang hidup—yang bisa mereka sentuh, perdebatkan, bahkan olok-olok demi menemukan maknanya sendiri. Karena justru dari kebebasanlah kesadaran tumbuh. Dan dari kesadaran, cinta tanah air menjadi otentik.
Kita semua, pada suatu titik dalam sejarah hidup bangsa ini, pernah menjadi Luffy. Para pejuang kemerdekaan dulu pun tak tunduk pada tatanan yang berlaku. Mereka memberontak. Mereka dikucilkan. Mereka dituduh subversif. Tapi justru karena keberanian itulah kemerdekaan hadir. Karena itu, jika hari ini anak-anak muda mengangkat bendera bajak laut, boleh jadi mereka sedang melanjutkan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan—dengan gaya mereka sendiri.
Simbol memang penting, tapi bukan untuk dipertuhankan. Ketika bendera Luffy lebih menyentuh hati anak muda ketimbang pidato pejabat, publik harus bertanya: Apa yang telah diabaikan selama ini? Mengapa suara yang datang dari anime bisa lebih memikat daripada seruan resmi dari podium kekuasaan? Mungkin jawabannya tak terletak pada mereka yang mengibarkan bendera, melainkan pada kita semua yang selama ini terlalu sering menyuruh diam, tapi jarang mendengar.
Kini, saat bangsa ini bersiap menyambut delapan dekade kemerdekaannya, publik dihadapkan pada pertanyaan yang tak bisa dihindari: Apakah bangsa ini benar-benar sudah merdeka? Bukan hanya dari penjajahan fisik, tapi dari ketakutan untuk berbeda, dari kebiasaan menyalahkan yang muda, dari kedangkalan membaca simbol.
Kemerdekaan sejati adalah ketika negara mampu melihat perbedaan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai sumber daya. Ketika pemerintah berani mendengar, bukan hanya memerintah. Ketika kritik dianggap vitamin, bukan virus. Ketika bendera bajak laut tak lantas dituding sebagai pemberontakan, tapi dilihat sebagai simbol kegelisahan yang menuntut pemahaman. Nasionalisme masa depan bukan lagi soal siapa yang paling keras berteriak “Merdeka”, tapi siapa yang paling dalam mendengar bisik keresahan rakyatnya. Mungkin, yang dibutuhkan negeri ini bukan penguatan pasal-pasal hukum, tapi penguatan telinga.
Jika para pemimpin benar-benar mau mendengar—bukan sekadar menghakimi dari balik podium kekuasaan—mereka mungkin akan melihat sesuatu yang tak kasat mata: di balik gambar tengkorak bertopi jerami itu, ada denyut kegelisahan yang tak bisa lagi ditampung oleh seremoni dan jargon. Ada hati-hati muda yang masih mencintai negeri ini, tapi dengan cara mereka sendiri—jujur, spontan, terkadang gamang, dan sering kali tak konvensional. Cinta tanah air tak melulu soal berdiri tegak, tetapi juga soal berani bersuara—meski dengan simbol yang berbeda.
Penulis adalah Founder Ethics Of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, Dosen UMSU.
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.