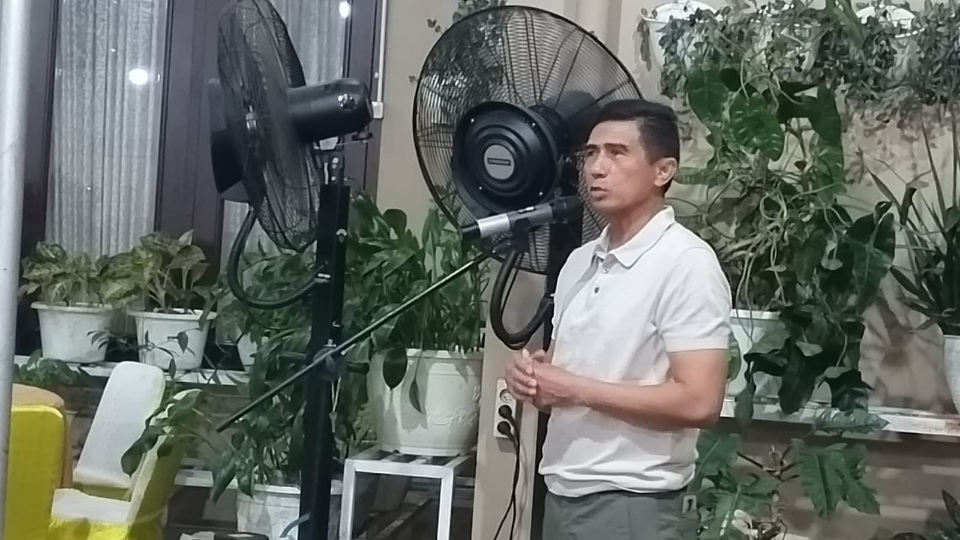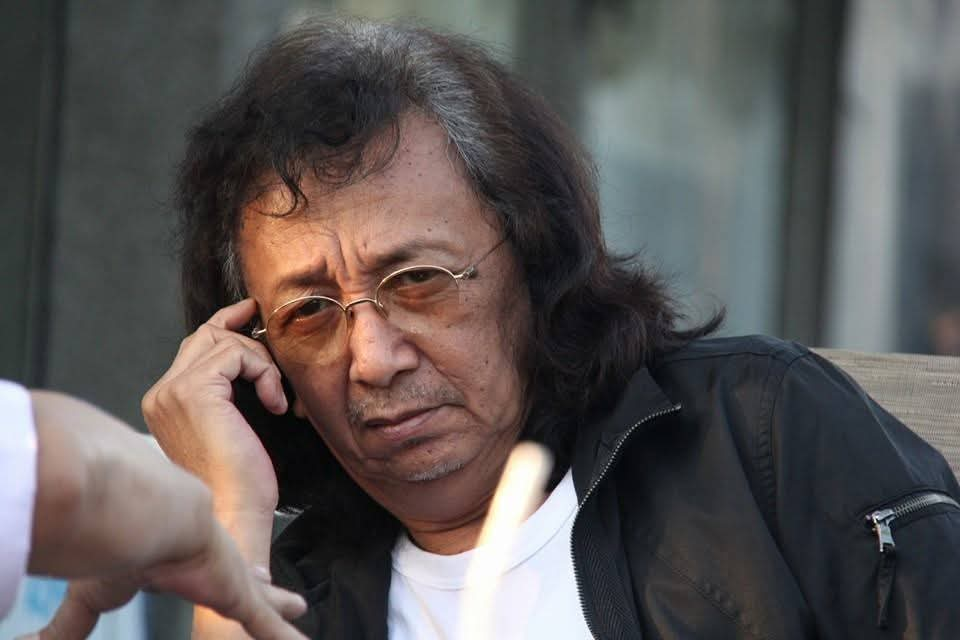Oleh: Yanhar Jamaluddin1) dan Syafrial Pasha2)
KETIKA Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, publik mungkin belum sepenuhnya menyadari arah baru yang akan dibawanya. Namun hanya dalam waktu satu bulan pertama, sederet kebijakan besar langsung diumumkan menandai langkah cepat, berani, dan berbeda.
Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN
Langkah-langkah Purbaya bukan sekadar manuver teknokratis, melainkan sinyal reformasi moral dan struktural dalam pengelolaan fiskal: menghadirkan kembali transparansi sebagai cahaya kebijakan.
Dalam tradisi filsafat, transparansi sering diibaratkan sebagai terang yang menyingkap kegelapan. Aristoteles (350 SM) sudah menasihati, agar perbendaharaan negara dilaporkan secara terbuka di depan publik untuk menghindari penipuan.
Pandangan ini berabad-abad kemudian ditegaskan oleh Sundelson (1935) yang menyebut, bukanlah disebut anggaran jika publik tidak dapat masuk ke dalam seluruh strukturnya. Dua pemikiran klasik ini menegaskan satu hal: anggaran adalah milik rakyat, bukan milik penguasa.
Namun, dalam praktik kontemporer birokrasi, seringkali posisi anggaran publik bergeser ke tempat yang remang, bahkan gelap, di mana alasan rahasia negara kerap menjadi dalih untuk menutup ruang akses publik. Di titik inilah pentingnya gebrakan fiskal Purbaya menemukan relevansinya: membawa keuangan publik kembali ke tempat yang terang.
Dua Belas Kebijakan Awal
Hanya dalam empat minggu, Purbaya mengguncang birokrasi fiskal dengan 12 kebijakan strategis. Dari suntikan Rp. 200 triliun ke Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) untuk memperkuat likuiditas, hingga tidak menaikkan cukai rokok 2026 demi melindungi pekerja dan petani tembakau.
Ia juga membentuk tim ahli independen untuk menuntaskan persoalan sistem Coretax, sebuah langkah langka di kementerian yang biasanya tertutup.
Purbaya menarik anggaran lembaga yang tak efisien dan mengalihkannya ke program prioritas nasional. Ia meluncurkan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja bergaji menengah, memburu 200 penunggak pajak besar senilai hingga Rp 60 triliun, dan memerangi rokok serta tekstil ilegal yang selama ini menggerus penerimaan negara.
Bahkan, ia memperluas transfer ke daerah menjadi Rp. 693 triliun, memperpanjang insentif pajak UMKM 0,5%, menambah penempatan dana pemerintah di bank daerah, serta berencana membangun kawasan industri hasil tembakau untuk mengalihkan produsen ilegal ke sektor formal.
Langkah-langkah ini jelas berpihak pada rakyat, industri nasional, dan pemerataan ekonomi. Namun di atas itu semua, gebrakan ini memiliki makna yang lebih dalam: penegakan transparansi fiskal dan akuntabilitas publik.
Transparansi Fiskal sebagai Fondasi Keadilan Ekonomi
Transparansi adalah jantung dari keuangan publik yang sehat. Tanpa keterbukaan, kebijakan fiskal berisiko menjadi sekadar instrumen kekuasaan dijalankan untuk kepentingan elit birokrasi dan oligarki, bukan untuk kesejahteraan rakyat.
Menurut Kopits dan Craig (1998), transparansi anggaran bukan hanya prosedur administratif, tetapi prasyarat keberlanjutan ekonomi. Keterbukaan memungkinkan publik memahami aliran uang negara, mengawasi belanja publik, dan menekan peluang penyimpangan. Sebaliknya, ketika anggaran berpindah ke ruang gelap, maka kekuasaan dapat mengendalikan informasi, menciptakan ilusi efisiensi, padahal sesungguhnya terjadi kebocoran (leakage) di berbagai lini.
Purbaya tampaknya memahami risiko itu. Dengan melibatkan ahli independen dan membenahi sistem digital perpajakan, ia sedang berupaya menarik kembali posisi anggaran ke tempat yang terang. Ia memulai apa yang bisa disebut sebagai reformasi moral keuangan publik, dimana transparansi bukan hanya alat, tetapi nilai.
Fenomena Gelapnya Anggaran Publik
Selama dua dekade terakhir, praktik transparansi di birokrasi Indonesia berjalan setengah hati. Informasi fiskal memang tersedia, namun sering kali tidak utuh, tidak tepat waktu, atau tidak berguna bagi publik.
Sebagian besar data keuangan bersifat teknis dan tidak dapat dipahami oleh masyarakat awam. Dalam banyak kasus, publik dihadapkan pada transparansi semu: data dibuka, tetapi maknanya ditutup.
Fenomena ini menciptakan jarak antara negara dan warga. Ketika publik kehilangan akses terhadap informasi fiskal yang jelas, kepercayaan terhadap pemerintah pun menurun. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Brunetti dan Weder (2003), korupsi cenderung tumbuh subur di ruang gelap informasi.
Pejabat korup dapat dengan mudah menggelapkan dana publik melalui kontrak palsu, biaya non-struktural, atau program fiktif yang hanya berfungsi menarik dukungan politik.
Dalam kondisi seperti itu, media yang bebas dan independen menjadi benteng terakhir transparansi. Tanpa media yang berani, informasi anggaran mudah direkayasa dan dikaburkan. Maka, langkah Purbaya memperkuat keterbukaan fiskal harus didukung oleh ekosistem informasi yang sehat birokrasi terbuka, media independen, dan masyarakat yang kritis.
Transparansi Dan Nilai Publik
Jika dilihat dari perspektif administrasi publik, transparansi bukan hanya tentang melihat, tetapi tentang mempercayai. Konsep nilai publik (public value), sebagaimana dijelaskan oleh Bozeman (2007) dan Dewey (1927), menekankan bahwa kebijakan publik harus berorientasi pada apa yang dianggap baik oleh masyarakat.
Artinya, keberhasilan fiskal tidak diukur semata oleh neraca dan pertumbuhan, tetapi oleh sejauh mana kebijakan tersebut menciptakan keadilan, partisipasi, dan kesejahteraan.
Dalam kerangka ini, Purbaya tampak mencoba menyeimbangkan antara efisiensi teknokratis dan nilai sosial.
Ia memahami bahwa reformasi pajak dan kebijakan fiskal hanya akan bertahan jika ditopang oleh kepercayaan publik (public trust). Kepercayaan itu tidak dapat diperoleh lewat propaganda, melainkan melalui keterbukaan informasi, partisipasi warga, dan keberanian menghadapi penyimpangan di dalam tubuh birokrasi itu sendiri.
Menuju Keberlanjutan Keuangan Publik
Isu keberlanjutan keuangan publik (fiscal sustainability) tidak hanya berbicara soal defisit dan utang, melainkan tentang daya tahan etika dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Ketika masyarakat tidak memiliki akses informasi yang komprehensif dan akurat, partisipasi mereka dalam pengawasan fiskal menjadi lumpuh.
Inilah akar dari siklus lemahnya akuntabilitas yang pada akhirnya menggerus keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Dalam hal ini, organisasi masyarakat sipil dan media memiliki peran penting. Mereka harus memperjuangkan penerapan undang-undang kebebasan informasi agar publik dapat mengakses data anggaran untuk tujuan analisis dan advokasi.
Dengan demikian, pengawasan terhadap APBN tidak lagi bersifat vertikal semata (dari atasan ke bawahan), tetapi juga horisontal dari warga kepada pemerintah dan sebaliknya. Model pengawasan dua arah inilah yang akan memperkuat fondasi demokrasi fiskal.
Refleksi: Cahaya di Tengah Birokrasi
Gebrakan Purbaya Yudhi Sadewa memang memunculkan pro-kontra. Ada yang menilai kebijakannya terlalu cepat, ada pula yang menganggapnya populis. Namun, jika dibaca dalam konteks yang lebih luas, langkah-langkahnya justru menandai pergeseran paradigma dalam pengelolaan keuangan negara: dari birokrasi tertutup menuju tata kelola terbuka dan berorientasi nilai publik.
Kebijakan seperti tidak menaikkan cukai rokok, memperkuat peran bank daerah, hingga pemberantasan pajak dan produk ilegal menunjukkan kesadaran bahwa ekonomi tidak boleh dilepaskan dari dimensi keadilan sosial. Dan keadilan itu hanya bisa tumbuh dalam sistem yang transparan.
Transparansi bukanlah kemewahan demokrasi; ia adalah syarat dasar agar negara tetap dipercaya. Sebagaimana cahaya yang menyingkap kegelapan, keterbukaan fiskal menuntun publik melihat arah pembangunan, sekaligus mencegah penyimpangan di jalan yang gelap.
Penutup
Keuangan publik yang berkelanjutan hanya dapat tercapai bila dijalankan dengan transparansi dan integritas. Langkah Purbaya di awal masa jabatannya patut dicatat sebagai momentum pembaruan fiskal Indonesia — mengembalikan keuangan negara ke tangan rakyat, dan menempatkan anggaran kembali di tempat yang terang.
Kini, tugas selanjutnya adalah memastikan agar semangat itu tidak padam. Pemerintah harus memperkuat akses data terbuka, masyarakat sipil perlu aktif dalam pengawasan, dan media wajib menjaga independensinya.
Karena tanpa cahaya transparansi, anggaran publik akan kembali tenggelam dalam gelapnya kepentingan sempit birokrasi. (1) Ketua Pusat Kajian MAP-UMA dan Sekjen PB. Ikatan Sarjana Melayu Indonesia, 2) Etnografer Sumatera Utara)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.