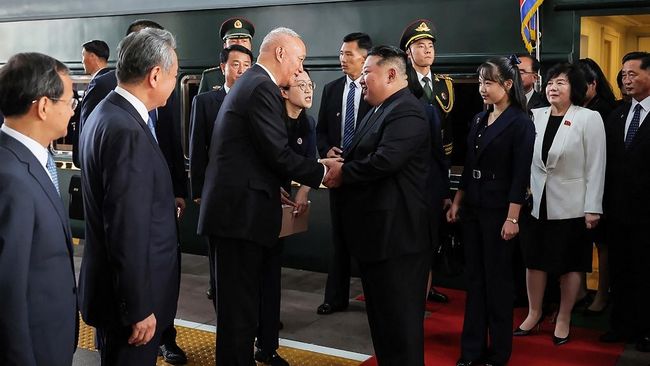Oleh Yanhar Jamaluddin & Syafrial Pasha
Di tengah dinamika perencanaan kebijakan publik di Indonesia, aspirasi kelompok masyarakat yang terpinggirkan sering kali terabaikan oleh dominasi pendekatan teknokratis dan paradigma pembangunan yang seragam. Padahal, Indonesia bukanlah sebuah kesatuan homogen, melainkan heterogen terdiri atas beragam identitas budaya, ratusan suku bangsa, ribuan bahasa, serta warisan nilai-nilai lokal yang terus hidup dari generasi ke generasi.
Dalam konteks keberagaman ini, penerapan kebijakan publik yang berlandaskan kearifan lokal bukan hanya menjadi opsi tambahan, melainkan sebuah tuntutan epistemologis dan moral guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Kearifan lokal merupakan hasil akumulasi pengetahuan, nilai, dan praktik masyarakat yang terbentuk dari interaksi historis dengan lingkungan sosial dan alam.
Menurut Haverkort et.al. (2003), kearifan lokal adalah bagian dari endogenous development, yaitu pembangunan berbasis kekuatan internal masyarakat, mencakup pengetahuan lokal, pertanian tradisional, struktur sosial, dan nilai spiritual.
Di Sumatera Utara, kearifan lokal tercermin dalam pengelolaan sumberdaya alam berbasis komunitas, seperti tradisi lubuk larangan dikalangan Batak Toba dan Mandailing.
Tradisi ini menetapkan area sungai sebagai zona larangan menangkap ikan untuk menjaga ekosistem dan mata pencaharian. Aturan adat yang disepakati bersama menjadi dasar pelaksanaannya. Contoh praktik ini ada di Pidoli Lombang, Danau Toba, dan DAS Tapanuli Selatan, dengan pembatasan penangkapan pada musim tertentu atas dasar ekologis dan adat.
Praktik-praktik pengelolaan sumberdaya alam yang tumbuh dari akar budaya masyarakat mencerminkan bentuk kearifan lokal yang telah teruji oleh waktu.
Dalam komunitas Batak, misalnya, dikenal tradisi lubuk larangan sebagai sistem konservasi perairan yang bersifat sakral. Selain itu, pengaturan wilayah adat (huta) dan praktik kerja kolektif seperti marompak, yakni mencakup pengelolaan ladang dan sistem irigasi sehingga ini menjadi contoh kelembagaan lokal yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial antarwarga.
Kearifan serupa juga ditemukan di komunitas pesisir seperti di Langkat dan Serdang Bedagai, di mana masyarakat mempraktikkan aturan adat dalam penangkapan ikan serta menjaga kelestarian hutan bakau.
Semua ini berlandaskan pada kesepakatan sosial yang mengikat secara moral dan kultural, menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya tidak hanya berbasis ekonomi, melainkan juga nilai-nilai kolektif yang hidup dalam tradisi. Namun, dalam konteks tata kelola modern, pemerintah daerah kerap menghadapi tantangan serius ketika berhadapan dengan kelompok masyarakat yang berada dilapisan paling bawah dalam struktur sosial.
Perbedaan dalam bahasa komunikasi, minimnya pemahaman terhadap norma dan praktik lokal, hingga pendekatan birokratis yang cenderung top-down, sering menjadi penghambat efektivitas kebijakan. Di sinilah pendekatan budaya memegang peranan strategis.
Dalam masyarakat Melayu, misalnya, medium-medium kultural seperti pantun, petuah adat, upacara tradisional, hingga peran tokoh agama dan adat dapat dijadikan sarana efektif dalam menyampaikan pesan kebijakan.
Ketika pesan kebijakan dibungkus dalam bahasa budaya yang familiar, legitimasi sosial pun menguat, dan partisipasi masyarakat menjadi lebih aktif serta berkelanjutan. Ini sangat relevan dalam melihat keberhasilan implementasi suatu pesan kebijakan (Goggin, 1990) yang sangat ditentukan oleh metode komunikasi, yang diikuti atas faktor isi (content), bentuk (form) berupa atribut dan symbol, dan reputasi komunikator dalam pesan kebijakan.
Legitimasi Budaya, Efektivitas Kebijakan dan Solusi
Kebijakan publik tidak dapat berdiri hanya di atas legalitas formal. Ia membutuhkan legitimasi sosial dan budaya. Dalam perspektif Habermas (1984), suatu kebijakan akan diterima apabila melewati discourse ethics, yaitu proses deliberasi yang mengakui kebenaran bukan hanya berdasarkan otoritas, tetapi dari kesepakatan rasional dalam ruang publik. Artinya, ketika kebijakan selaras dengan nilai-nilai lokal yang dipahami dan diyakini masyarakat, maka ia akan memperoleh daya dukung yang tinggi.
Kebijakan publik berbasis kearifan lokal menjadi antitesis dari pendekatan top-down yang serba seragam. Ia adalah bentuk pengakuan bahwa masyarakat memiliki kapasitas, pengetahuan, dan sistem nilai yang sah untuk menjadi dasar kebijakan. Menghadapi tantangan ini, sejumlah solusi strategis dapat ditawarkan :
- Integrasi dalam Siklus Kebijakan, yakni kearifan lokal harus menjadi bagian dari seluruh siklus kebijakan: mulai dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi. Pemerintah daerah dan pusat perlu menyusun mekanisme konsultasi budaya yang melibatkan tokoh adat, pemuka agama, serta pelaku lokal dalam proses deliberatif kebijakan.
- Desentralisasi Pengetahuan dan Kewenangan, yakni mendorong desentralisasi bukan hanya dalam kewenangan administratif, tetapi juga dalam epistemologi. Artinya, negara harus mengakui validitas pengetahuan lokal sebagai basis pengambilan keputusan. Dalam hal ini, konsep co-production of knowledge (Ostrom, 1996) dapat diterapkan, yakni proses dimana pemerintah dan masyarakat bersama-sama memproduksi kebijakan berbasis pengalaman lokal.
- Pendidikan dan Dokumentasi Kearifan Lokal. Institusi pendidikan perlu (benar-benar) diberi ruang untuk mengembangkan kurikulum berbasis kearifan lokal. Universitas lokal dan lembaga adat dapat bekerja sama dalam mendokumentasikan praktik kearifan lokal yang selama ini hidup dalam ingatan kolektif tetapi belum diangkat sebagai referensi kebijakan.
- Penataan Hukum dan Perlindungan Hukum Adat
Kearifan lokal harus memperoleh jaminan hukum. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebenarnya) telah memberi ruang bagi pengakuan desa adat dan kelembagaan lokal. Namun implementasinya masih lemah. Karenanya diperlukan kebijakan turunan yang lebih eksplisit untuk melindungi praktik kearifan lokal dari ancaman penggusuran oleh proyek-proyek pembangunan skala besar. Bila perlu adanya legalisir izin kelayakan kearifan lokal terhadap praktik-praktik pembangunan dan pemerintahan.
Kesimpulan
Clifford Geertz menolak pandangan budaya sebagai sistem tertutup yang deterministik. Sebaliknya, ia menempatkan budaya sebagai medan tafsir yang hidup dan dinamis. Dalam semangat ini, kebijakan publik semestinya tidak menjadi instrumen dominasi negara atas rakyat, tetapi menjadi ruang dialog antar dunia nilai.
Membangun Indonesia bukan sekadar soal menambah jalan, bendungan, atau fasilitas publik lainnya. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa pembangunan itu tidak mengorbankan nilai, identitas, dan sistem pengetahuan yang telah menjaga harmoni masyarakat selama berabad-abad.
Dengan menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi kebijakan, kita tidak mundur ke masa lalu, melainkan melangkah ke masa depan dengan pijakan yang lebih berdaulat atas budaya lokal. Kita harus menjadi bangsa yang tidak hanya ingin maju, tetapi juga tahu arah dan akar kemajuannya. (1)Ketua Pusat Kajian MAP-UMA dan Sekjen PB. Ikatan Sarjana Melayu Indonesia, 2)Etnografer Sumatera Utara)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.