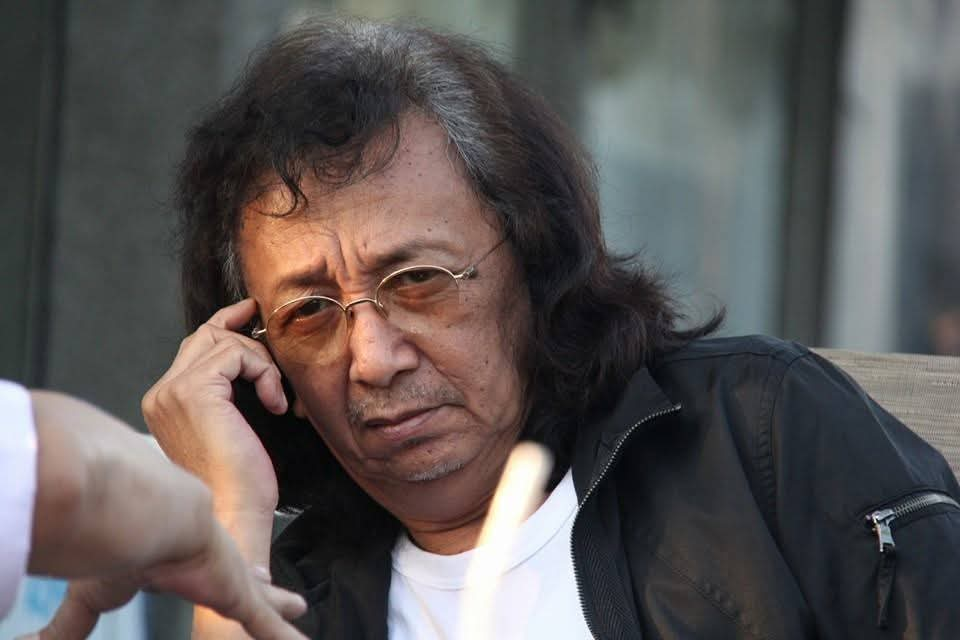Oleh Andi Rachmad, S.H., M.H.
Ilmu sebagai aktivitas rasional manusia berkembang melalui tiga ranah utama: ilmu murni (pure science), ilmu dasar (basic science), dan ilmu terapan (applied science). Masing-masing memiliki karakteristik, tujuan, dan orientasi epistemologis yang berbeda. Scroll Untuk Lanjut Membaca IKLAN
Dalam konteks filsafat ilmu, memahami perbedaan dan hubungan ketiganya penting untuk menelusuri bagaimana suatu gagasan abstrak dapat bertransformasi menjadi perangkat konseptual yang sistematis dan akhirnya menjadi praktik atau kebijakan konkret dalam masyarakat.
Ilmu murni adalah cabang ilmu yang berorientasi pada pencarian kebenaran dan pemahaman hakikat fenomena tanpa mempertimbangkan manfaat praktis langsung. Tujuannya adalah memperluas horizon pengetahuan secara teoritis.
Dalam ilmu murni, motivasi utama adalah knowing for the sake of knowing mengetahui demi pengetahuan itu sendiri. Ilmu dasar berfungsi sebagai fondasi sistematis bagi pengembangan ilmu terapan. Ia berusaha menyusun teori-teori umum dan kerangka metodologis yang memungkinkan penerapan prinsip-prinsip ilmu murni secara lebih terstruktur.
Jadi dalam konteks hukum, ilmu dasar menjembatani antara filsafat hukum (abstrak) dengan disiplin hukum yang konkret. Ilmu terapan berorientasi pada pemecahan masalah nyata dengan menggunakan prinsip dan teori yang berasal dari ilmu dasar.
Tujuannya bersifat praktis, yakni menciptakan kebijakan, peraturan, atau instrumen sosial yang konkret. Contohnya adalah ilmu dasar seperti teori Kelsen dan Hart menjadi pijakan bagi bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan lain-lain. Misalnya, teori grundnorm Kelsen menjadi dasar bagi pemahaman tentang supremasi konstitusi dalam hukum tata negara modern.
Ilmu hukum sebagai disiplin ilmiah tidak hanya berfungsi menata kehidupan sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasionalitas. Namun, dalam praktiknya, hukum terkadang digunakan secara berlebihan hingga mengancam prinsip dasar kebebasan berpikir.
Salah satu contoh fenomena yang memunculkan perdebatan adalah menjadikan buku sebagai alat bukti dalam tindak pidana, misalnya ketika sebuah buku dianggap mengandung ajaran berbahaya, hasutan, atau ujaran kebencian.
Dari perspektif filsafat ilmu, fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah tindakan menjadikan karya intelektual sebagai alat bukti hukum dapat dibenarkan secara ilmiah dan moral? Apakah langkah tersebut masih berada dalam koridor ilmu hukum (yang rasional dan sistematis), ataukah sudah keluar menjadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan hukum?
Menjadikan buku sebagai alat bukti sama artinya dengan menempatkan ekspresi intelektual sebagai potensi tindak kejahatan. Dari sudut pandang epistemologis, tindakan ini bertentangan dengan prinsip ilmu murni karena mengkriminalisasi aktivitas berpikir, yakni aktivitas yang justru menjadi dasar dan fondasi dari keberadaan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu dasar dalam hukum bertugas menyusun kerangka konseptual dan metodologis hukum positif.
Teori Hans Kelsen tentang Pure Theory of Law dan H.L.A. Hart tentang struktur hukum menjadi pijakan bagaimana hukum dipahami sebagai sistem norma. Namun, teori-teori tersebut juga menekankan bahwa hukum harus autonom dan rasional, bukan ditentukan oleh kekuasaan atau penilaian subjektif terhadap isi pikiran.
Dengan demikian, menjadikan buku sebagai alat bukti berpotensi mengacaukan struktur norma hukum, karena memperluas makna alat bukti dari fakta obyektif menjadi tafsir ideologis atas teks.
Dalam konteks hukum pidana, penerapan harus mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHAP yang hanya mengakui alat bukti sah seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Buku sebagai karya ilmiah tidak seharusnya langsung diposisikan sebagai alat bukti pidana, kecuali dapat dibuktikan bahwa buku tersebut merupakan alat kejahatan konkret, bukan sekadar wadah ekspresi gagasan. Ketika buku dijadikan bukti karena isinya dianggap berbahaya, penegak hukum telah melewati batas epistemologis ilmu hukum, sebab yang dinilai bukan tindakan hukum, melainkan isi pemikiran.
Dalam praktik hukum di Indonesia, terdapat beberapa kasus di mana buku dijadikan alat bukti, misalnya buku pemikiran Karl Marx karya Franz Magnis Suseno, Anarkisme karya Emma Goldman, dan Kisah Para Diktator karya Jules Archer oleh Polda Jawa Timur pada bulan September 2025. Namun, pendekatan semacam ini membawa konsekuensi serius:
- Kriminalisasi Pemikiran. Buku adalah hasil proses ilmiah dan intelektual. Menjadikannya alat bukti berarti mengkriminalkan kegiatan berpikir, yang secara moral dan ilmiah merupakan pelanggaran terhadap asas kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat.
- Degradasi Ilmu Hukum. Ilmu hukum yang seharusnya berfungsi rasional dan sistematis berubah menjadi instrumen kekuasaan yang menilai isi pikiran, bukan perbuatan hukum. Ini bertentangan dengan teori dasar hukum Kelsen, yang menegaskan bahwa hukum harus terpisah dari moralitas dan politik praktis.
- Penyimpangan dari Prinsip Keadilan. Dalam kerangka ilmu murni, keadilan menuntut perlakuan yang proporsional dan rasional. Menghukum seseorang berdasarkan isi pikirannya yang tertuang dalam buku adalah bentuk ketidakadilan epistemik (epistemic injustice), karena mengabaikan konteks, interpretasi, dan hak penulis untuk mengekspresikan gagasannya.
Dalam idealnya, transformasi ilmu hukum berjalan dari nilai-nilai abstrak (ilmu murni), menuju sistem hukum (ilmu dasar), hingga penerapan hukum positif (ilmu terapan). Namun, dalam kasus ini, proses tersebut mengalami distorsi epistemologis:
a. Ilmu murni yang seharusnya melindungi kebebasan berpikir tidak dijadikan acuan normatif;
b. Ilmu dasar yang menekankan sistem norma rasional justru ditundukkan oleh interpretasi politis;
c. Ilmu terapan yang seharusnya menyelesaikan masalah konkret malah dijadikan alat pembenaran tindakan represif.
Akibatnya, hukum kehilangan sifat keilmuannya dan bergeser menjadi instrumen kekuasaan (law as a tool of repression).
Beberapa faktor yang mendorong praktik menjadikan buku sebagai alat bukti antara lain:
- Kebutuhan Politik dan Kekuasaan. Hukum digunakan untuk mengontrol wacana publik dan membatasi kebebasan berpikir yang dianggap mengancam stabilitas.
- Krisis Kepercayaan terhadap Rasionalitas Publik. Negara sering kali meragukan kemampuan masyarakat menilai informasi secara kritis, sehingga mengambil langkah represif.
- Kurangnya Etika Keilmuan dalam Penegakan Hukum. Penegak hukum tidak selalu berpijak pada prinsip ilmiah dan etika akademik, melainkan pada kepentingan praktis.
Dari sudut pandang filsafat ilmu, kondisi ini menunjukkan kemunduran epistemologis, di mana ilmu hukum kehilangan kemandirian dan rasionalitasnya. Mengacu pada gagasan Karl Popper, hukum semacam ini tidak bersifat falsifikatif, artinya tidak bisa diuji secara rasional karena fokusnya menilai niat atau pikiran, bukan fakta objektif.
Filsafat ilmu menuntun kita untuk selalu mempertanyakan dasar-dasar epistemologis dan etis dari setiap praktik hukum. Jika hukum ingin tetap dianggap sebagai ilmu, maka ia harus berpijak pada rasionalitas, keadilan, dan kebebasan intelektual. Menjadikan buku sebagai alat bukti justru menegasikan prinsip-prinsip tersebut, sebab:
a. Praktik ini mengaburkan batas antara fakta hukum dan ide ilmiah.
b. Praktik ini menggeser hukum dari domain rasional ke domain ideologis.
c. Praktik ini mengancam keberlanjutan kebebasan akademik serta pengembangan ilmu pengetahuan.
Oleh karena itu, dalam kerangka filsafat ilmu, praktik tersebut harus ditolak, bukan berarti menolak hukum, melainkan untuk menjaga agar hukum tetap menjadi ilmu yang rasional, terbuka, dan berpihak pada kebebasan berpikir manusia.
Kesimpulan
Fenomena menjadikan buku sebagai alat bukti dalam tindak pidana merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip-prinsip dasar ilmu hukum. Ia bertentangan dengan ilmu murni yang menjunjung kebebasan berpikir, merusak struktur ilmu dasar hukum yang rasional, dan menyesatkan penerapan ilmu terapan yang seharusnya berfokus pada fakta konkret.
Dari sudut pandang filsafat ilmu, praktik ini harus dikritisi dan dihentikan karena menimbulkan bahaya epistemologis yaitu hukum kehilangan watak ilmiahnya dan berubah menjadi alat kekuasaan. Dengan demikian, mempertahankan kebebasan berpikir dan berekspresi bukanlah tindakan melawan hukum, tetapi justru bentuk paling tinggi dari penghormatan terhadap hakikat ilmu hukum itu sendiri. WASPADA.id
Penulis adalah Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.