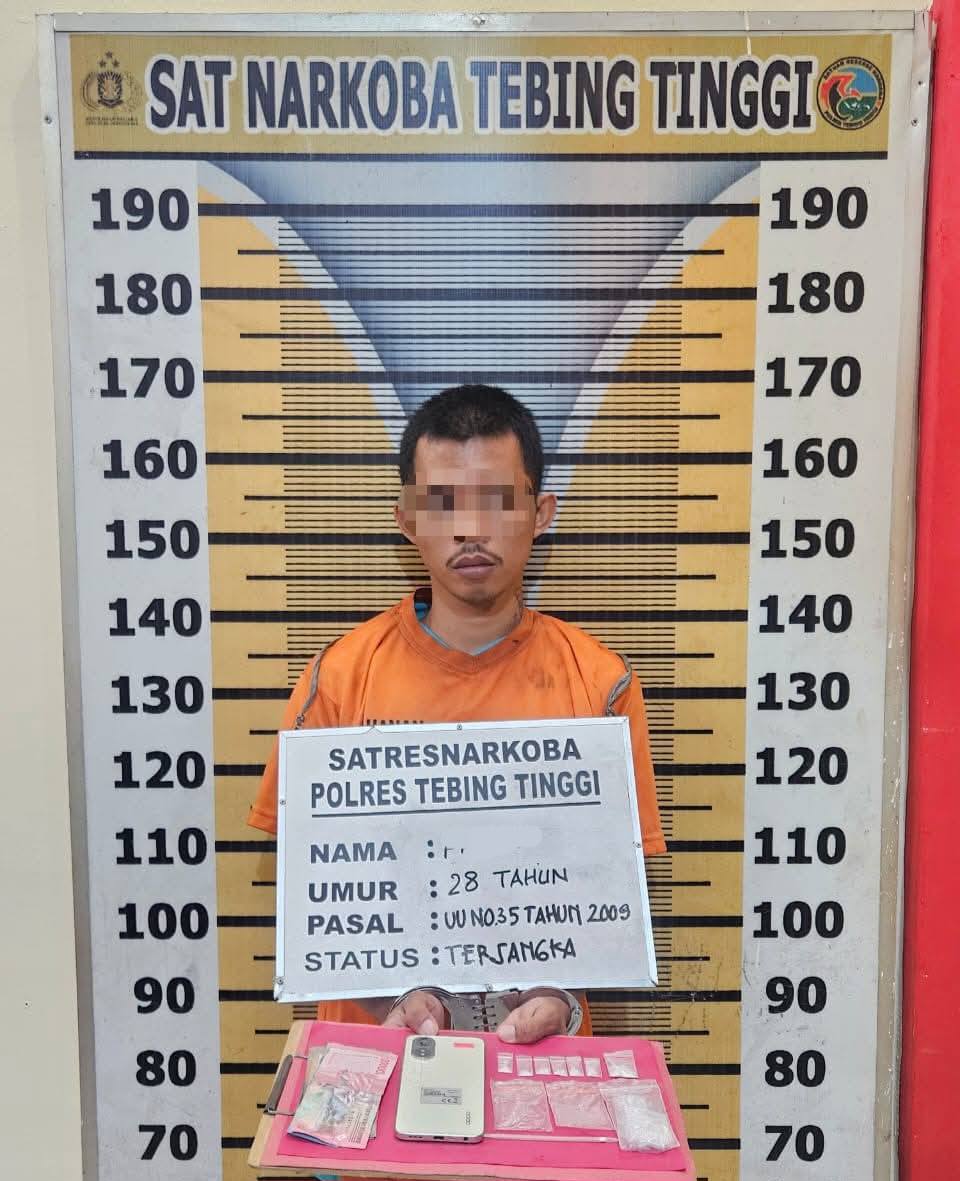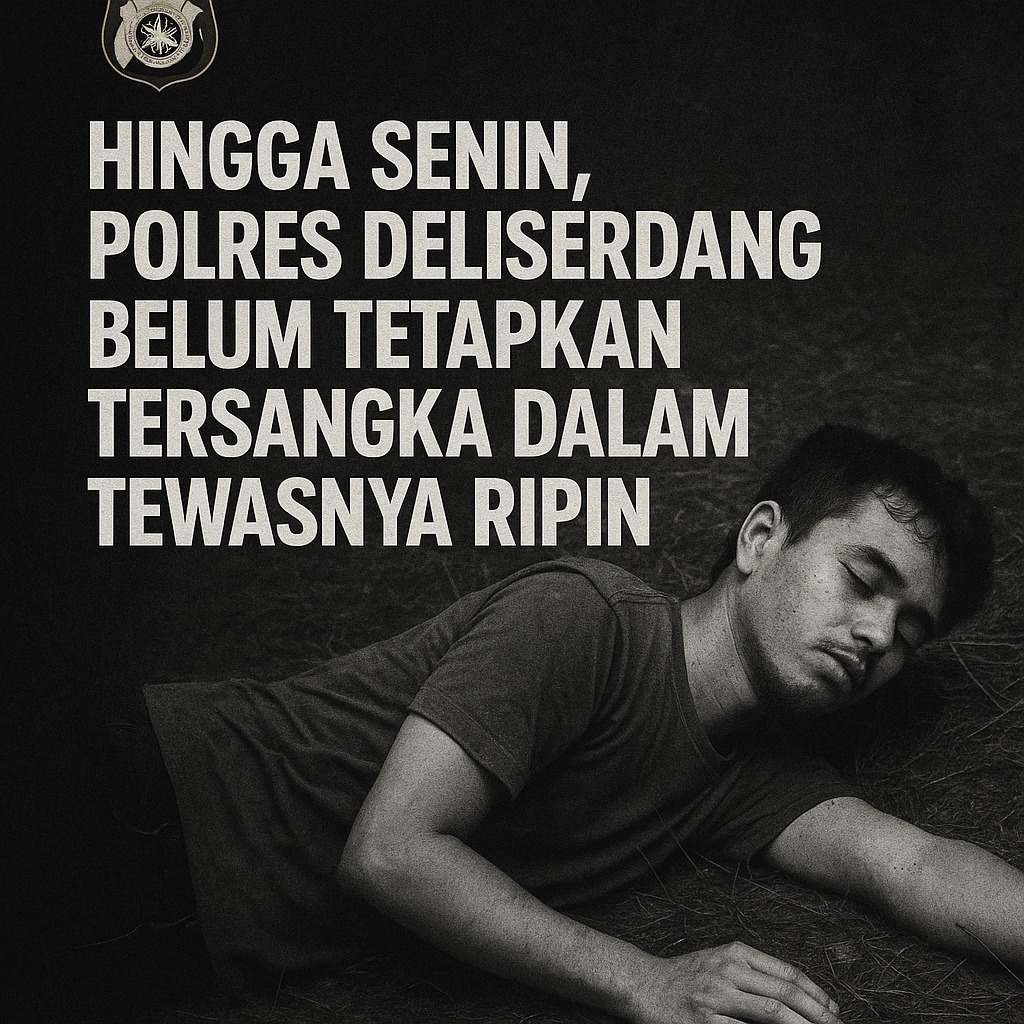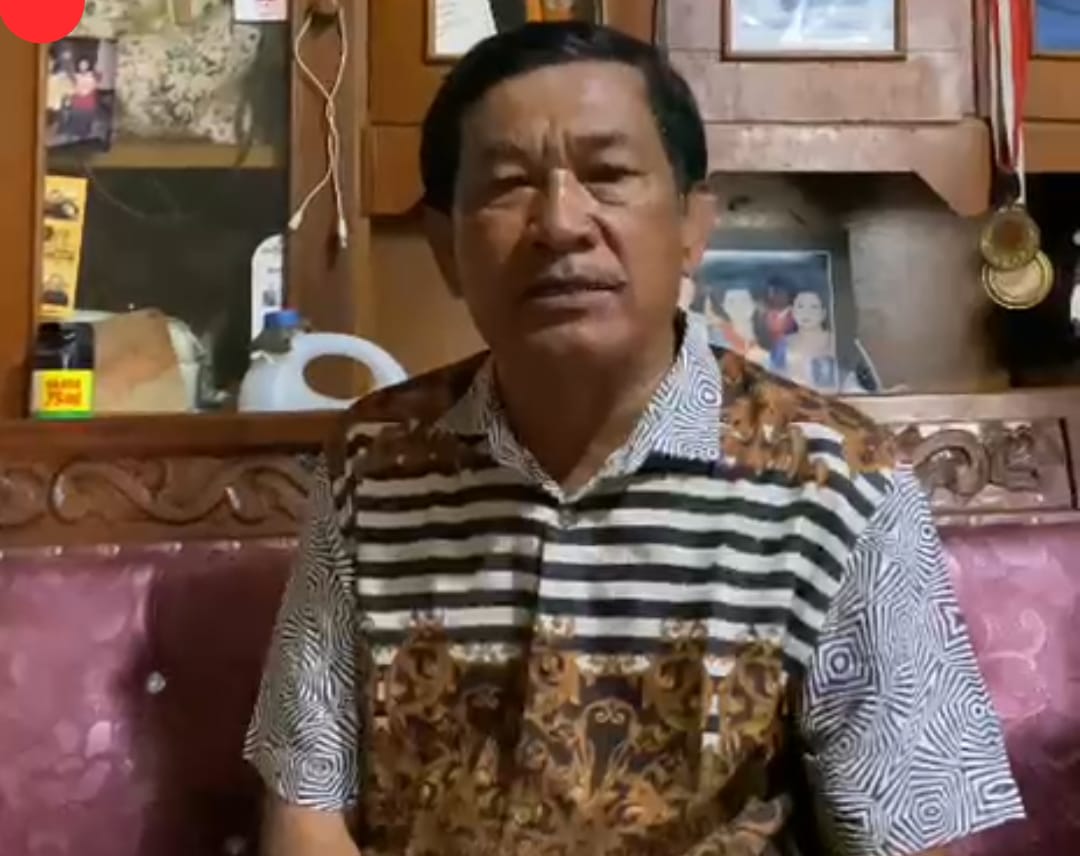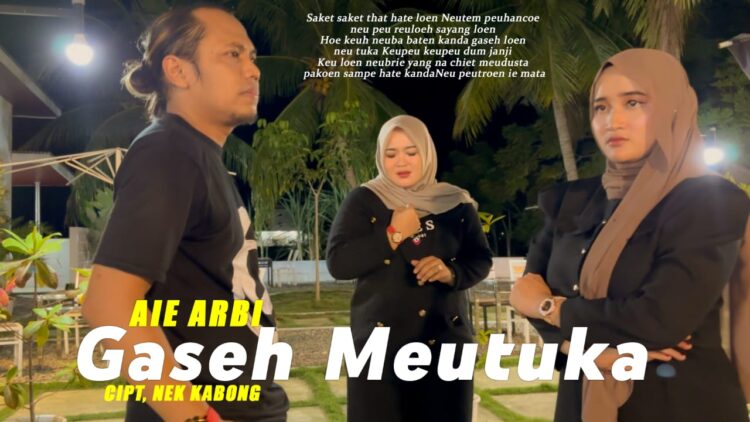Oleh Dr. H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn
Jika seluruh pemangku kepentingan—negara, akademisi, praktisi, dan masyarakat—dapat bergerak bersama dalam satu ekosistem pembaruan hukum digital, maka sertifikat elektronik akan menjadi lebih dari sekadar dokumen; ia akan menjadi fondasi dari tatanan hukum agraria yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di masa depan.
Pendahuluan
Transformasi digital dalam sektor agraria bukan lagi wacana futuristik, melainkan keniscayaan struktural yang tengah berlangsung. Di tengah tuntutan efisiensi layanan publik dan perlindungan hak kepemilikan tanah, penerbitan sertifikat elektronik menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dalam mewujudkan sistem pertanahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Kebijakan ini diperkuat dengan peluncuran berbagai regulasi baru yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan sertifikat elektronik, termasuk Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023.
Namun demikian, di balik semangat modernisasi, terdapat sejumlah tantangan multidimensi yang memerlukan perenungan mendalam, mulai dari kejelasan legalitas normatif, kesesuaian dengan asas-asas hukum pertanahan, hingga dampaknya terhadap praktik kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan perlindungan data pribadi masyarakat. Konsekuensinya, kebijakan ini tak hanya memantik diskursus teknokratik semata, tetapi juga menuntut pendekatan filosofis-yuridis untuk merumuskan sintesis pembaruan hukum pertanahan nasional yang inklusif, progresif, dan berpihak pada keadilan substantif.
Sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh hanya menjadi alat kekuasaan yang kaku (instrument of power), tetapi harus hadir sebagai sarana pembebasan dan pemberdayaan. Dalam konteks ini, penting untuk menelaah: (1) Sejauh mana sertifikat elektronik telah memiliki dasar hukum dan kekuatan legal yang memadai? (2) Bagaimana transformasi digital ini mengubah fungsi dan tanggung jawab PPAT dalam menjaga keabsahan dan keamanan dokumen pertanahan? (3) Apa saja tantangan hukum, teknis, dan sosial dalam implementasinya? Dan (4) Apa rekomendasi konkret yang dapat mendorong sistem hukum nasional agar lebih siap menghadapi era digitalisasi pertanahan?
Pembahasan ini bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dan filosofis, dengan menelaah kerangka peraturan perundang-undangan, asas dan teori hukum yang relevan, serta praktik empirik di lapangan, guna menyusun gagasan reformasi hukum nasional di bidang pertanahan.
1. Legitimasi Yuridis Sertifikat Elektronik: Memenuhi Unsur Legalitas dan Kepastian Hukum
Secara yuridis, landasan hukum dari sertifikat elektronik dapat ditelusuri dari berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.” Norma ini memberikan pijakan konstitusional terhadap pendaftaran tanah, termasuk inovasi digitalnya.
Kemudian, Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 secara eksplisit mengatur mekanisme penerbitan dokumen pertanahan secara elektronik, termasuk digital signature, integrasi data, dan pengamanan sistem. Hal ini diperkuat oleh Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, yang menyatakan bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah sebagai alat bukti di hadapan hukum. Lebih lanjut, Pasal 84 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021 menyatakan bahwa data dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat digunakan sebagai alat bukti hukum.
Dengan demikian, penerbitan sertifikat elektronik bukan semata kebijakan administratif, tetapi telah memiliki legitimasi hukum yang kuat dan dapat dikualifikasikan sebagai authentic deed apabila memenuhi prinsip-prinsip integritas sistem, keamanan data, serta akuntabilitas proses.
Namun, kritik tetap muncul dari segi fragmentasi norma dan kekosongan hukum sektoral, khususnya dalam pengakuan sertifikat elektronik sebagai objek agunan oleh lembaga keuangan. Hingga kini, belum ada aturan eksplisit yang menyatakan bahwa sertifikat elektronik dapat dijadikan jaminan kredit, padahal peran ekonominya sangat krusial. Tanpa regulasi turunan yang adaptif, potensi sertifikat elektronik sebagai alat pendorong pertumbuhan ekonomi akan terhambat.
2. Transformasi Praktik PPAT: Dari Analogue-First Menuju Digital-First
Implementasi sistem sertifikat elektronik telah mengubah secara fundamental cara kerja PPAT. Prosedur verifikasi, unggah dokumen, dan penandatanganan akta kini dilakukan secara daring melalui aplikasi seperti MITRA, e-Sertifikat, dan HT-el. Proses ini menuntut ketelitian lebih tinggi karena kesalahan input data digital bisa berakibat fatal secara hukum. Di sinilah pentingnya prinsip prudent person rule dan due diligence dalam menjalankan profesi PPAT.
Transformasi ini tidak hanya teknis, tetapi juga bersifat epistemologis. PPAT bukan lagi sekadar notulen hukum atas akta tanah, tetapi juga berperan sebagai data validator, information security agent, dan compliance officer. Peran ini menuntut peningkatan kompetensi digital dan pemahaman atas aspek hukum siber, yang selama ini belum menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan kenotariatan dan pertanahan.
Kendati digitalisasi menghadirkan efisiensi, hambatan masih dijumpai, terutama pada kesenjangan akses teknologi, keterbatasan pelatihan, serta resistensi budaya kerja konvensional. Sebagian PPAT di daerah mengeluhkan minimnya pelatihan menyeluruh tentang penggunaan sistem elektronik, sehingga tidak semua dapat beradaptasi dengan optimal.
3. Keamanan Data Pribadi: PPAT sebagai Garda Etik dan Teknis
Digitalisasi dokumen pertanahan tidak lepas dari ancaman cyber risk yang semakin kompleks. Sebagai pemroses data utama, PPAT berkewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi klien sesuai dengan prinsip privacy by design. Penggunaan sistem verifikasi digital, KTP reader, dan tanda tangan elektronik yang telah memenuhi standar ISO/IEC 27001:2013 menjadi bagian dari protokol keamanan data yang diterapkan.
Namun, sistem sekuat apapun tetap rentan terhadap serangan apabila tidak didukung oleh pemahaman etik dan tanggung jawab individual. Dalam hal ini, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi dasar penting bagi perlindungan hukum terhadap potensi kebocoran atau penyalahgunaan data, baik yang disebabkan oleh kelalaian maupun oleh cyber breach.
Meskipun belum ada kasus kebocoran data yang secara langsung melibatkan PPAT, risiko tetap ada. Maka, pelatihan teknis berkala, audit sistem, dan kebijakan enkripsi harus diintegrasikan secara sistemik. Dalam konteks ini, PPAT harus diposisikan sebagai aktor hukum yang bertanggung jawab secara etik dan legal terhadap keamanan sistem pertanahan digital.
4. Konflik Norma dan Studi Kasus: Ketika Hukum Belum Menyatu dengan Teknologi
Salah satu persoalan utama yang muncul adalah konflik antara norma hukum lama dan praktik teknologi baru. Misalnya, dalam sejumlah kasus, seperti Putusan PT Tanjung Karang No. 13/PDT/2021/PT TJK, sertifikat yang dikeluarkan secara elektronik diperdebatkan keabsahannya karena tidak memiliki bentuk fisik yang visible.
Padahal dalam kerangka hukum acara perdata, alat bukti elektronik sah digunakan sepanjang dapat dibuktikan integritasnya. Ini sejalan dengan doctrine of functional equivalence, yang menyatakan bahwa dokumen digital dan fisik dapat memiliki kekuatan hukum setara bila memenuhi syarat legal formalitas. Sayangnya, belum semua aparat penegak hukum dan lembaga pembiayaan mengadopsi pemahaman ini.
Konflik norma juga terlihat dalam ketidaksinkronan antara UUPA 1960 dan UU ITE, yang memerlukan legal harmonization agar tercipta kepastian hukum yang progresif. Di sinilah pentingnya pembaruan hukum yang tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat agraris.
5. Infrastruktur, SDM, dan Edukasi Publik: Pilar Kesiapan Sistem Pertanahan Digital
Kesiapan infrastruktur teknis di sejumlah Kantor Pertanahan, seperti di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang di Sumatera Utara, menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, pelatihan teknis belum menjangkau seluruh PPAT secara merata. Ini menjadi tantangan dalam mewujudkan sistem pertanahan digital yang inklusif.
Selain PPAT, masyarakat juga perlu diedukasi secara komprehensif. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keabsahan sertifikat elektronik menciptakan resistensi dan ketidakpercayaan terhadap sistem. Untuk itu, pemerintah perlu mengembangkan strategi komunikasi publik berbasis inklusivitas dan partisipasi, agar digitalisasi pertanahan tidak menciptakan digital divide baru di masyarakat.
6. Asas dan Nilai Hukum yang Mendasari: Mewujudkan Keadilan Agraria Digital
Penerapan sertifikat elektronik harus berpijak pada asas-asas hukum pertanahan, antara lain asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kesederhanaan. Dalam ranah etika profesi, prinsip good governance dan accountability juga menjadi landasan yang tak terpisahkan.
Jika ditilik dari teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, sistem sertifikat elektronik dapat menjadi instrumen pembaruan hukum sepanjang ia memihak pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menjadi produk teknologi yang melayani elit administratif. Dengan kata lain, hukum harus hadir untuk melayani, bukan dilayani.
Mewujudkan Tata Kelola Sertifikat Elektronik yang Responsif dan Inklusif
Dalam kerangka transformasi digital pertanahan nasional, penerapan sertifikat elektronik bukanlah semata kebijakan administratif, melainkan agenda strategis yang memerlukan pendekatan lintas sektor dan kolaboratif. Oleh karena itu, untuk menjamin efektivitas, keberlanjutan, dan akuntabilitas kebijakan ini, diperlukan langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pembuat kebijakan, pemerintah, akademisi, praktisi hukum, hingga masyarakat luas.
1. Untuk Pembuat Kebijakan: Harmonisasi Hukum dan Kepastian Sebagai Objek Jaminan Kredit
Langkah pertama yang harus segera diambil oleh pembuat kebijakan adalah merumuskan regulasi turunan yang eksplisit mengenai status sertifikat elektronik sebagai objek jaminan utang yang sah. Meskipun secara yuridis telah diakui dalam berbagai regulasi, namun hingga kini belum terdapat norma yang secara langsung menyatakan bahwa sertifikat elektronik dapat digunakan sebagai agunan dalam transaksi perbankan. Akibatnya, banyak lembaga keuangan masih enggan menerimanya karena dinilai kurang tangible dan berisiko tinggi secara legal.
Hal ini menunjukkan adanya celah antara legal substance dan legal structure, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk itu, harmonisasi antara UUPA Tahun 1960, UU ITE (terakhir direvisi melalui UU No. 1 Tahun 2024), dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27 Tahun 2022) harus segera dilakukan. Harmonisasi ini tidak hanya menyatukan bahasa hukum antar regulasi, tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip interoperabilitas sistem, validitas digital evidence, dan perlindungan data pribadi berjalan selaras dan mendukung satu sama lain. Tanpa fondasi hukum yang kohesif, sertifikat elektronik akan terus terjebak dalam posisi ambigu: diakui oleh regulasi tetapi ditolak oleh praktik.
2. Untuk Kementerian ATR/BPN: Penguatan Kapasitas Teknis dan Kompetensi Digital bagi PPAT
Sebagai lembaga eksekutor kebijakan, Kementerian ATR/BPN memegang peran sentral dalam menjamin bahwa seluruh sistem digitalisasi pertanahan berjalan dengan standar tinggi. Untuk itu, ATR/BPN perlu secara berkala menyelenggarakan pelatihan teknis dan hukum bagi PPAT di seluruh Indonesia, terutama dalam penggunaan sistem aplikasi seperti MITRA, SIP4T, HT-el, dan e-Sertifikat.
Pelatihan ini tidak boleh bersifat seremonial atau insidental semata, tetapi harus berbasis kurikulum yang berorientasi pada kompetensi digital dan pemahaman hukum siber, termasuk aspek risiko keamanan data. Selain itu, perlu dikembangkan kebijakan internal yang berbasis risk-based approach, agar perlindungan data pribadi yang tersimpan dalam sistem digital dapat dimitigasi secara sistematis terhadap potensi kebocoran, phishing, dan cyber attack.
Dalam kerangka ini, Kementerian ATR/BPN juga diharapkan membangun unit audit sistem digital pertanahan secara independen, untuk memastikan integritas dan akurasi data dapat terjaga dan dievaluasi secara berkala.
3. Untuk Akademisi: Riset Interdisipliner dan Pengembangan Teori Hukum Digital Indonesia
Di era hukum digital, dunia akademik tidak lagi dapat berdiri di menara gading. Keterlibatan akademisi sangat penting dalam membangun fondasi konseptual, teoretis, dan empirik dari sistem sertifikat elektronik. Untuk itu, diperlukan dorongan riset yang bersifat interdisipliner, khususnya pada pertemuan antara ilmu hukum, teknologi informasi, dan kebijakan publik.
Kampus-kampus hukum dan teknologi informasi di Indonesia diharapkan dapat mengembangkan program studi, mata kuliah, dan proyek riset yang fokus pada hukum digital pertanahan, data governance, serta cyberlaw dalam konteks agraria. Lebih jauh, riset ini diharapkan dapat melahirkan teori hukum digital Indonesia yang mampu menjawab tantangan era 5.0, yang tidak hanya mengandalkan analogi dari hukum konvensional, tetapi menyusun prinsip-prinsip hukum baru yang adaptif terhadap dunia digital dan tetap berpihak pada keadilan sosial. Publikasi ilmiah, policy paper, hingga usulan amandemen regulasi merupakan kontribusi nyata yang dapat diberikan akademisi kepada pembuat kebijakan dan masyarakat luas.
4. Untuk PPAT dan Praktisi Hukum: Aktor Kunci dalam Menjaga Trust dan Etika Profesi Digital
Di garis depan implementasi sertifikat elektronik, PPAT dan praktisi hukum memiliki tanggung jawab etis dan teknis yang tidak ringan. Mereka bukan sekadar pelaksana administratif, tetapi juga penjaga keabsahan hukum dan keamanan data klien. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas diri dalam memahami hukum siber, perlindungan data pribadi, dan keamanan sistem elektronik menjadi kebutuhan mendesak.
PPAT harus membekali diri dengan pemahaman tentang UU ITE, UU PDP, serta standar internasional seperti ISO/IEC 27001 dalam pengelolaan sistem informasi. Pelatihan mandiri, sertifikasi profesi digital, hingga kolaborasi dengan pakar teknologi informasi adalah langkah nyata yang dapat dilakukan oleh setiap PPAT.
Lebih dari itu, PPAT harus menjadi pilar kepercayaan publik (trust-building actor) terhadap sistem pertanahan elektronik. Dalam masyarakat yang masih diliputi keraguan terhadap digitalisasi, peran PPAT sebagai figur profesional yang kompeten, jujur, dan berintegritas sangat menentukan keberhasilan reformasi hukum agraria digital ini.
5. Untuk Masyarakat Umum: Literasi Digital Pertanahan sebagai Hak Sipil Baru
Transformasi sistem pertanahan tidak akan berjalan secara utuh tanpa keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital pertanahan perlu dijadikan agenda nasional, setara pentingnya dengan literasi keuangan atau literasi hukum.
Masyarakat harus memahami bahwa sertifikat elektronik bukanlah bentuk pelemahan hak atas tanah, tetapi justru bentuk perlindungan hak yang lebih efisien, aman, dan tahan manipulasi. Untuk itu, perlu dilakukan edukasi publik yang masif, inklusif, dan adaptif terhadap konteks lokal, baik melalui media digital, penyuluhan lapangan, layanan tatap muka di Kantor Pertanahan, hingga integrasi dalam program pendidikan formal dan non-formal.
Selain itu, pemerintah dan PPAT perlu menyediakan pusat informasi digital dan layanan pengaduan yang responsif, agar masyarakat tidak merasa ditinggalkan dalam proses perubahan sistem ini. Sertifikat elektronik bukan milik negara atau korporasi teknologi, melainkan milik warga negara sebagai subjek hukum yang dijamin konstitusinya.
Penutup:
Menuju Sistem Pertanahan Digital yang Adil dan Progresif
Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa sertifikat elektronik tanah telah memiliki legitimasi hukum yang sah, baik dari segi regulasi nasional maupun prinsip hukum acara. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, mulai dari ketimpangan infrastruktur, kekosongan norma sektoral, rendahnya literasi digital, hingga resistensi lembaga keuangan dan sebagian masyarakat.
Inti pokok pembahasan ini terletak pada sintesis antara aspek normatif, filosofis, dan praksis yang menjelaskan keterkaitan antara transformasi digital, perlindungan data pribadi, perubahan fungsi PPAT, dan keadilan agraria dalam konteks hukum Indonesia. Esai ini juga menegaskan bahwa sertifikat elektronik bukan sekadar dokumen digital, tetapi instrumen hukum yang harus dikawal integritasnya oleh semua pemangku kepentingan.
Rekomendasi di atas bukan hanya rangkaian teknis administratif, melainkan bagian dari visi besar untuk membangun sistem hukum pertanahan Indonesia yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan. Digitalisasi tidak boleh hanya menjadi simbol modernitas birokrasi, tetapi harus menjadi sarana pembebasan dan pemenuhan hak-hak konstitusional rakyat atas tanah dan ruang hidupnya.
Jika seluruh pemangku kepentingan—negara, akademisi, praktisi, dan masyarakat—dapat bergerak bersama dalam satu ekosistem pembaruan hukum digital, maka sertifikat elektronik akan menjadi lebih dari sekadar dokumen; ia akan menjadi fondasi dari tatanan hukum agraria yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di masa depan.
Penulis merupakan Ketua Pengwil Ikatan Notaris Indonesia Sumatera Utara
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.