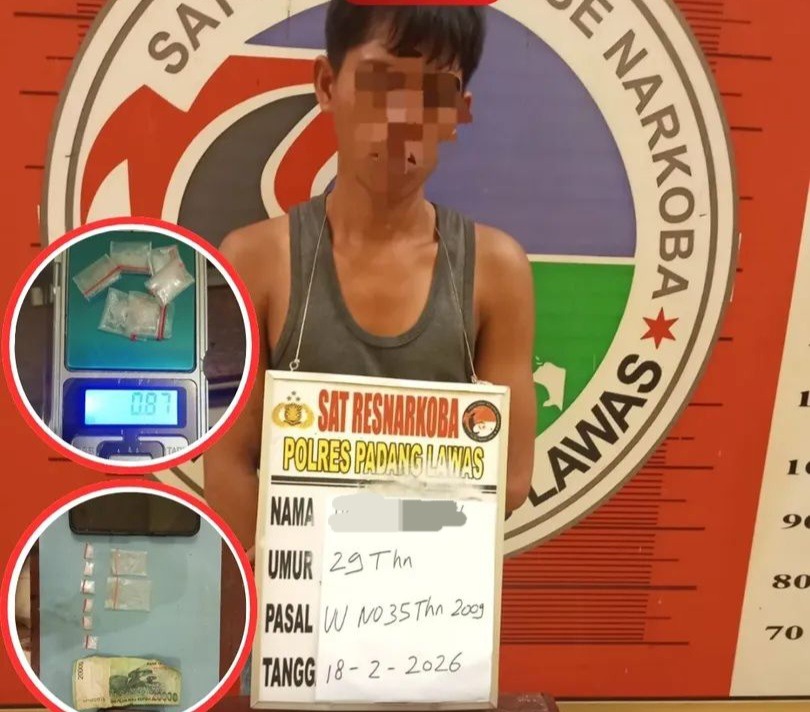Inspektur Wilayah III Kementerian Haji dan Umrah, Mulyadi Nurdin (tengah), berfoto bersama peserta Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) IKADIN DPD Provinsi Aceh usai memaparkan materi tentang sistem peradilan adat Aceh di Banda Aceh, Ahad (15/2/2026). Waspada.id/Ist
Inspektur Wilayah III Kementerian Haji dan Umrah, Mulyadi Nurdin (tengah), berfoto bersama peserta Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) IKADIN DPD Provinsi Aceh usai memaparkan materi tentang sistem peradilan adat Aceh di Banda Aceh, Ahad (15/2/2026). Waspada.id/IstUkuran Font
Kecil Besar
14px
Paparan Inspektur Wilayah III Kementerian Haji dan Umrah, Mulyadi Nurdin, kepada calon advokat yang diselenggarakan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) DPD Aceh menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali posisi strategis peradilan adat dalam sistem hukum di Aceh.
Kegiatan yang turut menggandeng Universitas Muhammadiyah Aceh itu bukan sekadar agenda akademik, melainkan langkah konkret memperkuat literasi hukum berbasis kekhususan daerah.
Aceh memang memiliki keistimewaan yang dijamin melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Salah satu substansi pentingnya adalah pengakuan terhadap sistem hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar peradilan umum.
Dalam konteks ini, peradilan adat bukan sekadar tradisi, melainkan bagian sah dari tata hukum yang hidup (living law) dan diakui negara. Paparan tersebut juga mengingatkan bahwa struktur peradilan adat di Aceh tersusun rapi dalam dua tingkat lalu, Gampong dan Mukim.
Di tingkat Gampong, keuchik berperan sebagai ketua hakim adat bersama unsur Imum Meunasah dan Tuha Peut. Sementara di tingkat Mukim yang juga berfungsi sebagai tingkat banding, Imeum Mukim memimpin proses bersama perangkat adat lainnya. Struktur ini menunjukkan bahwa peradilan adat memiliki sistem kelembagaan yang jelas, bukan sekadar forum musyawarah informal.
Menariknya, peradilan adat di Aceh berorientasi pada “keputusan damai” yang berlandaskan persetujuan para pihak melalui mediasi. Konsep ini sejalan dengan teori Ajaran Keputusan (Beslissingenleer) yang menempatkan kesepakatan sebagai basis legitimasi putusan. Dalam praktiknya, model ini lebih mengedepankan pemulihan hubungan sosial ketimbang penghukuman semata.
Ada 18 jenis perkara yang dapat diselesaikan secara adat, mulai dari perselisihan rumah tangga, sengketa warisan (faraidh), perselisihan antarwarga, hingga pencemaran lingkungan skala ringan. Daftar ini menunjukkan bahwa peradilan adat dirancang untuk menangani perkara-perkara yang menyentuh langsung harmoni sosial masyarakat.
Di sinilah nilai tambahnya, penyelesaian cepat, biaya ringan, dan berbasis kearifan lokal. Namun demikian, peradilan adat juga memiliki batasan tegas. Melalui kesepakatan antara Pemerintah Aceh, Majelis Adat Aceh, dan Polda Aceh, sejumlah bentuk sanksi yang merendahkan martabat seperti kekerasan fisik atau tindakan yang tidak sesuai nilai Islami dilarang. Artinya, modernisasi hukum adat tetap berjalan dalam koridor hak asasi manusia dan prinsip keadilan.
Di tengah meningkatnya kompleksitas perkara hukum, calon advokat di Aceh tidak cukup hanya memahami hukum positif nasional. Mereka juga perlu memahami mekanisme adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sah dan efektif.
Justru di sinilah profesionalisme advokat diuji: mampu menilai kapan perkara lebih tepat dibawa ke pengadilan formal dan kapan cukup diselesaikan melalui jalur adat.
Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga adat sebagaimana diamanahkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008.
Aparat perlu memberi ruang bagi penyelesaian adat sebelum perkara masuk ke ranah litigasi formal, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Peradilan adat Aceh bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan instrumen strategis membangun keadilan restoratif berbasis budaya.
Dengan pemahaman yang komprehensif dari para advokat muda, sistem ini berpeluang menjadi model integrasi hukum nasional dan hukum adat yang harmonis.
Muhammad Riza
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.