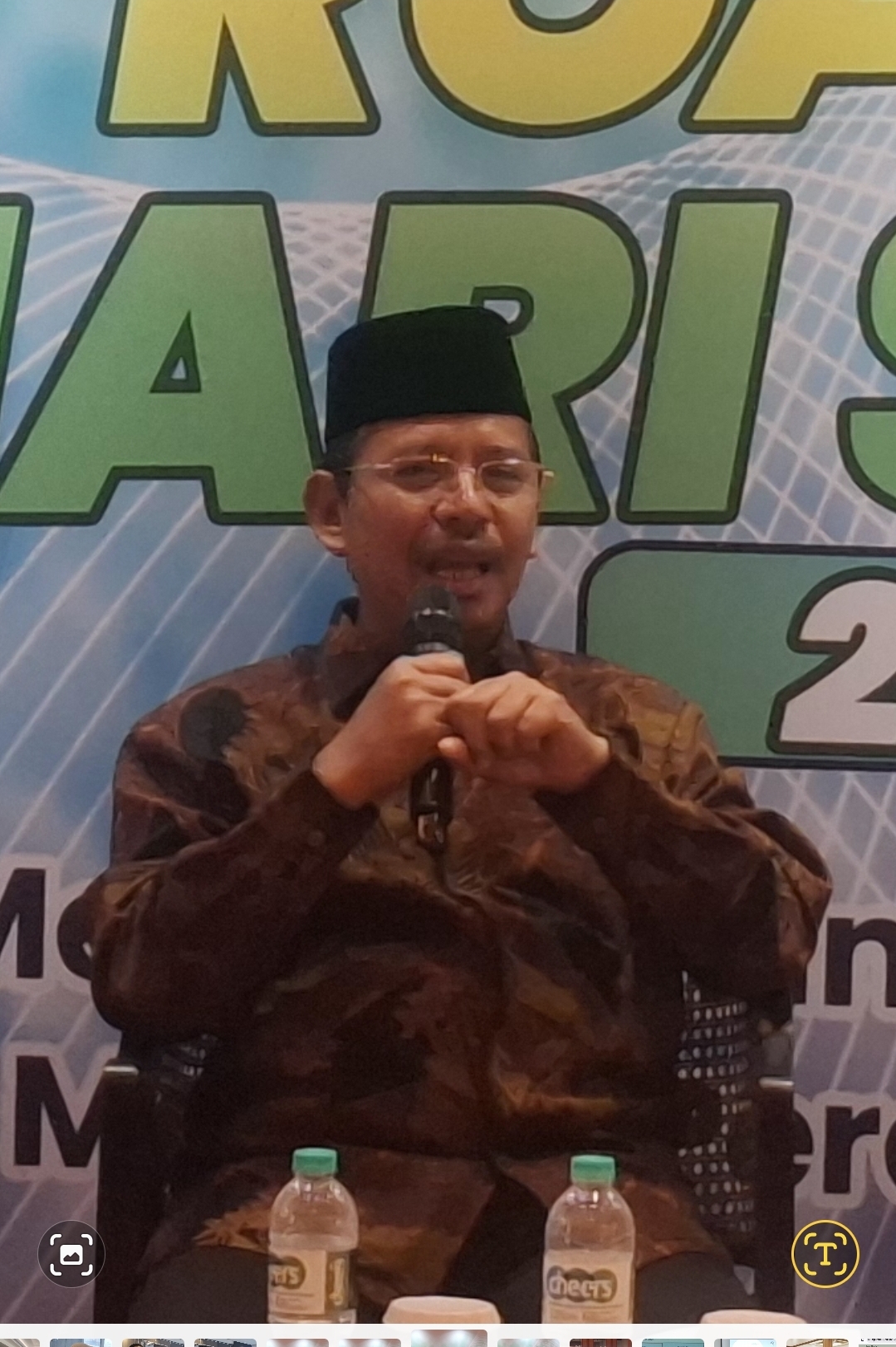Oleh Shohibul Anshor Siregar
Di bawah kepemimpinan yang berpotensi memiliki kecenderungan populis, kembalinya figur militer ke dalam posisi strategis sipil, serta wacana pembentukan unit-unit baru dengan fungsi non-militer, memunculkan pertanyaan kritis tentang arah dan keberlanjutan reformasi hubungan sipil-militer
Analisis komparatif mengenai fenomena tendensi militeristik dalam praktik pemerintahan menyajikan sebuah tantangan konseptual yang mendalam bagi studi demokrasi kontemporer. Dengan menempatkan studi kasus Indonesia dalam konteks teori hubungan sipil-militer global, kajian ini berupaya membedah sebuah gejala yang semakin lazim: menguatnya otoritarianisme sipil yang memanfaatkan dan menginstrumentalisasi institusi militer untuk agenda politik partikular.
Berbeda secara fundamental dari rezim militer tradisional yang dipimpin oleh junta atau dewan perwira, fenomena ini berlangsung di bawah fasad pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Penempatan personel militer aktif maupun purnawirawan di jabatan-jabatan strategis sipil, pembentukan unit-unit militer untuk menjalankan urusan non-pertahanan, serta penggunaan narasi populis-nasionalis untuk menjustifikasi tindakan tersebut, berfungsi sebagai indikator utama dari erosi supremasi sipil.
Untuk memahami dinamika ini, analisis akan melacak akar historis keterlibatan militer yang mengakar kuat dalam politik Indonesia, mulai dari mobilisasi politiknya di era Orde Lama, pelembagaan Dwi-Fungsi ABRI di era Orde Baru, hingga pergulatan demiliterisasi pasca-Reformasi 1998. Kajian ini akan memperbandingkan visi para tokoh kunci yang membentuk doktrin militer Indonesia, terutama antara konsepsi “Jalan Tengah” dari Abdul Haris Nasution dan implementasinya yang dieksploitasi oleh Soeharto menjadi aparatus kekuasaan otoriter.
Dengan menempatkan fenomena kontemporer ini dalam dialog dengan tren serupa di negara-negara yang dipimpin oleh figur populis seperti Turki, Filipina, dan Brasil, analisis ini menyoroti bahaya potensial yang inheren terhadap konsolidasi demokrasi. Pada akhirnya, kajian ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan sipil yang efektif dan kewaspadaan institusional dalam melawan ancaman otoritarianisme yang disamarkan dalam bentuk populisme, sebuah ancaman yang tidak hanya mengikis institusi demokrasi tetapi juga profesionalisme militer itu sendiri.
Konsolidasi demokrasi pasca-otoritarianisme sering kali diuji oleh relasi sipil-militer yang rumit dan penuh ketegangan. Dalam kanon teori politik modern, supremasi sipil atas militer adalah prasyarat fundamental bagi berfungsinya sebuah demokrasi liberal yang stabil dan terkonsolidasi. Prinsip ini mengacu pada sebuah doktrin di mana tanggung jawab utama dan otoritas final untuk pengambilan keputusan strategis negara—terutama yang berkaitan dengan kebijakan pertahanan dan keamanan—berada di tangan otoritas sipil yang dipilih secara demokratis, bukan pada petinggi militer profesional.
Konsep ini, sebagaimana dirumuskan secara klasik oleh Samuel P. Huntington dalam karyanya The Soldier and the State (Huntington, 1957), dirancang untuk mencegah kondisi praetorianisme. Praetorianisme menggambarkan sebuah tatanan politik di mana militer menjadi aktor politik otonom yang dapat mengintervensi, mendominasi, atau bahkan menggulingkan pemerintahan sipil yang sah. Dengan demikian, supremasi sipil bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen kekerasan negara tetap menjadi alat yang tunduk pada kehendak politik yang legitim, bukan menjadi penentunya.
Namun, dalam beberapa dekade terakhir, bangkitnya pemimpin populis di berbagai belahan dunia telah memunculkan sebuah paradoks yang menantang asumsi-asumsi klasik ini. Alih-alih mereduksi atau membatasi peran militer sesuai dengan norma-norma demokrasi liberal, beberapa pemimpin sipil justru secara aktif memperkuat dan memperluas keterlibatan militer dalam ranah sipil.
Fenomena ini, yang dapat disebut sebagai militerisasi pemerintahan sipil, terwujud dalam berbagai bentuk: penempatan sejumlah besar perwira militer, baik aktif maupun purnawirawan, di posisi-posisi kunci dalam kabinet, birokrasi, dan badan usaha milik negara; pembentukan satuan tugas atau unit militer ad hoc untuk menangani masalah-masalah non-pertahanan seperti distribusi logistik, pembangunan infrastruktur, atau penegakan protokol kesehatan; dan penggunaan militer sebagai alat untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial-ekonomi yang kompleks.
Pola ini seringkali dibenarkan dengan narasi populis yang tajam, yang mengidentifikasi musuh-musuh internal atau eksternal yang kuat—seperti korupsi yang mengakar, kejahatan terorganisir, elite politik yang dekaden, atau ancaman ideologis asing—yang konon tidak dapat diatasi oleh birokrasi sipil yang lamban dan korup. Dalam narasi ini, militer diproyeksikan sebagai satu-satunya institusi yang efisien, disiplin, patriotik, dan tidak tercemar oleh politik, menjadikannya instrumen yang ideal bagi pemimpin populis untuk mewujudkan “kehendak rakyat” secara langsung. Studi kasus Indonesia menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Pasca-Reformasi 1998, Indonesia telah melalui sebuah proses demiliterisasi yang monumental, berupaya keras untuk menjauhkan militer dari arena politik dan menghapus konsep Dwi-Fungsi ABRI yang telah menjadi ciri khas rezim otoritarian Orde Baru.
Namun, di bawah kepemimpinan yang berpotensi memiliki kecenderungan populis, kembalinya figur-figur militer ke dalam posisi-posisi strategis sipil, serta wacana pembentukan unit-unit baru dengan fungsi non-militer, memunculkan pertanyaan kritis tentang arah dan keberlanjutan reformasi hubungan sipil-militer. Artikel ini menganalisis fenomena kontemporer tersebut, membandingkannya dengan tren serupa di negara demokrasi lain, dan menempatkannya dalam konteks panjang sejarah politik militer Indonesia yang unik dan kompleks.
Analisis klasik Samuel Huntington (1957) membedakan dua model ideal kontrol sipil atas militer. Model pertama, Kontrol Sipil Objektif, bertujuan untuk memaksimalkan profesionalisme militer. Model ini mendorong militer untuk menjadi sebuah institusi yang sangat profesional, hierarkis, apolitis, dan otonom dalam lingkup keahliannya yang spesifik: pengelolaan kekerasan. Militer sepenuhnya tunduk pada otoritas sipil dalam penentuan tujuan-tujuan politik, namun ia mempertahankan otonomi profesional yang luas dalam menjalankan tugas-tugas pertahanan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah militer yang ahli dalam bertarung dan secara politik netral, sehingga meminimalkan insentif dan kemampuannya untuk melakukan intervensi politik.
Model kedua, Kontrol Sipil Subjektif, sebaliknya, berupaya memaksimalkan kekuasaan sipil dengan cara mengintervensi urusan internal militer. Dalam model ini, pemimpin sipil berusaha untuk memastikan loyalitas militer bukan melalui penghormatan terhadap prinsip-prinsip konstitusional, melainkan melalui loyalitas personal atau ideologis.
Hal ini seringkali dilakukan dengan cara mempolitisasi proses promosi perwira, menempatkan individu-individu yang loyal secara politik di posisi-posisi komando kunci, tanpa memandang kompetensi profesional mereka. Model ini cenderung mempolitisasi militer, mengubahnya menjadi alat faksional dari rezim yang berkuasa, dan berisiko tinggi mengikis profesionalisme, netralitas, dan kohesi internal angkatan bersenjata.
Fenomena yang terjadi di Indonesia dan negara-negara populis lainnya, di mana seorang pemimpin sipil secara sengaja menempatkan personel militer di jabatan-jabatan kunci untuk memastikan loyalitas dan efektivitas implementasi kebijakan, lebih mendekati bentuk Kontrol Sipil Subjektif. Ini berbeda secara fundamental dengan konsep Dwi-Fungsi ABRI, sebuah institusionalisasi peran politik militer yang sah secara doktrinal. Fenomena kontemporer ini lebih mengarah pada instrumentalisasi militer oleh elite sipil untuk tujuan-tujuan partikular.
Kerangka Huntington ini dapat diperkaya dengan konsep “prerogatif militer” yang dikembangkan oleh Alfred Stepan (Stepan, 1988). Prerogatif militer merujuk pada hak-hak dan kekuasaan formal maupun informal yang dimiliki oleh institusi militer yang tidak tunduk pada akuntabilitas demokratis, bahkan dalam sebuah rezim sipil.
Prerogatif ini dapat mencakup peran militer dalam intelijen internal, keterlibatan dalam perusahaan-perusahaan ekonomi, otonomi atas anggaran pertahanan, atau peran dalam sistem peradilan. Konsep ini sangat berguna untuk menganalisis kasus Indonesia, di mana meskipun peran politik formal militer telah dihapus, berbagai prerogatif—seperti struktur komando teritorial (Koter) yang paralel dengan administrasi sipil hingga ke tingkat desa—masih bertahan dan menyediakan landasan institusional bagi pengaruh militer di luar ranah pertahanan.
Keterlibatan militer dalam politik tidak dimulai pada era Reformasi atau Orde Baru, melainkan berakar jauh pada periode revolusi kemerdekaan. Pada masa Orde Lama, militer telah memainkan peran signifikan dalam politik. Presiden Soekarno, dengan ideologi “Nasakom”-nya (Nasionalisme, Agama, Komunisme), berusaha menyeimbangkan kekuatan-kekuatan politik utama: militer, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan dirinya sendiri.
Namun, militer, yang lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan, telah memiliki legitimasi politik yang kuat dan otonom. Mobilisasi mereka untuk mengatasi berbagai pemberontakan regional, seperti PRRI/Permesta, dan untuk menjalankan kampanye-kampanye nasionalis seperti Trikora (1961-1962) untuk merebut Irian Barat dan Dwikora (1964) untuk konfrontasi dengan Malaysia, memberikan militer peran sentral dalam urusan negara dan memperkuat posisi politik mereka jauh di luar fungsi pertahanan semata. Hal ini menjadi fondasi awal bagi pelembagaan peran politik militer di masa depan.
Dalam konteks inilah lahir dua visi yang berbeda dan saling bersaing mengenai peran militer, yang dipersonifikasikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution dan Jenderal Soeharto. Nasution, yang prihatin dengan potensi destabilisasi akibat intervensi militer yang tidak terstruktur, merumuskan doktrin “Jalan Tengah” pada akhir dekade 1950-an. Visi Nasution didorong oleh keinginan untuk memberikan militer sebuah peran politik yang formal dan terlembaga, agar militer tidak lagi menjadi kekuatan politik gelap di belakang layar yang berpotensi melakukan kudeta, seperti yang ia saksikan di negara-negara tetangga (Nasution, 1965).
Ia memandang militer bukan hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai “kekuatan sosial-politik” yang memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah sebuah upaya teoretis untuk mengkanalisasi dan mengendalikan energi politik militer di dalam sebuah kerangka konstitusional, dengan harapan dapat mencegah praetorianisme yang liar.
Visi teoretis Nasution ini dieksploitasi dan diubah secara fundamental oleh Soeharto setelah ia merebut kekuasaan pada tahun 1966. Doktrin “Jalan Tengah” ditransformasikan menjadi Dwi-Fungsi ABRI, yang implementasinya di bawah rezim Orde Baru jauh melampaui konsep awal Nasution. Soeharto memanfaatkan Dwi-Fungsi bukan sebagai mekanisme keseimbangan, melainkan sebagai instrumen utama untuk membangun dan melanggengkan rezim otoriter-birokratiknya.
Militer ditempatkan di setiap sektor pemerintahan, ekonomi, dan sosial, mulai dari posisi gubernur, bupati, dan kepala desa, hingga direksi BUMN, duta besar, dan bahkan hakim agung (Crouch, 1978). Alih-alih menjadi kekuatan politik yang seimbang, militer justru menjadi tulang punggung rezim dan alat utama bagi Soeharto untuk mempertahankan kekuasaan, mengontrol masyarakat, dan menekan segala bentuk oposisi. Visi Soeharto adalah menjadikan militer sebagai instrumen kekuasaan personalnya, sebuah penyimpangan total dari konsep “Jalan Tengah” Nasution yang berusaha menemukan tempat yang sah dan terbatas bagi militer di dalam sistem politik.
Penulis adalah Dosen Fisip UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS).
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.