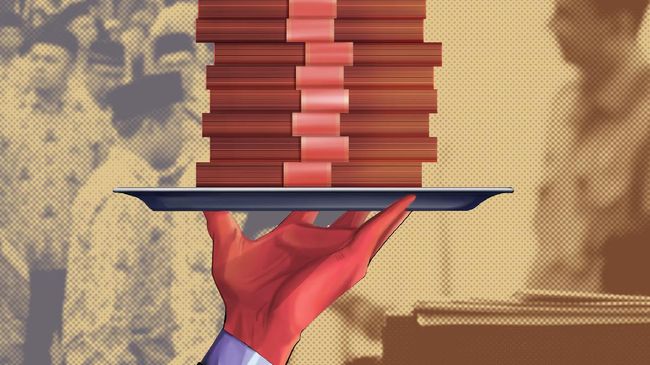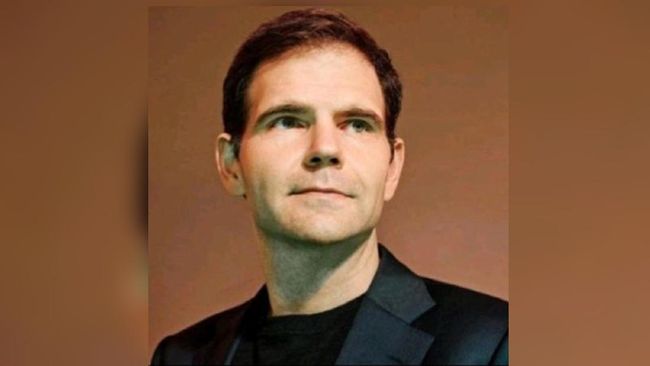Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945 telah memberikan panduan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal ini dijadikan sebagai dasar dari kewajiban negara untuk melindungi kelompok rentan dan mengalami marjinalisasi seperti perempuan, disabilitas, dan masyarakat hukum adat.
Dalam konteks penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan, pemerintah melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 meratifikasi Convention on the Rights of Person With Disability (CRPD) yang kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD). Kedua instrumen hukum tersebut dijadikan sebagai dasar penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak disabilitas dengan mengadopsi model pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM).
Maksud dari pendekatan model HAM dalam konteks disabilitas berarti disabilitas dipandang sebagai bagian dari keragaman manusia dalam konteks kemasyarakatan. Model pendekatan ini juga memandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan individu nondisabilitas lainnya.
Ciri terpenting dari model pendekatan HAM menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas oleh negara sembari mendorong aktif partisipasi penuh penyandang disabilitas di segala bidang seperti pendidikan, pekerjaan, politik, ekonomi, dan lain-lain.
Pendekatan ini sejalan dengan konsep affirmative action yang telah hadir terlebih dahulu. Affirmative action merupakan upaya sementara yang dilakukan untuk mendorong kesempatan yang seluas-luasnya bagi kelompok rentan untuk mengembangkan dirinya dan mendapatkan akses, terutama dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan politik. Langkah ini perlu dilakukan guna mendorong partisipasi yang setara bagi kelompok rentan, termasuk pula penyandang disabilitas.
Contoh konkret dalam konteks disabilitas ialah terdapat kuota khusus bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan bekerja sebesar dua persen di instansi pemerintah dan satu persen di instansi swasta serta pemberian konsesi berupa tarif khusus bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik.
Konsesi Sebagai Instrumen Kebijakan
Secara umum, konsesi dapat diartikan sebagai pemberian izin, hak, atau keringanan khusus kepada individu atau kelompok tertentu oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Dalam konteks penyandang disabilitas, konsesi bermakna serangkaian penyesuaian, kemudahan, atau perlakuan khusus yang diberikan untuk mengatasi hambatan dan memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara setara dalam setiap aspek kehidupan.
UUPD kemudian mendefinisikan konsesi sebagai segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau seseorang berdasarkan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.
Sebagai gambaran, seorang disabilitas biasanya membutuhkan extra cost (tambahan biaya) untuk melakukan aktivitas dan perannya sehari-hari. Hasil penelitian yang dilakukan oleh National Disability Institute di Amerika Serikat pada tahun 2017, penyandang disabilitas usia 18-60 tahun membutuhkan tambahan biaya sekitar 17-20 persen lebih banyak dibanding non-disabilitas.
Tambahan biaya tersebut merupakan hasil akumulasi dari tambahan kebutuhan bagi disabilitas, misalnya kebutuhan akan pendampingan dalam melakukan suatu aktivitas, alat bantu tertentu, dan intervensi obat-obatan.
Padahal, sebagaimana data Bappenas per tahun 2025, ada sekitar 11,46 persen penyandang disabilitas yang berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah tersebut lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,57 persen.
Terbaru, penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) pada tahun ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah sudah memiliki program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi), namun kondisi tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dengan disabilitas.
Lebih jauh, dalam hasil penelitian tersebut menunjukkan fakta bahwa rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas lebih rentan sekaligus memiliki probabilitas peningkatan kemiskinan secara multidimensional, baik dari segi angka kemiskinan maupun intensitas deprivasi.
Oleh karenanya, peran negara dalam menyediakan aturan yang mendorong konsesi bagi penyandang disabilitas sangat penting. Konsesi di sini bukan berarti pengistimewaan terhadap hak, tetapi mendorong bagaimana kelompok disabilitas mendapatkan kemudahan akses untuk mendapatkan haknya.
Implementasi Konsesi Disabilitas
UUPD sejatinya telah menggariskan 22 hak yang perlu dipenuhi oleh negara. Dari 22 hak tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tujuh bagian yakni: eksistensi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pelayanan publik, serta satu klasifikasi khusus untuk perempuan dan anak.
Sejumlah peraturan turunan UUPD pun sudah hampir semuanya diundangkan. Tercatat hingga saat ini sudah ada sepuluh regulasi turunan UUPD di tingkat peraturan pemerintah yakni sebanyak tujuh dan tiga sisanya berupa Peraturan Presiden.
Namun, hingga saat ini, peraturan pemerintah yang khusus mengatur mengenai konsesi penyandang disabilitas belum pernah diundangkan. Padahal, sudah hampir berjalan tiga bulan terhitung mulai dari Maret 2025 aturan ini sudah dalam masa harmonisasi.
Kehadiran PP Konsesi Disabilitas menjadi amat sangat penting karena sesuai amanat dari UUPD memberikan waktu dua tahun untuk segera mengundangkan seluruh aturan turunan dari UUPD. Jika UUPD diundangkan sejak 2016, maka sudah tujuh tahun kekosongan hukum akibat belum diundangkannya aturan mengenai konsesi penyandang disabilitas.
Hal ini ditambah dengan adanya restukturisasi khususnya di beberapa kementerian/lembaga sehingga menyebabkan proses birokrasi akan cenderung terhambat. Sebagai gambaran, sejatinya PP Konsesi yang juga mengatur insentif bagi perusahaan sudah dalam proses harmonisasi di awal tahun 2025.
Kendati begitu, restrukturisasi di dalam Kementerian Keuangan yang menyebarkan fungsi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai salah satu leading sector ke beberapa direktorat dan kedeputian menyebabkan langkah-langkah penyusunan harus menyesuaikan kembali baik ritme, alur birokrasi, maupun pendekatan advokasi yang dilakukan.
Memang, dalam praktiknya konsesi sudah diimplementasikan dalam beberapa layanan publik. Sebagai contoh, dalam mengakses Kereta Api Jarak Jauh, penyandang disabilitas mendapatkan potongan sebesar 20 persen. Di tingkat daerah misalnya, bagi penyandang disabilitas dapat menggunakan transportasi publik secara gratis dan mudah diakses dengan menggunakan kartu disabilitas.
Kendati begitu, PP Konsesi akan menjadi dasar kewajiban untuk menyediakan pelayanan bagi disabilitas utamanya dalam mengakses layanan publik seperti dalam hal mengakses kesehatan, transportasi umum, dan fasilitas lainnya dengan adanya penyesuaian harga.
PP konsesi juga dapat menjadi panduan pemberian insentif bagi pihak swasta yang mendorong budaya inklusivitas baik berupa penyediaan akomodasi yang layak dan penyesuaian harga dalam penggunaan layanan untuk penyandang disabilitas.
Secara teknokratik, hal demikian membutuhkan banyak tantangan yang menjadi alasan mengapa soal konsesi belum juga diundangkan hingga saat ini. Persoalan pertama ialah mengenai data penyandang disabilitas yang tidak terpadu. Masalah pendataan amat sangat penting karena berkaitan dengan tepat sasaran atau tidaknya suatu program.
Masalah kedua ialah berkenaan dengan kapasitas fiskal, utamanya dari pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan pembiayaan. Nyatanya, saat proses pembahasan pun terdapat saling lempar kepentingan pembebanan pembiayaan dari satu instansi dengan instansi lainnya. Selain saling lempar tanggung jawab, satu hal yang menjadi sorotan ialah mengenai berapa persen tarif konsesi yang diberikan dari tiap-tiap layanan publik.
Pun apabila PP ini diundangkan, masih panjang jalan untuk menerapkan konsesi. Sebab dalam beberapa sektor, pemberian konsesi perlu untuk diturunkan ke dalam aturan di tingkat peraturan menteri. Dalam aturan di level peraturan menteri inilah yang mengatur teknis penerapan konsesi termasuk pula di dalamnya pihak yang memiliki kewenangan eksekusi, besaran konsesi, serta tata cara pemberlakuan konsesi.
Namun apapun itu, segala upaya untuk mendorong keberadaan atau tidaknya konsesi bagi penyandang disabilitas amat erat kaitannya dengan 'political will' dan kemampuan leadership pemerintahan itu sendiri. Publik akan menjadi saksi bagaimana prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mendorong kesetaraan bagi penyandang disabilitas.
Terlebih, perhatian terhadap penyandang disabilitas menjadi salah satu fokus kepemimpinan Presiden Prabowo dalam masa jabatannya. Hal demikian tercantum dalam Asta Cita keempat pemerintahan Prabowo-Gibran yakni: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Maka dari itu, patut ditunggu sekaligus dapat pula mempertanyakan bagaimana pemerintahan Prabowo-Gibran di waktu yang tersisa dapat benar-benar serius untuk menjalankan program besar dalam pemerintahannya dalam bentuk Asta Cita keempat bagi penyandang disabilitas.
(miq/miq)

 2 months ago
25
2 months ago
25