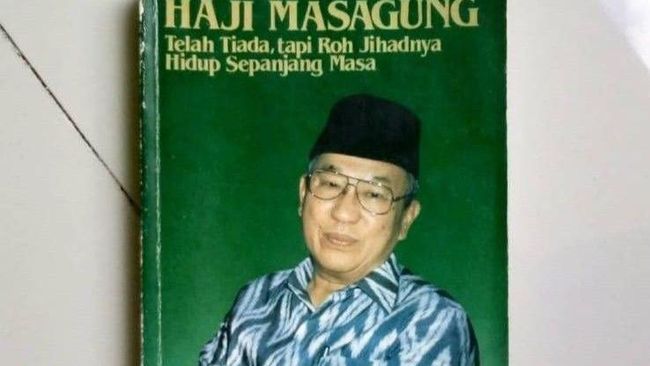Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Pengantar Serial Matinya Ilmu Ekonomi: Di tengah dunia yang terus bergerak cepat namun terasa semakin kosong, kami mengajak anda untuk berhenti sejenak, untuk menoleh ke belakang, menatap ke dalam, dan melihat ke depan. Serial Matinya Ilmu Ekonomi bukan sekadar kumpulan kritik.
Ia adalah upaya jujur untuk memandang ilmu ekonomi dari sudut yang jarang diterangi: dari sisi yang tidak selalu efisien, tidak selalu rasional, tapi sepenuhnya manusiawi.
Di sini, kami ingin menyegarkan kembali ingatan kita akan mengapa ekonomi ada, bukan hanya sebagai alat hitung, tetapi sebagai cermin kegembiraan, pencapaian, penderitaan, ketimpangan, dan harapan zaman. Adapun Episode Ke-12 ini kami beri judul: "Senyum Pembangunan". Semoga bermanfaat, Selamat Menikmati.
---
Jehan masuk ke galeri itu dengan langkah cepat, seperti seseorang yang terbiasa mengejar deadline laporan pasar. Tas selempangnya berat: berisi kalkulator keuangan, catatan statistik, dan satu map berdebu berjudul APBN Outlook 2026. Ia tak pernah mengira bahwa kunjungannya ke National Gallery of Victoria akan berakhir menjadi salah satu pertemuan paling penting dalam hidupnya.
Ia mendengar rumor dari teman-temannya yang kuliah di Melbourne: "Coba mampir ke NGV, di sana ada pameran foto-foto tua yang cantik." Jehan, yang terbiasa berpikir dalam angka, tidak terlalu peduli pada hal-hal cantik. Tapi ia punya waktu senggang sore itu; kelasnya selesai lebih cepat. Ia berjalan ke galeri itu tanpa tujuan jelas.
Ketika masuk, udara sejuk menyambutnya. Aroma halus kayu tua dan karpet museum mengisi ruangan. Lampu-lampu putih lembut menyinari foto-foto hitam putih di dinding, potret keluarga dari akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20.
Jehan mendekati salah satu foto: sebuah keluarga kecil dari tahun 1900-an-ayah berjenggot rapi, ibu bergaun panjang, dua anak dengan rambut dikuncir. Tidak ada yang tersenyum. Semuanya menatap kamera seperti menatap peradilan akhir zaman: wajah tegang, bibir terkunci, mata muram tanpa harapan.
Jehan mengerutkan dahi. Pameran ini terasa aneh. Seolah-olah manusia yang ada di foto itu bukan jenis yang sama dengan manusia hari ini. Tiba-tiba, Suara lembut datang dari sampingnya. "Nak, pernahkah kamu memperhatikan wajah orang di foto-foto lama?" Jehan menoleh.
Di sampingnya berdiri seorang pria sepuh, berambut putih keperakan, wajah teduh dengan garis-garis usia yang tidak melelahkan, melainkan menyimpan cerita panjang. Ia memakai jas linen coklat muda, dan kacamata kecil bertengger di ujung hidungnya.
Jehan mengangguk sopan. "Ya, Pak. Mereka semua... kelihatan sedih?" Pria itu tersenyum. Senyum yang tidak terburu-buru. Senyum yang seperti terbuat dari kebijaksanaan. "Perkenalkan. Saya Wicaksana Adiwinata. Tinggal di Melbourne sudah hampir 40 tahun. Saya... seorang sejarawan, kalau boleh sedikit sombong."
Jehan tertawa kecil. Nama itu mengingatkannya pada nama-nama tokoh dalam serat-serat Jawa "Nak, boleh saya tanya?" "Silakan, Pak." "Dari fakultas apa kamu?" "Ekonomi, Pak. Baru S-2." "Hmm," katanya sambil menyipitkan mata nakal, "pantas kamu melihat dunia lewat angka."
Pak Wicaksana berjalan pelan ke foto berikutnya, foto tahun 2025 yang dipasang bersebelahan. Foto itu penuh warna: sekelompok remaja di taman kota Melbourne, tertawa lebar sambil berpose bersama kamera digital. Gigi terlihat. Mata berbinar. Senyum-senyum tanpa beban. Kontrasnya menyakitkan.
"Coba lihat dua foto ini," kata Pak Wicaksana, "Dulu manusia menatap masa depan dengan waspada. Sekarang manusia menatap kamera dengan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja."
Jehan tertegun. Ia hanya bisa melihat perbedaan teknis. "Mungkin... karena teknologi kamera, Pak?" Jehan mencoba berkelakar." Dulu shutter speed lama, sekarang cepat." Pak Wicaksana menoleh pelan. "Itu jawaban mahasiswa ekonomi. Tapi bukan jawaban sejarah."
Jehan terdiam. Ada sesuatu dalam suara lelaki tua itu, seperti pintu yang dibuka perlahan. Pak Wicaksana mendekatkan wajahnya ke foto tua itu. "Tidak, nak. Bukan itu alasan utamanya.""Lalu apa, Pak?" Sejarawan itu menepuk bahu Jehan perlahan, seolah mengajak seseorang masuk ke sebuah ruangan penuh rahasia.
"Wajah manusia berubah karena pembangunan. Senyum adalah revolusi sosial terbesar yang pernah diciptakan manusia." Ia berhenti sejenak, menatap Jehan lembut. "Dan kamu... sebagai ekonom, wajib memahami kisah itu."
Pak Wicaksana berjalan pelan ke sebuah panel besar yang berjudul The Changing Face of France. Di sana, foto-foto dari berbagai era dipasang berurutan seperti garis waktu: 1850, 1880, 1900, 1920, 1960, hingga 2020. Jehan mengikuti dari belakang, membawa rasa ingin tahu seperti membawa sebuah bejana kosong.
Pak Wicaksana berhenti di depan foto pertama: seorang pria berpakaian ala Victorian, berdiri kaku, tak bergerak, menatap lurus. Bahkan helai rambutnya tampak tidak berani berubah arah.
"Nak, dulu kamera bekerja seperti ritual," katanya lembut. "Shutter speed-nya lambat sekali. Orang harus berdiri diam selama puluhan detik. Dan kamu tentu tahu, senyum bukan sesuatu yang stabil. Dia terlalu rapuh. Terlalu cepat runtuh."
Jehan mengangguk. "Jadi orang tidak tersenyum karena teknis kamera?". "Secara permukaan, ya," jawab Pak Wicaksana. "Tetapi perhatikan baik-baik." Ia mengangkat telapak tangan, menunjuk ke mata pria dalam foto itu."Mata manusia zaman itu punya cerita yang jauh lebih gelap dari sekadar shutter speed."
Ia melanjutkan, suaranya seperti membaca manuskrip lama: "Waktu itu mahal, nak. Kesempatan untuk memejamkan beban sehari-hari hampir tidak ada. Berfoto adalah momen yang sangat serius. Seolah dunia hanya memberikan satu kesempatan untuk mengabadikan keberadaan."
"Teknologi kamera berubah," kata Pak Wicaksana, "Tapi perubahan wajah manusia tidak dimulai dari teknologi. Teknologi hanya menangkap apa yang sesungguhnya terjadi di dalam jiwa zaman." Ia melirik Jehan sambil tersenyum kecil: "Senyum adalah indikator batin kolektif. Kamera hanya cermin."
Mereka berjalan ke foto berikutnya: para buruh tambang Inggris tahun 1890-an. Wajah hitam penuh debu batu bara, mata seperti dua titik putih yang kehilangan keyakinan. "Lihat ini," kata Pak Wicaksana. "Senyum di sini akan tampak seperti penghinaan terhadap kenyataan."
Jehan menahan napas. Ia merasakan sesuatu yang mirip rasa takut, walau ia hanya melihat foto. "Di abad ke-19," lanjut sang sejarawan, "manusia bekerja dengan otot, bukan mesin. Pekerjaan adalah perpanjangan dari penderitaan."
Ia menghitung dengan jarinya: kecelakaan kerja setiap hari, umur pendek, tidak ada asuransi, tidak ada hak cuti, tidak ada upah minimum, jam kerja 12-16 jam, dan kematian bayi yang tinggi.
"Bagaimana manusia bisa tersenyum," katanya, "Ketika dunia menuntut seluruh tenaga hanya untuk bertahan hidup sampai senja?" Jehan menunduk. "Di Jawa juga begitu, Pak?"
"Oh, lebih tua lagi," jawabnya. "Bayangkan petani yang hidup dalam tanam paksa. Bayangkan rakyat kecil yang melihat tuannya datang. Senyum mereka... bukan senyum. Itu survival."
Ia menatap jauh ke foto itu. "Manusia dulu hidup dalam defisit energi." "Dalam defisit aman.", "Dalam defisit martabat.", "Dalam defisit harapan."
Pak Wicaksana memalingkan wajahnya ke foto tahun 2025, remaja tertawa di pinggir sungai Yarra. "Dan ketika semua defisit itu pelan-pelan berubah menjadi surplus," katanya, "Wajah manusia ikut berubah."
Jehan tersentak. "Senyum itu, nak," kata Pak Wicaksana, "adalah luxury good yang hanya bisa dibeli ketika sebuah masyarakat telah melewati ambang penderitaan struktural." Ia menambahkan, dengan suara hampir berbisik:
"Senyum adalah indikator paling tua dari pembangunan."
Mereka berjalan menuju satu sudut galeri di mana terdapat sebuah instalasi seni: lingkaran besar berisi serangkaian potret manusia dari berbagai decade, dari wajah kaku 1880-an hingga wajah generasi selfie 2020-an.
Lampu kuning keemasan dari atas jatuh lembut, membuat wajah-wajah itu tampak seperti sedang menunggu percakapan. Jehan berdiri dekat dengan foto seorang ibu rumah tangga tahun 1930-an. Wajahnya tegas, tangan menggenggam apron. Tak ada senyum, hanya keteguhan.
Pak Wicaksana berhenti tepat di sampingnya. "Jehan," katanya, "banyak ekonom bicara tentang surplus dalam konteks produksi dan konsumsi. Tetapi ada surplus yang jauh lebih purba, lebih menentukan wajah manusia daripada surplus beras atau baja."
Ia mengangkat empat jarinya perlahan. "Senyum itu muncul ketika empat jenis surplus ini ada dalam masyarakat. Dan tanpa empat ini, PDB setinggi apa pun tidak akan menghasilkan wajah yang tenteram."
1. Surplus Energi: Wajah yang Tidak Lagi Lelah.
Pak Wicaksana menunjuk foto seorang buruh pabrik baja tahun 1910. "Dulu, kerja fisik adalah inti kehidupan. Ototlah yang menyalakan dunia. Setiap jam kerja adalah jam kematian yang dipercepat."
Jehan menelan ludah. "Ketika seluruh energimu diarahkan untuk bertahan hidup... tidak ada sisa untuk tersenyum." Lalu sejarawan itu menunjuk foto perempuan modern di sebuah kafe, tersenyum sambil membaca buku.
"Sekarang, tubuh manusia tidak lagi mesin produksi. Energi manusia perlahan dikembalikan untuk hidup, bukan sekadar bertahan." Ia menyentuh bahu Jehan. "Senyum butuh energi. Dan energi itu baru muncul ketika pekerjaan tidak lagi mencuri seluruh hidupmu."
2. Surplus Waktu: Ketika Nafas Manusia Tidak Lagi Dikejar Kehidupan
Mereka beralih ke panel tentang sejarah waktu kerja. Ada infografik kecil yang menunjukkan jam kerja di abad ke-19: 14-16 jam per hari. "Jehan, kamu tahu kapan 'weekend' ditemukan?", Jehan menggeleng. "Tahun 1908, perlahan. Diberi oleh serikat pekerja, bukan oleh pasar."
Ia mendekat ke foto buruh Inggris tahun 1880, wajah penuh jelaga. "Dulu manusia tidak punya waktu luang. Tidak ada golden hour. Tidak ada duduk santai sambil menatap matahari tenggelam." "Tapi Pak," kata Jehan ragu, "Apa waktu senggang berhubungan dengan senyum?"
Pak Wicaksana tertawa kecil. "Justru itulah rahasianya!" Wajahnya bersinar ketika mengatakan ini: "Senyum adalah tanda waktu yang tidak terancam. Tanpa waktu, manusia tidak punya ruang untuk membiarkan wajahnya melunak." Ia mengibaratkan: "Senyum itu tumbuh di tanah jeda."
3. Surplus Aman: Ketika Ketakutan Tidak Lagi Mengisi Ruang Dalam
Di galeri berikutnya terdapat foto ruang bawah tanah yang digunakan sebagai tempat perlindungan bom pada Perang Dunia II. Pak Wicaksana berdiri lama di depan foto itu.
"Jehan... manusia itu hanya bisa tersenyum jika aman. Titik." "Ini hukum primitif. Jika ada ancaman macan, perang, utang, atasan kejam, wajah akan mengencang seperti kulit kendang." Ia menatap mata Jehan dalam-dalam.
"Di dunia feodal, rakyat takut pada raja. Di dunia kolonial, rakyat takut pada penjajah,Di dunia industrial awal, pekerja takut pada majikan." "Jika rasa takut menguasai hidup, senyum mati." Jehan merasakan udara galeri menjadi lebih berat.
"Dan inilah yang banyak dilupakan para ekonom," lanjutnya. "Kamu bisa naikkan upah, bisa turunkan inflasi, bisa bangun pabrik-tetapi jika masyarakat tidak merasa aman... tidak ada satu pun kebijakan yang akan menciptakan wajah yang damai."
4. Surplus Martabat: Ketika Manusia Tidak Lagi Dianggap Alat
Mereka berjalan menuju instalasi terakhir-foto-foto buruh pabrik tahun 1900 dibandingkan dengan pekerja modern di kantor teknologi. "Senyum hanya lahir dari martabat, Jehan." "Martabat?", "Ya. Dignity."
Ia menatap foto seorang kuli di pelabuhan tua Semarang, tahun 1920. Punggung bungkuk, kulit terbakar matahari, kepalanya menunduk pada kamera. "Lihat ini. Ia bukan manusia dalam sistem itu. Ia adalah tenaga, Ia adalah alat." "Kamu pernah melihat alat tersenyum?" Jehan menggeleng pelan.
"Ketika manusia tidak dihargai, tidak dianggap penting, tidak dihormati, sangat sulit bagi wajahnya untuk membuka diri." Lalu Pak Wicaksana mengajak Jehan memandang foto seorang perawat muda tahun 2020, tersenyum lembut setelah shift malam.
"Lihat ini. Di sini martabat hadir. Dia tahu bahwa pekerjaannya berarti.Bahwa hidupnya punya nilai." "Ketiadaan martabat merenggut senyum. Hadirnya martabat melahirkan senyum."
Pak Wicaksana mengulang empat jarinya, energy, waktu, keamanan, martabat. Ia memandang Jehan, wajahnya berubah serius. "Jehan, untuk memahami pembangunan, kamu harus berhenti melihat PDB sebagai tujuan."
"Pembangunan adalah proses panjang manusia memulihkan senyumnya.Karena senyum, nak... hanya lahir ketika sebuah masyarakat sudah melewati ambang penderitaan sejarahnya." Jehan merasakan ada sesuatu dalam dadanya, seolah konsep ekonomi yang selama ini ia pelajari... baru pertama kali punya wajah.
Pak Wicaksana mengajak Jehan ke sebuah ruangan lain di NGV, ruangan yang memamerkan potret bangsawan Eropa. Dinding-dindingnya dipenuhi lukisan besar: raja, ratu, adipati, paus, serta anak-anak bangsawan dengan baju sutra.
Semua wajah itu... sama. Tidak ada yang tersenyum. Jehan langsung menyadarinya. "Pak, di sini juga tidak ada yang tersenyum." "Ya," jawab Pak Wicaksana. "Itu bukan kebetulan. Itu struktur."
Pak Wicaksana menunjuk lukisan besar Raja Louis XIV. "Perhatikan wajahnya. Tegang, mulut rapat, mata lurus ke depan." "Kenapa tidak tersenyum, Pak? Apa bangsawan dulu memang pemarah?" Sejarawan itu tertawa kecil. "Tidak, nak. Mereka tidak boleh tersenyum." Jehan terdiam.
"Raja-raja Eropa hidup dalam politik jarak. Kekuasaan bekerja melalui rasa takut-penuh-hormat. Senyum memecah jarak itu. Senyum membuat raja tampak manusiawi, dan itu berbahaya."
Ia melanjutkan sambil berjalan ke lukisan lain. "Senyum adalah bahasa kesetaraan.Di dunia feodal, kesetaraan adalah ancaman." Jehan mengangguk pelan. Ia baru mengerti: wajah dingin itu bukan pilihan, melainkan instrumen politik.
"Senyum dianggap menurunkan martabat, menurunkan hierarki, membuka celah bagi rakyat untuk merasa setara." Ia menepuk dada Jehan dengan lembut. "Ingatlah, Jehan: kadang ketidaksenyuman adalah hasil dari desain kekuasaan, bukan kepribadian."
Mereka beralih ke sudut ruangan yang menampilkan seni dan artefak Jawa: keris, batik, dan sebuah potret tua bangsawan Mataram. Pak Wicaksana berdiri di depan potret itu lama-lama.Wajahnya seperti pulang ke masa kecilnya.
"Nak, saya lahir di Jogja. Di keraton, wajah itu adalah bahasa tersendiri." Ia menunjuk ke potret Pangeran Diponegoro.Wajah tegas, rahang kuat, mata dalam, tanpa senyum.
"Di Jawa, ada konsep yang disebut alusan. Wajah yang halus, terkendali, tidak meledak-ledak." "Raja Jawa tidak boleh tertawa lepas, apalagi sampai kelihatan gigi. Itu dianggap tidak bijaksana, tidak 'wisdom-like'." Jehan membayangkan suasana keraton-tenang, ritualistik, penuh harmoni yang ketat. "Pak, jadi raja Jawa juga... tidak boleh tersenyum?"
"Boleh," kata Pak Wicaksana, "tapi hanya sedikit. Senyum tipis. Senyum yang menyampaikan belas kasih, tetapi tetap menjaga jarak kosmis." Ia menirukan gaya itu: senyum kecil, hampir tidak terlihat.
"Itu disebut senyum sak madya. Tanda bahwa ia pemimpin, bukan teman. Bahwa ia melindungi, bukan sejajar." Jehan merasakan kegetiran di balik keindahan budaya itu. "Senyum Jawa yang halus itu indah, Jehan. Tetapi ia lahir dari struktur hierarki yang sangat ketat."
Pak Wicaksana mengajak Jehan mendekati potret seorang abdi dalem keraton, berbusana sederhana. "Perhatikan senyum ini." Jehan melihatnya: sebuah senyum lembut, tetapi bukan senyum bebas, lebih seperti senyum yang meminta izin.
"Rakyat kecil, nak, tersenyum untuk mengurangi ketegangan. Untuk menunjukkan hormat. Untuk meredakan amarah tuannya." Ia berkata pelan: "Ini adalah senyum bertahan hidup. Bukan senyum kebahagiaan."
Jehan menatap lama. "Di Jawa," lanjut Pak Wicaksana, "rakyat tersenyum ketika takut. Itu mekanisme sosial." "Senyum ini berbeda dengan senyum yang kita lihat di foto modern.Yang satu adalah senyum kompresi tekanan. Yang lain adalah senyum ekspansi jiwa."
Jehan menutup mata sejenak. Rasanya seperti ada pintu yang terbuka lebar, pintu yang menghubungkan ekonomi, budaya, dan psikologi sosial.
Sang sejarawan merangkum dengan sangat lembut: "Jehan, selama ribuan tahun, mayoritas manusia tidak punya hak untuk tersenyum. Senyum itu bukan sekadar ekspresi, itu adalah insinyur sosial."
Ia berbisik: "Ketika kamu melihat rakyat dan raja tersenyum bersama... itu adalah fenomena baru dalam sejarah dunia." Jehan menelan rasa haru yang tiba-tiba membesar. "Dan ketika kita bicara pembangunan, kita sebenarnya sedang bicara tentang bagaimana manusia... akhirnya memulihkan wajahnya."
Jehan mengikuti langkah Pak Wicaksana menuju ruangan pameran kontemporer. Di dindingnya terpampang foto ikonik: Raja Belanda, Willem-Alexander, menari bersama Armin van Buuren di Koningsdag.
Jehan menganga. "Raja... menari?" Pak Wicaksana tersenyum kecil.Dengan senyum yang seakan berkata: Nak, kamu sedang melihat sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam 1000 tahun sejarah kerajaan Eropa. "Ya, Jehan, raja menari. Dan bukan hanya menari. Ia tersenyum."
"Pada zaman feodal," kata Pak Wicaksana sambil menunjuk foto itu, "Kekuasaan dibangun di atas jarak, ketegangan, dan rasa takut." Raja tidak boleh bersenda gurau. Tidak boleh menari. Tidak boleh cengar-cengir di depan rakyat. "Jika jarak itu runtuh, kekuasaan dianggap runtuh." Jehan mengangguk.
"Tapi sekarang lihat." Ia menyorot foto raja yang tertawa lepas, tangan terangkat, disinari lampu LED festival EDM. "Raja kita hidup di zaman yang aman. Zaman stabilitas institusi, bukan stabilitas ketakutan."
"Raja bisa menari karena rakyat sudah tidak perlu tunduk lewat rasa takut." "Raja bisa tersenyum karena martabat rakyatnya sudah naik.""Dan ketika martabat rakyat naik, martabat raja justru tidak turun-ia ikut naik."Jehan merasa ada yang bergetar di dadanya. Ada sesuatu yang lembut tentang dunia yang menjadi lebih bersahabat.
Mereka berjalan ke instalasi seni berikutnya: sebuah robot industri yang sudah pensiun, kini menjadi karya seni modern. "Nak," kata Pak Wicaksana dengan suara yang lebih lirih,"perubahan wajah manusia sangat berkaitan dengan perubahan mesin-mesin di dunia."
Ia memandang robot tua itu dengan penuh hormat. "Dulu mesin perekonomian berbasis otot manusia. Dunia dibangun dengan tulang, darah, dan airmata." Ia menyebutnya: ekonomi batu bara, ekonomi peluh, ekonomi tangan, ekonomi luka.
"Buruh pabrik baja, buruh tambang batu bara, kuli pelabuhan, pekerja kebun tebu-mereka semua bekerja pada batas fisik bertahan hidup." Jehan mendengar suaranya seperti nyanyian duka untuk generasi yang tidak pernah diberi kesempatan tersenyum.
"Lalu dunia berubah." Mesin uap, kemudian listrik. Robot industri menggantikan bagian paling berbahaya dari pekerjaan manusia. Traktor menggantikan cangkul. Lift menggantikan 10 lantai tangga. AC menggantikan panas yang mencekik. Komputer menggantikan ribuan jam manual kerja. Otomasi menghapus risiko paling mematikan.
"Nak," bisik Pak Wicaksana, "ketika mesin mengambil risiko, manusia mendapat ruang untuk menjadi manusia." "Dan di ruang itulah... lahir senyum." Jehan terpaku saat sejarawan itu memegang kedua pundaknya.
"Jehan, dengarlah baik-baik." "Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia bisa bekerja tanpa hancur. Untuk pertama kalinya, pekerjaan tidak merampas wajah seseorang.Untuk pertama kalinya, orang tua pulang kerja dan masih punya energi untuk tersenyum kepada anaknya." Jehan menunduk, merasakan air hangat mengisi sudut matanya.
Pak Wicaksana melanjutkan, suaranya seperti serenade: "Dulu ayah-ayah kita pulang dengan wajah yang keras. Itu bukan karena mereka tidak menyayangi kita. Tetapi karena dunia membuat wajah mereka berat seperti besi."
Jehan menahan napas. Ia mengingat ayahnya sendiri, yang dulu pulang kerja dengan diam panjang. "Sekarang, meski dunia masih berat, banyak manusia punya kesempatan untuk pulang dengan wajah yang lebih ringan."
Pak Wicaksana kembali ke foto Raja Belanda yang menari. "Nak, lihat wajah rakyat yang menonton raja itu. Lihat mereka tertawa bersama. Tidak ada ketakutan.Tidak ada jarak." Itu revolusi sosial yang tak dilihat para ekonom.
"Dulu," katanya, "rakyat tidak boleh memandang raja. Sekarang raja memandang rakyat... dan tersenyum." Jehan tertegun. "Ini bukan sekadar budaya pop, bukan sekadar festival.Ini adalah rekonsiliasi panjang antara kekuasaan dan kemanusiaan."
Ia menunjuk foto itu sekali lagi: "Wajah manusia menjadi lebih ringan. Dan ketika wajah rakyat ringan, wajah raja pun ikut ringan." Sang sejarawan menutup bagian ini dengan sebuah kalimat yang membuat Jehan nyaris meneteskan air mata. "Jehan... pembangunan bukan jalan tol, Bukan gedung tinggi, Bukan inflasi rendah, Bukan pertumbuhan ekonomi." Ia mendekat, menatap mata Jehan.
"Pembangunan adalah seni meringankan wajah manusia. Ketika beban sejarah turun, ketika mesin mengambil alih bahaya, ketika negara tidak lagi memerintah lewat rasa takut, di sanalah muncul ruang paling suci dari peradaban..."
Ia berhenti sejenak. Suaranya turun menjadi bisikan: "...ruang untuk manusia tersenyum." Jehan menutup matanya. Di balik kelopak itu, ia merasakan dunia yang baru, dunia yang lebih lembut, dunia yang lebih indah, dunia yang lebih manusia.
Mereka berdiri di ruang terakhir: sebuah instalasi seni digital yang memproyeksikan ribuan wajah manusia dari berbagai belahan dunia, tertawa, menangis, bingung, tersipu, terkejut, tersenyum.
Cahaya lembut pantulannya jatuh ke wajah Jehan dan Pak Wicaksana. "Jehan," kata Pak Wicaksana pelan, "ilmu ekonomi adalah ilmu yang hebat. Tapi ia sering lupa bahwa manusia... bukan grafik."
Jehan terpaku pada wajah-wajah yang muncul: seorang ibu tertawa di Kerala; seorang anak kecil tersenyum malu di Kyoto; seorang petani tua di Flores tersenyum ke kamera; seorang perawat di London yang tersenyum meski matanya lelah.
Pak Wicaksana melanjutkan: "PDB itu penting. Tapi PDB tidak tahu rasanya pulang malam dan tidak sempat menatap wajah anak. Inflasi itu perlu diatur. Tapi inflasi tidak tahu rasanya kehilangan tawa istri karena ia terlalu capek bekerja."
Jehan menelan keras. Air hangat mulai menggenang di matanya. Pak Wicaksana menatapnya penuh simpati. "Banyak temanmu hari ini sibuk sampai wajahnya hilang, bukan?" Jehan mengangguk pelan. "Ibu bapakmu juga mungkin pulang dengan wajah yang tidak sempat istirahat? "Jehan membuang pandang, mencoba menyembunyikan air mata.
"Pak... iya." Suaranya patah. "Kenapa kita semua... begitu sibuk, begitu tertekan... padahal kita hidup di era yang seharusnya lebih ringan?" Pak Wicaksana tersenyum lembut. "Nak... karena ekonomi kita masih melihat manusia sebagai mesin produksi, bukan sebagai wajah yang harus dijaga."
"Dan tugasmu... sebagai ekonom muda... adalah membawa kembali wajah itu ke dalam rumusan pembangunan." Jehan mengusap matanya cepat-cepat, malu. Pak Wicaksana menepuk punggungnya. "Sudahlah, jangan sedih begitu. Nanti dikira saya lagi ceramah filsafat berat di museum," katanya sambil tertawa kecil.
Jehan ikut tertawa, walau air matanya belum sepenuhnya kering. "Di dunia ini, Jehan, kita butuh lebih sedikit grafik... dan lebih banyak tawa." Ia menambahkan, sambil mengangkat alis nakal: "Kalau perlu, kamu ajari teman-temanmu cara tersenyum lagi. Ekonom jarang tersenyum, kan? Itu masalah struktural!"
Jehan tertawa keras kali ini. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk NGV sore itu, wajah keduanya sama-sama ringan, seperti dua manusia yang baru saja memahami bahwa pembangunan terbaik... adalah pembangunan yang memulihkan wajah manusia.
(miq/miq)

 2 months ago
26
2 months ago
26