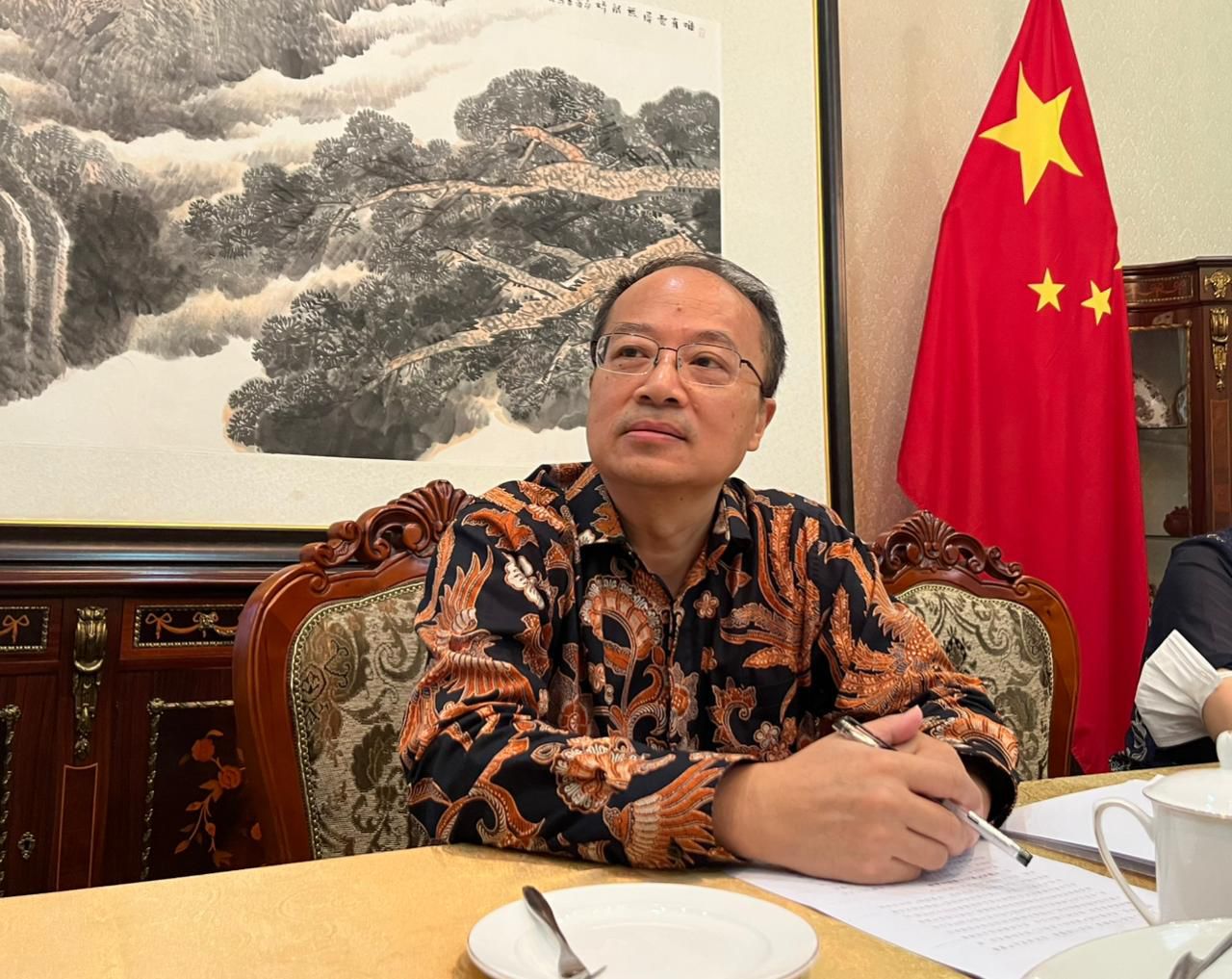Farid Wajdi
Farid Wajdi
Ukuran Font
Kecil Besar
14px
MEDAN (Waspada.id): Farid Wajdi selaku Founder Ethics of Care/Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, pada Senin(1/12/2025) menyampaikan, penetapan status bencana nasional adalah mandat konstitusi.
Disebutkan, dalam setiap jam yang berlalu, jumlah korban bertambah, wilayah terdampak melebar, dan bukti kerusakan makin telanjang.
Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN
Namun status bencana nasional belum juga muncul dari meja pemerintah pusat. Publik wajar mempertanyakan apa yang menghambat keputusan yang seharusnya menjadi refleks pertama negara ketika nyawa ribuan orang dipertaruhkan.
Situasi ini bukan hanya soal prosedur administratif, melainkan soal sensitivitas moral, keberanian politik, dan komitmen terhadap dasar konstitusional: melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.
Narasi resmi yang menyebut kondisi masih dapat ditangani daerah menimbulkan ironi. Kapasitas daerah sudah jelas kolaps: akses listrik terputus, logistik terhambat, ribuan rumah hilang, evakuasi tersendat, dan pengungsian nyaris tanpa standar kemanusiaan.
Jika kondisi seperti ini masih dianggap “dapat ditangani”, publik pantas bertanya seperti apa definisi kolaps menurut pemerintah. Kesan yang muncul justru negara enggan mengakui bobot tragedi, entah karena hitungan politik, kekhawatiran citra, atau kalkulasi ekonomi yang tidak pernah dijelaskan terang kepada publik.
Keengganan menaikkan status kerap disertai argumen teknokratis soal mekanisme berjenjang dan penilaian kapasitas daerah. Namun publik tidak hidup dalam ruang prosedur. Mereka hidup di antara puing rumah, lantai masjid yang berubah ruang tidur, minimarket yang dijarah karena tidak ada makanan, dan jenazah yang harus diletakkan di sudut bangunan yang masih utuh.
Ketika warga kelaparan sampai harus merobek pintu toko demi bertahan hidup, itu bukan sekadar potret kriminalitas, melainkan alarm keras bahwa negara terlambat hadir.
Menjaga Narasi Stabilitas
Faktor politik-ekonomi tidak bisa dihilangkan dari analisis. Status bencana nasional otomatis membuka keran intervensi negara: pengerahan aparat besar, pendanaan lintas kementerian, hingga kemungkinan bantuan internasional.
Konsekuensinya signifikan bagi pemerintah, termasuk pengakuan implisit mitigasi lingkungan, pengawasan izin, dan tata kelola ruang tidak berjalan.
Bagi sebagian elite, pengakuan itu tidak hanya memalukan, tetapi berpotensi menyeret tanggung jawab institusional. Di titik inilah publik mencium adanya kalkulasi: menjaga narasi stabilitas lebih penting dibanding menyelamatkan manusia yang terjebak lumpur.
Masalahnya, bencana tidak pernah tunduk pada strategi komunikasi politik. Setiap jam keterlambatan berdampak langsung pada jumlah korban, kualitas penanganan, dan trauma sosial yang semakin dalam.
Ketika negara ragu mengaktifkan seluruh perangkat daruratnya, korbanlah yang membayar harga keraguan itu. Mereka yang mengantre bantuan yang tak kunjung tiba, mereka yang meratap kehilangan keluarga, dan mereka yang bertahan hidup di ruang sempit tanpa sanitasi.
Ketidakadilan juga terasa. Masyarakat di kawasan ini seperti ditempatkan sebagai warga kelas dua.
Mereka melihat betapa cepat negara bertindak di beberapa wilayah lain ketika bencana menyerang, sementara kini keputusan seakan digantung tanpa kepastian.
Keadilan ekologis dan keadilan sosial seolah tidak memiliki posisi sama dalam skala prioritas nasional.
Jika negara terus memelihara keraguan, publik akan mengingat momen ini sebagai kegagalan moral paling telanjang.
Penetapan status bencana nasional bukan hadiah, bukan pula simbol politis, melainkan mandat konstitusional. Ketika bencana sudah sedemikian masif, berhitung terlalu lama sama saja dengan menegaskan sesuatu yang lebih pahit: negara melihat, negara tahu, tetapi negara memilih tidak bergerak secepat yang seharusnya.(id18)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.