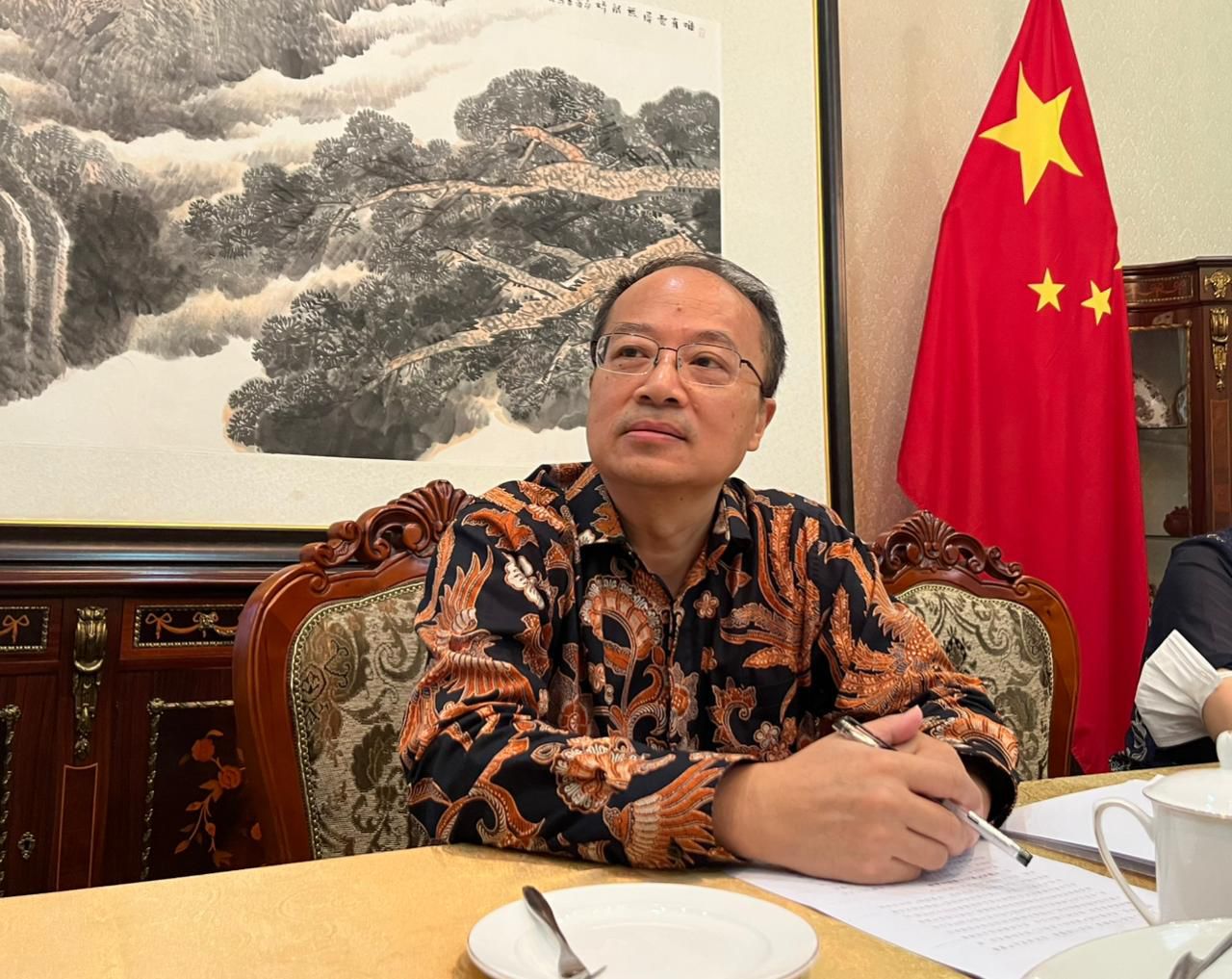Oleh: Farid Wajdi
Setiap kali banjir bandang dan longsor kembali menghantam Sumatera, publik menyaksikan pola yang nyaris sama: alam yang disalahkan, pejabat yang berkelit, dan fakta lapangan yang berbicara lebih keras daripada narasi resmi.
Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN
Bencana di Sumatera bukan sekadar peristiwa ekstrem, sebab bencana merupakan akumulasi dari kerusakan ekologis yang sudah lama dibiarkan, bahkan dipelihara oleh kebijakan yang kompromistis dan pengawasan yang rapuh.
Laporan Tempo mengenai banjir-longsor di Sumatra menegaskan selain curah hujan tinggi, terdapat kerusakan hutan yang luas di kawasan hulu, ditambah penurunan daya dukung sungai akibat sedimentasi yang masif.
Fakta-fakta itu selaras dengan temuan Badan Geologi yang merilis penyebab utama banjir Aceh dan Sumatera: kemiringan lereng yang telah termodifikasi oleh aktivitas manusia, perubahan fungsi hutan, serta peningkatan aliran permukaan yang mempercepat arus banjir (CNBC Indonesia, 29 November 2025).
Greenpeace menambahkan sesuatu yang lebih gamblang. Organisasi itu menyebut kombinasi siklon Senyar dengan deforestasi sebagai “pemicu ganda”, sebab hutan yang hilang membuat curah hujan ekstrem berubah menjadi bencana ekologis. Dalam pernyataan resminya,
Greenpeace menjelaskan “banjir besar tidak mungkin terjadi tanpa degradasi struktural terhadap bentang alam; hulu yang rusak menciptakan efek domino pada wilayah hilir”. Laporan itu diperkuat oleh liputan Kompas TV yang menampilkan kayu-kayu gelondongan dengan bekas potongan mesin tersebar di aliran sungai: bukti visual lereng hulu telah “dipanen” sebelum akhirnya diterjang arus.
Pada saat publik menuntut transparansi, sebagian pejabat justru terjebak pada penjelasan yang menyederhanakan peristiwa. Beberapa menyebut hujan ekstrem sebagai faktor tunggal. Pernyataan seperti ini tidak hanya bertentangan dengan sains, tetapi juga menyingkirkan bukti empiris yang tersaji jelas di hadapan publik.
BMKG sendiri dalam peringatan cuaca ekstremnya tidak pernah menyatakan hujan menjadi penyebab tunggal bencana; yang ditekankan justru risiko meningkat bila bertemu dengan wilayah yang telah mengalami perubahan penggunaan lahan, deforestasi, dan penurunan daya resap tanah.
Pembelokan Narasi
Sikap sebagian pejabat yang memilih menonjolkan alam sebagai pihak bersalah menimbulkan pertanyaan serius. Ketika kayu-kayu bulat berpola potongan gergaji mesin mengalir di sungai, sulit bagi publik menerima narasi yang memutihkan faktor antropogenik.
Bahkan Badan Geologi tidak menyederhanakan isu ini; lembaga itu menegaskan perubahan bentang lahan berperan besar dalam memperparah dampak cuaca ekstrem. Artinya, bencana ini bukan sekadar produk atmosfer, tetapi produk politik-ekologis.
Pada titik ini publik merasakan adanya pembelokan narasi sebagai upaya menggeser fokus dari persoalan struktural ke argumentasi alamiah yang dangkal. Padahal kajian akademik selama dua dekade terakhir konsisten menunjukkan kesimpulan yang sama: curah hujan ekstrem hanya menjadi bencana bila tata kelola lingkungan sudah rusak.
Laporan IPCC menegaskan wilayah dengan deforestasi akan mengalami kenaikan debit banjir hingga 27–40 persen dibandingkan wilayah yang masih berhutan. Kajian Universitas Gadjah Mada menemukan indeks kerentanan banjir di Sumatera meningkat secara signifikan akibat ekspansi perkebunan, pembukaan hutan, serta izin tambang yang berada di zona resapan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan ratusan ribu hektare hutan Sumatera hilang dalam dekade terakhir.
Fakta-fakta ini memperkuat argumen bencana Indonesia bukan sekadar musibah, tetapi konsekuensi dari struktur industri ekstraktif yang merusak.
Ironisnya, struktur ini sering berlangsung di bawah perlindungan aparat, kolaborasi oknum pejabat lokal, atau ketidakberdayaan institusi pengawas. Bukan tanpa alasan publik menyimpulkan pembalakan liar tidak mungkin bekerja tanpa jaringan perlindungan.
Bencana Bukan Takdir
Akademisi seperti Hariadi Kartodihardjo (IPB) sejak lama menyampaikan kerusakan hutan Indonesia “tidak mungkin berdiri sendiri; ia selalu terkait dengan lingkaran kuasa yang membiarkan, melindungi, atau mengambil manfaat dari perusakan”.
Pada saat bersamaan, pakar kebencanaan seperti Sutopo Purwo Nugroho (almarhum) pernah menegaskan “lebih dari 90 persen bencana hidrometeorologis di Indonesia diperparah oleh perusakan lingkungan dan tata ruang yang buruk”.
Jika pejabat masih menyebut bencana sebagai “takdir hujan”, publik tentu berhak mempertanyakan integritas narasi tersebut. Kerapuhan koordinasi antara pusat dan daerah memperburuk keadaan.
Peringatan dini BMKG tidak selalu diterjemahkan menjadi langkah penataan ruang, pembersihan daerah aliran sungai, atau penghentian aktivitas ilegal di wilayah rawan.
Penegakan hukum kehutanan masih sporadis. Adapun kepentingan dan kerakusan ekonomi sering mengalahkan kewajiban ekologis.
Pada akhirnya, bencana di Sumatera seolah memperlihatkan dua hal: alam bekerja sesuai hukumnya, dan manusia bekerja melawan hukum alam. Curah hujan ekstrem tidak dapat dicegah, tetapi deforestasi dapat dihentikan. Siklon tidak bisa dikendalikan, tetapi tata ruang dapat diperbaiki. Longsor tidak dapat dihapus, tetapi risikonya dapat ditekan melalui kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan.
Namun semua itu membutuhkan satu hal yang hingga kini masih hilang: kejujuran negara dalam mengakui akar persoalan.
Selama narasi resmi masih memilih menuding langit daripada memandang pohon terakhir yang tumbang, publik akan terus menjadi korban dari pembelokan dan pembalakan.
Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.