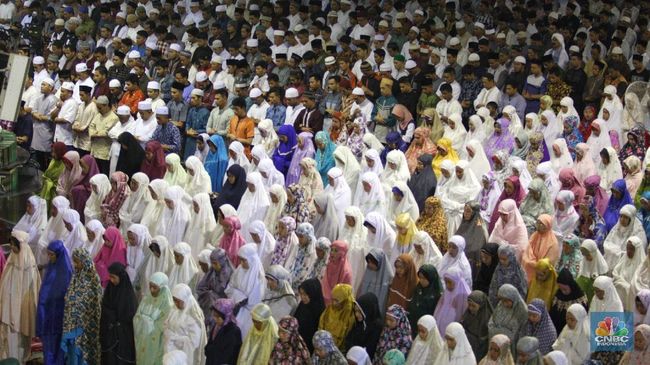Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025/2026 kini sudah memasuki momentumnya karena berdasarkan Permendikbud No.3 tahun 2025 Pasal 38 Ayat 3 disebutkan bahwa pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilaksanakan paling lama minggu pertama bulan Mei 2025 ini, sehingga seluruh pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia kini dituntut segera bergerak melakukan sosialisasi kepada publik.
Namun, SPMB bukan sekadar formalitas adminstratif tahunan semata, melainkan kebijakan yang mencerminkan keberpihakan negara terhadap akses pendidikan yang adil, bermutu, inklusif serta mampu mendorong integrasi sosial dan memperkuat kohesivitas sosial.
Bangsa Indonesia kini tengah berjuang mengejar pemulihan pembelajaran pasca mengalami learning loss selama Pandemi Covid-19. Learning loss dalam artian bahwa motivasi belajar, kemampuan akademis para siswa menurun karena tidak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka selama masa pandemi sehingga berpengaruh pada kualitas pembelajaran.
Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN
Indonesia juga terus bersiap menyambut era bonus demografi yang menjadi momentum strategis untuk memacu kemajuan bangsa yang didorong dengan sumber daya yang unggul, sehat dan juga berpendidikan sehingga Generasi Emas 2045 dapat membawa Indonesia menjadi negara maju. Akan tetapi, bonus demografi hanyalah potensi, dan tanpa sistem pendidikan yang menjangkau semua, hal itu bisa berubah menjadi beban sosial yang berat.
Pada saat yang sama dunia pendidikan kita juga mengalami tantangan yang tidak ringan. Berdasarkan Programme for International Student Assessment (PISA) Tahun 2022 sebanyak 75 persen anak usia 15 tahun di Indonesia memiliki kemampuan membaca di bawah standar, tepatnya di bawah level 2 PISA. Ini berarti para murid kesulitan memahami gagasan utama dari sebuah teks panjang. Lebih mengkhawatirkan lagi, 82 persen anak usia 15 tahun memiliki kemampuan matematika di bawah standar berarti mereka kesulitan memahami aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Data ini menggarisbawahi bahwa kualitas hasil belajar masih menjadi tantangan utama pendidikan nasional.
SPMB menjadi refleksi dari komitmen negara terhadap pengembangan sumber daya manusia. Pilihan kebijakan dalam SPMB baik jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi berdampak langsung pada pemerataan akses, peningkatan kualitas pendidikan, serta pembentukan generasi masa depan yang unggul dan berdaya saing. Namun di balik hiruk-pikuk penerimaan murid baru yang menyedot perhatian publik setiap tahunnya, terselip kenyataan mendesak yang semestinya menggugah kepedulian dan tanggung jawab kita bersama karena masih tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia.
Berdasarkan data Pusdatin Kemendikdasmen per 15 April 2025 tercatat sebanyak 3,9 juta ATS di Indonesia di mana separuh dari jumlah tersebut yakni sekitar 1,2 juta adalah anak-anak berusia 15 tahun ke atas yang merupakan penduduk usia produktif yang turut berkontribusi pada terwujudnya Generasi Emas atau justru sebaliknya Generasi Cemas pada tahun 2045 nanti.
ATS: Alarm Masa Depan Yang Tidak Boleh Diabaikan
Anak Tidak Sekolah merujuk pada kelompok anak usia sekolah 7 s.d 18 tahun yang tidak bersekolah baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal yang terdiri dari tiga jenis yakni anak yang putus sekolah (DO), anak lulus tidak melanjutkan, serta anak belum pernah bersekolah. Setiap anak yang berada dalam situasi ini sejatinya adalah alarm bagi masa depan bangsa. Cita-cita mewujudkan Generasi Emas 2045 yang unggul dan berdaya saing akan terdengar utopis jika jutaan ATS terus dibiarkan berada di luar sistem pendidikan tanpa intervensi yang nyata dan berkelanjutan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), lebih dari 30 persen penduduk Indonesia berada dalam rentang usia pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan menengah. Fakta ini menegaskan bahwa akses pendidikan yang terjangkau serta peningkatan kualitas pendidikan bagi kelompok usia tersebut merupakan faktor krusial dalam menentukan arah dan kualitas pembangunan sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang.
Penanganan ATS membutuhkan pendekatan multisektoral yang tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor pendidikan saja.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa ATS merupakan konsekuensi dari berbagai persoalan meliputi kemiskinan, kerentanan struktur keluarga, ketimpangan akses layanan publik, hingga kekerasan dan tekanan sosial di lingkungan pergaulan remaja.
Peran SPMB Dalam Menekan Angka Anak Tidak Sekolah
SPMB memainkan peran yang sangat vital sebagai momentum untuk membawa ATS kembali ke dalam sistem pendidikan.
Terlebih Kemendikdasmen telah menetapkan persentase daya tampung untuk jalur afirmasi untuk calon murid yang berasal dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas sebesar minimal 15 persen untuk jenjang SD, 20 persen untuk jenjang SMP dan 30 persen untuk jenjang SMA. Kebijakan afirmasi ini tentu menjadi pintu masuk untuk menjangkau ATS yang selama ini berada di luar sistem pendidikan.
Peserta didik yang masuk ke dalam sistem pendidikan melalui mekanisme SPMB maka secara langsung berkontribusi dalam menurunkan jumlah ATS dan memberikan efek kausal terhadap peningkatan Angka Partisipasi Sekolah.
Gerak Cepat Pemda, Kunci Mengembalikan Anak ke Sekolah
Masalah Anak Tidak Sekolah merupakan potret nyata dari generasi yang tercecer dari arus utama pembangunan pendidikan.
Kecepatan dan komitmen pemerintahan daerah (Pemda) dalam merespons isu ATS akan sangat menentukan seberapa banyak anak yang berhasil ditarik kembali ke dalam sistem pendidikan.
Mengembalikan ATS ke bangku sekolah bukan perkara sepele karena menuntut kerja keras lintas sektor. Penanganan ATS membutuhkan strategi intervensi dan pencegahan.
Semua itu hanya bisa berhasil jika dijalankan secara seirama dengan dukungan lintas lembaga pemerintahan baik pendidikan, kependudukan, sosial, pemberdayaan masyarakat desa hingga kesehatan agar intervensi yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Hingga saat ini belum ada sumber data yang secara tepat menggambarkan tingkat permasalahan ATS di setiap daerah di Indonesia.
Permasalahan ini disinyalir muncul akibat masih minimnya verifikasi dan intervensi yang dilakukan untuk mengatasi jumlah ATS di Indonesia. Namun, sebelum pemda dapat melakukan intervensi yang efektif, langkah awal yang sangat krusial adalah melakukan identifikasi guna menelusuri akar penyebab yang mendorong anak-anak tidak bersekolah.
Salah satu tantangan utama saat ini yakni rendahnya tingkat verifikasi data di lapangan.
Mekanisme intervensi penanganan ATS idealnya dibangun melalui tiga tahapan yakni identifikasi, intervensi, dan pemantauan. Namun hingga Mei 2025, data dari Pusdatin menunjukkan bahwa tingkat verifikasi ATS masih sangat rendah, yaitu baru mencapai sekitar 12 persen dari total 3,9 juta anak yang tercatat tidak bersekolah. Rendahnya angka ini mencerminkan lambatnya respons pemda dalam menindaklanjuti data yang sudah tersedia, sehingga upaya penanganan belum dapat bergerak ke tahap berikutnya secara optimal.
Penanganan ATS terkesan lambat disebabkan oleh proses verifikasi yang berjalan di tempat bahkan stagnan, sehingga banyak daerah masih terjebak pada tahap tersebut dan belum beranjak ke fase intervensi maupun pemantauan.
Ketika verifikasi tak segera dituntaskan, maka seluruh rantai penanganan mulai dari pemetaan kebutuhan hingga penyaluran program ikut terhambat. Alhasil, upaya untuk menurunkan jumlah ATS pun mandek.
Sebagai contoh, di Provinsi Sumatera Utara tercatat sekitar 243 ribu Anak Tidak Sekolah.
Namun masih sekitar 6 persen yang telah diverifikasi, atau setara dengan 15 ribu anak. Penanganan ATS tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi juga bukan hal yang mustahil untuk diatasi. Diperlukan keterlibatan banyak pihak dan koordinasi lintas sektor. Pemda harus membangun komunikasi dan kerja sama yang kuat antar instansi pendukung, termasuk mendorong operator Dapodik maupun operator desa untuk aktif melakukan proses verifikasi.
Ketika seluruh data ATS telah diverifikasi secara menyeluruh, pemda akan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang dihadapi anak-anak tersebut. Dengan begitu, setiap pemda dapat merancang intervensi yang sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal secara lebih tepat sasaran. Strategi penanganan ATS yang berbasis kearifan lokal dapat menjadi fondasi penting untuk direplikasi, diadaptasi, dan diperluas ke wilayah lain.
Bahkan, pendekatan yang berhasil di tingkat daerah berpotensi diangkat menjadi kebijakan nasional, selama mampu menunjukkan efektivitas dan keberlanjutan.
Momentum SPMB adalah panggilan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk tidak hanya fokus pada proses penerimaan murid baru, tetapi juga menjemput mereka yang tertinggal: Anak Tidak Sekolah, agar kembali ke sistem pendidikan formal maupun nonformal.
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.