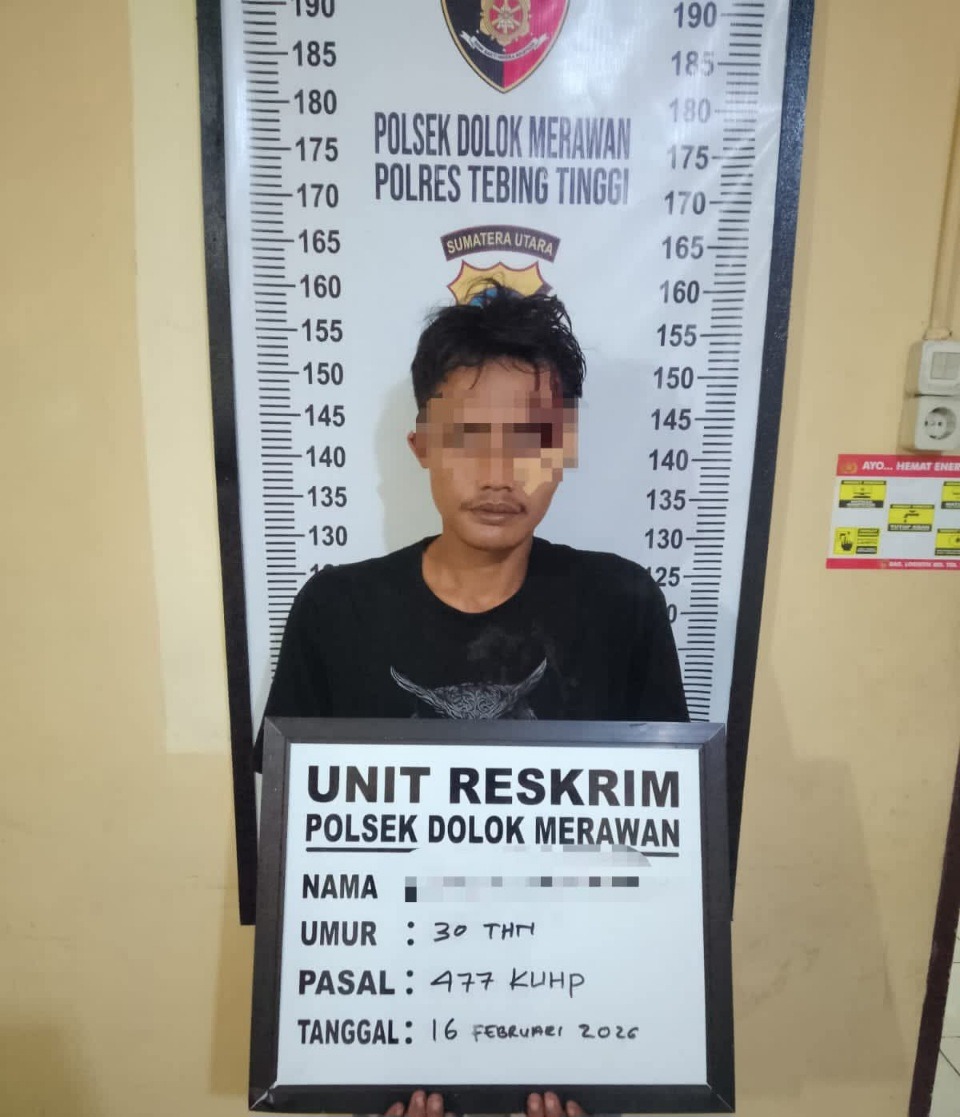Oleh: Farid Wajdi
Ada lagu yang tak pernah benar-benar usai karena luka yang diceritakannya terus berulang. “Berita Kepada Kawan” karya Ebiet G. Ade adalah lagu semacam itu. Ia lahir dari peristiwa duka, tetapi hidup jauh lebih lama dari bencana yang melahirkannya.
Setiap kali banjir kembali menelan kampung, setiap kali longsor menutup jalan dan memutus ingatan, lagu ini kembali beredar, seperti surat lama yang selalu relevan karena alamat penderitaannya tak pernah berubah.
Sejak awal kemunculannya pada akhir dekade 1970-an, lagu ini memang tidak dimaksudkan sebagai catatan peristiwa, melainkan renungan kemanusiaan (Ebiet G. Ade, 1979-an).
Ia tidak berdiri sebagai arsip sejarah yang kaku, tetapi sebagai cermin. Dan cermin, sebagaimana mestinya, tidak berfungsi untuk menunjuk kesalahan orang lain, melainkan mengembalikan pandangan kepada diri sendiri.
Dalam tradisi reflektif, cermin semacam ini mengajak manusia berhenti sejenak, menimbang arah langkahnya, bukan sekadar menunjuk keluar dan mencari kambing hitam.
Dalam khazanah keislaman, sikap ini sejalan dengan semangat tadabbur, yaitu merenungi tanda-tanda kehidupan agar manusia tidak sekadar melihat, tetapi menyadari makna di balik peristiwa. Alam bukan hanya latar, melainkan pesan. Namun pesan itu sering datang berulang karena tak kunjung dipahami.
Yang kerap terjadi justru sebaliknya. Lagu itu diputar, dibagikan, bahkan dikutip, tetapi hanya sebagai pengiring kesedihan sesaat. Setelah itu, kehidupan berjalan kembali seperti biasa.
Hutan tetap dibuka atas nama investasi. Sungai tetap dipersempit demi perluasan kota. Lereng tetap dibebani bangunan, seolah tanah tak pernah punya batas daya dukung. Lalu manusia kembali merasa heran ketika air tak lagi tahu ke mana harus mengalir.
Seperti dicatat dalam sejumlah refleksi kebudayaan, lagu ini sering hadir sebagai simbol empati, tetapi jarang menjadi pemicu perubahan cara pandang (Kompas.id, 2024).
“Berita kepada kawan, tentang perjalanan ini…” Kalimat pembuka itu terdengar sederhana, hampir bersahaja. Namun di sanalah letak kekuatannya. Ia bukan laporan teknis, bukan kronik kebencanaan, melainkan pengakuan batin.
Ebiet tidak sedang menyusun kronologi hujan dan longsor. Ia sedang menyampaikan kesaksian: ada sesuatu yang keliru dalam perjalanan manusia bersama alamnya. Bukan hujan yang patut dicurigai, melainkan cara manusia memperlakukan tanah dan air, dua unsur yang justru menopang hidup.
Lagu ini tidak menawarkan solusi kebijakan. Ia tidak berbicara tentang tanggul, bendungan, atau regulasi teknis. Ia berbicara tentang jarak: jarak emosional dan etis antara manusia dan lingkungan yang menopangnya.
Dalam perspektif etika, jarak ini muncul ketika alam tidak lagi dipandang sebagai mitra hidup, melainkan sekadar objek eksploitasi. Dalam bahasa agama, manusia lupa perannya sebagai penjaga, bukan penguasa mutlak.
Ketika Ebiet menulis tentang hujan yang tak lagi bersahabat dan tanah yang kehilangan daya dukung, ia tidak sedang meramal masa depan. Ia mencatat kebiasaan yang sudah lama berlangsung: menebang tanpa jeda, menggali tanpa jeda, membangun tanpa rasa cukup.
Bencana dalam lagu itu bukan kejadian mendadak, melainkan hasil dari rangkaian pilihan yang terus dianggap wajar, sebuah pola yang juga ditegaskan dalam banyak kajian tentang degradasi lingkungan di Indonesia (UNY, 2016).
Di titik inilah lagu tersebut menjadi cermin yang tak nyaman. Ia tidak menunjuk langit sebagai penyebab, melainkan mengajak manusia menoleh ke bawah, ke tanah yang gundul, sungai yang disempitkan, dan kebijakan yang lebih setia pada angka pertumbuhan daripada keseimbangan ekologis. Ia lirih, tetapi tidak netral.
Kesedihannya mengandung kritik. Dan kritiknya justru tajam karena disampaikan tanpa teriakan.
Rakuskah Manusia atau Enggan Belajar
Setiap kali bencana datang, selalu ada kalimat yang diulang seperti doa singkat: ini bencana alam. Kalimat itu terdengar pasrah, bahkan menenangkan.
Namun di balik kepasrahan itu tersimpan kecenderungan lama: memindahkan tanggung jawab dari manusia ke cuaca. Alam dijadikan pelaku, manusia diposisikan sebagai korban murni, bersih dari kesalahan.
Padahal laporan demi laporan menunjukkan banjir dan longsor bukan sekadar urusan hujan. Ia adalah pertemuan antara faktor alam dan kerusakan yang terencana: deforestasi, alih fungsi lahan, pertambangan, serta tata ruang yang dikalahkan oleh kepentingan jangka pendek (Media Indonesia, 2024; Kompas.id, 2025). Dalam istilah etika, manusia sering melampaui batas tanpa merasa sedang melanggar apa pun.
Apakah ini soal kerakusan? Pertanyaan ini kerap dianggap terlalu moral, bahkan naif. Namun justru di sanalah persoalannya. Kerakusan hari ini tidak selalu tampil kasar atau vulgar. Ia hadir dalam bentuk izin, kebijakan, dan narasi pembangunan.
Ia dilegalkan, dinormalisasi, lalu dilupakan akibatnya. Seperti dicatat dalam refleksi sejarah sosial, keserakahan modern jarang berwujud individual; ia lebih sering hadir sebagai sistem yang rapi dan berlapis (Ibn Khaldun, 1377).
Ebiet tidak menyebut kata serakah. Ia memilih kesedihan sebagai bahasa. Namun justru karena itu kritiknya lebih menusuk. Ia tidak menggurui, tetapi mengundang rasa malu. Seolah berkata: lihatlah apa yang kita lakukan, lalu dengarkan akibatnya.
Dalam banyak tafsir kebudayaan, kekuatan lagu ini terletak pada kemampuannya menegur tanpa berteriak, menyentuh tanpa menghakimi (Antara News, 2024).
Masalah lain yang disinggung secara halus adalah cara manusia belajar dari bencana. Setiap peristiwa disebut sebagai pelajaran, tetapi pelajaran itu jarang berlanjut menjadi perubahan. Ia berhenti sebagai slogan, lalu menguap ketika air surut.
Dalam bahasa reflektif, ini bukan sekadar lupa, melainkan ghaflah, yaitu kelalaian kolektif yang membuat kesalahan lama diulang dengan keyakinan baru (Quraish Shihab, 2002).
Belajar dari bencana seharusnya berarti mengubah cara memandang alam. Mengakui batas manusia. Menyadari bumi bukan sekadar sumber daya, melainkan amanah.
Namun yang sering terjadi justru sebaliknya: bencana dijadikan pembuka proyek, beton ditambah, eksploitasi dilanjutkan, dan akar persoalan tetap dibiarkan (Media Indonesia, 2024).
Di sinilah “Berita Kepada Kawan” terasa semakin aktual. Lagu ini tidak berbicara tentang teknokrasi, melainkan tentang hilangnya kepekaan.
Tentang manusia yang terlalu sibuk mengatur alam hingga lupa mendengarkannya. Sebuah kritik yang, secara etik, sejalan dengan gagasan kerusakan di bumi lahir dari tangan manusia sendiri, bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai konsekuensi.
Urgensi bencana hari ini bukan hanya soal korban jiwa atau kerugian ekonomi. Ia adalah krisis cara pandang. Pemerintah kerap melihat bencana sebagai gangguan pembangunan, sementara masyarakat melihatnya sebagai takdir.
Padahal, dalam refleksi etis dan spiritual, takdir tidak pernah dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari tanggung jawab.
“Berita Kepada Kawan” seharusnya tidak hanya diputar saat duka. Ia layak dibaca ulang sebagai kritik kebijakan, kritik moral, dan kritik peradaban. Ia menagih kesadaran, bukan sekadar simpati.
Ebiet menutup lagunya dengan nada lirih. Tidak ada amarah, tidak ada makian. Hanya kabar yang disampaikan dengan jujur. Seolah ia berkata: aku sudah mengingatkan, selebihnya pilihan kalian.
Kini, puluhan tahun setelah lagu itu lahir, kabar itu masih sama. Bencana datang lagi. Lagu itu diputar lagi. Pertanyaannya tetap menggantung di udara yang makin sesak: sampai kapan manusia hanya mendengar, tanpa sungguh-sungguh menghayati?
Seperti lirik yang ia tinggalkan sebagai penutup yang getir: “Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.”
Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.