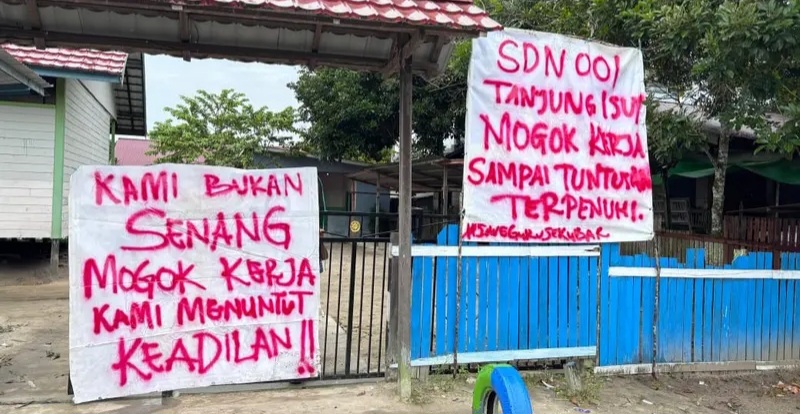Oleh Shohibul Anshor Siregar
Setiap kali aparat menyiksa warga, kepercayaan publik pada negara retak sedikit demi sedikit
Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN
Kabut pagi di Medan belum sepenuhnya mengangkat ketika peluru mengakhiri hidup Muhammad Suhada. Remaja 15 tahun itu terkapar di aspal jalan, darah menggenang di perutnya yang tertembus. Ia bukan gugur di medan perang, tetapi di jalanan kotanya sendiri di Sumatera Utara. Tangan yang menembaknya berseragam polisi, institusi yang seharusnya menjadi pelindung. Kematiannya bukan sekadar tragedi individu, melainkan simbol kegagalan negara yang mengkhianati rakyatnya sendiri.
Laporan KontraS Sumut periode Juli 2024–Juni 2025 menguak kenyataan pahit: 17 kasus penyiksaan aparat dalam setahun, melukai 36 warga, dan merenggut 5 nyawa. Angka ini melonjak drastis dari rata-rata 7 kasus per tahun (2019–2022). Di balik statistik itu, ada cerita tentang pemukulan di ruang interogasi, sengatan listrik di balik tembok markas, dan anak-anak yang trauma melihat ayahnya “diamankan” aparat.
Anatomi Kekerasan Yang Terlembaga
Teori Johan Galtung (1990) tentang kekerasan struktural menemukan bentuk nyatanya di sini. Kekerasan fisik hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya, ada sistem yang membiarkan polisi dan tentara lepas dari hukuman, institusi pengawas yang mandul, dan kebijakan yang mengizinkan senjata digunakan untuk menaklukkan warga tak bersenjata. Kematian Suhada, misalnya, bukan hanya soal peluru yang menghujam perutnya. Ia juga korban stigmatisasi aparat yang menyebutnya “pelaku tawuran layak diberi pelajaran”, narasi yang kemudian diadopsi media arus utama.
Nancy Bermeo (2016) akan menyebut ini sebagai kemunduran demokrasi (democratic backsliding). Di permukaan, Indonesia masih menyelenggarakan pemilu, tetapi otot-otoritarianisme perlahan menguat. Ketika polisi menembak remaja tanpa proses hukum, ketika Komnas HAM hanya bisa mengeluarkan laporan tanpa daya paksa, dan ketika DPR bungkam melihat pelanggaran HAM, demokrasi sedang sekarat secara diam-diam.
Dari 17 kasus penyiksaan di Sumut, 70% tak pernah dilaporkan. “Keluarga korban takut dibalas, atau lebih buruk, dijerat pasal kriminal,” papar aktivis KontraS Sumut dalam wawancara gelap. Seorang ibu di Deli Serdang bercerita bagaimana laporan penyiksaan suaminya ditolak polisi dengan alasan: “Dia perampok, pantas disetrum!” Padahal rekaman CCTV membuktikan suaminya sedang memarkir motor saat digelandang aparat.
Keterlibatan TNI dalam urusan sipil memperkeruh situasi. Meski reformasi 1998 melarangnya, seragam hijau masih kerap muncul dalam razia narkoba, penggusuran, bahkan pembubaran unjuk rasa. Studi Croissant dkk (2010) membuktikan: di negara yang di sana tentara tak sepenuhnya di bawah kendali sipil, kekerasan negara menjadi epidemi.
Demokrasi yang Terluka Parah
Di Brasil, polisi menewaskan 6.000 warga miskin dalam setahun (2022). Dengan pro dan kontra sengit, di Filipina, perang narkoba Duterte membunuh 30.000 orang tanpa pengadilan. Indonesia tidak jauh berbeda. Rule of Law Index 2023 menempatkan Indonesia di peringkat 68 dari 142 negara untuk perlindungan HAM, di bawah Rwanda dan Botswana.
Tapi ada secercah harapan dari Belanda dan Norwegia. Di sana, polisi menjalani pelatihan 3 tahun yang berfokus pada deeskalasi konflik dan komunikasi non-kekerasan. Hasilnya? Tingkat kematian akibat tembak polisi hampir nol. Bandingkan dengan Indonesia, yang di sana pendidikan polisi hanya 6 bulan dan kurikulumnya penuh latihan tembak, bukan mediasi. Mekanisme rekrutmennya pun sangat diragukan basis meritokrasinya.
Setiap kali aparat menyiksa warga, kepercayaan publik pada negara retak sedikit demi sedikit. Survei Indikator Politik (2024) menunjukkan, kepercayaan pada Polri anjlok 40% pasca kasus Suhada. “Mereka yang tumbuh dalam bayang-bayang kekerasan negara akan menjadi generasi sinis,” tulis Fareed Zakaria (2003). Di sekolah-sekolah Sumut, guru-guru kini kesulitan menjelaskan makna “Bhinneka Tunggal Ika” ketika murid-muridnya menyaksikan tentara menggaruk-garukan senjata ke kepala pengemudi becak yang “melanggar jalur”.
UUD 1945 Pasal 28G menjamin hak warga bebas dari penyiksaan, tetapi di Sumut, hukum itu mati. Yang hidup adalah hukum rimba: siapa pun yang berseragam bisa menodongkan senjata, menyiksa, lalu bebas tanpa sanksi.
Jalan Keluar
Reformasi tidak bisa sekadar mengirim polisi ikut pelatihan HAM beberapa hari. Perlu revolusi institusi, karena mekanisme pengawasan independen seperti Independent Office for Police Conduct di Inggris, yang di sana penyidiknya bukan rekan seangkatan pelaku. Pelatihan aparat selama 3 tahun ala Norwegia, mengganti pelatihan tembak dengan resolusi konflik. Pemisahan tegas TNI-Polri: tentara kembali ke markas, polisi fokus ke keamanan sipil tanpa intervensi militer. Penuntutan wajib untuk pelaku penyiksaan, termasuk atasan yang diidentifikasi membiarkan.
Reformasi bukan sekadar tempelan pelatihan HAM berhari-hari di ruang ber-AC. Ia menuntut pembongkaran tata kelola keamanan yang busuk. Di jantung solusinya, mekanisme pengawasan independen harus lahir, bukan boneka yang mengangguk pada institusi yang diawasinya. Ambil contoh Independent Office for Police Conduct (IOPC) di Inggris: penyidiknya direkrut dari kalangan sipil, jaksa, bahkan mantan hakim. Mereka berwenang menyita senjata, membuka rekaman tubuh (bodycam), dan merekomendasikan pemecatan tanpa perlu izin Kapolri. Ketika aparat di Medan menembak remaja, penyelidikan tak boleh lagi diserahkan pada Propam Polri yang ibarat “serigala mengadili serigala”.
Revolusi juga mesti menyentuh dasar pendidikan aparat. Bayangkan jika polisi Indonesia menjalani pelatihan tiga tahun ala Norwegia, bukan sekadar enam bulan hafalan regulasi. Di Oslo, calon polisi diajari psikologi kerumunan, negosiasi krisis, dan mediasi konflik sebelum menyentuh pistol. Latihan tembak hanya 10% dari kurikulum. Bandingkan dengan Akademi Kepolisian di Indonesia: puluhan jam di lapangan tembak, tapi minim simulasi menghadapi emosi warga marah. Hasilnya? Ketika tawuran pecah di Belawan, pilihan pertama AKBP Oloan Siahaan adalah peluru, bukan dialog.
Deviasi yang melahirkan fenomena “pisau bermata dua bernama TNI-Polri” harus dipatahkan. Reformasi 1998 memerintahkan tentara mundur dari politik, tapi praktiknya, seragam hijau masih berkeliaran di razia narkoba, penggusuran, bahkan sweeping warung remang-remang. Studi Croissant dkk (2010) membuktikan: di negara yang di sana militer menguasai urusan sipil, penyiksaan warga meningkat 300%. Polri harus berani mengatakan, “Urusan preman pasar bukan tugas Kostrad!” Sementara TNI perlu dikembalikan ke markas, fokus pada ancaman bersenjata, bukan becak yang “mengganggu ketertiban”.
Tapi semua itu sia-sia tanpa penuntutan hukum yang menghabisi akar impunitas. Selama ini, hukuman bagi pelaku penyiksaan sekadar mutasi atau denda administratif. Padahal, UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan menjerat pelaku dengan hukuman penjara 15 tahun. Kasus Suhada harus jadi preseden: bukan cuma penembak yang diadili, tapi juga komandan yang memberi izin pakai senjata api, pejabat yang menutupi laporan, bahkan dokter yang memalsukan visum. David Petrasek (1995) mengingatkan: impunitas adalah epidemi, ia menular ke aparat lain yang melihat kekerasan tak berganjar sanksi.
Apa yang diinginkan ketika pengawasan, pendidikan, dan penuntutan saling bertaut? Di Den Haag, Belanda, ada mekanisme bernama “Veiligheidsonderzoek”: setiap tembakan polisi wajib diselidiki tim independen dalam 24 jam. Hasilnya dipublikasikan real-time, termasuk rekaman bodycam. Jika Indonesia mengadopsinya, kasus seperti Suhada tak akan tenggelam dalam berita tumpang-tindih.
Sedangkan di pedalaman Norwegia, pelatihan polisi di Kota Stavern mengharuskan kadet tinggal bersama komunitas minoritas: imigran, penyandang disabilitas, bahkan mantan napi. Mereka diajak diskusi tentang trauma kekerasan negara. “Kami tak ingin polisi jadi robot berseragam,” kata instrukturnya.
Untuk TNI, Jerman memberi pelajaran berharga: Pasukan Bundeswehr dilarang keras turun ke jalan kecuali darurat konstitusional seperti terorisme. Pelanggarannya? Pengadilan militer langsung menggeledah markas. Tentang penuntutan, Argentina punya formula radikal: Kejaksaan Agungnya membentuk tim Unidad Fiscal para la Investigación de la Tortura (Unit Khusus Penyiksaan). Mereka berwenang menyadap telepon jenderal, membuka arsip rahasia militer, dan menahan menteri yang menghalangi penyelidikan.
Ini sama sekali bukan sekadar senjata yang perat jinak, tapi juga mentalitas penyimpangan yang harus dibasmi. Reformasi sejati dimulai ketika negara berani memutus rantai kekerasan yang sistemik. Bukan dengan seremonial pelatihan HAM, tapi dengan membubarkan mafia internal yang melindungi pelaku penyiksaan; menghancurkan doktrin “penegakan hukum = penaklukan warga”; dan menjadikan setiap luka korban sebagai cermin bagi aparat: “Ini yang kau tinggalkan pada ibu, anak, dan demokrasi.”
Volker Türk, Komisaris Tinggi HAM PBB, berpesan: “Keamanan publik bukan pembenaran untuk menebar ketakutan publik.” Senjata baru bisa jinak ketika hukum benar-benar hidup, hidup dalam tindakan tegas pada penyiksa, hidup dalam pelatihan yang memanusiakan, hidup dalam pengawasan yang tak pandang pangkat. Dan hidup dalam keberanian kita menyuarakan yang Suhada tak sempat selesaikan: “Negara ini milik kami, bukan milik bedil kalian”.
“Setiap penyiksaan adalah pengkhianatan ganda: pada korban dan pada masyarakat,” tegas David Petrasek (1995). Ketika Volker Türk, Komisaris Tinggi HAM PBB, berkata: “Penyiksaan harus diakhiri, akuntabilitas harus dimulai,” ia sedang menuding Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan namun membiarkannya jadi dokumen usang.
Antara Demokrasi Atau Kuburan
Bulan Juni 2025, ibu Suhada masih menuntut keadilan di pengadilan Medan. Di luar ruang sidang, bendera merah putih berkibar. Tetapi bagi warga Sumut, sang saka kini lebih menyerupai kain kafan, membungkus mayat demokrasi yang dibunuh oleh tangan-tangan yang seharusnya menjaganya.
Kisah Suhada adalah cermin bagi kita semua: apakah kita akan membiarkan negara menjelma menjadi algojo, atau bangkit menuntut aparat yang takluk pada hukum, bukan senjata? Masa depan Indonesia mungkin ditentukan di jalanan ini: di antara derap sepatu lars aparat dan jeritan pilu korban yang menuntut keadilan. Seperti peringatan KontraS: “Diam kita hari ini adalah persetujuan pada penyiksaan esok.”
Penulis adalah Dosen Fisip UMSU, Ketua Lembaga Hikmah & Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara.
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.