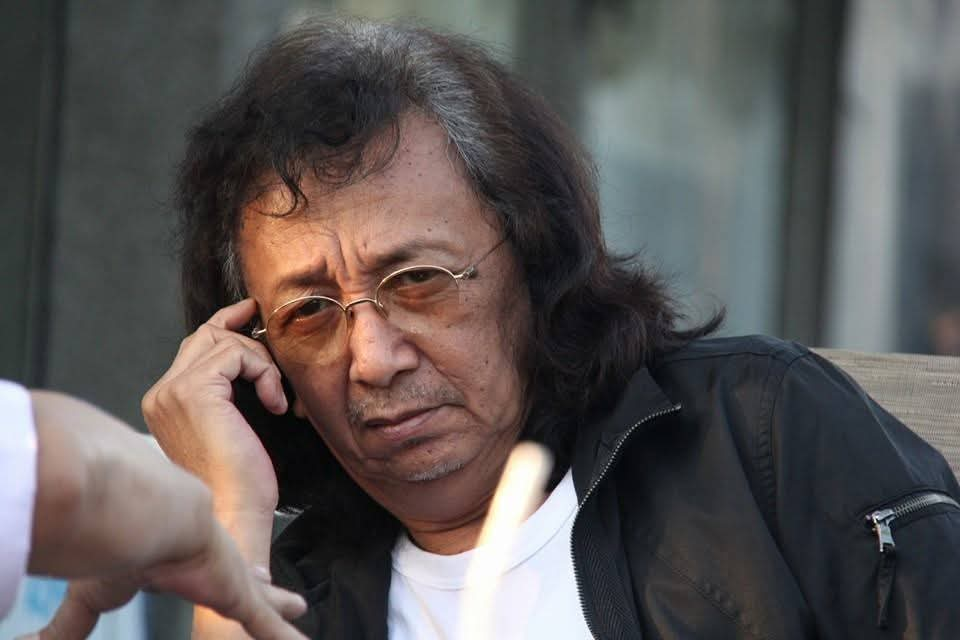Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting untuk meninjau arah kebijakan energi nasional. Di banyak kesempatan Prabowo menegaskan Indonesia tak boleh terus bergantung pada impor energi, melainkan harus mampu memproduksi, mengolah, dan memanfaatkan sendiri kekayaan alamnya.
Ide soal biofuel, hilirisasi, dan diversifikasi energi sering digaungkan sebagai poros transisi. Tetapi di balik jargon itu, kita harus bertanya sejauh mana kebijakan mampu menjangkau rakyat Indonesia secara adil?
Keadilan energi bukanlah istilah teknokratis semata. Ia menuntut bahwa setiap warga negara, tanpa memandang lokasi, status ekonomi atau latar belakang, bisa mendapat akses pada energi yang bersih, terjangkau, dan berkelanjutan.
Bukan hanya soal suplai, tetapi soal distribusi manfaat dan beban dalam sistem energi. Sebuah negara bisa memproduksi banyak listrik, tetapi kalau jutaan orang di pelosok masih hidup dalam remang, maka kemandirian itu belum lengkap.
Sejauh ini, capaian kebijakan energi pemerintah masih belum sepenuhnya terealisasi dan masih terdapat ketimpangan antara rencana dan realitas yang terjadi di lapangan. Data resmi menyebut rasio elektrifikasi nasional mendekati 99 persen.
Namun angka ini menyamarkan fakta bahwa di banyak sudut Nusa Tenggara Timur dan Papua listrik hanya menyala beberapa jam per hari. Harga bahan bakar di pulau kecil bisa melonjak tiga kali lipat dari harga resmi. Sementara itu, wilayah industri Jawa dan Sumatra menikmati pasokan melimpah dengan harga disubsidi. Ketahanan energi memang bertambah, tetapi keadilan energi belum menyentuh kerangka realitas masyarakat.
Masih berlaku paradigma equality dalam kebijakan energi selama ini. Tarif listrik diseragamkan, subsidi BBM dibagi merata, penugasan proyek pembangunan diarahkan menyeluruh tanpa mempertimbangkan keragaman konteks.
Secara formal, ini tampak adil. Namun di lapangan, subsidi seragam lebih sering dinikmati kelompok menengah ke atas, kalangan masyarakat yang memiliki kendaraan, rumah besar, dan konsumsi energi tinggi, sedangkan masyarakat miskin tetap membeli energi dengan harga lebih mahal karena kendala akses. Kesetaraan perlakuan tidak selalu menghasilkan keadilan substantif.
Model keberpihakan yang berbasis equity harus menjadi pijakan baru. Dengan cara ini kebijakan tidak memperlakukan semua orang sama, melainkan memberi perhatian lebih pada mereka yang punya keterbatasan.
Dalam konteks energi, itu berarti memprioritaskan daerah tertinggal, mendukung rumah tangga miskin beralih ke energi bersih, dan memberi ruang bagi komunitas lokal menentukan pemanfaatan sumber daya di wilayah mereka. Keadilan energi menuntut negara hadir bukan hanya sebagai penyedia pasokan, tetapi sebagai penjamin kesejahteraan energetik bagi warganya.
Refleksi satu tahun kebijakan energi pemerintahan ini mengarah ke tiga kelemahan utama. Pertama, ketimpangan geografis sangat tajam antara wilayah barat dan timur Indonesia. Sebagian besar investasi masih tertumpu di pulau dengan potensi ekonomi tinggi, sedangkan wilayah terluar jauh tertinggal.
Ketahanan energi nasional seharusnya bukan hanya soal menambah kapasitas, tetapi bagaimana memastikan pasokan itu menjangkau kawasan paling butuh. Energi terbarukan skala kecil seperti mikrohidro, biogas desa, atau panel surya atap bisa jadi solusi lokal, tetapi dukungan kebijakan dan akses pembiayaan belum memadai.
Kedua, secara ekonomi subsidi energi menunjukkan terjadinya ketimpangan. Pemerintah menjaga daya beli melalui subsidi BBM dan listrik, tetapi skema ini cenderung konsumtif dan kurang mendorong perubahan.
Keadilan energi mensyaratkan bahwa subsidi harus menjadi alat transformasi. Dana subsidi dapat dialihkan menjadi program dukungan energi bersih bagi masyarakat miskin. Misalnya pemasangan panel surya rumah tangga, bantuan bioenergi untuk desa, atau kredit lunak untuk energi berkelanjutan lokal.
Tarif listrik juga bisa dirancang progresif, misalkan untuk masyarakat golongan berpenghasilan tinggi membayar lebih untuk mensubsidi golongan rentan. Dengan desain ini, subsidi tidak sekadar jaring pengaman tetapi instrumen pembangunan energi adil.
Ketiga, keadilan lingkungan sering terabaikan. Daerah penghasil energi malah sering menanggung beban ekologis besar. Sebagai contoh, tambang batubara yang merusak habitat di Kalimantan, proyek biofuel atau geothermal yang mengancam ekosistem di Papua.
Ironisnya, wilayah yang kaya energi kerap paling tertinggal dalam pembangunan sosial ekonomi. Negara harus mengakui bahwa ketahanan energi nasional tidak bisa dibangun di atas ketidakadilan ekologis. Mekanisme kompensasi lingkungan, dana rehabilitasi, dan keterlibatan masyarakat lokal wajib diintegrasikan dalam setiap kebijakan energi.
Partisipasi publik juga krusial. Banyak proyek energi dijalankan top-down, dengan keterlibatan masyarakat hanya sebagai formalitas administratif. Padahal partisipasi publik yang nyata adalah hak rakyat untuk menentukan masa depan energi mereka.
Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) harus diterapkan secara konsisten, terutama pada wilayah adat dan ekosistem sensitif. Energi adil berarti proyek energi dibangun bersama rakyat, bukan dipaksakan pada mereka.
Di ranah hukum, kebijakan keadilan energi memiliki pijakan yang belum sepenuhnya kuat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi menegaskan bahwa sumber daya energi harus dikelola dengan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, dan kesinambungan sosial dan lingkungan.
Pasal 2 UU 30/2007 menyebut bahwa pengelolaan energi harus berdasarkan asas "efisiensi berkeadilan". Selain itu, PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional menetapkan target porsi energi baru dan terbarukan minimal 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2050.
Di ranah tata pemerintahan, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 memperkuat peran percepatan pembangkit EBT melalui RUPTL dan roadmap penghentian operasi PLTU. Sedangkan Peraturan Menteri ESDM menetapkan pedoman jual beli listrik EBT dan regulasi surya atap yang memberi insentif lebih luas. Lebih lanjut, Perpres 11/2023 mengatur urusan konkuren di sub bidang Energi Baru Terbarukan di daerah sebagai instrumen desentralisasi energi.
Salah satu aspek kebijakan strategis yang perlu dimunculkan adalah Peta Jalan Keadilan Energi Nasional. Alih-alih mengejar kapasitas semata, pemerintah harus mengukur sukses dari seberapa merata manfaat energi dirasakan. Indikator baru bisa mencakup jumlah rumah tangga kurang mampu yang beralih ke energi terbarukan, jumlah desa mandiri energi, dan pengurangan kesenjangan akses antar wilayah.
Langkah berikutnya adalah membentuk Dana Transisi Energi Berkeadilan. Dana ini dapat digerakkan melalui pungutan ekspor sumber daya fosil, kontribusi korporasi energi besar, atau insentif pajak CSR sektor energi.
Dana itu kemudian diarahkan untuk membiayai proyek energi terbarukan di daerah tertinggal, membiayai inovasi lokal, dan memperkuat program energi komunitas. Dengan demikian transisi bukan hanya proyek teknologi tetapi gerakan inklusif yang memperkuat kemandirian masyarakat lokal.
Kebijakan ke depan harus mengusung prinsip Just Energy Transition secara konsisten. Transisi ke energi bersih tidak boleh menciptakan ketidakadilan baru, misalnya menggantikan batubara dengan biofuel yang merampas lahan petani atau mengorbankan lingkungan lokal.
Transisi adil berarti perubahan yang berpihak pada manusia dan alam secara bersama. Ini harus memprioritaskan kelompok paling rentan, memastikan distribusi manfaat, dan mencegah munculnya korban baru di balik proyek energi hijau.
Ketahanan dan keadilan energi sejatinya saling memperkuat. Tanpa keadilan, ketahanan hanya stabilitas semu. Tanpa ketahanan, keadilan tak punya dasar operasional. Pemerintah harus menyadari bahwa kekuatan energi nasional bukan diukur dari megawatt yang dihasilkan, melainkan dari seberapa dalam energi itu mampu menyalakan harapan masyarakat di pelosok negeri. Energi bukan sekadar bahan bakar pabrik, tetapi urat nadi kehidupan dan keadaban.
Refleksi atas satu tahun pemerintahan ini adalah kesempatan memperbaiki arah. Visi kemandirian energi telah muncul, namun harus dipertajam dengan keberpihakan konkret. Keadilan energi bukan hanya wacana retoris, tetapi fondasi untuk ketahanan sejati. Indonesia tidak akan benar-benar berdaulat energi jika sebagian rakyatnya masih hidup dalam kegelapan, baik secara harfiah maupun sosial.
Pemerintah dan DPR masih memiliki ruang untuk menulis bab baru dalam sejarah energi Indonesia. Bab yang tidak lagi bicara tentang keseragaman kebijakan, tetapi keberagaman kebutuhan. Bab yang tidak hanya bicara kapasitas, tetapi keadilan. Mari wujudkan energi yang adil, agar listrik yang menyala bukan hanya di kota besar, tetapi di setiap sudut negeri.
(miq/miq)

 3 months ago
32
3 months ago
32