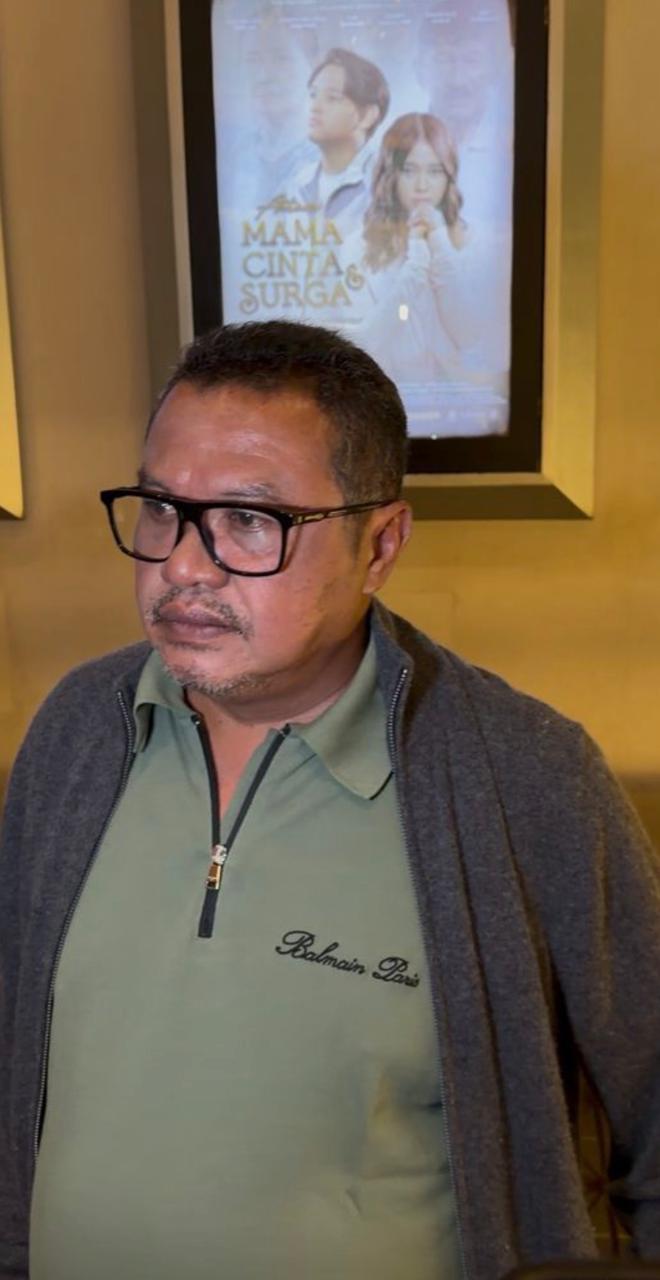Oleh: Farid Wajdi
Program Makan Bergizi Gratis dipromosikan sebagai terobosan sosial. Negara hadir, anak-anak kenyang, angka gizi buruk diklaim menurun.
Narasi ini bekerja efektif di ruang politik dan kampanye. Ia menyentuh emosi sekaligus memberi kesan keberpihakan. Namun di balik janji besar itu, pertanyaan mendasar justru terlewat: bergizi versi siapa, sehat untuk apa, dan berkelanjutan sampai kapan.
Program ini berdiri di atas asumsi sederhana: persoalan gizi selesai jika negara menyediakan makanan. Logika ini tampak masuk akal, tetapi rapuh.
Gizi tidak hanya soal isi piring hari ini, melainkan kualitas pangan, kebiasaan makan, rantai produksi, serta dampak kesehatan jangka panjang.
Ketika kompleksitas itu dipadatkan menjadi program distribusi massal, yang lahir bukan solusi, melainkan ilusi kebijakan.
Piring Gratis, Standar Gizi Murah
Kritik pertama terletak pada standar gizi yang digunakan. Program berskala nasional menuntut kecepatan, keseragaman, dan efisiensi biaya.
Akibatnya, kualitas pangan menjadi variabel yang paling mudah dikompromikan. Menu cenderung berbasis karbohidrat murah, protein olahan, dan pangan instan yang mudah didistribusikan.
Carlos Monteiro (2019) menegaskan, “Makanan ultra-olahan diproduksi untuk efisiensi industri, bukan kesehatan, dan konsumsi jangka panjangnya berkaitan dengan obesitas serta penyakit kronis”.
Ketika pangan jenis ini masuk program negara, risiko kesehatan tidak hilang hanya karena label gratis.
Fortifikasi sering dijadikan pembenaran. Vitamin dan mineral sintetis ditambahkan, lalu menu dinyatakan bergizi.
Padahal gizi tidak bekerja seperti suplemen. Tubuh memerlukan keutuhan pangan: serat, mikrobiota, struktur alami protein dan lemak.
Hardinsyah (2020) mengingatkan, “Gizi seimbang tidak bisa digantikan oleh pangan instan meski diperkaya zat gizi, sebab tubuh membutuhkan kualitas pangan utuh”. Pesan ini relevan, terutama ketika negara memilih jalur praktis.
Masalah lain muncul pada homogenisasi selera. Anak-anak dari Aceh sampai Papua disuguhi menu seragam. Pangan lokal tersisih.
Padahal keragaman pangan merupakan kunci gizi berkelanjutan. Ketika selera dibentuk oleh menu massal, generasi muda tumbuh jauh dari sumber pangan lokalnya sendiri.
Program gratis juga mengubah relasi sosial terhadap makanan. Makan bukan lagi proses belajar, melainkan rutinitas konsumsi.
Anak-anak menerima, tanpa diajak memahami. Dalam jangka panjang, kebiasaan makan sehat sulit tumbuh jika negara hanya berperan sebagai penyedia, bukan pendidik.
Politik Anggaran dan Harga Kesehatan
Di balik dapur besar program makan gratis, tersimpan persoalan anggaran. Program ini menyedot dana publik dalam jumlah masif.
Setiap rupiah yang masuk ke skema distribusi pangan instan berarti rupiah yang tidak dialokasikan ke pendidikan gizi, perbaikan sanitasi, akses air bersih, atau penguatan pangan lokal.
Marion Nestle (2018) menulis, “Kebijakan pangan jarang digerakkan oleh ilmu gizi semata; kepentingan politik dan ekonomi sering lebih dominan”.
Program makan gratis tidak kebal dari logika ini. Ia mudah dijual secara politik, sulit dikritik tanpa dicap tidak pro-rakyat.
Di sisi lain, risiko kesehatan muncul pelan-pelan. Beban penyakit tidak menular meningkat. Obesitas anak tumbuh berdampingan dengan stunting. Fenomena ini bukan paradoks, melainkan konsekuensi pola makan rendah kualitas.
FAO (2019) mendorong konsep sustainable healthy diets, pola makan sehat, terjangkau, relevan secara budaya, dan ramah lingkungan. Program makan gratis bergerak ke arah sebaliknya: terpusat, seragam, dan bergantung pada rantai pasok industri.
Rita Ramayulis (2021) menekankan, “Pangan lokal berpotensi memenuhi kebutuhan gizi jika didukung kebijakan, edukasi, dan pengolahan yang tepat”.
Program makan gratis justru berisiko mematikan insentif pengembangan pangan lokal karena negara memilih jalur cepat.
Masalah tata kelola juga tak terhindarkan. Skala besar membuka ruang pemborosan, kualitas turun, dan potensi penyimpangan.
Kontrol mutu sulit dilakukan ketika target utama sekadar jumlah porsi. Dalam situasi ini, keberhasilan administratif menutup kegagalan substantif.
Pertanyaan penting muncul: apa yang tersisa setelah program selesai atau anggaran menyusut? Kebiasaan makan sehat tidak otomatis terbentuk.
Infrastruktur pangan lokal tidak tumbuh. Yang tertinggal hanya ingatan pernah makan gratis, tanpa jaminan masa depan lebih sehat.
Program makan bergizi gratis tampak heroik di permukaan. Namun tanpa keberanian mengubah paradigma, ia berisiko menjadi monumen kebijakan populis.
Piring terisi hari ini, tetapi kesehatan publik dibayar mahal esok hari. Gizi sejati menuntut lebih dari sekadar gratis. Ia memerlukan kualitas, keberlanjutan, dan kejujuran kebijakan.
Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.