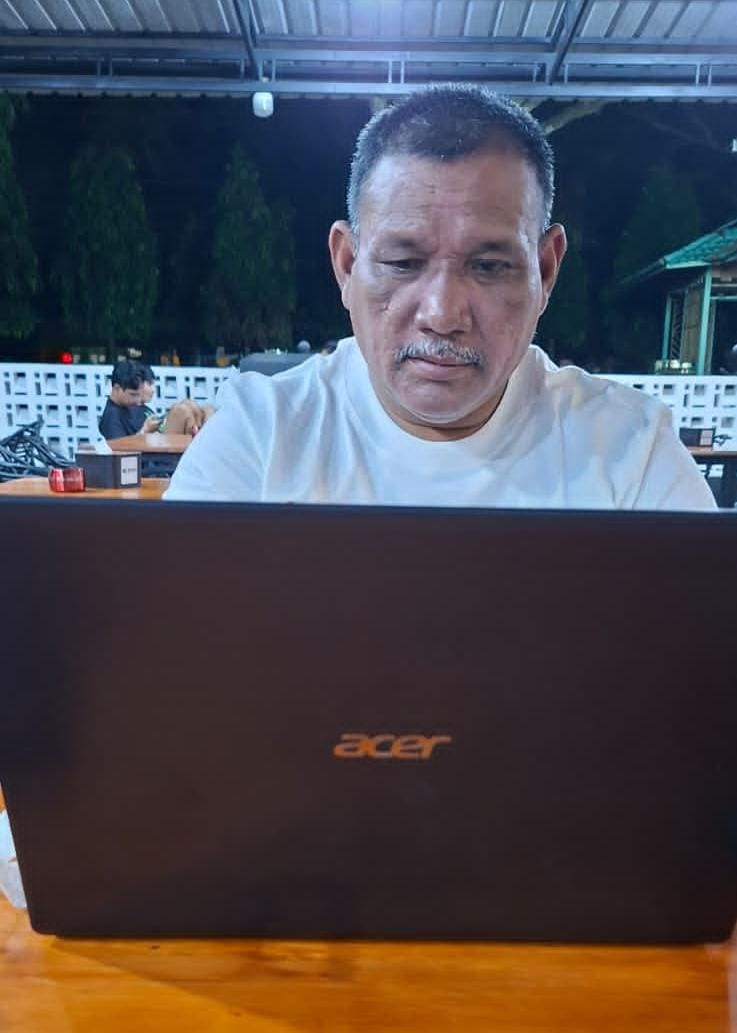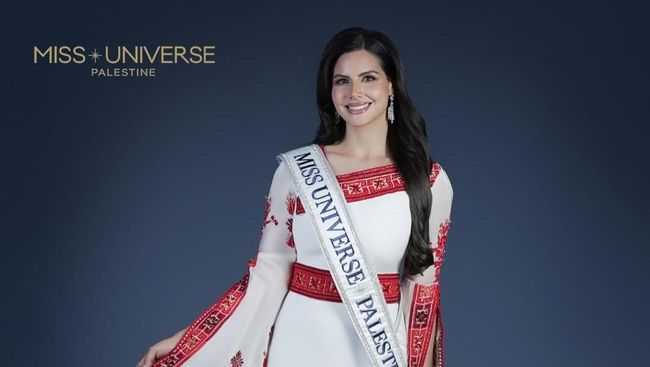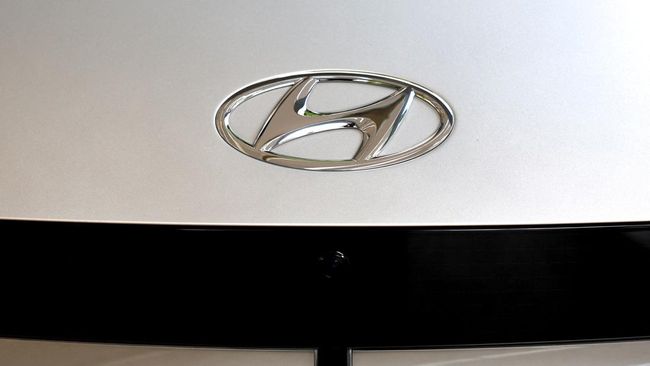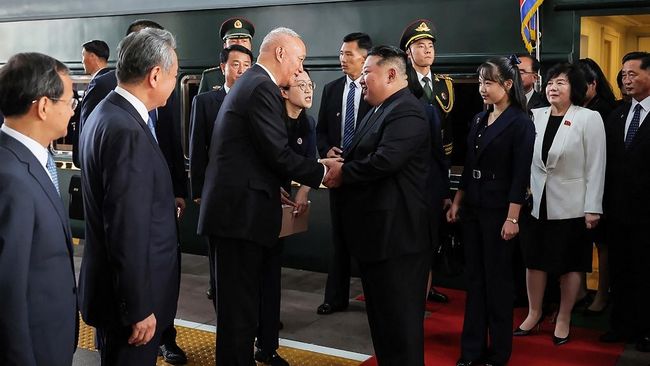Oleh: Assoc Prof Dr Farid Wajdi, SH, MHum
Kisruh soal “dana mengendap” Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuka luka lama dalam tata kelola fiskal daerah: uang rakyat yang seharusnya bekerja untuk pembangunan justru dibiarkan tidur di rekening bank.
Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN
Alih-alih membedah akar persoalan dan memperbaiki sistem belanja, Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut justru sibuk meluruskan perbedaan angka antara klaim Kementerian Keuangan dan data versi daerah.
Perdebatan nominal bukan inti masalah; yang genting adalah fakta uang publik gagal menjalankan fungsi sosial dan ekonominya.
Kementerian Keuangan sebelumnya mengungkap dana daerah mengendap secara nasional mencapai Rp234 triliun.
Dari jumlah itu, sekitar Rp3,1 triliun dikaitkan dengan Sumatera Utara.
Bobby menampik, menyebut saldo kas daerah hanya Rp990 miliar. Namun, bantahan itu tidak otomatis menepis persoalan utama: rendahnya penyerapan anggaran dan lemahnya disiplin fiskal.
Uang sebesar apa pun yang tidak dibelanjakan untuk kepentingan publik tetaplah simbol kegagalan pemerintahan daerah dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.
Fakta kepala daerah lebih sibuk membantah angka daripada memperbaiki kinerja belanja menandakan pergeseran fokus dari tanggung jawab publik menuju pencitraan politik.
Padahal, setiap rupiah yang mengendap di rekening pemerintah daerah adalah bukti pelayanan publik tertunda, infrastruktur tak terbangun, dan ekonomi lokal kehilangan denyutnya.
Dana yang “diam” di bank ibarat darah yang berhenti mengalir dalam tubuh perekonomian daerah—dan pada titik tertentu, itu menjadi penyakit fiskal.
Lebih buruk lagi, pengendapan dana dalam jumlah besar membuka ruang bagi moral hazard.
Tak tertutup kemungkinan dana-dana tersebut “diparkir” dalam bentuk deposito yang menghasilkan bunga.
Sekalipun bunga itu masuk ke kas daerah, praktik ini tetap melanggar etika keuangan publik.
Negara tidak berbisnis dengan uang rakyat; negara berkewajiban menggerakkannya untuk kemaslahatan rakyat.
Bila bunga itu dinikmati pihak tertentu, maka bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi berpotensi menjadi korupsi terselubung.
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sepatutnya tidak berhenti pada klarifikasi angka.
Keduanya memiliki otoritas untuk menegakkan disiplin fiskal dan menjatuhkan sanksi terhadap pemerintah daerah yang gagal merealisasikan anggarannya.
Pemotongan transfer pusat, pembekuan dana insentif, atau audit khusus oleh BPK bisa menjadi langkah konkret.
Pengawasan harus menyentuh akar: dari perencanaan, proses pengadaan, hingga evaluasi belanja. Tanpa ketegasan, budaya “uang parkir” ini akan terus berulang setiap tahun anggaran.
Bagi Pemprov Sumut, langkah penyelamatan citra seharusnya dimulai dari transparansi penuh.
Publikasikan posisi kas daerah secara berkala, ungkap alasan keterlambatan realisasi, dan pastikan setiap rupiah digunakan tepat sasaran.
Reformasi manajemen belanja mesti menjadi prioritas: sederhanakan birokrasi, percepat proses pengadaan, dan pangkas tahapan yang menghambat eksekusi program publik.
Krisis fiskal daerah bukan hanya soal defisit, tetapi juga soal keengganan menggunakan uang yang tersedia secara efektif.
Ketika uang publik mengendap di kas pemerintah, rakyatlah yang menanggung akibat: jalan rusak tak diperbaiki, sekolah kekurangan sarana, dan layanan kesehatan tertinggal.
Sudah saatnya kepala daerah berhenti membela diri dan mulai bekerja memperbaiki sistem. Karena uang publik bukan milik pejabat, melainkan milik rakyat.
Uang rakyat tidak seharusnya tidur di rekening pemerintah—ia harus bekerja, menghasilkan kesejahteraan, dan menghidupkan keadilan sosial.
Ethics Of Care: Etika Yang Hilang Di Balik Kursi Kekuasaan
Mundurnya dua pejabat tinggi bukan sekadar riak politik, itu adalah ledakan alarm atas kegagalan mendasar dalam seni memerintah.
Ketika pejabat yang seharusnya menjadi pilar implementasi kebijakan memilih angkat kaki, yang tersisa bukan hanya kekosongan jabatan, tetapi jaringan kesalahan sistemik.
Jangan bermimpi menutup-nutupi hal ini sebagai masalah “kepribadian”; ini soal bagaimana kekuasaan dipraktikkan, apakah untuk melayani publik atau menegakkan dominasi personal?
Secara hukum-administratif, tindakan pejabat publik harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik: kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, dan kepentingan umum.
Bila seorang kepala daerah diduga memperlakukan bawahannya secara merendahkan atau sewenang-wenang di forum resmi, itu lebih dari pelanggaran etika, dan itu adalah potensi pelanggaran asas kepatutan dan bentuk maladministrasi yang merusak legitimasi tindakan administrasi berikutnya.
Keputusan yang lahir dari suasana takut dan tekanan psikologis dapat dipertanyakan keabsahannya; mereka berisiko menjadi dasar hukum yang rapuh dan rawan diuji di ranah pengawasan administratif ataupun perdata.
Lebih lanjut, gaya kepemimpinan yang dominan dan intimidatif menimbulkan biaya publik yang konkret. Birokrasi yang hidup dalam ketakutan tidak akan mengedepankan inovasi, melainkan kepatuhan pasif yang menghambat pelaksanaan program.
Anggaran tersendat, proyek melambat, serta potensi pembengkokan prosedur menjadi konsekuensi yang terukur—bukan sekadar retorika.
Dalam konteks ini, kegagalan manajerial berubah menjadi risiko hukum: pergeseran anggaran berulang dan praktik kontraktual yang terburu-buru meningkatkan eksposur terhadap penyimpangan dan penindakan koruptif.
Ada pula isu independensi fungsi pengawasan internal. Inspektorat dan badan kepegawaian seharusnya menjadi garansi akuntabilitas; bila lembaga-lembaga ini dilipat oleh logika kekuasaan, maka sistem kontrol internal runtuh.
Hasilnya bukan hanya hukum yang dilanggar, tapi kepercayaan publik yang terkikis — modal paling penting dalam legitimasi pemerintahan.
Ketika check-and-balance internal menjadi alat politik, tidak ada lagi pembaruan struktural yang berarti; hanya pergantian figur tanpa perubahan budaya.
Krisis ini menuntut respons hukum yang tegas sekaligus remedial administratif.
Pertama, perlu klarifikasi publik yang komprehensif mengenai alasan pengunduran diri pejabat: bukan sekadar pernyataan singkat, melainkan dokumen yang memaparkan fakta, proses, dan dasar hukum tindakan yang diambil pimpinan.
Kedua, penguatan mekanisme pengawasan internal harus menjadi prioritas: inspektorat dan lembaga terkait harus dipastikan punya akses, sumber daya, dan independensi untuk melakukan audit forensik kebijakan dan anggaran.
Ketiga, pembinaan etika administrasi dan kepemimpinan berbasis hukum harus diberlakukan wajib untuk semua pejabat eselon, bukan seminar seremonial, melainkan program evaluasi kinerja yang berkesinambungan dan transparan.
Kepemimpinan sejati diuji bukan oleh kekuatan untuk memaksa, melainkan oleh kapasitas untuk memelihara aturan.
Jika kekuasaan di daerah dibiarkan bertindak tanpa batas etika, negara hukum akan terkikis dari dalam.
Masyarakat tidak butuh penguasa yang pamer otoritas; ia butuh penyelenggara yang menegakkan hukum dan martabat manusia.
Bila tidak ada koreksi serius sekarang, yang tinggal hanya pemerintahan yang kuat di atas kertas, tetapi mati moral dan rapuh legalitasnya!
Etika publik bukan pelengkap; ia adalah prasyarat ketahanan hukum. Karena itu, setiap penyelenggara yang meremehkannya wajib dipanggil untuk mempertanggungjawabkan, secara politis, administratif, dan bila perlu, secara hukum.
Penulis adalah Founder Ethics Of Care/Anggota Komisi Yudisial 2015-2020
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.