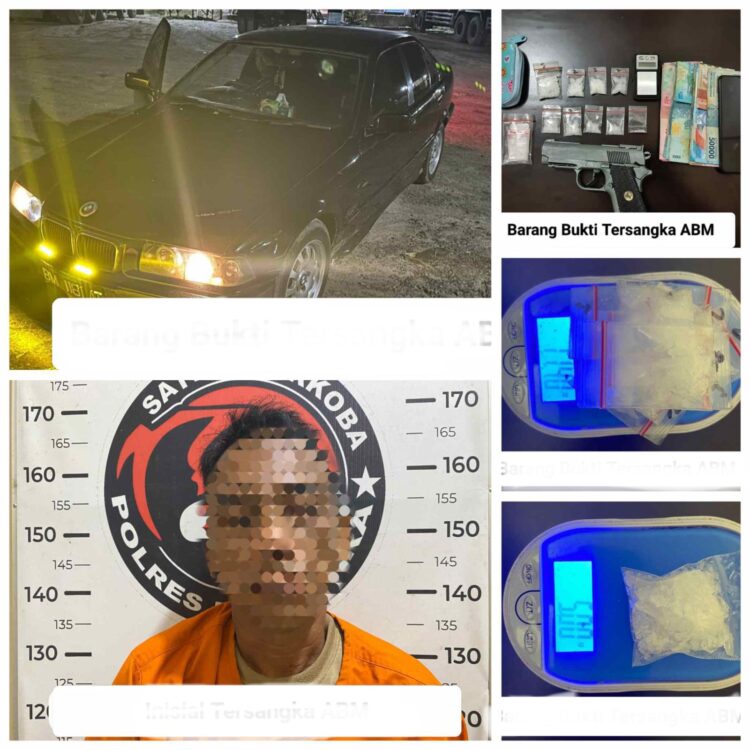Oleh: Farid Wajdi
Sumatera kerap tampil sebagai lanskap paradoks. Hutan hujan tropis, sungai-sungai besar, dan Pegunungan Bukit Barisan membentuk kekayaan ekologis yang mengagumkan. Namun, di ruang yang sama, bencana hadir berulang.
Banjir, longsor, kebakaran hutan, gempa bumi, dan tsunami menorehkan luka kolektif. Pulau ini seperti menulis eleginya sendiri, tahun demi tahun, lewat peristiwa serupa dengan korban berbeda.
Media massa mencatat pola tersebut secara konsisten. Kompas (2019–2024) memberitakan banjir tahunan di Sumatera Selatan dan Jambi, longsor di Sumatera Barat, serta kebakaran hutan di Riau. Tempo (2020–2023) menempatkan bencana sebagai persoalan struktural, bukan sekadar peristiwa alam.
Judul berita berubah, substansi tetap sama. Rumah terendam, jalur publik terputus, warga mengungsi. Situasi ini memberi kesan krisis berkepanjangan.
Dari sudut pandang geologi, Sumatera berada di kawasan rawan. BMKG (2023) menegaskan posisi Sumatera di jalur subduksi aktif lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Kondisi ini menjadikan gempa dan tsunami sebagai ancaman permanen.
Danny Hilman Natawidjaja (2022) dari BRIN, dalam wawancara dengan Tempo, menyebut pesisir barat Sumatera menyimpan potensi gempa besar akibat akumulasi energi tektonik yang belum sepenuhnya terlepas.
Namun, faktor alam hanya menjelaskan sebagian cerita. Banjir dan longsor menunjukkan relasi kuat dengan tata kelola lingkungan. Bambang Hero Saharjo (2020), guru besar kehutanan IPB, menjelaskan melalui Kompas tentang degradasi daerah aliran sungai di Sumatera.
Vegetasi penyangga berkurang, daya serap tanah menurun, dan limpasan air meningkat tajam saat hujan. Banjir lalu bergeser dari peristiwa ekstrem menjadi agenda musiman.
Arah pembangunan turut menjadi sorotan. Emil Salim (2018) menilai kerusakan ekologis di Sumatera lahir dari kebijakan pembangunan jangka panjang yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
Pandangan ini kerap dikutip media nasional setiap kali krisis banjir dan asap terjadi. Kritik tersebut tidak hanya bersifat moral, melainkan juga normatif, mengingat Indonesia telah memiliki kerangka hukum lingkungan yang relatif lengkap.
Dalam konteks hukum, bencana ekologis di Sumatera menyingkap persoalan penegakan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat prinsip pencegahan, kehati-hatian, dan tanggung jawab mutlak.
Namun, berbagai laporan media menunjukkan kesenjangan antara norma dan praktik. Tempo (2021) mencatat lemahnya penindakan terhadap pelanggaran izin lingkungan dan pembakaran lahan.
Dimensi hukum ini memperlihatkan bencana bukan hanya kegagalan ekologis, melainkan juga kegagalan institusional.
Kebakaran hutan dan lahan memperjelas persoalan tersebut. WALHI (2019) mengaitkan kebakaran berulang dengan ekspansi perkebunan skala besar. The Jakarta Post (2019) menyoroti dampak lintas negara akibat asap.
Dari perspektif hukum, kasus-kasus kebakaran menunjukkan penerapan sanksi administratif dan pidana sering berhenti pada aktor lapangan, sementara korporasi besar kerap luput dari pertanggungjawaban penuh. Situasi ini menimbulkan kritik tentang efektivitas rezim hukum lingkungan.
Trauma Historis
Dimensi sosial bencana tak kalah penting. Siti Zuhro (2021) dalam wawancara dengan Media Indonesia menekankan ketimpangan dampak.
Korban terbesar hampir selalu masyarakat lapisan bawah. Petani kecil, nelayan sungai, dan warga pinggiran kota kehilangan rumah sekaligus sumber penghidupan.
Dari sudut hukum, kelompok ini juga paling lemah aksesnya terhadap keadilan, baik dalam klaim ganti rugi maupun pemulihan hak pascabencana.
Gempa dan tsunami di pesisir barat Sumatera meninggalkan trauma historis mendalam. Tragedi Aceh 2004 dan Mentawai 2010 masih membekas. UNDP (2011) dalam laporan rekonstruksi Aceh mencatat solidaritas sosial tumbuh cepat pascabencana.
Namun, fase pemulihan jangka panjang menghadapi persoalan tata kelola, termasuk sengketa lahan dan distribusi bantuan. Dimensi hukum kebencanaan muncul melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama perlindungan warga terdampak. Implementasi norma ini kerap diuji di lapangan.
Di ruang opini, kritik terhadap tata ruang semakin menguat. Nirwono Joga (2022) dalam kolom Kompas menilai praktik pembangunan sering mengabaikan peta risiko bencana.
Kawasan resapan berubah menjadi permukiman, hutan lindung tergerus izin. Dari perspektif hukum tata ruang, kondisi ini mencerminkan lemahnya konsistensi antara rencana dan pelaksanaan, sekaligus minimnya sanksi terhadap pelanggaran zonasi.
Jurnalisme investigatif ikut memperdalam pembacaan publik. Tempo (2020–2023) mengungkap relasi kuasa antara korporasi, izin lahan, dan elit lokal.
Temuan ini menegaskan bencana ekologis tidak berdiri sendiri. Ada jejaring kepentingan ekonomi dan politik yang memengaruhi penegakan hukum. Kritik publik menguat, namun perubahan kebijakan berjalan lambat.
Di tengah situasi tersebut, kearifan lokal Sumatera sering disebut sebagai modal terabaikan. Taufik Abdullah (2018) menulis tentang peran pranata adat, seperti hutan larangan dan sistem nagari, dalam menjaga keseimbangan alam.
Pandangan ini dikutip Kompas sebagai contoh pengetahuan lokal relevan bagi mitigasi modern. Dalam perspektif hukum, pengakuan masyarakat adat dan hak ulayat membuka ruang integrasi antara hukum negara dan norma lokal.
Elegi bencana Sumatera pada akhirnya menjadi cermin kolektif. Ia memantulkan wajah kebijakan, etika pembangunan, dan kualitas penegakan hukum.
Media massa, pakar, dan masyarakat sipil telah lama menyuarakan peringatan. Tantangan terbesar terletak pada keberanian politik dan konsistensi institusional.
Selama eksploitasi tetap menjadi poros utama pembangunan, elegi ini akan terus ditulis ulang. Namun, bila norma hukum, pengetahuan ilmiah, dan kearifan lokal dijalankan secara sungguh-sungguh, Sumatera memiliki peluang keluar dari siklus duka.
Alam selalu memberi isyarat. Respons manusia terhadap isyarat itulah yang menentukan apakah elegi berubah menjadi pelajaran, atau tetap menjadi ratapan panjang di halaman berita media massa.
Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.