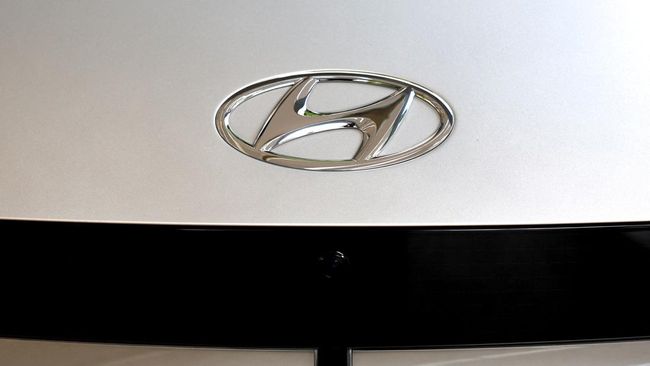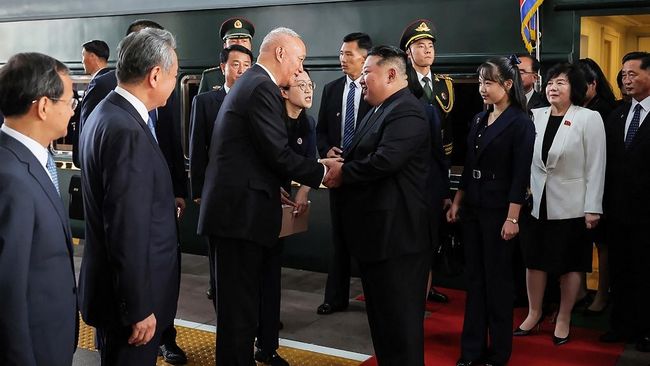Ukuran Font
Kecil Besar
14px
Oleh Edy Suhartono
Intro
Artikel ini diinspirasi oleh pidato inagurasi Saturnino M. Boras atau akrab disapa Jun Borras, Professor bidang kajian Agraria di International Institute of Social Studies (ISS) ,The Hague, saat memberikan kuliah umum pada 14 April tahun 2016 dengan judul pidato “Land politics, Agrarian Movements and Scholar-Activism”. Kuliah umum dan pidato inagurasi ini kemudian digambarkan secara lebih detail dalam buku yang ditulisnya bersama dengan Jennifer C. Franco yang diterbitkan pada tahun 2023 oleh Practical Action Publishing, UK dengan judul “Scholar – Activism and Land Struggle”.
Kuliah umum serta buku yang diterbitkan oleh Jun Borras ini mengungkap secara detail tentang eksistensi scholar activism (aktivis akademisi ) kaitannya dengan perjuangan petani mendapatkan tanah (land struggle) dan lazim dikenal sebagai gerakan reforma. Eksistensi scholar activism ini menjadi sangat menarik untuk dilihat lebih jauh , tidak hanya pada konteks perjuangan petani untuk mendapatkan tanah (gerakan reforma agraria) sebagaimana yang dikemukakan oleh Jun Borras, tapi juga pada aspek maupun issu issu lainnya yang dilakukan oleh NGO di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Posisi dan eksistensi serta relasi antara akademisi dan aktivis menjadi sebuah tema yang menarik untuk dicermati ditengah semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi dalam rangka mengatasi berbagai problem yang ada saat ini baik terkait dengan masalah demokrasi, hak azasi manusia, ketidakkeadilan, kerusakan lingkungan hidup, ekploitasi dan akses terhadap sumber daya alam serta ancaman terhadap keberlanjutan eksosistem dan peradaban manusia.
Secara konseptual, scholar- activism (aktivis – akademisi) menurut Jun Borras adalah sebuah kategori yang merupakan subkumpulan dari akademisi ketika mereka bekerja di institusi akademis, atau dari aktivis ketika mereka bekerja di organisasi-organisasi aktivis atau gerakan agraria. Ini berarti, mereka hanya merupakan subkumpulan kecil dari kategori yang lebih besar – dan mereka bukan satu-satunya aktor relevan yang menghasilkan ide-ide radikal dan progresif. Akademisi dan aktivis progresif serta radikal bahkan merupakan produsen pengetahuan yang lebih besar (Borras, 2023).
Ada tiga type yang membedakan akademisi aktivis yang terkoneksi dengan gerakan perubahan politik di masyarakat, menurut Jun Borras, (i) akademisi-aktivis yang terutama berada di institusi akademik yang melakukan pekerjaan aktivis; (ii) akademisi-aktivis yang terutama berbasis di gerakan sosial atau proyek politik dan melakukan akademisi-aktivisme dari dalam; dan (iii) akademisi-aktivis yang terutama berada di lembaga penelitian independen non-akademik.
Dari konsepsi aktivis akademis sebagaimana yang digambarkan oleh Jun Borras di atas, Frances Fox Piven (2010), melihat bahwa akademisi aktivis akan berada pada situasi yang terpecah sebagaimana yang diungkapkannya di bawah ini;
“Ketika kita berkomitmen pada gerakan yang sering kali tidak teratur yang mencoba memajukan penyebab politik kelompok-kelompok ini, ketika kita bergabung dalam kritik kita terhadap pengaturan institusional yang coba diubah oleh gerakan tersebut — untuk berkomitmen pada gerakan itu sendiri… Inilah jenis komitmen yang terpecah, antara karir akademis dan aktivisme pembangkang, yang memicu refleksi tentang bagaimana melakukan keduanya”
Terkait dengan hal di atas, Charles Hale melihat adanya komitment ganda (dual commitment) yang mewarnai karakter diatas, yakni sebagai karakter yang menentukan dari akademisi-aktivis: kepada akademisi dan perjuangan politik. Argumen Hale bukanlah metode penelitian aktivis yang cocok untuk semua proyek akademik, atau bahwa semua pengetahuan inovatif, radikal, atau transformatif dihasilkan dengan cara ini. Sebaliknya, metode penelitian aktivis berdiri sebagai salah satu opsi di antara banyak opsi lainnya, tetapi sangat cocok digunakan ketika sekelompok orang yang terorganisir dalam perjuangan sangat memperhatikan pertanyaan analitis yang dihadapi dan ketika kondisi perjuangan mereka sendiri melibatkan tantangan terhadap paradigma analitis yang ada
Aktivis Akademisi di Indonesia
Menarik apa yang dikemukakan beberapa ahli di atas bila dikaitkan dengan konteks Indonesia saat ini, di mana hubungan antara aktivis dan akademisi sangat begitu terkait satu sama lain. Akademisi yang duduk di perguruan tinggi menjadi dosen biasanya adalah mereka yang saat menjadi mahasiswa adalah seorang aktivis (bedakan dengan aktivis dalam konteks kerja di NGO). Namun, ketika sudah menjadi akademisi (dosen) mereka tidak lagi aktif sebagai aktivis di lapangan, namun tetap terhubung dengan aktivis dan beberapa diantaranya (walau tak banyak) tetap aktif sebagai aktivis di lembaga lembaga non pemerintah (baca: /NGO).
Aktivis akademisi adalah mereka yang selama ini berada di kampus (dunia akademis) yang melakukan kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat namun ada juga yang aktif atau menjadi bagian dari aktivis gerakan NGO yang melakukan pemberdayaan dan pendampingan serta pemihakan dan pembelaan terhadap kelompok dampingan dan masyarakat yang terkena dampak dari berbagai persoalan yang ada akibat pembangunan dan penerapan kebijakan yang merugikan. Mereka bisa aktif di berbagai bidang dan issu seperti: Demokrasi, HAM, lingkungan hidup, perempuan, anak, buruh , tani, nelayan, masyarakat adat serta masyarakat miskin di perkotaan.
Orientasi aktivis dan gerakan NGO yang ada di Indonesia saat ini menunjukkan perubahan seiring dengan perubahan yang ada baik di elit politik kekuasaan (rezim) dan dinamika trend gerakan NGO yang ada. Pergantian rezim kekuasaan dari Orde Reformasi ke Orde Pasca Reformasi secara nyata dan signifikan berhasil melemahkan gerakan NGO di negeri ini. Elemen masyarakat sipil (civil society) termasuk NGO sepertinya terhipnotis secara politis oleh rezim yang berhasil “menjinakkan” gerakan dan aktivitas NGO yang ada dengan cara merekrut para aktivis masuk ke dalam lingkaran kekuasaan dan menduduki berbagai posisi dan jabatan strategis. Inilah strategi yang berhasil diterapkan untuk meredam progresivitas gerakan para aktivis dan NGO yang ada. Dan realitas ini tampaknya masih berlanjut hingga saat ini.
Berbeda dengan fenomena hubungan Aktivis dan NGO dengan kekuasaan di atas, dinamika relasi aktivis akademisi (scholar activism) menunjukkan hal yang berbeda di mana tidak banyak aktivis – akademis yang aktif dan benar benar serius mendukung sepenuhnya dan berpihak pada masyarakat melalui hasil kajian yang bisa dijadikan alat advokasi untuk memperjuangkan masalah yang sedag dihadapi. Mereka para aktivis akademi hanya sekedar meneliti dan memberikan rekomendasi terhadap persoalan yang diteliti. Untuk memastikan bahwa hasil kajian akan diterapkan tidak menjadi kewenangan para aktivis akdemisi apalagi memberikan dampak nyata perubahan bagi masyarakat yang diteliti.
Kolaborasi aktivis dan akademisi belum sepenuhnya memberi manfaat dan dampak konkrit perubahan baik di masyarakat maupun ditingkat elitdalam bentuk perubahan kebijakan secara politis. Sebaliknya, kelindan antara akademisi (baca : kampus) dan aktivis (baca : NGO) lebih didasarkan pada kebutuhan praktis dan pragmatis. Akademisi (kampus ) membutuhkan kerjasama atau kolaborasi dengan para aktivis (NGO) untuk menaikkan akreditasi maupun indeks kinerja utama kampus dalam rangka penilaian oleh para assessor sehingga hal ini menjadi semacam tuntutan yang harus bisa dipenuhi. Bagi kalangan aktivis maupun NGO, sebenarnya tidak ada manfaat yang dirasakan secara langsung kecuali sebatas membantu mengkampanyekan issu dan program yang sedang dijalankan; dan berharap kalangan akademisi bisa menjadi “kawan” (friend of activism/NGO) untuk mendukung sepenuhnya perjuangan yang sedang dilakukan melalui publikasi hasil penelitian maupun testimoni (kesaksian) bila diperlukan. Sejauah mana kolaborasi ini akan memberi dampak perubahan secara konkrit dimasyarakat dan secara politis di level kebijakan, tampaknya masih jauh dari yang diharapkan. Pelibatan aktivis dan NGO, tak lebih hanya sekadar menjadi stempel, untuk menunjukkan bahwa pemerintah maupun kampus yang bersangkutan sudah melibatkan masyarakat maupun NGO.
Apa yang diungkapkan oleh Jun Borras melalui pidato dan bukunya tentang “scholar activism and land struggle” menunjukkan korelasi yang cukup signifikan bagi perjuangan gerakan reforma agraria, yang secara serius ditunjukkan oleh para scholar activism yang intens memberikan pengaruh dan kontribusi bagi perubahan tidak hanya pada tataran politis (kebijakan) tapi juga tingkatan praktis di lapangan khususnya dalam perjuangan mendapatkan tanah (“land struggle”) melalui berbagai kajian dan kegiatan intelektual. Hasil kajian/riset ini tidak hanya disimpan sebagai arsip dokumen hasil peneitian tapi juga menjadi alat “advokasi” bagi petani untuk berjuang mendapatkan tanah (reforma agraria). Dan upaya ini mendapat dukungan sepenuhnya dari kampus baik secara politis maupun akademis serta jejaring gerakan sosial dan intelektual di tingkat global. Realitas inilah yang tampaknya belum terbangun sepenuhnya di negeri ini ketika pola hubungan aktivis akademisi masih lebih banyak memberikan manfaat dan berorientasi pada kepentingan dunia akademik (baca: kampus) ketimbang memberikan solusi dan pemihakan pada persoalan di tingkat grass root. Inilah realita yang tergambar dari hubungan antara aktivis akademisi di negri ini. Demikian kurang lebih. WASPADA.id
Penulis adalah Dosen Antropologi UNIMED
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.