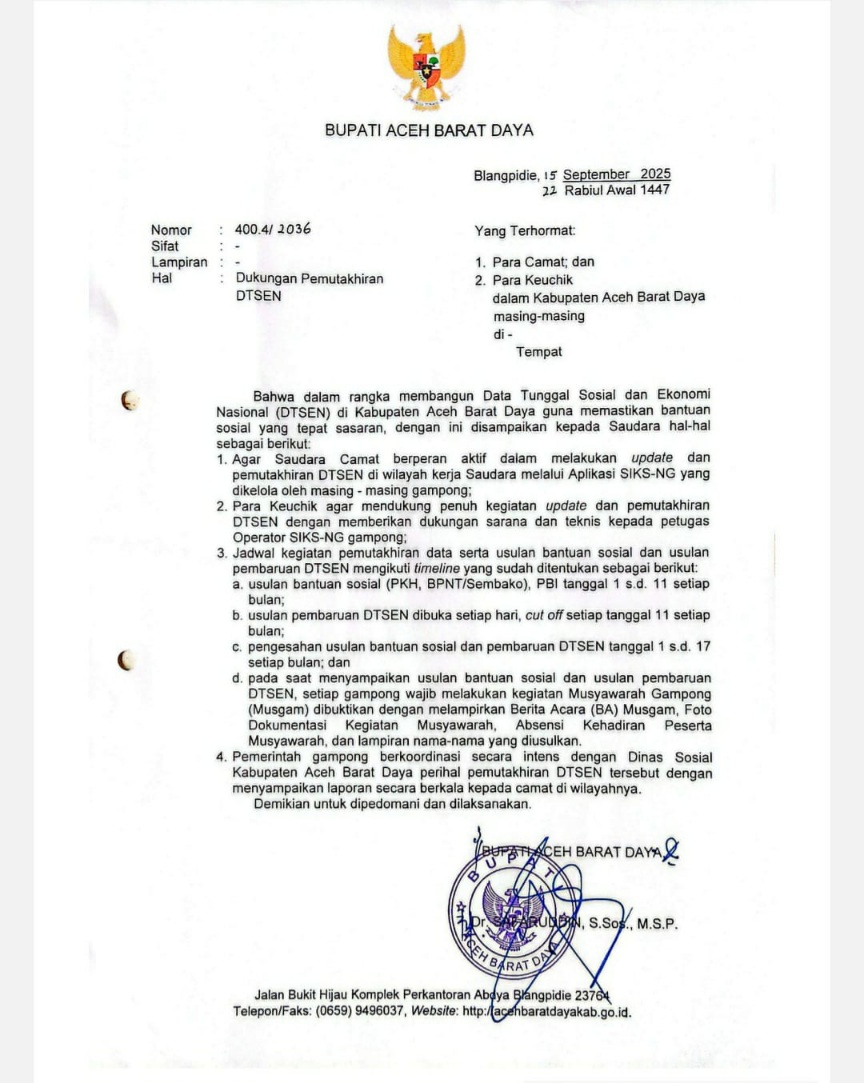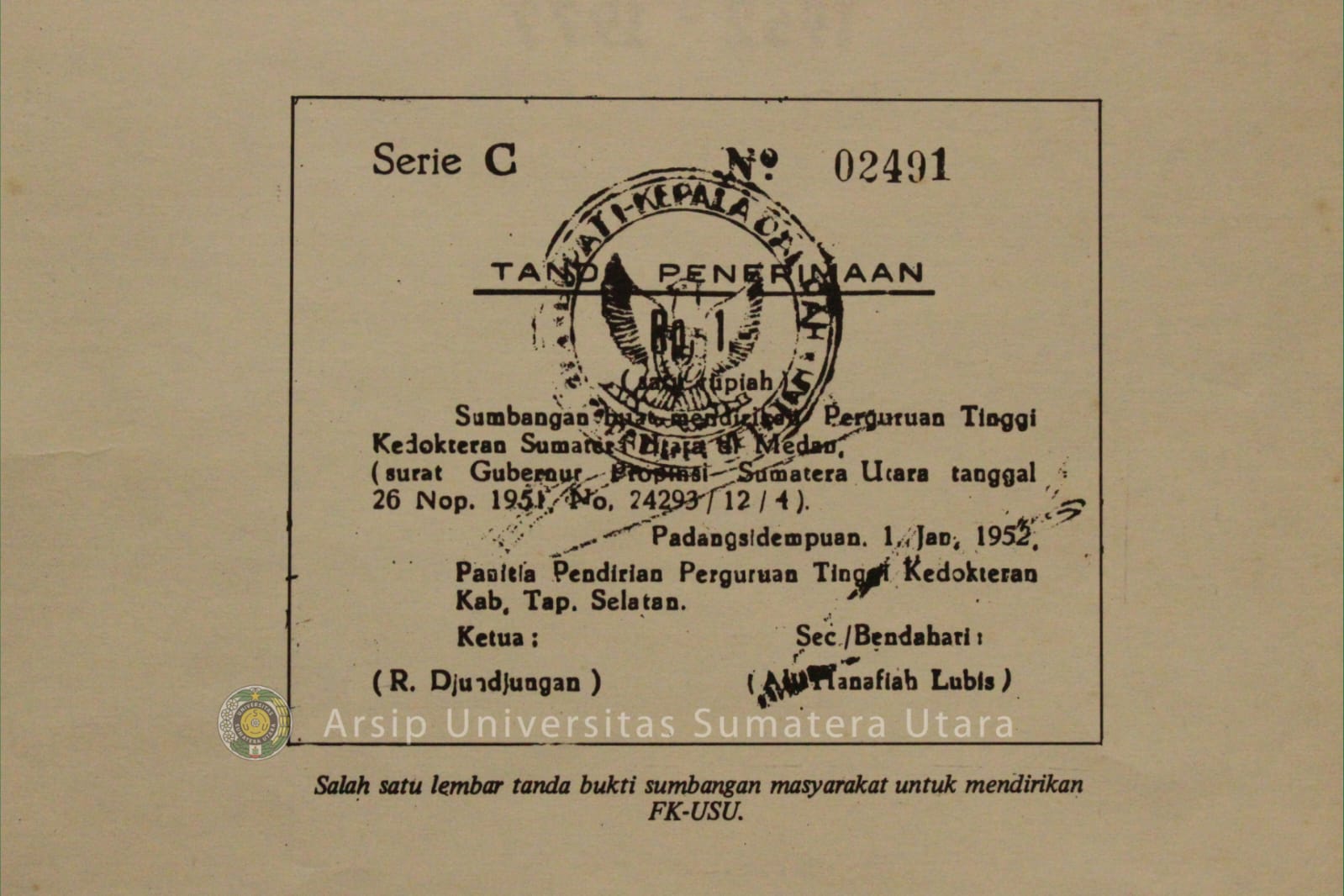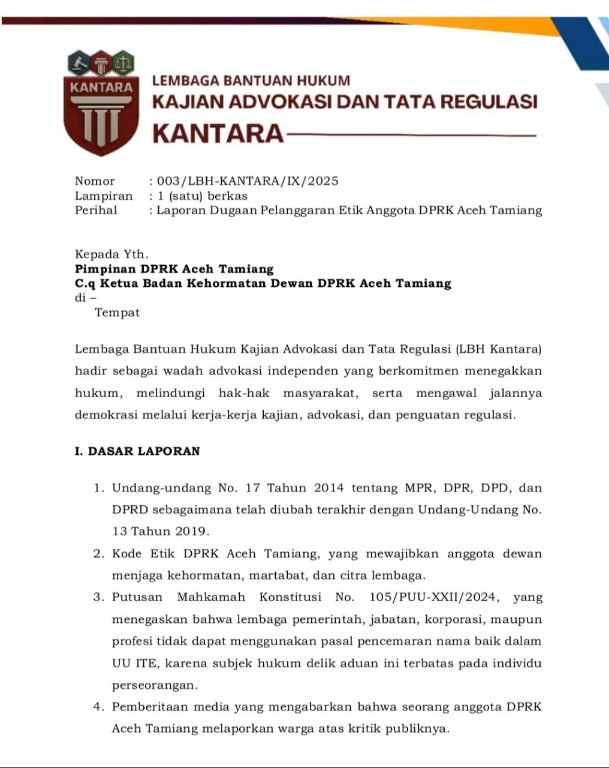Oleh: Dr. H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn
Dalam pergaulan hukum tata negara modern, pengampunan merupakan salah satu instrumen negara yang mencerminkan sisi humanisme dan kebijaksanaan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem hukum Indonesia, pengampunan terbagi menjadi empat bentuk: grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Namun dari keempatnya, amnesti dan abolisi memiliki posisi strategis karena secara eksplisit diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”
Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN
Kedua bentuk pengampunan ini kerap digunakan dalam konteks politik, dan di sinilah ketajaman problematika konstitusional dan etikanya muncul. Untuk itu, membedah secara tajam perbedaan, fungsi, serta implikasi dari abolisi dan amnesti bukan sekadar diskursus akademik, tetapi kebutuhan demokrasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang justru melemahkan supremasi hukum.
Memahami Perbedaan Konseptual: Bukan Sekadar Istilah
Secara konseptual, amnesti adalah pengampunan yang menghapuskan seluruh akibat hukum dari suatu tindak pidana, biasanya pidana politik, yang dapat diberikan sebelum atau sesudah adanya proses hukum. Amnesti bersifat kolektif, dan dapat melibatkan sekelompok individu, sebagai bagian dari proses rekonsiliasi politik atau pemulihan sosial nasional. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pemberian amnesti kepada eks-pemberontak PRRI/Permesta di masa Orde Lama menjadi contoh penting betapa negara menggunakan instrumen ini untuk meredakan ketegangan politik.
Sementara itu, abolisi adalah penghapusan proses hukum terhadap seseorang yang sedang berhadapan dengan mekanisme penegakan hukum, sebelum dijatuhkannya putusan pengadilan. Abolisi bersifat individual dan preventif, dan lebih ditujukan untuk menghentikan perkara yang dipandang tidak tepat atau menimbulkan potensi eskalasi politik dan sosial. Oleh karena itu, abolisi tidak menghapus perbuatan pidananya, tetapi menghentikan proses hukum terhadap pelakunya.
Tantangan Yuridis: Antara Prerogatif dan Pengawasan
Meskipun Pasal 14 UUD 1945 menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden harus dengan pertimbangan DPR, namun pada praktiknya muncul pertanyaan kritis: Sejauh mana DPR benar-benar menjalankan fungsi kontrol secara objektif terhadap keputusan Presiden? Apakah pertimbangan DPR bersifat prosedural formal ataukah betul-betul substantif dalam menguji dasar pemberian pengampunan?
Ketika DPR bersikap pasif atau hanya menjalankan fungsi kontrol secara simbolik, maka yang terjadi adalah delegasi kekuasaan absolut dalam pengampunan, yang rawan disalahgunakan untuk melindungi afiliasi politik, kelompok tertentu, atau bahkan menutup skandal hukum yang sesungguhnya harus diselesaikan secara transparan di pengadilan.
Keseimbangan antara Keadilan Hukum dan Keadilan Politik
Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, pengampunan tidak boleh dimaknai sebagai jalan pintas untuk meloloskan seseorang dari tanggung jawab hukum. Baik amnesti maupun abolisi harus dilandasi pada prinsip kepentingan umum yang lebih besar, seperti menjaga stabilitas nasional, meredakan konflik politik, atau memulihkan trauma sejarah akibat represi atau kekerasan politik.
Namun demikian, penting untuk disadari bahwa keadilan politik tidak boleh mengorbankan keadilan hukum. Negara harus memastikan bahwa dalam setiap pemberian pengampunan, ada argumen yuridis dan rasionalitas moral yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sipil, media, dan akademisi untuk terus mengawasi dan mengkritisi pemberian pengampunan agar tidak menyimpang dari semangat konstitusi.
Menjaga Marwah Konstitusi melalui Etika Kekuasaan
Abolisi dan amnesti sejatinya adalah cermin dari wajah moral konstitusi, yang mengedepankan perikemanusiaan di atas legalisme yang kaku. Tetapi ketika keduanya digunakan tanpa akuntabilitas, maka yang terjadi bukanlah pengampunan, melainkan abuse of power yang merusak fondasi negara hukum itu sendiri.
Dalam situasi politik kontemporer yang kerap diwarnai polarisasi dan instrumentalitas hukum, negara membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya memiliki hak prerogatif, tetapi juga kebijaksanaan konstitusional. Presiden bukan hanya kepala negara, tetapi juga simbol moral tertinggi bangsa, yang harus menjadikan setiap keputusan pengampunan sebagai bentuk penegakan nilai-nilai keadilan yang substantif dan beradab.
Membangun Tradisi Pengampunan yang Adil
Pemberian amnesti dan abolisi harus diperlakukan sebagai tindakan konstitusional luar biasa, bukan sebagai mekanisme rutin apalagi politis. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan reformulasi kebijakan pengampunan negara yang lebih akuntabel, termasuk dengan memperkuat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan strategis tersebut.
Hanya dengan cara itulah kita dapat menjaga marwah konstitusi, memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum, dan membangun tradisi pengampunan negara yang adil, etis, dan berkeadaban.
Penulis adalah Akademisi dan Ketua Pengwil Sumut Ikatan Notaris Indonesia
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.