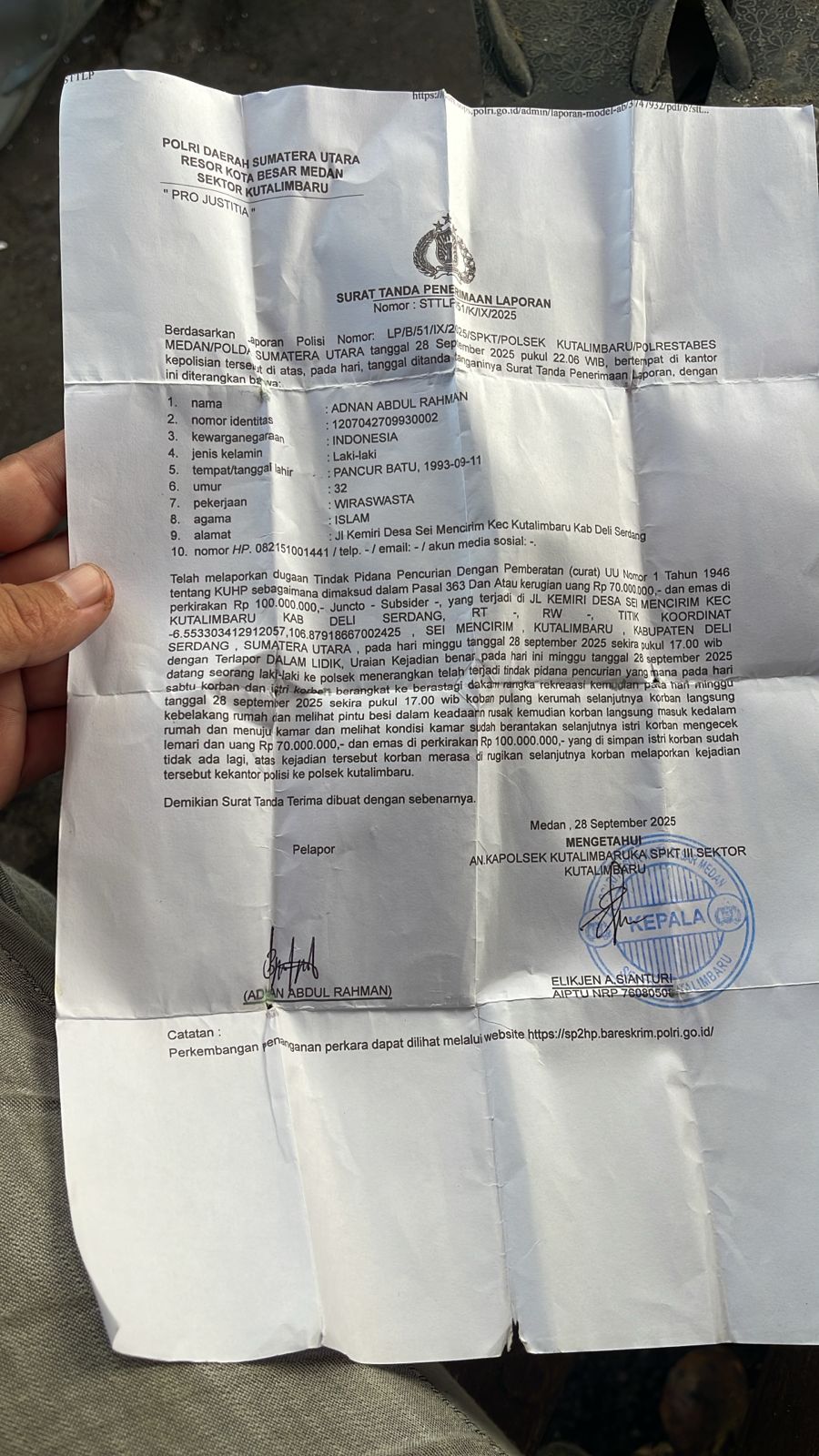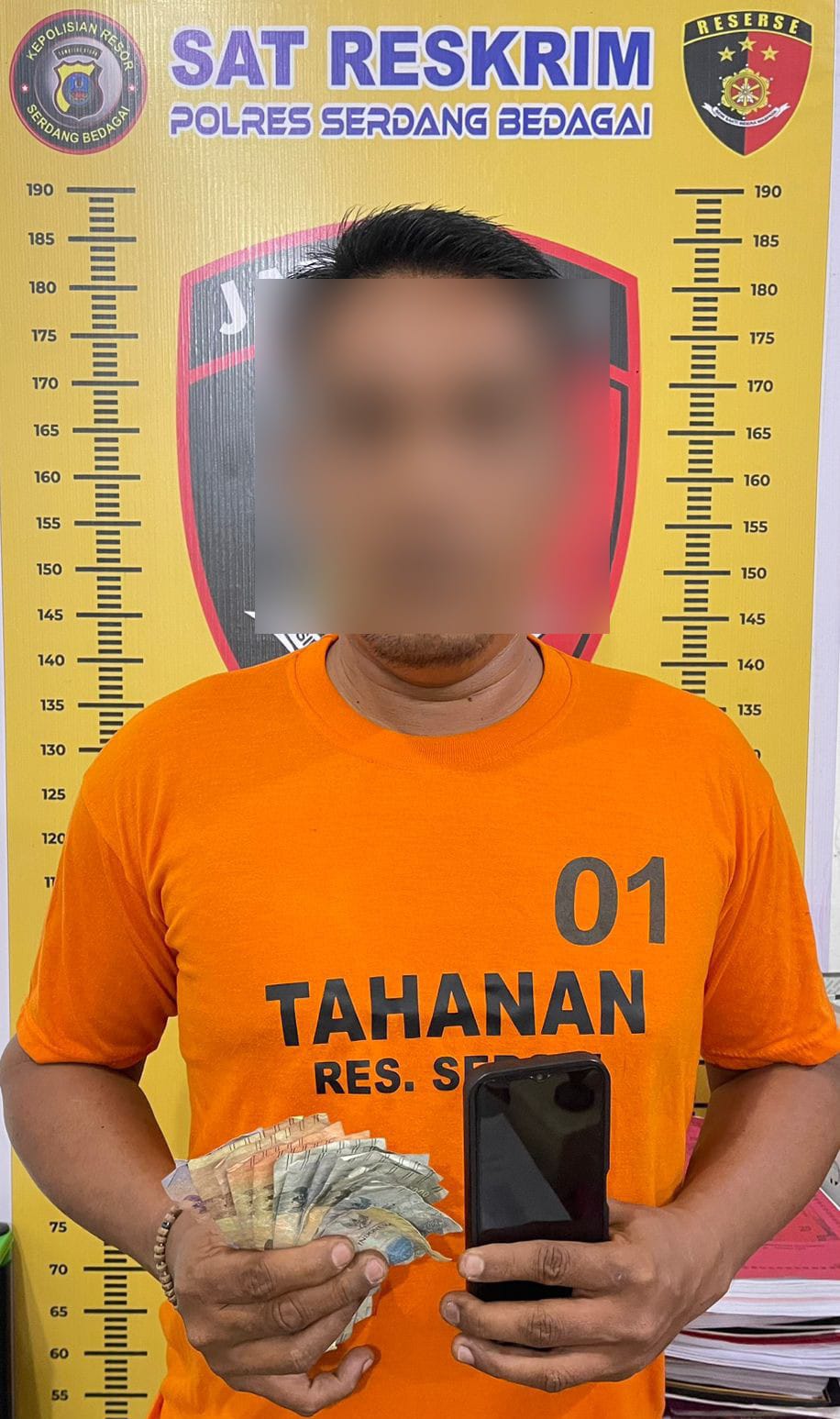Ukuran Font
Kecil Besar
14px
Oleh Fitriani, S.Pd., M.Sc
Pertanian pernah menjadi denyut nadi dan jantung kehidupan masyarakat pedesaan. Sawah bukan hanya sekadar lahan produksi pangan, melainkan identitas sosial dan ekonomi yang diwariskan secara turun-temurun. Namun hari ini, muncul fenomena yang mengkhawatirkan dan meresahkan: semakin banyak anak muda tidak lagi ingin bertani. Ketika generasi penerus bergegas meninggalkan sawah, pertanian bukan hanya kehilangan regenerasi tenaga kerja muda melainkan kehilangan jati dirinya. Bila ini dibiarkan terus-menerus, Indonesia akan menghadapi alarm krisis identitas pertanian dan kita tampaknya belum siap menghadapinya.
Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN
Fenomena ini lahir bukan tanpa sebab, karena bertani tidak lagi dipandang sebagai profesi yang bermartabat dan menjanjikan secara ekonomi. Anak-anak petani tumbuh menyaksikan sendiri orang tua mereka bekerja dari matahari terbit hingga petang tanpa menghiraukan panasnya terik matahari dan dinginnya hujan, kondisi cuaca yang tidak menentu, harga gabah yang jatuh, biaya produksi yang tinggi, serta ketergantungan pada tengkulak sehingga terjadi kemerosotan ekonomi petani.
Belum lagi bencana alam seperti yang terjadi sekarang ini di Sumatra, khususnya Aceh yang menenggelamkan ribuan hektare sawah yang siap panen di beberapa kabupaten seperti Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Bisa dibayangkan berapa besar kerugian yang dialami oleh petani sawah hanya karena ulah keserakahan manusia terhadap hasil alam.
Lalu, bagaimana mungkin profesi petani itu tampak sebagai masa depan yang cerah? Modernisasi pendidikan, urbanisasi, dan arus teknologi semakin mempertegas pandangan bahwa kesuksesan harus diraih bukan melalui bertani melainkan melalui profesi non-agraris.
Berdasarkan pengalaman di lapangan, orang tua tanpa sadar juga mendorong anak-anak mereka menjauhi sawah. Kalimat yang paling sering diucapkan orang tua kepada anaknya adalah “Belajarlah yang rajin agar tidak seperti kami,”. Namun, sayangnya pesan ini bukan sarana untuk memperkuat pertanian, namun lebih kepada memupuk rasa minder terhadap pertanian, bukan kebanggaan terhadap profesi petani dan menganggap pendidikan menjadi jalan keluar dari sektor pertanian.
Bertani sebenarnya itu profesi yang menjanjikan jika ditinjau dari aspek ekonomi, pendapatan masyarakat akan meningkat pesat jika harga jual gabah lebih tinggi dibandingkan harga produksi. Ironisnya, harga jual gabah yang diterima petani kerap tidak mampu menutupi biaya produksi. Meskipun pemerintah telah menetapkan harga dasar gabah minimal Rp6.500,00/kg, praktik di lapangan menunjukkan harga sering ditekan jauh lebih rendah karena dominasi tengkulak dalam rantai distribusi. Situasi ini semakin parah saat panen raya, ketika harga gabah jatuh ke kisaran Rp5.500.00 – Rp6.000,00/kg, sehingga keuntungan petani semakin menipis bahkan berpotensi merugi.
Saat bencana yang terjadi sekarang ini di Aceh harga gabah dibeberapa wilayah ditawar seharga Rp4.000.00/kg, bagaimana petani tidak menangis, modal yang mereka keluarkan tidak sesuai dengan hasil panen, dan bagaiman kaum millenial tertarik menjadi petani. Perlu diingat “tanpa generasi penerus, pertanian bukan sekadar menurun tapi berpotensi kolaps”.
Jadi apakah pertanian benar-benar tidak menjanjikan, atau sistemnya yang membuat petani tidak sejahtera? Pengalaman menunjukkan bahwa ketika pertanian dipadukan dengan teknologi, inovasi, dan akses pasar digital, anak muda mau kembali turun ke sawah. Munculnya petani milenial, komunitas agripreneur, tren urban farming, dan smart farming membuktikan bahwa generasi muda sebenarnya tidak anti bertani, mereka hanya anti kemiskinan yang melekat pada sektor pertanian selama ini.
Jadi, kuncinya bukan sekadar mengajak anak muda bertani, tetapi menciptakan sistem pertanian yang membuat mereka bangga dan sejahtera. Sudah saatnya negara mengubah cara pandang terhadap regenerasi petani. Transformasi pertanian tidak akan terjadi hanya dengan slogan “petani milenial,” tetapi melalui dukungan konkret berupa:
- Akses modal dan teknologi yang mudah, sehingga petani dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
- Jaminan harga hasil panen untuk melindungi petani dari fluktuasi pasar yang merugikan.
Stabilitas pasar dan pendidikan pertanian yang relevan dengan kebutuhan era modern. - Penyediaan fasilitas pertanian yang memadai, termasuk infrastruktur irigasi, alat mesin, dan sarana produksi lainnya.
Industrialisasi berbasis desa guna memperkuat rantai nilai pertanian dari hulu hingga hilir. - Jaminan sosial bagi petani dan keluarganya sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko usaha tani.
Jika hal-hal ini ada, sawah bukan lagi simbol penderitaan, melainkan simbol kemajuan. Indonesia dapat menjadi negara yang kuat hanya jika pertaniannya kuat. Dan pertanian hanya akan kuat jika anak-anak petani masih ingin bertani. Bila generasi penerus terus menjauh, kita akan menghadapi masa depan pangan yang genting bukan karena lahan habis, tetapi karena pewarisnya hilang.
Karena itu, mari jadikan bertani bukan sekadar warisan yang dipaksakan, tetapi pilihan yang membanggakan. Mari ciptakan dunia di mana anak petani tidak malu mengatakan saya ini seorang petani dan saya akan menjadikan bertani bukan sekadar warisan, tetapi pilihan. Bukan sekadar profesi, tetapi identitas yang membanggakan. Sebab tanpa petani, tak ada pangan dan tanpa pangan, tak ada peradaban. WASPADA.id
- Penulis dosen pada Program Studi Biologi, Universitas Samudra, yang saat ini tengah menempuh pendidikan pada Program Doktor Biologi Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada.
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.