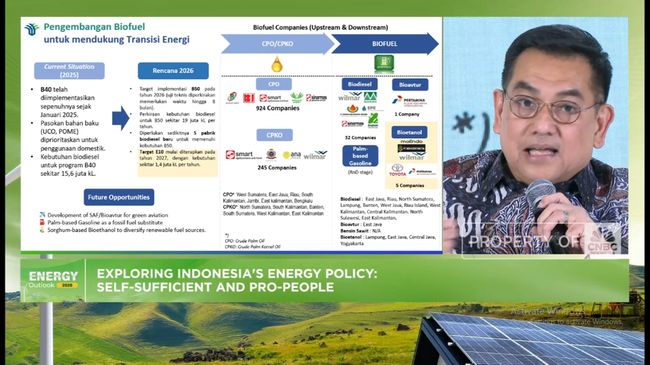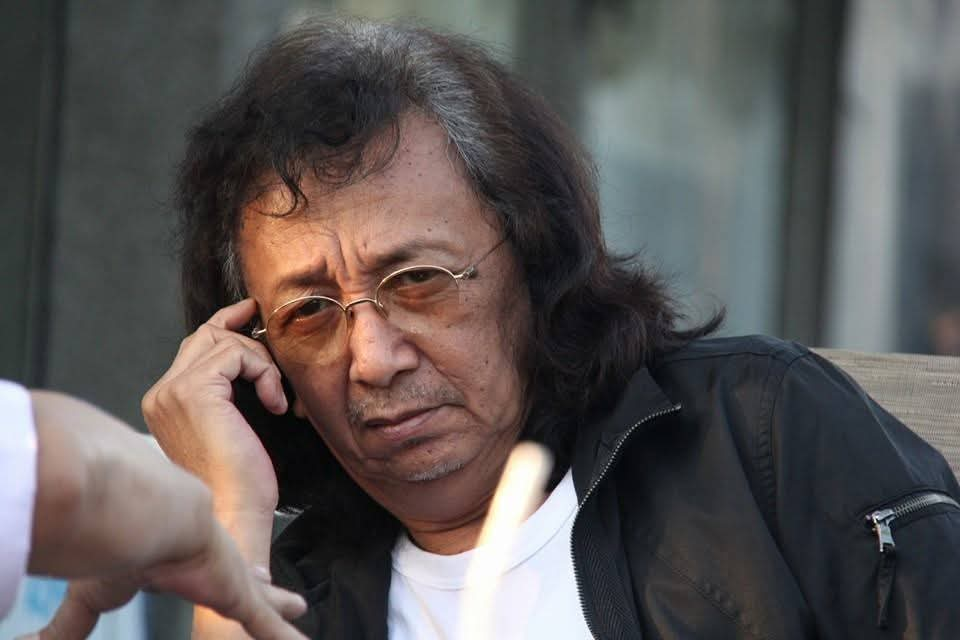Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Pada literasi sejarah ekonomi Indonesia, nama Sumitro Djojohadikusumo hadir bagai pelita yang menyinari jejak industrialisasi dan nasionalisme ekonomi. Gagasannya tentang pembentukan instrumen pengelola industri negara, dengan BUMN sebagai pilar utama, merupakan bentuk economic statecraft yang visioner.
Sebuah rekayasa sosio-ekonomi di mana negara bukan sekadar regulator, melainkan pelaku utama yang mengarahkan denyut nadi perekonomian menuju cita-cita kemandirian dan keadilan sosial.
Namun, lebih dari setengah abad kemudian, ketika kita menatap wajah pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) hari ini, sebuah kegelisahan muncul, yaitu sejauh mana kita telah beranjak dari mimpi besar itu, dan makin samar kah roh Pancasila sebagai napas pengelolaannya?
Memasuki tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, kegelisahan ini menemui momentum aktualnya. Duet kepemimpinan ini mewarisi lanskap BUMN yang kompleks, yakni terjepit di antara dua logika yang penuh tuntutan efisiensi korporasi dan mandat sosial sebagai agen pembangunan.
Pada tahun krusial ini, sorotan tertuju pada bagaimana visi "Indonesia Maju" akan dielaborasi menjadi kebijakan BUMN yang konkret. Akankah pemerintahan ini memilih jalur pragmatis dengan mempercepat divestasi BUMN "non-strategis" untuk membukukan kesehatan fiskal? Atau justru mengambil langkah transformatif dengan memperkuat peran BUMN sebagai strategic instrument untuk membangun kedaulatan di sektor pangan, energi hijau, dan teknologi masa depan?
Tindakan nyata terhadap Danantara dan Indonesia Investment Authority (INA) akan menjadi barometer. Akankah Danantara ditempatkan sebagai "KDB-nya Indonesia", dengan modal dan mandat kuat untuk memimpin investasi di sektor pionir? Atau ia tetap menjadi portfolio manager yang gagap menanggung risiko?
Begitu pula dengan INA: akankah ia berani menjangkau sektor high-risk high-reward seperti semikonduktor dan farmasi, atau tetap nyaman berlabuh di aset infrastruktur yang telah matang?
Di sisi lain, wacana penciptaan "Nonghyup ala Indonesia" harus diuji dengan transformasi nyata, misalnya, membangkitkan kembali BRI Agro dan Bulog menjadi tulang punggung logistik dan keuangan bagi koperasi serta UMKM. Tahun pertama ini adalah momen penentuan: meletakkan fondasi grand design BUMN yang terpadu dan berjangka panjang, yang tak tergantung pada siklus politik dan konsisten pada roh Pancasila.
Struktur pengelolaan BUMN kita hari ini, dengan Danantara dan BP BUMN sebagai dua kutub, menggambarkan lanskap yang tumpang-tindih dan kadang tak selaras. Pertanyaan mendasarnya adalah di mana sebenarnya titik dasar pengambilan strategi itu bermuara?
Kebijakan yang tak sinkron, seperti satu sisi berbicara optimalisasi portofolio, sisi lain menekankan fungsi agen pembangunan, menciptakan disorientasi di tingkat direksi. BUMN menjadi seperti raksasa limbung: tak cukup lincah di pasar bebas, tapi juga tak cukup fokus menjalankan mandat negara.
Kehadiran INA yang sempat digadang-gadang sebagai lompatan baru pengelolaan kekayaan negara juga memantik tanya. Sebagai sovereign wealth fund, INA diharapkan menjadi kendaraan investasi yang lincah, mendatangkan modal, dan meningkatkan nilai aset. Namun dalam narasi statetecraft, INA masih terlihat gamang: antara mengejar imbal hasil finansial atau menjadi instrumen strategis membangun kedaulatan ekonomi jangka panjang.
Kekhawatiran kian menjadi ketika meninjau portofolio dan strategi INA. Jika ia hanya berkutat pada aset-aset matang dan berarus kas stabil-seperti telekomunikasi dan infrastruktur tol tanpa menyentuh sektor inisial yang vital bagi masa depan bangsa (seperti semikonduktor, farmasi, atau teknologi hijau), maka INA tak lebih dari asset manager biasa.
INA seperti gagal memainkan peran transformatifnya. INA semestinya menjadi katalis untuk membidik sektor-sektor yang belum bankable namun punya nilai strategis tinggi, yakni sesuai semangat Sumitro membangun inti industri bangsa.
Wacana divestasi BUMN di sektor "kurang strategis" juga menyisakan paradoks. Di satu sisi, argumen efisiensi dan fokus negara pada sektor krusial terdengar masuk akal. Tapi, siapa yang mendefinisikan "kurang strategis"? Apakah hotel, perkebunan, atau manufaktur tekstil tak lagi punya nilai strategis bagi penyerapan tenaga kerja, penguatan rantai pasok domestik, dan pemerataan ekonomi?
Kita tak perlu jauh-jauh mencari contoh best practice. Korea Selatan menghadirkan dua model sukses yang saling melengkapi: Korea Development Bank (KDB) dan Nonghyup (NH). KDB adalah contoh sempurna statecraft di sektor industrial frontier, atau permulaan.
Melalui modal yang memadai, ia mendanai fase riset dan pengembangan yang berisiko tinggi, memayungi industrialisasi dari industri berat ke teknologi mutakhir. KDB sukses karena mandatnya jelas, yaitu bukan mengejar laba jangka pendek, melainkan membangun *national champion* seperti Samsung dan Hyundai yang mampu bersaing di panggung global.
Sementara Nonghyup (NH) menunjukkan kekuatan berbeda. Bermula dari koperasi pertanian yang diinisiasi pemerintah era 1960-an, NH berevolusi menjadi raksasa keuangan dan logistik yang dimiliki petani sendiri.
NH tak hanya menyediakan permodalan, tapi juga menyangga seluruh ekosistem pertanian: pemasaran, distribusi, logistik, asuransi, hingga perbankan. NH membuktikan bahwa entitas yang lahir dari kebijakan negara bisa tumbuh mandiri, dikelola profesional, dan mengakar pada basis anggotanya.
Bayangkan jika Indonesia memiliki BUMN "KDB ala Indonesia" yang fokus pada industri futuristik, dan BUMN "NH ala Indonesia" yang mengonsolidasi serta memperkuat koperasi dan UMKM di sektor pangan, maritim, dan kerajinan.
Persoalannya, kita kerap terjebak pada solusi simplistis: merger. Merger dipaksakan tanpa analisis mendalam tentang sinergi strategis dan budaya organisasi hanya akan melahirkan raksasa birokratis yang lamban. Masalah mendasarnya adalah kejelasan visi. Semestinya, kita merasionalisasi BUMN bukan sekadar berdasarkan jumlah, melainkan berdasarkan peta jalan industrial Indonesia ke depan.
Lantas, bagaimana merangkai economic statecraft Indonesia di tengah pusaran globalisasi dan kepentingan kapital global? Jawabannya mungkin terletak pada filsafat dasar ekonomi kita: Pancasila. Jika Korea Selatan punya Saemaeul Undong yang bermakna Gotong Royong, Indonesia memiliki Pancasila yang menjadi sudut pangkal dari semangat kolektivitas itu.
Pertama, Indonesia membutuhkan grand design BUMN yang terpadu dan jelas. Sebuah peta navigasi yang menjabarkan tegas peran Kementerian BUMN, Danantara, dan INA dalam orkestra besar pembangunan nasional. Peta ini harus melampaui visi lima tahunan, menjadi komitmen jangka panjang bangsa, tak terganti setiap kali kepemimpinan berganti.
Kedua, BUMN harus dikembalikan pada khittahnya sebagai public service corporation. Orientasi laba penting, tapi bukan tujuan akhir. Laba adalah oksigen untuk tetap hidup dan berkembang, sementara tujuannya adalah memakmurkan rakyat.
Kinerja direksi BUMN tak boleh hanya diukur dari rasio keuangan, tapi juga dari kontribusinya pada penguatan rantai pasok domestik, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan penyediaan barang/jasa strategis yang terjangkau.
Ketiga, Danantara harus berani menjadi pionir, mengambil risiko dalam investasi yang strategis bagi masa depan bangsa, menjadi rumah bagi mimpi-mimpi besar teknologi Indonesia.
Keempat, Indonesia perlu menciptakan "Nonghyup-nya Indonesia". Alih-alih melepas BUMN di sektor riil yang dianggap kurang strategis, atau membangun Koperasi Merah Putih yang tak jelas konsepnya, mengapa tidak mentransformasikannya menjadi koperasi-koperasi modern yang dimiliki petani, nelayan, dan pengusaha kecil, dengan dukungan perbankan dan logistik dari negara di fase awal? Ini adalah bentuk nyata Pasal 33, yang jauh lebih bermakna daripada sekadar divestasi.
Ekonomi Indonesia hari ini, dengan kesenjangan yang menganga dan ketergantungan impor di sektor strategis, menunjukkan kita mungkin sedang menjauh dari cita-cita keadilan sosial. Kita terjebak dalam pragmatisme jangka pendek dan kehilangan kompas strategis jangka panjang, seperti melupakan Pancasila.
(miq/miq)

 3 months ago
33
3 months ago
33