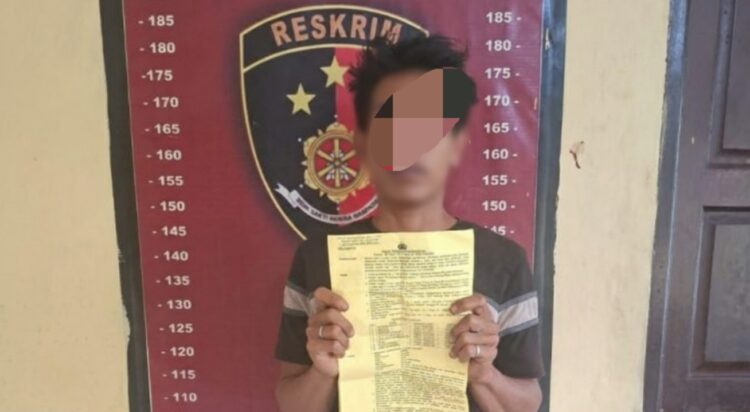Oleh: Farid Wajdi
Main hakim sendiri terus berulang sebagai ritual sosial yang ganjil. Setiap kali terjadi kejahatan jalanan, hukum seolah diberi waktu tunggu, sementara emosi publik bergerak cepat.
Massa menghakimi, memukul, menyeret, bahkan menghabisi. Setelah itu, aparat datang mencatat kerusakan. Hukum hadir sebagai notulis tragedi, bukan penentu keadilan.
Dalam tradisi hukum pidana Eropa Kontinental, praktik ini dikenal sebagai eigenrichting atau eigenmachtige rechtshandhaving. Istilah tersebut menunjuk tindakan penegakan “keadilan” secara sepihak tanpa prosedur hukum.
Hazewinkel-Suringa (1953) menempatkan eigenrichting sebagai penyangkalan langsung terhadap rechtsstaat. Negara hukum berdiri di atas satu fondasi utama: hak menghukum dimonopoli negara melalui peradilan, bukan diserahkan kepada individu atau massa.
Alasan yang paling sering diajukan untuk menjelaskan fenomena ini ialah runtuhnya kepercayaan publik terhadap hukum dan penegak hukum.
Proses dianggap lamban, hasil dinilai timpang, keadilan terasa mahal. Dalam persepsi semacam ini, hukum formal kehilangan wibawa sosial. Ketika hukum tidak lagi dipercaya, kekerasan tampil sebagai jalan pintas yang dianggap efektif.
Barda Nawawi Arief (2010) membaca main hakim sendiri sebagai gejala kegagalan sistemik. Hukum positif gagal menghadirkan rasa keadilan sosial, lalu masyarakat mencari saluran alternatif.
Namun analisis tersebut tidak berhenti pada empati sosial. Ia menegaskan satu batas tegas: kegagalan sistem tidak pernah menghapus sifat pidana dari kekerasan kolektif. Penjelasan sosiologis berfungsi menerangkan sebab, bukan membenarkan perbuatan.
Di sinilah paradoks muncul. Ketidakpercayaan terhadap hukum justru melahirkan pelanggaran hukum yang lebih telanjang. Kekerasan massa merusak asas praduga tak bersalah, meniadakan hak pembelaan, dan membuka ruang kesalahan fatal.
Vonis dijatuhkan tanpa pembuktian, hukuman dilaksanakan tanpa pertimbangan, korban berjatuhan tanpa mekanisme koreksi.
Krisis Literasi Hukum
Moeljatno (1985) mengingatkan hukum pidana tidak hanya mengatur larangan perbuatan, tetapi juga melarang cara-cara ilegal dalam merespons kejahatan.
Menghukum tanpa putusan pengadilan berarti melakukan pelanggaran ganda: terhadap individu yang dituduh dan terhadap ketertiban hukum. Dalam logika hukum pidana, kemarahan moral tidak pernah diakui sebagai dasar penghukuman.
KUHP memposisikan main hakim sendiri sebagai tindak pidana melalui ketentuan tentang kekerasan, penganiayaan, pengeroyokan, hingga pembunuhan. Pendekatan keadilan substantif yang berkembang dalam kebijakan hukum pidana tidak mengendurkan larangan tersebut.
Sudarto (2009) mengingatkan keadilan substantif tidak identik dengan pembenaran tindakan ekstra-yudisial. Keadilan tetap mensyaratkan prosedur, rasionalitas, dan pengendalian kekuasaan.
Sindiran paling tajam terletak pada logika moral yang sering digunakan publik. Pelaku kejahatan dianggap pantas dipukuli demi efek jera. Logika ini rapuh. Hari ini massa yakin telah menghukum pelaku, esok hari terbukti salah sasaran. Sejarah kekerasan kolektif mencatat banyak korban meninggal tanpa pernah terbukti bersalah. Setelah emosi surut, hukum dipanggil untuk membersihkan puing, bukan mencegah tragedi.
Aparat penegak hukum tidak bisa sekadar menunjuk massa sebagai biang masalah. Keterlambatan respons, absennya kehadiran negara di ruang publik, serta komunikasi hukum yang kaku memperlebar jarak dengan masyarakat.
Satjipto Rahardjo (2006) mengingatkan hukum kehilangan makna saat terlepas dari realitas sosial. Ketika negara hadir terlambat, ruang kosong otoritas diisi oleh amarah kolektif.
Namun menempatkan negara sebagai satu-satunya pihak yang bersalah juga menyesatkan. Main hakim sendiri mencerminkan krisis literasi hukum publik. Hukum dipahami sebatas alat balas dendam, bukan mekanisme perlindungan hak.
Emosi dipercaya lebih cepat daripada prosedur. Dalam kondisi seperti ini, hukum kalah bukan karena norma lemah, melainkan karena kesadaran hukum runtuh.
Jika praktik ini dibiarkan, konsekuensinya serius. Kekerasan kolektif akan terus berulang, legitimasi hukum terkikis, dan negara hukum berubah menjadi slogan kosong.
Ketertiban digantikan oleh rasa aman semu, sementara hak asasi dikorbankan atas nama kemarahan bersama.
Main hakim sendiri bukan solusi atas lemahnya penegakan hukum. Ia merupakan gejala krisis kepercayaan sekaligus penyebab kerusakan yang lebih dalam.
Jalan keluar tidak terletak pada pembiaran emosi massa, melainkan pada kehadiran hukum yang cepat, adil, dan dapat dipercaya. Tanpa itu, hukum akan terus tertinggal, sementara keadilan dicari di jalanan dengan kepalan tangan.
Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.