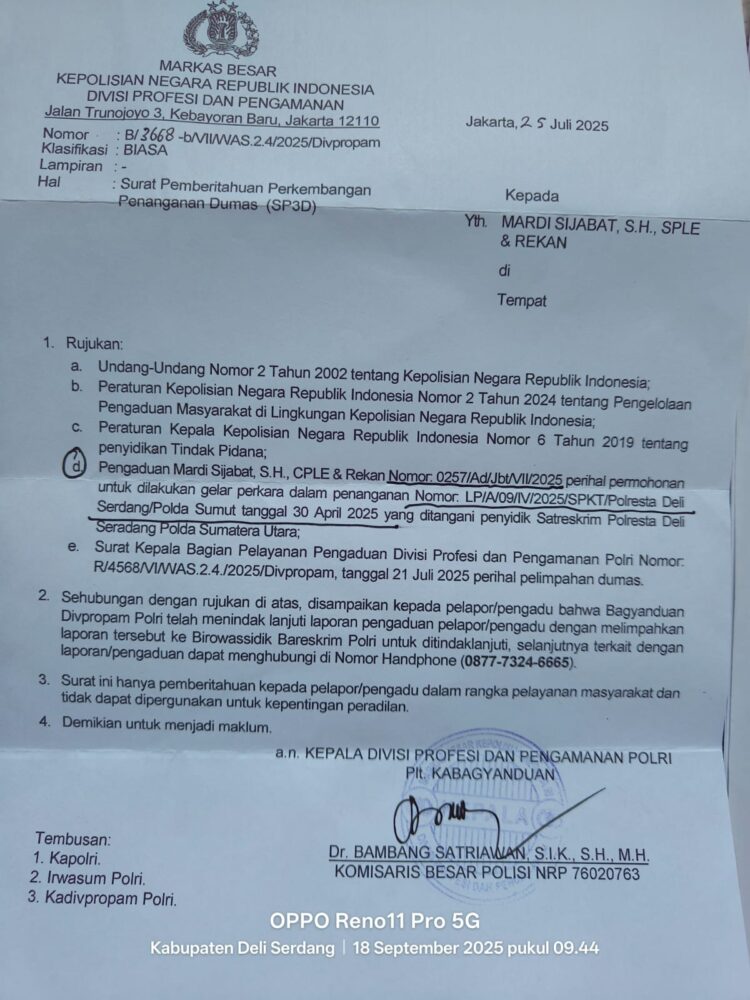Oleh: Muhibbullah Azfa Manik

Ukuran Font
Kecil Besar
14px
Negara seolah kalah tawar dalam lobi dagang. Itulah kesan kuat yang muncul dari terungkapnya klausul kesepakatan antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam penyelesaian sengketa tarif layanan digital di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Dalam dokumen yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), tercantum kesepakatan bahwa Indonesia akan membuka akses pemrosesan data pribadi warganya kepada perusahaan-perusahaan AS. Tak ayal, publik Tanah Air pun terperanjat: sejak kapan data pribadi menjadi alat tukar dalam diplomasi dagang?
Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN
Kisah ini bermula dari kebijakan Indonesia mengenakan bea masuk atas produk digital, termasuk perangkat lunak dan film digital impor. Kebijakan itu membuat Amerika Serikat—yang selama ini mengandalkan ekspor produk digital dari raksasa-raksasa teknologi mereka seperti Google, Amazon, dan Netflix—meradang. Sengketa pun bergulir ke meja WTO.
Setelah serangkaian negosiasi, Indonesia akhirnya menarik langkahnya dan menyetujui untuk tidak memperpanjang kebijakan bea masuk tersebut. Namun yang lebih mengejutkan bukan hanya penarikan tarif itu, melainkan lampiran dalam kesepakatan yang menyebut Indonesia mendukung “arus lintas data lintas batas” dan tidak akan memaksakan aturan lokalisasi data.
Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan asing, terutama dari AS, bebas memproses dan menyimpan data warga Indonesia di luar negeri, selama mengikuti prinsip-prinsip dasar keamanan dan perlindungan.
Klausul ini secara formal memang merujuk pada prinsip-prinsip “free flow of data with trust” yang selama ini digagas negara-negara G7. Tapi makna praktisnya sungguh politis: Indonesia tampak melunak pada tuntutan negara-negara maju yang selama ini mendesak pembebasan lalu lintas data global demi kepentingan bisnis teknologi mereka.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sempat menyangkal bahwa data pribadi warga Indonesia menjadi bagian dari “jual-beli.” Ia menyebut kesepakatan itu tak lain soal penyelesaian sengketa bea layanan digital.
Namun pernyataan sang menteri berseberangan dengan fakta bahwa Pemerintah Amerika Serikat sendiri yang menuliskan dalam rilis resminya bahwa Indonesia telah menyepakati prinsip keterbukaan arus data dan tidak akan menerapkan pemaksaan lokalisasi server.
Keganjilan lain muncul ketika DPR dan Komisi Informasi Pusat mengaku tidak tahu-menahu ihwal kesepakatan itu. Padahal, di dalam negeri, Indonesia baru saja mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang salah satu semangatnya adalah menjaga kedaulatan data warga negara, termasuk dalam hal lokasi penyimpanan dan pengendalian aksesnya.
Jika benar Indonesia menyerahkan kendali sebagian data kepada negara asing demi kompromi tarif digital, maka ini bukan sekadar langkah pragmatis, tapi sebuah pembelokan arah kebijakan.
Bukan hal baru sebenarnya jika negara-negara Global South berada dalam posisi tawar yang lemah dalam negosiasi digital internasional. Namun seharusnya Indonesia belajar dari pengalaman, bahwa data adalah aset strategis abad ke-21.
Dalam dunia yang terkoneksi lewat algoritma, siapa mengendalikan data, ia menguasai narasi dan keuntungan ekonomi. Data bukan hanya catatan angka, tapi cermin perilaku, selera konsumsi, bahkan potensi manipulasi.
Indonesia, yang memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet aktif, adalah tambang emas data yang luar biasa besar. Jika pengelolaan dan keamanannya tak dipagari dengan bijak, bukan tak mungkin bangsa ini hanya menjadi lumbung data yang ditambang habis oleh perusahaan global, tanpa kedaulatan atas pemanfaatannya.
Pemerintah seharusnya lebih transparan dan akuntabel dalam menyusun dan menyepakati kebijakan yang berdampak pada hak konstitusional warga. Data pribadi bukan sekadar aset ekonomi, tapi hak asasi yang melekat pada warga negara. Pengelolaannya pun harus tunduk pada prinsip kehati-hatian, bukan tergadai dalam tawar-menawar diplomatik.
Lebih dari itu, perlu ada audit kebijakan digital secara menyeluruh. Jangan sampai publik dibohongi dengan narasi “demi kepentingan dagang,” padahal yang dikorbankan adalah privasi dan keamanan data warga. DPR dan lembaga-lembaga pengawas informasi publik mesti bersuara dan menuntut klarifikasi resmi dari pemerintah. Termasuk, jika perlu, meninjau kembali kesepakatan tersebut dalam kerangka perlindungan data dan kedaulatan digital.
Kasus ini adalah alarm keras bagi bangsa ini, bahwa dalam era ekonomi digital, bukan lagi soal ekspor-impor barang konvensional yang menentukan posisi tawar, melainkan siapa yang mengendalikan aliran informasi dan siapa yang memiliki hak atas data. Jangan sampai kita menjadi “tuan rumah” yang dengan sukarela menyerahkan kunci rumah kepada tamu yang lebih pandai bernegosiasi.
Pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab pemerintah hari ini adalah: data siapa yang mereka jaga? Data kita, atau kepentingan mereka?
Penulis adalah Dosen Teknik dan Manajemen Industri Universitas Bung Hatta, Pemerhati Kebijakan Pemerintah
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.