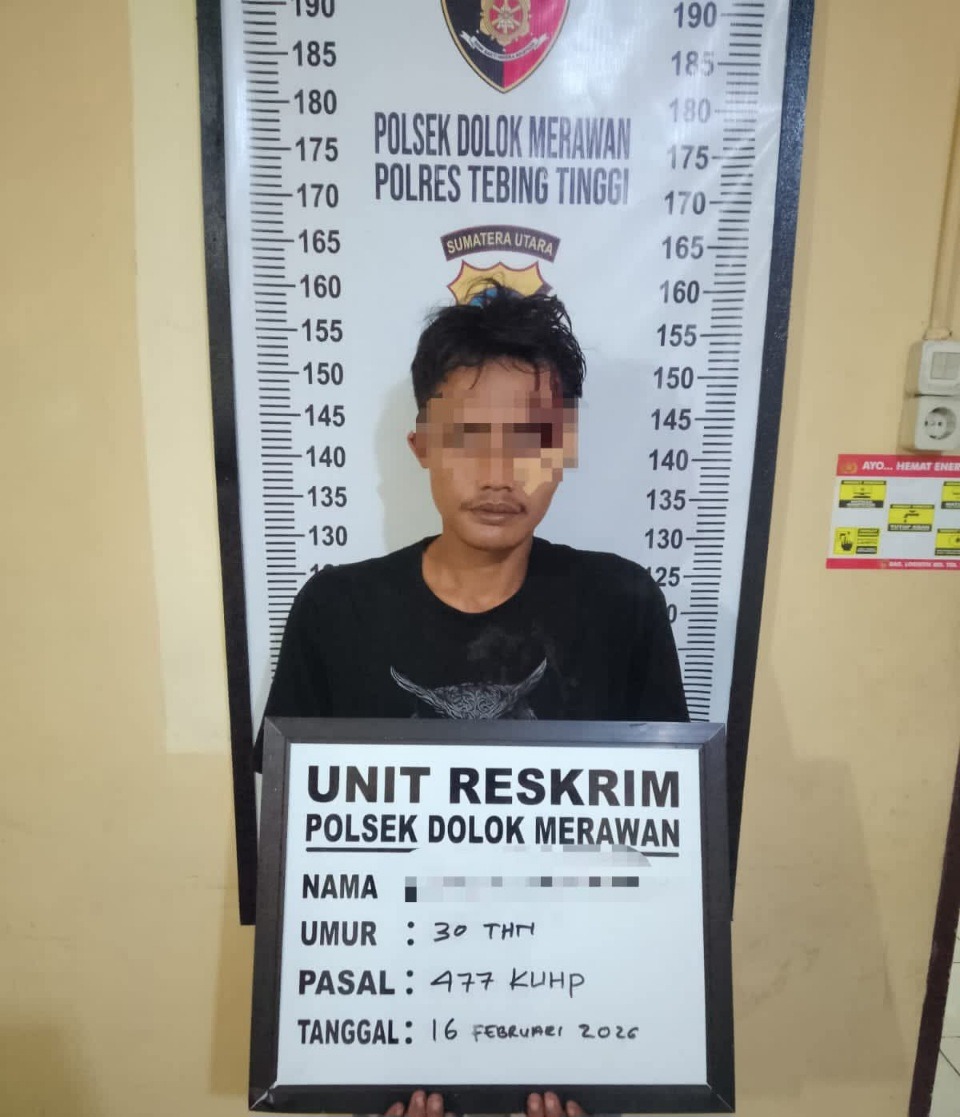Ukuran Font
Kecil Besar
14px
Oleh: Farid Wajdi
Pernyataan Presiden Prabowo dalam perayaan partai politik akhir 2025, yang mereduksi orang pintar sebagai pihak yang “hanya bicara” dan tidak mampu menjamin apa pun, memunculkan problem mendasar dalam imajinasi politik kita.
Ungkapan tersebut bukan sekadar kritik terhadap perilaku tertentu, melainkan refleksi dari kegamangan negara dalam menempatkan nalar kritis sebagai energi pembangunan (Antara News, 2025).
Dalam demokrasi modern, kritik tidak berposisi sebagai beban. Kritik berfungsi sebagai mekanisme koreksi kekuasaan. Robert A. Dahl (1989) menempatkan partisipasi kritis warga sebagai syarat demokrasi substantif. Ketika ruang kritik menyempit, demokrasi kehilangan isi dan berubah menjadi prosedur elektoral tanpa kedalaman nalar.
Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Arief Budiman (1991) yang menegaskan peran intelektual sebagai moral force dalam negara berkembang. Bagi Arief Budiman, intelektual tidak diukur dari kedekatannya dengan kekuasaan, melainkan dari keberaniannya menjaga jarak kritis demi kepentingan publik. Pembangunan tanpa kritik intelektual berisiko menjelma proyek teknokratis yang miskin orientasi keadilan.
Dalam praktik politik Indonesia, kritik kerap disalahartikan sebagai kegaduhan atau sikap tidak loyal. Pernyataan yang meremehkan orang pintar memperlihatkan kecemasan terhadap kebebasan berpikir dan pluralitas gagasan, unsur yang justru menjadi fondasi demokrasi deliberatif (Tempo.co).
Jürgen Habermas (1996) menempatkan kritik publik sebagai sumber legitimasi kebijakan. Kebijakan memperoleh keabsahan melalui proses argumentatif terbuka, bukan sekadar melalui kewenangan formal.
Kekeliruan dalam memandang kritik juga telah lama disorot Soedjatmoko (1983). Dalam berbagai esainya tentang pembangunan dan kebudayaan, Soedjatmoko menekankan pembangunan sebagai proses belajar sosial.
Proses ini menuntut keberanian mengoreksi diri melalui kritik. Tanpa refleksi kritis, pembangunan kehilangan kapasitas adaptif dan mudah terjebak dalam rutinitas administratif.
Narasi yang mempertentangkan kerja nyata dengan pemikiran kritis mencerminkan bias anti-intelektual. Richard Hofstadter (1963) menyebut kecenderungan ini sebagai anti-intellectualism, sikap politik yang mengagungkan kesederhanaan populis sambil mencurigai analisis rasional.
Dalam konteks Indonesia, bias ini berbahaya karena memperlemah fungsi intelektual sebagai pengawas kebijakan.
Nurcholish Madjid (1997) mengingatkan demokrasi tidak mungkin tumbuh tanpa kebebasan berpikir. Kritik publik bukan ancaman bagi stabilitas, melainkan syarat kematangan politik. Demokrasi tanpa kritik, menurut Cak Nur, hanya melahirkan kepatuhan semu, bukan partisipasi bermakna.
Dalam ekonomi publik, kritik bahkan berfungsi sebagai mekanisme teknis dan etis. Joseph E. Stiglitz (2000) menunjukkan kebijakan publik rentan distorsi akibat asimetri informasi dan kepentingan elite. Kritik independen berperan sebagai early warning system bagi pemborosan dan salah arah kebijakan.
Pandangan ini sejalan dengan analisis Faisal Basri (2012) yang berulang kali menekankan pentingnya kritik berbasis data untuk mencegah ilusi keberhasilan ekonomi dan jebakan kebijakan populis.
Amartya Sen (1999) menempatkan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari instrumental freedom yang meningkatkan kualitas pembangunan.
Dalam konteks Indonesia, gagasan ini dipertegas Sri Edi Swasono (2005) yang melihat kritik ekonomi sebagai wujud tanggung jawab konstitusional demi menjaga keberpihakan kebijakan pada kepentingan rakyat, bukan pada akumulasi segelintir elite.
Dari sudut administrasi negara, Dwight Waldo (1980) memperingatkan bahaya birokrasi tanpa kritik. Pemikiran ini beresonansi dengan kritik Mochtar Mas’oed (1994) terhadap teknokratisme Orde Baru, yang menempatkan efisiensi administratif di atas partisipasi dan akuntabilitas publik. Ketika kritik disingkirkan, kebijakan kehilangan kompas etik dan mudah terjebak dalam pembenaran internal.
Dalam demokrasi sehat, orang pintar kerap berperan sebagai wakil tak tertulis para pembayar pajak. Mereka menggunakan nalar sistematis untuk membaca dampak jangka panjang kebijakan dan menawarkan alternatif.
Hadiz dan Robison (2004) menunjukkan absennya kritik independen mempercepat pembajakan kebijakan oleh oligarki. Kritik intelektual berfungsi menahan laju konsolidasi kekuasaan ekonomi-politik semacam ini.
Kritik tanpa solusi memang tidak memadai. Namun kritik yang disertai tawaran perbaikan justru memperlihatkan nilai tertinggi orang pintar. Kritik semacam ini memadukan diagnosis masalah dengan peta jalan kebijakan. Inilah energi bangsa sejati, nalar kritis yang berpihak pada kemaslahatan publik.
Pemerintahan sehat tidak memusuhi kritik. Ia mengolahnya sebagai bahan koreksi. Soedjatmoko (1983) menyebut proses ini sebagai kedewasaan politik.
Tanpa kritik, pembangunan kehilangan refleksi. Tanpa refleksi, kekuasaan kehilangan arah. Bangsa besar tidak membungkam orang pintar. Bangsa besar memberi ruang kritik, mengubahnya menjadi dialog strategis, lalu memadukannya dengan kerja nyata demi masa depan bersama.
Kritik bukan cacat demokrasi. Kritik merupakan denyut nadi demokrasi itu sendiri. Tanpanya, demokrasi tinggal slogan tanpa kehidupan.
Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.