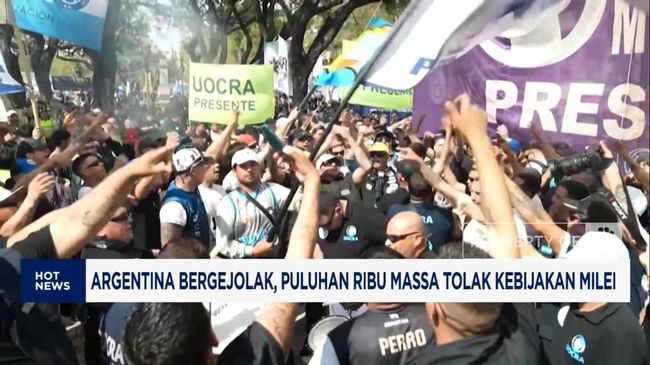Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Pada tanggal 16 Juli 2025, dua peristiwa penting menjadi sorotan yang kemudian disambut hangat oleh mayoritas pengamat ekonomi nasional. Pertama, Bank Indonesia (BI) kembali menurunkan suku bunga acuannya menjadi 5,25%. Kedua, Indonesia menandatangani kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat sebesar 19%, menjadikannya yang terendah kedua di Asia Tenggara setelah Singapura yang saat ini menetapkan tarif 10%.
Di mata publik dan media arus utama, ini adalah pertanda bahwa ekonomi akan kembali bergerak. Pasar saham melonjak. Ekonom lokal menyuarakan optimisme. Namun, bagi mereka yang melihat ekonomi dari kacamata Mazhab Austria, euforia ini justru menandakan sesuatu yang berbahaya sedang berlangsung secara diam-diam.
Bagi kebanyakan orang, memang tampaknya masuk akal menurunkan suku bunga ketika pertumbuhan kredit stagnan. Narasinya sederhana: jika biaya pinjaman masih terlalu tinggi, maka permintaan kredit tetap lemah. Solusinya? Buat uang lebih murah, dan permintaan akan meningkat. Tapi logika ini, yang sudah puluhan tahun menjadi dogma kebijakan moneter global, mengabaikan hakikat dari apa yang sebenarnya direpresentasikan oleh suku bunga.
Dalam teori ekonomi Austria, suku bunga bukan alat untuk "merangsang permintaan agregat", melainkan sinyal harga yang mencerminkan preferensi waktu masyarakat-yaitu seberapa besar orang menghargai konsumsi hari ini dibandingkan konsumsi di masa depan. Saat bank sentral mengintervensi suku bunga, mereka pada dasarnya membisukan sinyal ini.
Mereka menciptakan ilusi. Para pengusaha tidak lagi melihat biaya modal yang riil, tetapi biayayang telah dimanipulasi agar tampak lebih murah. Akibatnya adalah yang sejak lama diperingatkan oleh para ekonom Austria: malinvestment, investasi salah arah yang terjadi karena pelaku ekonomi mengambil keputusan berdasarkan sinyal harga yang keliru.
Proyek-proyek jangka panjang yang sebenarnya tidak layak secara fundamental pun diluncurkan karena tampak menjanjikan secara semu. Ekonomi mulai berkembang di atas fondasi ilusi, bukan realitas.
Dalam praktiknya, kita melihat bagaimana bisnis-melihat biaya pinjaman yang rendah-mulai melakukan ekspansi. Perusahaan manufaktur membeli mesin baru. Developer
membangun properti. Investor masuk ke proyek-proyek yang semula mereka anggap terlalu berisiko.
Konsumen pun ikut terhanyut-berbelanja dengan kartu kredit, mengambil pinjaman konsumtif, hidup sedikit lebih mewah dari kemampuan riil. Untuk sementara, semua
orang merasa makmur. Tapi ini bukan pertumbuhan sejati. Bukan hasil dari produktivitas yang meningkat atau akumulasi modal yang sehat. Ini hanyalah boom fase awal dari siklus ekonomi yang tidak berkelanjutan.
Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah memperlihatkan gejala-gejala khas dari boom palsu ini. Di saat kebijakan moneter terus dilonggarkan, indikator di lapangan menunjukkan cerita yang berbeda. PHK meningkat. Daya beli masyarakat terus tergerus inflasi. Perusahaan-perusahaan, terutama di sektor manufaktur dan B2B, pelan-pelan mengakui bahwa permintaan konsumen tak sesuai ekspektasi.
Industri tekstil adalah contoh nyata. Banyak pelaku industri menyalahkan produk murah China yang membanjiri pasar. Tapi di balik itu, banyak perusahaan tekstil kita yang sebenarnya telah melakukan ekspansi produksi dan pengadaan modal berdasarkan proyeksi permintaan yang keliru-yang sebetulnya hanyalah ilusi akibat suku bunga rendah.
Kesalahan ini bukan kegagalan pasar, tetapi kegagalan perencanaan-lebih tepatnya, kegagalan perencanaan sentralistik. BI, seperti banyak bank sentral lain, percaya bahwa
mereka bisa mengarahkan ekonomi dengan memutar kenop suku bunga. Tapi jika suku bunga tak lagi mencerminkan tabungan riil dan preferensi waktu masyarakat, maka keputusan investasi tak lagi berbasis perhitungan ekonomis yang jujur.
Yang muncul justru distorsi. Kredit murah mendorong pelaku yang paling berani berspekulasi, bukan yang paling produktif. Sementara penabung-pilar dari akumulasi modal sejati-terpinggirkan dan dirugikan.
Masalah ini sebenarnya juga berakar dari salah kaprah soal uang. Uang terlalu sering dianggap netral, hanya alat tukar. Padahal, uang adalah komoditas. Dan seperti komoditas lainnya, ia tunduk pada hukum penawaran dan permintaan.
Ketika bank sentral menyuntikkan likuiditas ke dalam sistem, uang tersebut tidak menyebar merata. Ia mengalir lewat jalur-jalur tertentu: bank besar, institusi keuangan, kontraktor pemerintah. Yang berada di "dekat keran" mendapat keuntungan duluan-sebelum harga-harga naik. Ini adalah efek Cantillon, dan dampaknya nyata: ketimpangan makin lebar, kelas menengah semakin tertekan, dan akumulasi kekayaan menjadi tidak merata.
Mencermati Trump Tariff
Lalu bagaimana dengan kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat? Di atas kertas, ini adalah langkah maju bagi liberalisasi perdagangan. Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi atas keberaniannya mencabut kebijakan proteksionis seperti TKDN, serta membuka sektor strategis seperti manufaktur dan kesehatan bagi kompetisi asing.
Tapi kita perlu jujur: reformasi ini bukan lahir dari prinsip, tapi dari tekanan diplomatik dan ekonomi. Ini bukan spontanitas pasar, tapi hasil kompromi politik. Dan jika tidak diikuti oleh reformasi kelembagaan yang sesungguhnya-seperti kepastian hukum, perampingan birokrasi, dan jaminan hak milik-maka manfaatnya akan bersifat jangka pendek.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia kalah bersaing dari Vietnam dan India bukan karena kita tidak punya potensi, tetapi karena kita terlalu birokratis dan inkonsisten dalam kebijakan. Investor butuh kepastian. Mereka mencari sistem yang berpihak pada kebebasan usaha, bukan intervensi negara. Dan mereka tidak bisa menunggu selamanya.
Jika kita ingin membuka diri terhadap modal global, maka kita juga harus membuka diri terhadap aturan main pasar bebas-di mana harga, termasuk harga uang dan modal, ditentukan oleh jutaan interaksi sukarela, bukan oleh keputusan teknokrat di ruang rapat bank sentral.
Maka pertanyaan utamanya: apakah Indonesia benar-benar sedang menuju pertumbuhan yang berkelanjutan, ataukah kita sekali lagi terjebak dalam ilusi stimulus jangka pendek?
Pemangkasan suku bunga, kesepakatan dagang, dan optimisme pasar mungkin terlihat menggembirakan. Tapi mereka tidak bisa menggantikan fondasi ekonomi yang sehat. Dalam pandangan Mazhab Austria, tabungan riil adalah sumber pertumbuhan. Bukan konsumsi utang. Bukan kredit murah. Bukan intervensi moneter.
Jika kita sungguh ingin bertumbuh, kita harus siap membiarkan suku bunga naik jika itu yang mencerminkan kondisi riil. Kita harus berani membiarkan investasi buruk gagal. Kita harus memberi insentif bagi penabung, bukan spekulan.
Dan yang paling penting, kita harus membiarkan harga-termasuk harga modal-muncul dari proses pasar yang bebas dan terbuka. Ekonomi bukan mesin yang bisa disetel. Ia adalah proses yang hidup-digerakkan oleh individu, oleh preferensi waktu, dan oleh kebebasan memilih.
Untuk saat ini, Indonesia telah diberikan rakit penyelamat. Tapi jika rakit ini dibangun di atas kredit semu, birokrasi yang mencekik, dan ilusi fiat money, maka kebocoran sudah dimulai bahkan sebelum kita menyentuh arus deras.
Kita masih punya waktu untuk membalik arah. Tapi itu hanya akan terjadi jika kita berani menanggalkan pendekatan teknokratis, dan kembali memercayai prinsip paling dasar dari kebebasan ekonomi: bahwa masyarakat bebas, ketika dibiarkan memilih sendiri, akan jauh lebih bijak daripada mereka yang mengaku bisa merencanakan segalanya dari atas.
(miq/miq)

 2 months ago
22
2 months ago
22